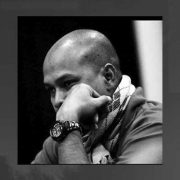Pengalaman Menonton Pertunjukan “Waringan Oncek-Oncek”
Oleh Razan Wirjosandjojo (Studio Plesungan, Karanganyar)
“Derai hujan menyambut, ketika saya, mas Akri, dan pak Halim sampai di Rumah Banjarsari untuk menyaksikan pertunjukan teater bertajuk, ”Waringan Oncek-Oncek”. Pertunjukan ini diselenggarakan oleh Teater Ruang dan Teater Sangir, dipentaskan satu kali pada malam minggu, 27 Januari 2024. Selayaknya pertunjukan di kota Solo, kami menikmati waktu yang mengulur ditemani teh dan gorengan. Pertunjukan dimulai usai hujan reda, pukul 8 malam.
Ketika masuk ke ruang pertunjukan, penonton duduk lesehan menghadap ke sisi selatan ruangan. Dinding diselimu kain hitam dengan lantai yang hitam, ada sebuah panci yang menggantung di tengah-belakang panggung. Pertunjukan di mulai ketika 5 aktor masuk ke panggung bernyanyi. Saya tidak tahu apa yang dinyanyikan, tapi saya menangkap hadirnya kata oncek-oncek, seperti yang saya lihat di judul. Teater ini dibawakan dalam bahasa Jawa, juga dengan gaya lelucon khas wong Jowo. Saya yang terbilang belum lama memahami bahasa Jawa, senang dapat mengikuti panjang percakapan yang mereka bawakan.

Poster pertunjukan “Waringan Oncek-Oncek” (Sumber: Penulis)
Arisan menjadi peristiwa yang melatari adegan pertama. Mereka berperan menjadi warga desa yang berisik, haus uang, dan sulit diatur. Empat tokoh muda yang terus mendahulukan keinginannya sendiri secara ekspresif, dilerai oleh satu aktor yang lebih tua. Pola ribut-lerai ini terus berlanjut sampai akhirnya teater ini memutuskan untuk membuat teater. Mereka ingin menjadi pejabat. Sejak awal, ketika salah seorang datang dengan dalih “menitip” kursi ke panggung, saya sudah curiga ini akan penuh dengan persoalan kekuasaan.
Betul saja. Mereka mengubah nama kumpul-kumpul mereka menjadi Dewan Permasalahan Rakyat. Mereka juga mengganti nama (peran) mereka dengan dengan imbuhan seperti elit, pamong, sugih (contoh: Sarinem Sugih). Kata-kata tersebut melekat dalam benak orang banyak atas citra orang berwenang. Mereka pun mengubah tampilan mereka, berlipstik dan berdasi warna-warni, menampakkan pejabat sebagai badut yang konyol. Mereka pun disemati variasi bentuk karakter khas pejabat. Ada yang menjadi pejabat religius, pejabat yang sosialita, pejabat yang suka ketiduran, semakin menjelaskan panggung politik sebagai liang keburukan.
Mereka lalu berpura-pura menjadi pejabat, menirukan gesturnya, mengulang jargon- jargon dan trik populer yang dilakukan para aparatur negara di panggung politik. Dibalik jubah pejabat tersebut, keliaran-keliaran mereka tidak surut. Sepertinya memainkan peran ganda ini justru menjadi kesempatan mereka untuk semakin menjadi-jadi. Para aktor tetap membicarakan topik-topik yang tidak bermutu seperti jemuran celana dalam, menggoreng tempe gosong, dan lain sebagainya. Mereka menyebut perkumpulan ini masih seperti “wong alas / orang hutan”. Lalu semakin lama, kegilaan mereka semakin runyam, mereka kesurupan nafsu. Bentuknya seperti tayangan televisi supranatural yang dulu saya lihat di televisi tengah malam. Situasi pertunjukan penuh teriakan dan seruan-seruan yang ganas.

Foto pertunjukan “Waringan Oncek-Oncek” (1). (Sumber: Penulis)
Budhe yang sejak awal berperan menjadi pamong kegilaan empat aktor, lalu mencabut dasi-dasi mereka. Seketika dasi itu menjelma susuk yang ketika dicabut, menghilangkan “setan” yang merasuk ke diri empat aktor tersebut. Pertunjukan ini berakhir dengan lirih-lirih tobat (yang terlihat seperti bentuk kesetanan baru). Si budhe berkhotbah dengan petuah-petuah agar mengurungkan mimpi sebagai pejabat, jika kamu hanya rakyat (saya merasa bagian ini sangat bermasalah secara makna dan penempatan).
—
Saya terbilang jarang menyaksikan pertunjukan teater. Jika dihitung dari semua pertunjukan yang pernah saya saksikan, pertunjukan teater tidak sampai seperlimanya. Tentu ini tidak baik, namun bukan semata karena saya tidak ingin menonton. Peta pertunjukan di Solo itu seperti kepulauan. Pulau tari terpisah dari pulau teater, juga terpisah dari pulau musik, mungkin seni rupa hidup di planet lain. Belum lagi setiap pulau terbagi menjadi beberapa negara, yang beberapa tidak menerima paspor tertentu. Entah karena warnanya, atau karena kewarganegaraannya, atau karena namanya masuk daftar cekal. Bagaimanapun, poster pertunjukan ini sampai ke pada saya melalui pak Halim, menjadi tiket saya untuk menyeberangi pulau.
Melalui pertunjukan “Waringan Oncek-Oncek”, saya menyadari senjata andalan dalam teater naratif, bahwa mereka punya keleluasaan berbicara secara verbal, seluas-luasnya, sebebas- bebasnya. Hal tersebut tidak terjadi ide tari atau musik. Walaupun begitu, bisa jadi sama saja seperti tari yang menggunakan gerak, atau musik yang menggunakan bunyi. Pertunjukan ini penuh dengan omongan. Mengiku= percakapan pada pertunjukan ini, saya terpikir, “Teater bisa membuat penonton putus asa, dengan mengatakan “ora usah ngimpi jadi pejabat, nek kowe rakyat jelata (tidak usah jadi pejabat, kala kamu rakyat jelata). Ia bisa menciptakan teks sebagai benda tajam, hampir memaksa. Walaupun menjadi kelebihan, jika “kelebihan” bisa jadi belati bermata dua. Saya menyaksikan belati ini menyayat saya lewat pertunjukan ini.

Foto pertunjukan “Waringan Oncek-Oncek” (2). (Sumber: Penulis)
Menyaksikan pertunjukan “Waringan Oncek-Oncek” membuat saya seperti menyaksikan perdebatan di kolom komentar sosial media. Semua sibuk dan kencang terhadap opini dan kemauannya masing-masin. Tidak terkendali, penuh sindiran, tapi kadang terasa terputus di tengah jalan, mulai kembali dengan topik yang lain. Semua ingin dibicarakan. Meskipun keberingasan sangat kentara pada wajah dan ucapan para aktor, bangunan topiknya begitu rapi. Saya terkadang bisa menebak-nebak satu poin sebagai tanda untuk masuk ke poin berikutnya, lalu merantai seperti pidato. Saya mengandaikan sutradara seperti calon-calon pejabat yang sedang menggunakan aktor sebagai buzzer yang sporadis meneriakkan opini sang calon, brutal dan struktural. Saya seperti sedang dididik untuk memilih dan/atau tidak memilih pihak, atau pendapat. Kelamaan membawa saya jauh dengan suara saya sendiri yang sebetulnya berhak ikut ngomong pada pertunjukan tersebut.
Memekik dan menyalak, Pertunjukan selama 1-5 jam disampaikan dengan penuh teriakan. Lalu saya menyimpan tanya, ”apakah teater harus selalu berteriak?”. Pertanyaan ini muncul bukan hanya karena satu pertunjukan, namun juga dari beberapa teater yang saya saksikan di Solo dan tempat lain. Sepanjang pertunjukan, sudut pikiran saya terus mencari alasan dibalik teriakan-teriakan itu. Apakah karena kebiasaan di tempat tinggalnya selalu berteriak? Atau pantulan dari lingkungan hidup yang tidak leluasa bicara? Karena faktor geografis, seperti tinggal di hutan, atau gunung? Atau agar terkesan dramatis?

Foto pertunjukan “Waringan Oncek-Oncek” (3). (Sumber: Penulis)
Saya merenungkan ini untuk melihat kembali kegandrungan tari dengan gerak. Kebisingan tersebut juga muncul ke=ka saya menyaksikan pertunjukan tari, melalui gerak yang terus dilebih-gelegarkan (overexanggerate). Gerak harus lebih besar, lebih keras, lebih cepat. Gerak harus “berteriak”, kalau perlu sekencang-kencangnya, antisipasi jika kurang terdengar. Pertunjukan menjadi pengulangan situasi jalan yang penuh klakson, geberan motor, dan teriakan pengendara. Semua ingin didengar tapi tidak ada yang jelas terdengar, ada yang bisa mendengar. Akhirnya lebih baik tidak mendengar. Bisa jadi ini menjadi salah satu gejala masyarakat budeg dan ndableg? Sensibilitas mencerap turun, sulit untuk tergerak dengan pendekatan-pendekatan halus. Menyaksikan “Waringan Oncek-Oncek” membuat saya melihat permasalahan ini dengan kuping. Buat saya, sejatinya tidak hanya masalah bunyi dan suara.
Elemen meniru hadir dengan kuat, mereka memanggungkan ucapan dan gelagat para politikus di media sosial dan berita. Lalu, diolah kembali menjadi laku slaps1ck yang lucu, bodoh, ironis, memancing tawa-tawa penonton. Namun hal itu sebetulnya sudah dugal sejak dilakukan oleh politikus itu sendiri. Menuju akhir pertunjukan, perlahan saya merasa lelah. Tidak terasa berbeda jika saya sandingkan dengan kampanye (beserta segala tangkalannya) melalui reels Instagram, X (dulu Twitter), dan Facebook. Manakala pertunjukan ini mengoncek (mengupas), yang sedang saya tonton adalah kulit kupasannya. Sesuatu di dalamnya belum tampak. Bagaimanapun, kulit tersebut cukup untuk menebalkan asumsi bahwa apa yang saya lihat di televisi, di sosial media, di berita adalah teater. Saya lihat jelas aktornya, adegannya, naskahnya, kadang ak1ng dan agedannya jelek, saya juga sampai tahu endingnya. Yang sekarang saya masih cari-cari, di mana sutradaranya?
----------