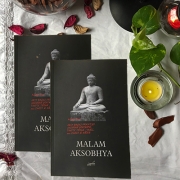Iklan Rongsok dalam koreografi “Harmoni Ruang Sosial”
Oleh Razan Wirjosandjojo (Studio Plesungan, Karanganyar)
Saya berseberangan dengan mbak yang sedang menggoreng sepasang paha ayam. Di papan menu, jari saya menunjuk gambar beserta tulisannya, tapi agak malu mendekati harganya . “Es teh kampul setunggal, mbak”. Mbak itu tidak dengar, sekali lagi saya bilang. Tangannya berpaling dari wajan ke pulpen untuk mencatat “s teh kpl” di bukunya. Seratus ribu saya sodorkan, ia bilang nanti saja. Saya kantongi kembali. Malam itu tidak hujan namun kursi dan meja di Rumah Banjarsari tetap basah. Saya usap kursi, lalu duduk dengan Agus Margiyanto yang juga hadir untuk menyaksikan pertunjukan “Harmoni Ruang Sosial” koreografi Danang Pamungkas.

Poster pertunjukan Harmoni Ruang Sosial” koreografi Danang Pamungkas.
Minuman saya putar searah jarum jam, siapa tahu bisa membuat waktu tidak melambat. Betul saja, pertunjukan sudah di depan es teh kampul saya pukul 20:00 tepat. Saya juga tidak perlu pindah tempat, arah kursi saya pun tidak berpaling. Persis di depan mata, Danang berdiri dengan pengeras suara. Merahnya diletakkan di abu-abu permukaan batu, di mana kakinya berpijak. Ia pemanasan dengan ponsel di tangannya. Bajunya biru ngejreng, pola nyentrik atasan dan bawahannya serasi. Namun mata saya terpaku pada sepatunya yang jreng, warnanya perak.
Pertunjukan terasa sah dimulai ketika Danang memutar musik dangdut. Ia bernyanyi, berdendang, bergoyang, terlihat sedang menikmati lagu dan menenggelamkan diri ke dalam liriknya. Sepertinya musik dangdut agak lawas, saya tidak tahu judul dan lagunya. Sama tidak tahunya, apakah musik itu betul-betul nikmat seperti yang ditunjukkan oleh Danang. Danang mencoba menebar kenikmatan tersebut, ia hinggap ke kiri, ke kanan. Glissade, jete, fan kick, oleh-oleh yang ia bawa sejak kembali dari Cloud Gate Dance Theatre tampil dengan putaran pinggul dangdutnya, Saya pikir sepatu peraknya itu memang sepatu menari, solnya enak sekali untuk pointe. Danang melompat ke kursi, menari di atas meja makan, mencolek penonton, geliatnya bak menonton La La Land (atau Bollywood?). Agus Mbendol dan Retno Sulistyorini, yang duduk di meja yang sama dengan saya, sangat menikmati laku jenaka yang dibawakan oleh Danang. Saya masih menikmati sepatu perak yang semakin saya lihat, tampak semakin mahal.

Foto pertunjukan Danang Pamungkas (1). (Foto: Halim HD)
Lagu dangdut itu hampir usai, Danang menyambar pengeras suaranya. Ia duduk bersama penonton di meja lain, memilih-milih musik di ponselnya. Musik kedua diputar, tapi kepencet balik ke musik pertama. “Kepencet kui!,Danang pegang ponsel kembali membetulkan. Bukannya semakin betul, justru yang terdengar adalah iklan Spotify untuk berlangganan. Seluruh penonton di ruang makan depan harus ikut mendengarkan 30-detik iklan tersebut. Sepertinya saya yang kurang banyak menyaksikan pertunjukan, tapi ini kali pertama saya mendapati iklan berhasil “menyerobot” kekhusyukan pertunjukan. Hebat juga, ia dapat celah untuk mengambil perhatian penonton dan penampil, tanpa izin. Saya tidak pusing, hati saya masih tercantol di tali-tali sepatu perak itu.

Foto pertunjukan Danang Pamungkas (2). (Foto: Halim HD)
Danang karaoke lagi, goyang lagi. Penonton cekikikan dan sesekali memberi senggakan. Entahlah, mungkin Danang menjelma kidang yang menarik hati para Sinta dan Rahwana. Mata saya menatap kilau kidang itu, yang memancar dari si sepatu perak. Musik usai ketika Danang sedang asyik di atas meja. Cengir-nya luntur, walaupun tidak sampai mengotori sepatu perak itu. Ia tiba-tiba menghunus serius ke penonton. Ke mana semua senyum Pepsodent yang ia obral sebelumnya?
Danang melangkah turun dan berjalan ke arah studio, di dalam. Penonton diam saja. Seperti baru saja dimarahi, bingung harus bagaimana. Sekejap Danang tegas “Melu ra??” Penonton tertawa, ternyata Danang masih lucu. Penonton diboyong memasuki ruang tengah.
Pertunjukan berlanjut pada ruang tengah, di antara dua studio. Danang berhenti seperti memagari batas langkah penonton. Saya menyelinap ke pojok selatan ruangan. Lima penari bergerak lamban di pojok-pojok ruangan, hampir tidak terdengar. Mbak Nur Suara Sinden berdiri di tengah. Sang vokalis, menggumam. Saya tidak paham apa yang digumamkan, seperti kalimat yang hurufnya diberantakin. Begitu pun, senyap-senyap saya mendengar kata. ‘Tradisi’, ‘pasar’, beberapa kata lainnya hanya kuping saya yang yakin, bahwa ia menangkap kata.
Danang menari kembali. Kali ini tidak dengan senyum Pepsodent-nya, dangdutnya, namun masih dengan sepatu peraknya. Pada tiap-tiap tendangannya yang bulat, atau lunges yang ceper, sesekali saya menangkap Danang mencari keseimbangan. Ia melenting tidak stabil. Muncul tanya, “di mana kepenarian Jawa miliknya?”. Saya tidak menanti tangannya nyekiting, atau torsonya njegeg. Sebetulnya, sesekali Danang melakukan ngukel dan noleh a la tari-tarian di Jawa, tapi kepenarian Jawa-nya bagi saya belum tampak, laras-nya masih bersembunyi dibalik gesit cambre–nya. Apakah (disiplin) tari hidup di tubuh kita dalam bilik-bilik kosnya sendiri? Kavling-kavling perumahannya sendiri?

Foto pertunjukan Danang Pamungkas (3). (Foto: Halim HD)
Saya sedikit tahu Danang menyimpan kepenarian Tari Klasik Gaya Surakarta, begitupun Tari Klasik Gaya Prancis dalam tubuhnya. Saya sendiri senang (hampir obsesif) belajar macam-macam disiplin gerak, dari breakdance, hip-hop, jazz, ballet, klasik surakarta, kebyaran bali, kecil saya senang berenang, pernah ikut wushu walaupun berhenti setelah tangan saya patah karena main bola. Pertunjukan ini membuat saya mengingat semua pengalaman (gerak) tersebut, lalu bertanya, “apakah mereka bertemu, saling ngobrol di dalam tubuh saya?”
Danang bergerak indah, namun saya menangkap keindahan gerak itu dimurnikan. Keindahan itu tidak seperti air got yang buteknya cokelat kehijauan, atau seperti es teh kampul yang dinginnya cokelat kekuningan. Indahnya seperti air mineral. Bening, tapi tidak ada bau, atau rasa. Tendu-nya hambar air putih. Saya melihat gerak mewujud sebagai yang bersih, yang putih, yang kinclong, seperti sang sepatu perak. Saya pikir, habis pertunjukan ini saya akan coba cari sepatu perak itu di internet, mungkin ketemu.
Mbak Nur masih anteng di posisinya, suaranya semakin melengking berkeping-keping. Para penari mendekat ke arah di mana Danang berdiri. Jeblosan mereka menggantikan sepasang sepatu perak dengan dress hitam rampak. Semua penari saya kenali namanya di poster publikasi pertunjukan. Walaupun begitu, wajah mereka tidak tampak karena tertutup topeng kawat nyamuk. Jika dibandingkan dengan lincah gerak Danang, para penari bergerak perlahan. Melihat ke atas, melihat ke bawah, berpegangan, seperti mencari wajah mereka sendiri. Lama saya melihat, lama-lama saya kenal juga tubuh mana-yang-siapa. Penting-tidak penting memikirkan perjudian wajah tersebut, saya tertarik melihat peristiwa wajah yang tunggal sedang merambat ke sepasang bahu, sepasang sikut, sepasang lutut, sepasang kelingking. Kali ini topeng tidak digunakan untuk menutupi wajah, namun untuk memindahkannya. Ia memberikan kesempatan untuk menonjolkan bagian tubuh yang lain. Rampak itu tidak pernah bersama, mereka seperti spanduk sepasang calon presiden yang bersama, namun sendiri-sendiri. Sama-sama bertopeng, bedanya pertunjukan ini tidak menunjukkan wajah dan kelaki-lakian sebagai nilai jual.

Foto pertunjukan Danang Pamungkas (4). (Foto: Halim HD)
Tubuh perempuan rentan. Ia disepakati sebagai penggerak roda setan permodelan, juga tersemat pada istilah Sales Promotion Girl (SPG). Ia diwajibkan hadir pada awak kabin pesawat, tak jarang pada resepsionis hotel dan tempat hiburan. Tubuh mereka berada di garis depan dunia periklanan. Wajah mereka memanjang dari mata kepala sampai mata kaki. Perempuan lahir menghadapi gang kecantikan yang sempit. Selain gang-gang itu tidak banyak jalan ke luar menuju jalan raya, di mana semua toko dan pembeli berada. Perempuan langka di bengkel, di konstruksi bangunan, di tiang listrik, atau di pigura foto presiden. Lain sisi, perempuan berserakan di brosur, bungkusan, sampul majalah, poster, atau thumbnail video masak atau gosip di Youtube. Apakah ini koreografi laki-laki, saya pikir tidak juga. Toh, banyak yang bos-nya, atau pelanggannya yang perempuan juga. Bagaimana pun, banyaknya tubuh perempuan tak berwajah di pertunjukan malam itu adalah sabda koreografer Danang Pamungkas bersepatu perak. Sepatu perak yang berubah menjadi beberapa pasang kaki yang kelihatan berkuku rapi dan tidak berdaki, membuat pikiran saya berkelana ke mana-mana. Terlalu jauh atau tidak, saya nikmati saja jalannya pertunjukan.
Jalan itu ternyata membawa saya dan penonton memasuki studio semi terbuka di sisi Barat. Para penari jalannya lambat, kami berdempetan. Mungkin banyak juga yang tidak sabar untuk melihat sepatu perak itu kembali. Memasuki studio tersebut, membuat saya sadar bahwa selama pertunjukan ini, banyak orang sedang jualan. Bernama Pasar Kenangan, ruang itu diisi oleh pedagang yang menjual barang-barang lama. Kacamata, buku, gelang, cincin, hiasan meja, poster, semua terlihat lawas, tapi mata saya tetap melihatnya cling. Sesekali saya mendapati para penari duduk di samping dagangan. Mereka memegang dagangan, kadang mereka pakai. Saya lihat lagi, mereka tidak beli. Mereka taruh lagi, atau mereka bawa untuk dipadukan dengan aksesoris atau pernak-pernik lainnya. Saya tidak lihat banyak dari mereka mengutak-atik buku, mungkin tidak menarik.

Foto pertunjukan Danang Pamungkas (5). (Foto: Halim HD)
Danang memiliki dagangannya sendiri. Lain dengan pedagang yang lain, barang-barang miliknya beralas kulit. Rumit menempel dan melilit pada setiap jengkal tubuh Danang. Alas dagangnya paling lebar, paling luas, tapi sepertinya paling sepi. Gerontang cething nasi di tubuhnya dikalahkan kilau dagangan lain, yang lebih cepat lenyap dari pertunjukan malam itu.
Lengking suara mbak Nur menyeruak sampai ke sela-sela terpal alas dagang. Ia menyapa para pedagang seperti MC yang menyapa para penampil. Para dagangan itu memang telah unggul bersaing dengan pertunjukan Danang. Mbak Nur mengambil salah satu dagangan, kacamata yang besar dan mahal. Modelnya tidak cocok di wajah mbak Nur, tapi ketidakcocokkan itu memberi lampu sorot. Saya melihat kacamata itu adu kuat dengan gaung suara mbak Nur yang sedang menawar-nawarkan barang dagang.

Foto pertunjukan Danang Pamungkas (6). (Foto: Halim HD)
Arief Budiman, Budi Darma, Che Guevara, Soeharto, dan Ben Anderson ikut serta dalam pertunjukan, lewat buku-buku bekas yang saya bolak-balik lembarannya. Sejak dagangan-dagangan itu terbit di ufuk mata, pertunjukan Danang menjadi inklusif sekaligus lenyap. Danang menjelma band keroncong di kafe. Ia pemanis malam bagi para hadirin yang sedang menikmati pemadangan dompetnya, yang isinya perlahan habis dicubit para pedagang. Saya harap, teriakan Danang yang menawarkan rantang dan barbel di tubuhnya tidak menjelma pengamen di angkringan ISI Surakarta. Diharapkan segera pergi, diusir dengan lima ratus perak. Saya juga sampai lupa dengan sepatu perak itu. Sedang sibuk diwejangi Sapardi Djoko Damono.
—
Gerak tubuh sebagai produk, koreografi sebagai iklan gerak tubuh, dan gerak tubuh sebagai iklan. Pertunjukan Harmoni Ruang Publik menyusupkan hubungan kusut seni (dan) pertunjukan dengan iklan. Saya memahami pertunjukan ini sebagai riset lanjutan Danang di Pasar Klithikan, yang ia lakukan tahun lalu. Saya menyaksikan langsung walau hanya sekilas. Kemudian, malam itu saya menyaksikan “pasar rongsok” dibawa ke Rumah Banjarsari, segelintir menempel pada tubuh Danang. Pada pertunjukan ini, Danang memperkenankan dirinya menjadi billboard untuk para rongsok itu. Memberikan nilai yang baru untuk barang-barang yang sempat tak bernilai. Rongsok bisa jadi antik, sampah bisa jadi mewah. Iklan sebagai sebuah pertunjukan, iklan dalam pertunjukan, pertunjukan sebagai iklan, rasanya hadir lengkap dalam pertunjukan ini.
Sejak lama kesenian kawin mesra dengan iklan. Tidak sedikit seniman merasa bangga jika karyanya menjadi bahan iklan. Pengiklan juga kerap mengklaim ciptaannya sebagai karya seni. Baik seni maupun iklan, keduanya memiliki kecenderungan untuk memberikan pengalaman rasa. Rasa haru, atau rasa lapar, sama-sama bisa dirasakan di tubuh. Jika gacor, ia mampu menggerakkan tubuh untuk melakukan sesuatu. Bagi saya koreografi Harmoni Tubuh Sosial – sebagai iklan ataupun pertunjukan – menggugah penonton untuk menubuhkan rasa memiliki. Tidak hanya itu, mendorong tubuh lebih jauh – untuk membeli.
Membeli kacamata membaur dengan membeli tubuh perempuan, membeli sepatu perak membaur dengan membeli gerak tari. Koreografi hadir dengan kapasitasnya untuk menggunakan tubuh sebagai iklan sebuah dagangan, sekaligus mendagangkan tubuh itu sendiri. Beberapa teman-teman kuliah saya mendapatkan penghasilan dari bisnis yang menggunakan fitur Tiktok Live. Sebagai model iklannya, mereka menjual baju sambil pargoy. Pembeli dihujam habis-habisan, sudah tertimpa daster, di-geyol pula. Tidak hanya berhenti pada baju, pun dilakukan Prabowo melalui goyangan gemoy–nya. Masyarakat menjadi penonton yang dipaksa membeli kebohongan dari goyang gemoy Letnan Jenderal Orde Baru tersebut. Tentu saja menggelikan, tapi buat saya kegelian itu tidak menjadi tawa.
Panggung pertunjukan kontemporer dalam dunia serba wani-piro ini, semakin rawan menjadi papan iklan. Seniman sadar-tidak sadar mengiklankan berbagai hal, tidak terbatas pada barang atau jasa (seringkali dalam tari; celana 3 garis a la Adidas, koreografi cepat a la atlit olahraga). Pertunjukan sangat mampu mengiklankan pemikiran. Diam-diam merasuk pada tubuh penonton. Ia bersembunyi melalui langsat kulit yang dibasahi keringat, atau gemerlap pakaian yang diterangi cahaya yang megah. Seketika kita menjadi hamba atas hasrat yang tidak kita ketahui dari mana asalnya. Hidup menjadi pertunjukan jual-beli. Maka, orang berlomba menjadi kaya, agar dapat menonton segala macam pertunjukan.
—
Sepasang lima puluh ribu saya hilang dari kantong. Sepasang buku merangkak naik ke dalam tas saya. Sepasang sepatu perak itu tidak tampak menari lagi, sudah saya cek sampai di halaman Tokopedia. Saya ke luar ruangan merasa pertunjukan masih belum juga usai. Gelisah masih merogoh tubuh saya, tidak tahu mencari apa dan mengapa.
Malam itu, saya menjadi hamba kepada segala yang sepasang.
***