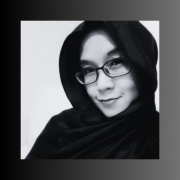Metamorfosis dari Puisi

Oleh Alexander Robert Nainggolan
Judul Buku : Sajak Ulat Bulu (puisi)
Penulis : Suyadi San
Penerbit : Kosa Kata Kita, Jakarta
Tahun : Oktober 2020
Tebal : xx + 438 halaman
Barangkali menulis puisi adalah proses pengalihan bentuk. Sebuah metamorphosis. Ketika kata-kata membentuk susunan, gaya ucap, pondasi yang baru—meninggalkan aura dengung yang panjang. Puisi dengan kehematan katanya seperti ingin mendeskripsikan suatu kejadian/peristiwa, memaksa kita untuk turut lebur dan masuk menjelajahi kemungkinan lainnya. Setiap temali kata seakan menyuguhkan lapisan makna lain. Bahkan ketika bermaksud untuk menjelaskan setiap riwayat, justru meninggalkan pengertian-pengertian baru, yang lesap ke dalam tubir sunyi dari batin manusia itu sendiri.
Demikianlah, terkadang kita berhadapan dengan sejumlah puisi yang menyuguhkan keindahan sederhana, namun melecut untuk tetap terjaga. Semacam ingin membangunkan kesadaran diri dan menyerap makna yang baru—begitu jauh. Sebagaimana yang pernah diungkap Oktavio Paz, sebagai suara yang lain—yang asing, tak bisa terperi bahkan oleh panca indera sekalipun.
Buku ini memuat 428 puisi. Barangkali kumpulan ini merupakan cermin yang lengkap dari penyairnya sendiri. Bagaimana puisi-puisi yang ditulis Suyadi San, seorang penyair yang telah lama bergelut dan bertungkuslumus dalam dunia puisi Indonesia—menyadap tema-tema yang sederhana, keseharian yang mungkin pula dekat dengan dirinya. Suyadi, penyair yang tinggal di Medan seperti ingin menunjukkan seperti pengakuan yang ditulisnya bahwa menulis merupakan kebutuhan baginya.
Ada sebuah lingkup kesunyian yang secara perlahan dibangun. Menggugah sebuah kesadaran diri. Semacam partikel yang terus mengapung, perpaduan antara keputusasaan dan kegairahan seseorang dalam mewarnai sebuah kehidupan. Dunia yang hiruk-pikuk, memang selalu mendedahkan ruang tersendiri, menepikan kita, dan memaksa kita kerap terperosok ke dalamnya. Sebuah ruangan tertutup, yang dipenuhi dimensi-dimensi, memaksa untuk mengetuk—berharap ada tangan yang membukanya.
Pun, kita telah lama tahu, betapa setiap hari kita disuguhi berita-berita, dari yang penting ataupun tidak. Bahkan, ketika kali membuka mata, andaikata kita tak membaca koran, mendengarkan berita di radio, atau menonton televisi. Sebuah berita bisa saja melayang dengan tiba-tiba. Bagai sebuah daun yang luruh tiba-tiba, jatuh ke tanah. Bahkan, sebuah berita dapat dengan segera menyeret kita, dari hal yang remeh-temeh, semacam bisik-bisik orang di sekitar. Maka hal-hal semacam itu terasa hadir, semacam juga dampak pandemi yang telah berjalan belakangan ini. Ihwal virus koronapun tak luput dari sejumlah puisinya.
Puisi yang bagus, memang bersifat multi tafsir. Ia meneguk seluruh ruang yang bisa disentuh pembaca. Ia membentuk sebuah medan kata-kata yang maksimal dieksplorasi. Tapi apakah perkembangan puisi kita sudah mencapai tahap ini? Berbagai eksplorasi memang telah dilakukan, bahkan tak jarang hadir ungkapan, bila sesudah Chairil Anwar, tak ada lagi sebuah puisi yang ditulis. Pendeknya, seorang penyair menulis puisi bukan semata-mata menulis secara utuh realitas yang ditangkapnya. Dengan melakukan pengosongan, sehingga yang nampak hanyalah realitas yang murni tanpa bayang-bayang. Penyair, bagaimanapun, harus membuka sekat-sekat yang menghalanginya—dengan tidak serta merta menuliskan sebuah kejadian secara mutlak. Penyair menulis puisi, karena ingin bicara sebuah hal yang berbeda. Suatu hal yang mungkin menggugah kesadaran dalam dirinya, entah itu cinta, ketimpangan, maut, atau kehidupan yang sederhana ini.
Puisi-puisi di buku ini ditulis dalam rentang waktu yang panjang. Suyadi seperti ingin menegaskan jika ia berbahagia dan terus konsisten dalam menulis puisi. Penyair yang bekerja sebagai wartawan dan staf peneliti di Balai Bahasa Sumatera Utara ini, banyak menyuduhkan dimensi keseharian dalam puisi-puisinya. Ia telaten dalam mendeskripsikan fragmen-fragmen kehidupannya. Semacam yang ditulisnya dalam “Sajak Selamat Pagi”: ini sudah pagi/sudahkah menggosok gigi/ supaya indah bak Pelangi// ingat, kita masih pandemic/ maka, kurangilah berperang pada matahari/ sebab, hidup cuma sekali// ini sudah pagi/ anak-anak riang bernyanyi/ ayah dan meka tahulah diri// ingat, musim terus berganti/ maka, sayangilah batang usia makin meninggi/ sebab, hidup cuma sekali// ini sudah pagi/ sudahkah kita mengaji/ daripada cuma berbangga pada diri sendiri// — ayo, carilah air/ segera basuh-basuh/ Tuhan begitu dekat (hal. 18)
Puisi Pendek
Sebagian besar puisi Suyadi ditulis dengan singkat, namun bermakna sangat luas. Ia seperti menelusup ke ruang-ruang lain, membuka aura tafsir yang berbalut dengan imajinasi tanpa batas. Puisi pendek terkadang memang menyuguhkan sejumlah lanskap yang jauh. Ia membenatangkan semacam enigma, multitafsir dan membuka rekam jejak baru. Sebuah wilayah baru—sebagaimana yang pernah ditulis Sitor situmorang dalam “Malam Lebaran”.
Dengan jumlah kata yang singkat, ia seperti menempuh dan bergelayut di jalan pikiran para pembacanya. Menghidupkan sejumlah pengalaman yang barangkali lebih unik dan berkelebat yang bisa jadi berbeda dengan apa yang dimaksud oleh si penyair sendiri. Maka puisinyapun turut mengebara sejauh imajinasi penyair. Dalam “Sajak Mati Lampu” Suyadi berucap: jelang berbuka, listrik padam (hal. 27). Peristiwa yang ganjil dan gigil seperti memanggil, sebuah usaha untuk menyentak ruang kesadaran kita. Saat-saat berbuka puasa, yang seharusnya dipenuhi dengan keriangan, mendadak suram. Meskipun Suyadi tak berpretensi untuk melakukan gugatan apapun. Ia mungkin hanya mengeluh, Ketika dua peristiwa hadir namun saling bertolak belakang: berbuka puasa dan listik yang padam.
Atau dalam puisi pendek lainnya “Sajak Tak Pulang Kampung”: Orang-orang sibuk menuai kampung/ Sedang kampungku ada di dalam hati// (hal. 106) dan dalam puisi “Terdampar” ia menulis dengan kecewa yang terlanjur luruh: kemarin aku terdampar di kotamu,/ kau malah pergi ke kota lain. ah…(hal. 115). Begitu terasa jika memang puisi pendek kerapkali meninggalkan gaung, getar dan iktibar. Dan tidak mengherankan jika puluhan tahun yang lalu seorang Chairil Anwar menuliskan surat kepada H.B. Jassin ihwal puisi-puisinya—yang baginya akan digali, dikorek hingga jauh ke akar kata.
Akhirnya, Suyadi memang telah menghadirkan banyak nuansa maupun kisah dalam buku ini. Ia sebagaimana puisi seperti terus gelisah dan mencari. Hingga melahirkan gaya ungkap yang baru namun utuh, sebagaimana dalam puisinya yang lain “Aku Datang”: aku datang menghela puisi/ sementara kau terus meradang/ aku tiriskan mimpi demi mimpi/ lembaran demi lembaran diagonal belantaramu/ sementara kau masih saja bersiteru dengan angin/ dunia apa yang kauinginkan/ sementara pernak-pernik peradaban berlintang-pukang/ memaksai renjana matahari/ telah akutiriskan sesobek angkuhmu dalam keabadian/ telah akutiriskan/ sudahlah usah lagi memesrai daun demi daun/ apalagi jagat ini sudah sampai ujung lautnya/ mari, kita bersidekap rindu (hal. 46)
* Penulis adalah penyair