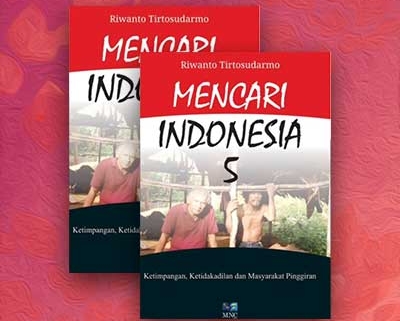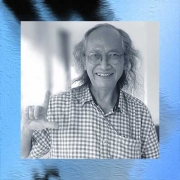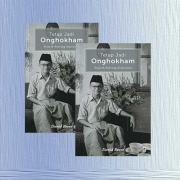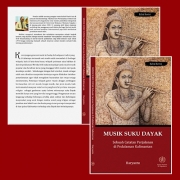Mencari Indonesia 5: Ketimpangan, Ketidakadilan dan Masyarakat Pinggiran

Oleh Maxensius Tri Sambodo*
Buku yang berjudul ‘Mencari Indonesia 5: Ketimpangan, Ketidakadilan dan Masyarakat Pinggiran’, karya Riwanto Tirtosudarmo, menjadi hadiah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Buku ini berjumlah 390 halaman (plus i – xxiv) dan diterbitkan oleh MNC Publishing. Sebelum masuk pada fase pentalogi bukunya, penulis berpandangan demikian ‘…sudah terbayang oleh saya bahwa Indonesia yang akan saya temukan adalah Indonesia yang jauh menyimpang dari Indonesia yang dicita-citakan ketika Proklamasi Kemerdekaan diucapkan oleh Sukarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945” (2025: x). Penulis (2025: 342) juga mengatakan “Dalam buku Mencari Indonesia 5 ini saya menunjukkan bahwa Indonesia masih belum menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi warganya”. Pandangan penulis tersebut, ada benarnya dengan melihat maraknya demonstrasi dan amuk masa yang terjadi akhir-akhir ini dibanyak wilayah.
Ketika mempelajari buku ini, saya menilai kemampuan penulis untuk meracik beragam hasil risetnya dalam rancangan yang kritis, reflektif, analitis, demografis, politis, historis, dan well referenced. Hal ini salah satu menjadi keunikan dan kekuatan dari buku ini. Berikut adalah catatan singkat atas 12 bab dalam buku ini. Bab 1: Pembangunan dan Perubahan Sosial di Minahasa, memperlihatkan kekaguman penulis melihat Minahasa sebagai kelompok masyarakat yang dinamis (demokratik dan egaliter). Potensi modal sosial, mapalus yang kaya akan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, kepercayaan, dan saling menghargai. Menjadi nilai moral yang penting untuk dilembagakan. Bab 2: Sentralisasi, Pembangunan Daerah dan Sikap Masyarakat di Lombok Barat dan Minahasa, memperlihatkan karakteristik sosial dan kultural yang berbeda antara kedua daerah tersebut akan berpotensi meningkatkan risiko kegagalan pendekatan one fit for all policy.
Bab 3: Banten dan Cirebon: Politik Identitas, Perubahan Infrastruktur dan Pembentukan Provinsi, penulis melakukan eksplorasi atas racikan politik identitas, perubahan konteks sosial dan perubahan infrastruktur penting untuk mencapai tujuan politik. Bab 4: KEDUNGSEPUR (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi) dan Aglomerasi Kota Semarang, memperlihatkan bagaimana dinamika peri- urban berkontribusi atas problem eksternalitas khususnya ketimpangan ekonomi dan ketegangan sosial. Bab 5: Trisobo: Perluasan Kota dan Konflik Agraria di Pinggiran Semarang, warna analisis historis yang kuat, penulis banyak mendiskusikan penguasaan lahan oleh perusahaan dan perebutan hak tanah warga. Bab 6: Pengusaha dan Buruh Jawa-Muslim dan Industri Kreatif di Pekalongan dan Jepara, menjelaskan atas kontestasi-kolaborasi lokal dan global, serta kehadiran negara dalam mempengaruhi konstruksi keadilan.
Bab 7 Persoalan Inklusivitas dan Ketidaksetaraan Masyarakat Adat: Relasi Kuasa dan Pengetahuan, memberikan perspektif historis dalam mendiskusikan transmigrasi dan kolonisasi Jawa ke wilayah luar Jawa seperti Lampung dan Papua Barat. Bab 8 Menempatkan Orang Baduy dan Orang Samin Dalam Konteks Masyarakat Adat, mendiskusikan perbedaan politik perjuangan, pergerakan, dan kekuatan sosial kedua kelompok masyarakat tersebut. Bab 9 Identitas dan Marginalisasi: Orang Kubu, Orang Rimba, Suku Anak Dalam, yang memberikan analisis terkait dengan identitas yang tidak pernah bermakna tunggal, tetapi jamak. Bab 10 Insurjensi Adat: Hambatan bagi Indonesia sebagai Proyek Bersama, memberikan beberapa catatan kritis untuk kembali menjelaskan bahwa masyarakat yang tertutup dan terisolir adalah fiksi bagi Indonesia saat ini dan masa depan. Lalu, disampaikan juga akan politik identitas yang kerap kali disalahgunakan untuk kepentingan politik. Selanjutkan disebutkan istilah adattrechpolitiek yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan otoritas kolonial dalam meredam peningkatan ancaman politik Islam. Pada bab ini penulis juga ingin menekankan bahwa kewargaan inklusif sebagai proyek bersama.
Di Bab 11 Migrasi di Papua: Sejarah dan Konteks Politik, penulis menjelaskan konteks historis yang menarik untuk dipahami atas Papua. Sisi peristiwa migrasi di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dijelaskan dengan sangat baik. Akhirnya, bab 12 Mungkinkah Indonesia Pecah Jika Otonomi Diberikan ke Provinsi?, memberikan pandangan bahwa tidak ada bukti empiris pemberian otonomi di tingkat provinsi akan menimbulkan diintegrasi.
Merujuk pada beragam gagasan dalam buku ini, setidaknya terdapat empat hal yang dapat diramu bersama dalam diskursus buku ini. Pertama, hingga saat ini, Indonesia masih terjebak dalam problematika limit tradisional sebagaimana disampaikan oleh Daoed Joesoef (2014: 128), yaitu: kemiskinan, kebodohan, penyakit, ketidaktahuan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, diskriminasi, intoleransi, pengekangan, kekacauan, dan penindasan berdarah. Hal ini sekaligus memperkuat argumen Boediono (2019) yang mengatakan, hal yang ‘hilang’ dalam bangun kebijakan di Indonesia yaitu: keteraturan, fokus, koherensi, rasionalitas, dan keterlanjutan. Di samping, hal-hal tersebut, buku ini menambahkan sikap abai terhadap kearifan lokal masih kerap terjadi dalam proses pengambilan kebijakan.
Kedua, dalam Orasi Guru Besarnya, yang bertema Keadilan untuk Pertumbuhan di tahun 2018, Arief Anshory Yusuf, menggambarkan posisi negara yang harus hadir untuk menciptakan pemerataan kesempatan, keadilan, dan menjaga/merawat lingkungan pendukung. Hal ini penting agar tercipta modal manusia yang semakin unggul (melaui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan nutrisi), serta kuatnya dinamikan inovasi.
Ketiga, Rodrik (2001), mengatakan institusi menjadi kunci penting bagi peningkatkan produktivitas. Hayami dan Godo (2005), juga melihat sub sistem budaya dan institusi, serta subsistem ekonomi menjadi dua komponen yang saling berinteraksi. Atas dasar ini, saya berpendapat pembangunan tidak hanya diukur dalam ruang ekspansi ekonomi semata, namun juga perlu penguatan di ruang sosial. Sisi terakhir ini yang mendapat perhatian besar penulis. Selama ini, ekspansi ruang sosial yang tercermin dari terbangunnya rasa saling percaya, empati, gotong royong, kekuatan jejaring sosial, dan solidaritas cenderung terpinggirkan. Padahal ruang sosial adalah modal sosial yang menjadi faktor penting untuk pembangunan yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, pembangunan adalah proses yang ‘mengembangbiakan’ kekuatan ruang sosial dan ekonomi secara simetris, dan berkelanjutan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa development is not just about to have more, but also to be more.
Akhirnya, dengan merefleksikan hasil-hasil riset yang telah saya lakukan, masih ada harapan untuk menarik kembali (take back) Indonesia on track. Paling tidak ada empat strategi pembangunan yang akan memampukan Indonesia untuk terhindari dari masalah ketimpangan, ketidakadilan dan peminggiran masyarakat. Pertama, meningkatan nilai tambah yang lestari, dengan mempertemuan sisi keberlanjutan lingkungan, kreativitas, dan teknologi dalam proses produksi berbasis sumber daya alam. Kedua, memperkuat peranan organisasi yang berwatak sosial (misalkan koperasi) sebagai instrumen untuk tercapaianya kesejahteraan dan ketahanan sosial. Ketiga, menginternalisasikan kearifan lokal dalam bangun kelembagaan dan organisasi formal. Keempat, sikap militansi untuk mengutamakan pencapaian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, akan semakin kuat jika digerak oleh kekuatan spiritual.
Jakarta 2 September 2025
—-
*Peneliti Ahli Utama – Badan Riset dan Ekonomi Nasional (BRIN)