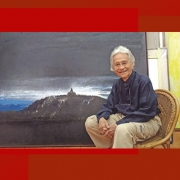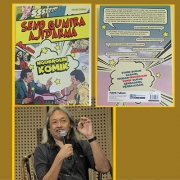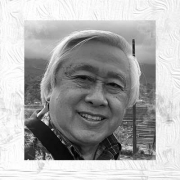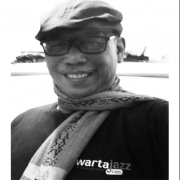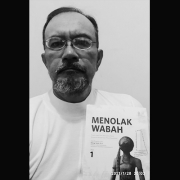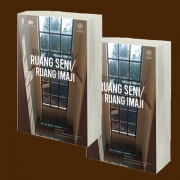Sounds Horeg sebagai Budaya Populer dan Akumulasi Modal
Oleh Pietra Widiadi*
Fenomena sounds horeg di Jawa Timur memperlihatkan pergeseran bentuk hiburan masyarakat tingkat desa menjadi praktik budaya populer dengan dimensi ekonomi, sosial, dan politik yang kompleks. Ini menunjukkan bahwa sounds horeg merupakan arena negosiasi antara tradisi dan modernitas, antara kebebasan berekspresi dan hegemoni kekuasaan. Regulasi berupa Surat Edaran Bupati (SEB) hanya berfungsi sebagai simbol ketertiban semu, tanpa daya paksa, sehingga mempertegas ambivalensi regulasi. Dengan demikian, sounds horeg mencerminkan bagaimana budaya populer bekerja menghidupi masyarakat sekaligus menyingkap relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik di ruang sosial pedesaan.
Awalan
Fenomena sounds horeg yang berkembang di ruang-ruang desa ini, merefleksikan dinamika sosial-budaya kontemporer. Apa yang sekilas tampak sebagai hiburan musik sederhana, sesungguhnya merupakan praktik budaya populer yang sarat kepentingan ekonomi, jejaring sosial, hingga legitimasi simbolik yang didasari dari Surat Edaran Bersama (SEB) Forkopimda Jawa Timur nomor 300.1/6902/209.5/2025, SE/1/VIII/2025, dan SE/10/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025.
SEB ini menjadi pedoman yang diterbitkan oleh Forkopimda Jawa Timur, yang mengatur penggunaan sound system, termasuk “sound horeg”. Pedoman juga dirujuk sebagai dasar untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Dan aturan ini dipakai untuk membatasi tingkat kebisingan, menetapkan batasan waktu dan tempat, serta mengharuskan uji kelayakan kendaraan, serta melarang aktivitas yang mengganggu ketertiban umum seperti merusak properti atau tindakan anarkis.
SEB ini dikeluarkan untuk mengendalikan potensi gangguan justru menghadirkan kegamangan sebagai aturan yang tidak mengikat. Hal ini melahirkan ambivalensi regulasi, di mana gangguan tetap berlangsung. Sementara masyarakat dipaksa mengelola dan melindungi dirinya sendiri ketiga gelaran karnaval dengan sungguhan utama sounds horeg.
Maka paparan ini, berupaya menyajikan analisis sounds horeg dengan menggunakan kerangka teori modal Pierre Bourdieu dan perspektif budaya populer Stuart Hall serta Raymond Williams. Dengan demikian, sounds horeg dapat dipahami tidak sekadar sebagai hiburan kelas desa, tetapi sebagai praktik budaya populer yang berkelindan dengan relasi kuasa dan ekonomi politik lokal.
Kajian budaya populer telah menjadi fokus bagi para peneliti sosial yang dilandasi dari Raymond Williams (1983) dengan menekankan budaya populer sebagai lived culture, yakni budaya sehari-hari yang dijalani masyarakat. Sementara Stuart Hall (1981) menyoroti budaya populer sebagai arena hegemoni, di mana kuasa dan resistensi saling berhadapan. Kedua kerangka ini membuka ruang untuk memahami sounds horeg bukan sekadar hiburan, tetapi juga arena pertarungan simbolik dan politik.
Dalam konteks musik dan hiburan di Indonesia, Weintraub (2010) dalam Dangdut Stories mengungkap bagaimana musik dangdut menjadi arena ekonomi-politik sekaligus ekspresi kelas sosial. Fenomena serupa tampak dalam studi Barendregt (2014) yang membahas budaya musik digital di Asia Tenggara sebagai praktik populer yang melampaui batas tradisi dan modernitas. Penelitian tentang electone di hajatan desa (Wallach, 2008) juga menegaskan pergeseran hiburan desa menjadi ruang komersialisasi dan arena identitas sosial.
Namun, kajian mengenai sounds horeg sebagai fenomena baru relatif terbatas. Fenomena ini menarik karena menunjukkan transformasi cepat, dari hiburan pinggiran menjadi pesta publik dengan perputaran ekonomi yang masif. Kekosongan kajian ini perlu diisi dengan analisis yang menempatkan sounds horeg dalam kerangka teori modal (Bourdieu) dan budaya populer (Hall & Williams), agar terlihat relasi kuasa, ekonomi, dan legitimasi simbolik yang menopangnya.
Kajian kecil ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif etnografi partisipatif. Data diperoleh melalui observasi di lapangan, khususnya dalam perhelatan sounds horeg pada momen peringatan kemerdekaan, bersih desa bulan Suro dan hajatan warga desa. Wawancara partisipatif dilakukan secara informal terstruktur dengan beberapa pemilik sound system, penyelenggara kegiatan, aparat desa, serta warga sebagai penonton.
Selain itu, kajian ini menerapkan analisis wacana kritis (Fairclough, 1995) untuk membaca teks regulasi, khususnya Surat Edaran Bersama (SEB) Forkopimda. Analisis dilakukan dengan menelaah bahasa, narasi, serta logika argumentasi yang digunakan dalam SEB dan pernyataan resmi pemerintah. Tujuannya adalah mengidentifikasi relasi kuasa, kepentingan ekonomi, dan simbolik yang beroperasi di balik teks regulasi tersebut.
Dengan kombinasi etnografi partisipatif dan analisis wacana kritis, pengkajian ini mencoba menyingkap sounds horeg bukan hanya sekedar hiburan kelas jalanan, tetapi juga sebagai praktik budaya populer yang berkelindan dengan modal ekonomi, politik dan regulasi simbolik.
Berpijak dari Pierre Bourdieu yang membagi modal menjadi empat, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Modal ekonomi berkaitan dengan akumulasi dana; modal sosial dengan jejaring relasi; modal budaya dengan praktik dan makna yang melekat; dan modal simbolik dengan legitimasi yang tampak “alami” atau “sah”. Keempat modal ini saling terkait dan menentukan posisi sebuah praktik sosial dalam struktur masyarakat.
Stuart Hall memandang budaya populer sebagai arena hegemoni, di mana kuasa berupaya menundukkan masyarakat melalui simbol dan praktik, namun selalu ada negosiasi. Sementara Raymond Williams menekankan bahwa budaya populer adalah lived culture, budaya sehari-hari yang benar-benar dijalani masyarakat. Perspektif ini membantu melihat sounds horeg sebagai hiburan yang sekaligus arena pertarungan kuasa, ekonomi, dan identitas.
Perspektif sosial budaya pop
Pertama, sounds horeg hidup dari akumulasi modal ekonomi. Penyewaan sound system, dukungan sponsor, hingga konsumsi masyarakat menjadikan praktik ini sebagai sirkuit ekonomi yang tidak kecil. Kedua, modal sosial bekerja melalui jejaring antara pemuda, aparat desa, dan komunitas lokal yang menopang keberlangsungan acara meski mendapat kritik sosial.
Ketiga, modal budaya terlihat dalam transformasi hiburan desa menjadi ekspresi budaya populer. Sounds horeg tidak lagi sekadar musik pesta, tetapi simbol gaya hidup, kebebasan berekspresi, dan modernitas pedesaan. Keempat, modal simbolik hadir melalui SEB dan sikap DPRD. Regulasi ini menciptakan ilusi kontrol, padahal justru mempertebal legitimasi simbolik bagi sounds horeg. Logika falasi terlihat di sini seolah ada pengendalian, padahal regulasi tidak memiliki daya paksa.
Dari perspektif budaya populer, sounds horeg menjadi arena negosiasi antara masyarakat dan kekuasaan. Ia lahir dari bawah, tetapi segera berkelindan dengan kepentingan ekonomi-politik. Hiburan desa ini bukan sekadar kegembiraan kolektif, melainkan ekspresi lived culture sekaligus bentuk hegemoni baru yang dikelola melalui regulasi simbolik.
Sounds horeg adalah praktik budaya populer yang lahir dari akumulasi berbagai modal yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Keberadaannya tidak bisa dipandang sekadar sebagai hiburan lokal, melainkan sebagai fenomena sosial yang menyingkap relasi kuasa dalam masyarakat. SEB yang tidak mengikat menunjukkan kegagalan regulasi dalam mengendalikan praktik ini, sekaligus mengukuhkan logika falasi dalam penanganannya.
Kekisruhan, perkelahian serta protes jalanan secara fisik mengikuti perspektif bergeraknya sounds horeg. Ini jelas bahwa SEB ataupun apapun namanya, menunjukkan impotensi kapasitas penyelenggara ketertiban. Ini adalah panggung, bukan panggung sounds horeg, tapi panggung ketidakberdayaan.
Dengan demikian membaca sounds horeg melalui kaca mata Bourdieu, Hall, dan Williams, tampak jelas bahwa fenomena sound horeg adalah representasi ambivalensi budaya populer antara kebebasan masyarakat untuk bergembira dan kekuatan ekonomi-politik yang menopang keberlangsungannya. Berkelidanya kekuatan modal dan pembiaran yang berselubung surat edaran bersama.
—-
*Pietra Widiadi, Petani kopi, tinggal di Desa Sumbersuko, lerang Timur Gunung Kawi, Kabupaten Malang; sosiolog kandidat PhD Ilmu Sosial di Unmer Malang.