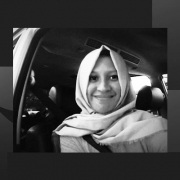Prahara Bandung Dan Trias Deventer

Oleh Doddi Ahmad Fauji
Patung itu kecil saja ukurannya, ditopang oleh tiang yang tingginya sekira 2,5 meter, yang terpancang di mulut jalan kecil. Tiang dan patungnya tampak kusam, seperti tak pernah mendapatkan perawatan, hingga kehilangan pesonanya sebagai ikon dan tetengger (penanda) sebuah kawasan. Sejujurnya, saya tak sengaja melihatnya, karena ukurannya yang kecil dan tidak mencolok mata, membuatnya tidak begitu mengundang perhatian. Tapi keberadaannya membuat saya penasaran. Kenapa patung di mulut jalan kecil?
Saya bertanya kepada penduduk yang kebetulan berpapasan. Ia menerangkan, “Itu patung Dewi Sartika, dan ini jalan Dewi Sartika.”
Pikiran saya langsung berputar, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Jadi, orang-orang sering menyebut jalan Destik, ternyata untuk akronim dari Dewi Sartika.
Kuamati patung itu lekat-lekat, memang tampak seperti potret Ibu Dewi Sartika yang banyak beredar di internet, dengan wajah murung seperti mengandung mendung. Ingatanku langsung berkelana pada kawih lawas, yang pernah diajarkan waktu SD, dan sering dinyanyikan bersama teman-teman.
Kantun jujuluk nu arum
Kari wawangi nu sengit
Nyebar mencar sa-Pasundan
Nyambuang sa-Nusantara
Sari puspa wangi arum
Sengit manis ngadalingding
Sari sekar nyurup nitis
Kana sukma istri Sunda
Tinggal jejuluk yang harum
tinggal aura yang membahana
Menyebar berpencar se-Pansuandan
berpendaran se-Nusantara
Sari bunga wangi harum
harum manis menggeliat
sari kembang merasuk menitis
pada sukma istri Sunda
(Saudaran dalam bahasa Indonesia).
Tembang itu terdengar begitu agung dan membahana, namun terasa kontras dengan wajah murung pada patung di mulut Jalan Destik itu, maupun pada foto Dewi Sartika yang beredar di internet. Kontradiksi tersebut membuat saya makin penasaran: Ada apa, dan kenapa pula patung Dewi Sartika mesti ada di Cicalengka.
Buru-buru saya pulang ke rumah, yang tak jauh dari belakang kantor Koramil Cicalengka. Kala itu, kuartal pertama tahun 2014, saya masih tinggal di Cicalengka, Kabupaten Bandung.
Di rumah, saya berseluncur dalam internet. Dari beberapa laman, didapat informasi, Dewi Sartika di Bandung, pada 4 Desember 1884, dan wafat di Cineam, Tasikmalaya, pada 11 September 1947. Ia diangkat menjadi pada Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno, melalui SK Nomor 252, pada 1 Desember 1966. Ia berjasa besar untuk bangsa kita, karena telah membangun institusi pendidikan untuk perempuan, dan mendirikan Sakola Istri pada 16 Januari 1904, yang tercatat sebagai sekolah formal pertama untuk kaum perempuan di Hindia Belanda. Sampai di sini, informasi yang didapat tentang Dewi Sartika, terasa wajar dan datar.
Kening saya mulai mengerut ketika sampai pada kata ‘Prahara Bandung’, yang saya dapatkan melalui bionarasi Dewi Sartika gubahan Yan Daryono (alm). Dewi Sartika ternyata dicap sebagai anak pemberontak, karena ayahnya, Raden Somanagara, divonis selaku aktor peledakan dinamit yang telah menghancurkan Jembatan Cikapundung pada 14 Juli 1893, bertepatan dengan pelantikan Bupati Bandung yang baru, Raden Adipati Aria Martanegara.
Raden Rangga Somanagara berserta istrinya, Raden Rajapermas, dihukum buang ke Ternate. Saat itu, Dewi Sartika menginjak usia 9 tahun. Ia tak pernah bersua kembali dengan ayahnya. Tapi ibunya dapat kembali berkumpul, setelah Rangga Somanagara wafat di pengasingan, dan raja Rajapermas kembali ke Bandung. Kala itu, usia Dewi Sartika memasuki 18 tahun. Artinya, hampir 8 tahun Dewi Sartika kecil, terpisah dari induk semangnya.
Selama orang tuannya menjalani pengasingan di Ternate, Dewi Sartika berpencar dengan kakak dan adik-adiknya karena mereka dititipkan pada kerabat yang berbeda-beda. Kakak Dewi Sartika (Raden Somamur), dan tiga adiknya (Raden Saripamerat, Raden Entis, Raden Yunus), dalam bionarasi gubahan Yan Daryono, tidak disebutkan ke siapa saja dititipkan. Namun Dewi Sartika diterangkan, dititipkan ke uwaknya (pak Dhe), Raden Demang Suriakarta Adiningrat (kakak kandung ibunya), yang menjadi Patih Afdeling Cicalengka.
Selama tinggal di Cicalengka, Dewi Sartika menerima perlakuan kurang baik. Kamar tidurnya ditempatkan di bagian belakang rumah, setara dengan kamar tidur para abdi dalem (pembantu). Dari situ dapat ditarik kesimpulan, Dewi Sartika disamakan dengan abdi dalem. Mungkin perlakuan Patih Cicalengka itu bukan atas kemauan hati nuraninya, melainkan karena status Dewi Sartika sebagai anak pemberontak, tentunya tidak lepas dari pengawasan pemerintah kolonialis Belanda. Siapapun yang merawat Dewi Sartika, akan mendapatkan pengawasan.

Wajah murung pada foto dan patung Dewi Sartika, bisa jadi merupakan refleksi dari kehidupan yang pahit di Cicalengka, yang berbanding terbalik dengan kehidupannya, saat menghuni rumah dinas besar nan asri di Kapatihan Bandung, ketika ayahnya menjabat Patih Bandung.
Raden Rangga Somanagara merupakan keturunan langsung menak Timbanganten, yang termasuk ke dalam wangsa pendiri Kabupaten Bandung. Kariernya cukup cemerlang sebagai ambtenar, dan digadang-gadang bakal menjadi Bupati Bandung, untuk menggantikan Raden Aria Adipati Sumadilaga yang didera rheumatic kronis.
Selama Sumadilaga sakit, tugas kebupatian diwakilkan kepada Somanagara, dan ia melaksanakannya dengan baik. Namun setelah Sumadilaga wafat pada Jum’at, 11 April 1893, ternyata yang dipilih dan dilantik menjadi Bupati adalah Raden Aria Adipati Martanegara, yang merupakan menak keturunan Sumedang. Somanagara dan para menak Bandung tidak setuju, bila Bandung dipimpin oleh menak Sumedang. Dari situ, Prahara Bandung meledak!
Akhir abad 19, pemerintah Kolonialis Belanda masih menerapkan politik devide et impera (politik adu domba). Residen Priangan JD Harders kala itu, menerapkan siasat licik untuk mengadu domba menak Bandung vis a vis menak Sumedang, supaya kekuasaan Pemerintah Kolonialis Belanda memiliki kedudukan yang tetap kuat. Percik-percik pemberontakan, akan dipadamkan sedini mungkin.
Bisa dikatakan, Dewi Sartika dan kakak-adiknya, menerima efek domino dari intrik politik yang tentunya belum bisa ia pahami karena usianya yang masih 9 tahun. Selanjutnya, ia harus menjalani kehidupan yang getir, karena menerima perlakuan tidak semestinya, karena dialamatkan kepada anak-anak yang tidak bersalah.

Selain kepahitan, Dewi Sartika juga menyaksikan kejanggalan dari kehidupan Patih Cicalengka yang memiliki empat istri. Kejanggalan ini, kelak melahirkan sikap seorang Dewi yang antipoligami.
Istri Patih Cicalengka yang terakhir, Gan Eni, tidak memiliki anak. Karena itu, ia lebih banyak mencurahkan waktunya dengan menjadi pengajar etika dan tradisi Sunda luhur, untuk para gadis yang mondok (belajar sambil menginap). Para gadis itu umumnya anak dari para Kuwu, Cutak, Carik, Mantri Ulu-ulu dan sebagainya, dan atau masih kerabat dekat Suriakarta. Mereka diajari adat, untuk menjadi perempuan yang trengginas dan pandai berbakti kepada suami.
Dewi Sartika ikut menerima pelajaran itu, dan memiliki talenta serta daya cerap yang cepat dalam menerima pelajaran, sehingga ia menjadi murid kesayangan Gan Eni. Tuhan menyelamatkan nasib anak malang itu, dengan menghadirkan Gan Eni sebagai pelipur lara.
Namun Dewi Sartika sering bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa pelajaran baca-tulis tak pernah diajarkan oleh Gan Eni. Apa karena Gan Eni sendiri tidak bisa membaca, atau memang ada larangan tidak tertulis, bahwa gadis pribumi dilarang diajari tulis baca?
Dewi Sartika sering membantu gadis-gadis yang nyantrik di rumah Patih Cicalengka, untuk membacakan surat yang diterima dari kekasihnya. Dewi Sartika sering terpaksa berbohong dalam membacakan isi surat. Dalam suatu kasus, seorang gadis menerima surat dari kekasihnya, yang menyatakan ingin putus darinya. Namun Dewi Sartika malah menerangkan, surat itu berisi pujian untuk sang gadis, dan kekasihnya ingin segera melamarnya. Dewi Sartika melakukan hal itu, semata-mata agar si gadis tidak bersedih hati.
Dewi Sartika menyaksikan dengan matanya sendiri, bila manusia tidak bisa tulis-baca, ia akan mudah dibodohi. Dari situ, terbersit naluri untuk mengajari baca-tulis anak-anak perempuan yang buta hurup. Di pekarangan rumah Patih Cicalengka, Dewi Sartika menggelar sekolah-sekolahan, latihan baca-tulis, dengan menggunakan arang dan bilik sebagai mediumnya. Kebanyakan pesertanya adalah anak-anak abdi dalem.
Keadaan perempuan kala itu, tampak kurang berdaya, atau sangat bergantung kepada lelaki. Bila menjadi perawan tua, atau menjadi janda karena ditinggal mati maupun cerai, kehidupan perempuan menjadi serbasusah, dan banyak yang kehilangan daya. Penyair WS Rendra menuturkannya seperti itu, dalam pengantar bionarasi Dewi Sartika karangan Yan Daryono. Hal itu terjadi, karena mereka tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk manjalani hidup. Oleh sebab itu, perempuan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa membuat mereka bisa mandiri.
Sangat mungkin Dewi Sartika juga becermin pada sikap Ibunya, yang rela meninggalkan anak-anaknya dan ikut suami menjalani pembuangan. Memang tidak disebutkan dalam buku Yan Daryono, apakah Rajapermas wajib menanggung hukuman buang padahal tak bersalah, atau Rajapermas ikut suami karena kewajiban berbakti kepada suami, atau karena takut kehilangan daya bila tidak bersama suami?
Kehidupan di Cicalengka telah membuka mata seorang Dewi yang beranjak remaja, bahwa perempuan seakan hanyalah mahluk yang berurusan dengan sumur, dapur, dan kasur. Bahkan dalam urusan kasur, perempuan seakan hanya objek yang pasrah menerima hasrat lelaki. Dewi menentang itu, juga menolak pologami seperti yang diperagakan oleh Patih Cicalengka. Kelak Dewi menolak pinangan sepupunya, Raden Kanjun, yang akan menjadikannya sebagai istri kedua.
Perjalanan hidup di Cicalengka, adalah perjalanan pahit-getir yang dialami Dewi Sartika. Namun kepahitan itu justru membentuk kepribadian Dewi Sartika menjadi gadis tangguh.
Yan Daryono menulis dalam bionarasi Dewi Sartika halaman 46.
Delapan tahun bermukim di rumah Patih Cicalengka merupakan masa yang penuh tekanan batin dan penuh duka. Bila sebelum peristiwa huru-hara di Bandung yang dipimpin ayahnya, Dewi Sartika mengenyam kehidupan yang harmonis dan berkecukupan bersama orangtua dan saudara-saudaranya. Tapi setelah ayah dan ibunya ditangkap lalu dibuang ke luar Pulau Jawa, kehidupannya berubah drastis. Sehingga selama delapan tahun menetap di rumah Patih Cicalengka, Dewi Sartika mengalami tempaan hidup yang membuat dirinya menjadi dewasa dan arif dalam mengarungi kehidupan.
Menurut sesepuh Sunda Popong Otje Djundjunan, yang senantiasa hadir bila diundang untuk memberikan ceramah telusur Jejak Dewi Sartika oleh Sanggar SituSeni, Dewi Sartika pernah meminta kepada murid-muridnya, bila kelak menuliskan kisah Dewi Sartika, agar tidak dikaitkan dengan kehidupannya semasa di Cicalengka.
“Jangan kaitkan saya dengan Cicalengka. Cicalengka adalah masa-masa pahit hidup saya,” tutur Otje Djundjunan, yang disampaikan dalam acara Dangiang Dewi, 19 Desember 2018, di SMAN 24 Bandung.
Namun seperti kata pepatah, tak ada hujan yang tak reda, penderitaan di Cicalengka itu diakhiri dengan cara minggat, ketika Dewi Sartika tahu, ibunya sudah kembali ke Bandung dari pembuangan pada 1902. Dewi Sartika pun bisa bersua kembali dengan ibu, kakak-adik, serta saudara-saudara yang lainnya.
Trias van Deventer
“Hutang yang demi kehormatan harus dibayar, walaupun tidak dapat dituntut di muka hakim!”
Pernyataan di atas, ditulis oleh Conrad Theodore van Deventer (1857-1915), yang dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis. Dari berbagai sumber disebutkan, ia bertolak ke Hindia Belanda pada usia muda, dan dalam 10 tahun, Deventer telah menjadi kaya, karena perkebunan swasta serta maskapai minyak yang bermunculan saat itu, membutuhkan jasa penasihat hukum.
Deventer rupanya senang berkelana, dan selama tinggal di Hindia Belanda, ia sering blusukan, dan menyaksikan sendiri kehidupan bangsa terjajah yang amat memprihatinkan. Pada 30 April 1886, ia menulis surat kepada orang tuanya, mengemukakan perlunya tindakan lebih manusiawi bagi pribumi, karena hawatir penderaitaan pribumi berdampak pada bangkrutnya Belanda, seperti dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan.
Pada 1899, Deventer menulis artikel dalam koran De Locomotief, berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan), yang digamblangkan menjadi “Hutang yang demi kehormatan harus dibayar, walaupun tidak dapat dituntut di muka hakim”.
Tulisan tersebut memuat data-data konkret yang menjelaskan kepada publik Belanda, betapa Belanda menjadi makmur dan aman (adanya kereta api, bendungan-bendungan, dst.) adalah hasil kolonialisasi atas Hindia Belanda, sementara penduduk Hindia Belanda amat miskin dan terbelakang. Sudah sepantasnya kekayaan orang Belanda dikembalikan.
Deventer menyerukan perlunya dilakukan politik etis, atau politik balas budi bagi warga pribumi. Selain Deventer, Pemimpin Redaksi De Locomotief, Pieter Brooshooft, juga sering menyuarakan tentang pentingnya dilaksanakan Ethische Politiek.
Politik Etik merupakan kritikan langsung dan gamblang terhadap cultuurstelsel (politik tanam paksa), yang dijalankan Kolonialis Belanda akibat bangkrutnya VOC setelah menjalani Perang Jawa (Perang dengan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan Cut Nyak Dhien). Pada masa Tanam Paksa itu, diberlakukan kerja rodi, yaitu kerja bakti yang amat berat, namun dengan upah rendah, bahkan terkadang tanpa upah.
Deventer dengan lantang menyuarakan kritiknya, yang membuka mata para anggota Parlemen Belanda, sehingga mereka meminta Pemerintah menjalankan politik Etik.
Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina naik tahta, dan dalam pidato pembukaan di depan Parlemen Belanda, menegaskan pemerintah Belanda punya panggilan moral serta hutang budi (een eerschuld) kepada bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Sang Ratu menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang merupakan pokok saran dari Deventer, sehingga pernyataan Ratu itu, dikenal dengan sebutan Trias Van deventer, yang meliputi:
- Irigasi, yakni membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan serta bendungan untuk keperluan pertanian.
- Migrasi, yakni mengajak penduduk pulau Jawa untuk bertransmigrasi ke pulau lain.
- Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
Politik Etis atau Trian Van Deventer tersebut, meskipun banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya, namun tampak seperti bola salju yang terus menggelinding dan makin besar, dan berdampak pada perubahan yang terjadi di Indonesia. Politik Etik juga menjadi semacam pijar yang menyulut sumbu revolusi.
Berkat Politik Etik, makin banyak anak-anak bumiputera yang tercerahkan, kemudian memimpin gerakan kebangkitan bangsa melalui pendidikan dan organisasi. Boedi Oetomo adalah salah satu orgnisasi yang lahir dari percik Politik Etik. Dalam organisasi tersebut, berkumpul para pemuda bumi putra yang memikirkan perlunya kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.
Sakola Istri
Ketika Dewi Sartika kembali ke Bandung, yaitu tahun 1902, adalah tahun-tahun awal Politik Etik dijalankan. Dalam pada itu, Dewi Sartika memiliki cita-cita ingin mendirikan sekolah khusus untuk kaum perempuan. Gayung pun kelak bersambut.

Sebelum mendirikan sekolah resmi, Dewi Sartika telah mengadakan kursus non-formal di rumahnya yang tidak begitu luas. Mulai berdatangan perempuan yang ikut untuk mendirikan Sekola Istri, perjuangannya tentu tidak mudah.
Pada tahun 1929 Dewi Sartika memperoleh Bintang Jasa Perak dari pemerintah Kolonialis Belanda, atas jasa-jasanya, dalam mengembangkan pendidikan, dan pada tahun 1939, memperoleh penghargaan Bintang Jasa Emas.
Dangiang Dewi
Prestasi Dewi Sartika itu, melahirkan rasa kagum, salut, sekaligus heran, kenapa tokoh yang telah berjasa besar bagi dunia pendidikan kaum perempuan, tak begitu dikenal di tingkat nasional bahkan di Jawa Barat sendiri. Kenapa masyarakat di Jawa Barat lebih mengenal pahlawan perempuan itu sebatas RA Kartini, Cut Nyak Dhien, dan Cut Meutia?
Saya melakukan riset kecil-kecilan mengenai peringatan Dewi Sartika, dan ternyata amat jarang yang menggelarnya. Saya menarik asumsi, Dewi Sartika tak begitu dikenal, karena kurang diperingati, kurang diperkenalkan oleh pemeritah dan masyarakat Jawa Barat. Maka sejak itu, terbersit niat untuk menggelar acara peringatan Dewi Sartika.
Upaya untuk menjalankan niat tersebut, saya wujudkan dengan menggelar latihan ngawih Dewi Sartika bersama bagi para remaja di Cicalengka, yang kebetulan saya bertemu dengan seorang pensiunan guru kesenian. Saya juga menemui salah satu tokoh budaya di Cicalengka, yaitu Abah Deden Agus Krisna.
Rencana menggelar peringatan Dewi Sartika itupun saya sampaikan kepada Ibu Ken Zuraida, sahabat dan guru saya dari Bengkel Teater Rendra. Ibu Ken antusias dengan rencana itu, dan datang ke Cicalengka untuk membantu mewujudkannya. Kami sempat menggelar beberapa kali pelatihan akting teater untuk para siswa. Namun keinginan tinggal keinginan, berbagai kendala, membuat rencana peringatan itu tak terwujud di Cicalengka.
Akhir tahun 2014, rencana itu dapat diwujudkan di kampus UPI Kota Bandung, dengan menggelar seminar Telusur Jejak 130 Tahun Ibu Dewi Sartika. Hadir sebagai pembicara, yaitu Ceu Popong Otje Djundjunan yang kala itu masih menjabat anggota DPR RI, Ibu Prof. Dr. Endang Caturwati yang menjabat Direktur Kesenian – Depdikbud, dan Ibu Dr. Chye Retty Isnendes, M.Pd. selaku dosen Pendidikan Bahasa Daerah UPI Bandung. Saya menggunakan Sanggar SituSeni sebagai penyelenggara acara.
Antusias warga kampus UPI untuk ikut memperingati Dewi Sartika ternyata tidak begitu besar. Di Jawa Barat memang tak begitu bergema peringatan terhadap tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa ini, seperti Ir. H. Djuanda, Pahlawan Toha, Hasan Mustapa, Inggit Garnasih, dan lain-lain. Bung Karno pernah berujar, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Mungkin warga Jawa Barat (dalam hal ini etnis Sunda), belum menjadi etnis yang besar.
Pada 2015 dan 2016, Sanggar SituSeni tidak dapat menggelar peringatan Dewi Sartika. Alasannya sungguh klasik, sulit mendapatkan pendonor dana, dan mencari relawan yang terlatih untuk menjadi panitia.
Pada Agustus 2016, Sanggar SituSeni membuka usaha di sektor penerbitan partikelir, supaya ada dana operasional untuk menjalankan visi dan misi sanggar, yaitu membangun kesadaran bagi peserta didik, sambil mengolah daya common sense (berpikir waras). Kegiatan peringatan Dewi Sartika, sekaligus menjadi sarana untuk menjalankan visi dan misi itu.
Ibu Dewi Sartika menjadi pahlawan, dengan alasan karena berjasa dalam membangun pendidikan modern untuk kamu perempuan. Namun di sekolah-sekolah, pahlawan yang diperingati itu adalah Ibu RA Kartini yang merupakan Pahlawan Emansipasi.
Ibu RA Kartini memang harus diperingati, terutama oleh Kementerian Pemberdayaan Peranan Perempuan, fungsionaris PKK, dan Dharma Wanita. Namun, instansi pendidikan mestinya memperingati Ibu Dewi Sartika sebagai pahlawan Pendidikan. Saya menilai, absennya sekolah memperingati Dewi Sartika, adalah kelalaian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengurusi pendidikan, bukanlah anak bangsa yang Besar, karena seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya.
Kesalahan kaprah (akal) tersebut, sangat mungkin menjadi ‘mamala’ bagi dunia pendidikan. Saya makin paham, jika dari waktu ke waktu, kualitas hasil pendidikan makin menurun, di mana makin banyak sarjana yang tidak memiliki keterampilan praktis, dan akhirnya menjadi pekerja yang tidak profesional.
Ciri pekerja profesional, menurut Mendikbud Muhajir Effendy, untuk di negara terbelakang seperti Indonesia, minimal harus memenuhi dua syarat: 1. Ahli di bidangnya, 2. Bertanggung jawab. Di negara modern, ditambah dengan dua syarat lagi, yaitu punya ijazah sesuai dengan bidangnya, dan bergabung dengan asosiasi profesi.
Muhajir menyatakan hal tersebut dalam Kongres ke-1 Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia (AGBSI) yang berlangsung di Jakarta pada 2018.
Adalah fakta, banyak sarjana pertanian yang bekerja di sektor perbankan atau jurnalistik, sarjana ekonomi jadi politikus, sarjana teknik mencoba jadi pengusaha, dan macam-macam lainnya. Dalam bahasa mantan Mendikbud Ing Wardiman Djojonegoro, antara pendidikan dan dunia kerja tidak ‘link and match’. Berjubal pekerja yang tidak nyambung dengan ijazahnya, menjadi sinyalemen banyaknya pekerja yang tidak memenuhi persyaratan profesional. Maka makin bisa dipahami, jika Badan Pusat Statistik mensinyalir 400-an BUMN di Indonesia terancam bangkrut, bukan karena kurang modal saja, namun karena SDM yang tidak sesuai.
Atas dasar fakta di atas itu, Sanggar SituSeni berusaha menggelar kembali peringatan Dewi Sartika pada 2017, dengan diawali oleh kegiatan sosialisasi Milangkala Dewi Sartika ke-133 pada 6 April 2017, yang diselenggarakan di Padepokan Seni Mayangsunda Bandung.
Acara sosialisasi itu dihadiri oleh tokoh Sunda Ceu Popong Otje Djundjunan, yang kala itu masih menjabat anggota DPR RI. Hadir pula Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil dalam kapasitasnya sebagai exoficio Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung. Muspika Kecamatan Bojongloa Kaler turut hadir, yaitu Camat (Eka Taofik Hidayat), Kapolsek (AKP Asep), Danramil (Kapten…), serta Lurah Sukaasih (Ade Rahayu) dan TP PKK Sukaasih Bergema sebagai pihak yang ikut menjadi tuan rumah bersama Sanggar SituSeni.
Setelah sosialisasi pada 6 Mei 2017, selanjutnya sosialisasi dilakukan di Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Cianjur, sambil malaksanakan pelatihan menulis untuk para guru dan siswa. Harapannya, tentu lebih banyak guru di Jawa Barat, yang tergugah untuk memperkenalkan ketokohan dan kepeloporan Ibu Dewi Sartika, dan tergerak untuk menyelenggarakan peringatan Ibu Dewi Sartika di tiap sekolah. Namun harapan itu, masih jauh panggang dari api, sebab hingga penyelenggaraan Dangiang Dewi 2019/2020, belum terdengar ada sekolah yang secara khusus memperingati Dewi Sartika, kecuali Sekolah Dewi Sartika yang memang merupakan warisan dari Sakola Istri.
Peringatan untuk Dewi Sartika kembali digelar pada tanggal 3 – 5 Desember di Padepokan Seni Mayangsunda, dan berlanjut pada 19 Desember di Sarana Olah Raga (SOR) Arcmanik. Saat dihelat di Padepokan seni, 3 – 5 Desember, SituSeni bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, serta beberapa organisasi/komunitas kesenian. Sedangkan pada saat digelar di SOR Arcamanik, SituSeni bekerja dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Nama acara pada 2017 adalah Milangkala Dewi Sartika ke-133. Materi acara yang disajikan pada Desember 2017 itu, adalah seminar Telusur Jejak Dewi Sartika, Lomba Baca Puisi, pameran karya kreativitas warga, dan pertunjukan seni.
Pada 2018, acara Milangkala Dewi Sartika diubah menjadi Dangiang Dewi atas usul sastrawan Sunda, Godi Suwarna. Dangiang Dewi dilaksanakan pada 19 Desember 2018, bertempat di SMAN 24 Bandung, dan seperti biasa, acara peringatan untuk Dewi Sartika, selalu menghadirkan Ceu Popong Otje Djundjunan selaku pinisepuh Sunda, yang mengalami jaman ketika Ibu Dewi Sartika masih hidup.
Dari penelusuran informasi terhadap entri Dewi Sartika, saya sampai pada laman yang menjajarkan nama-nama pahlawan nasional dari kalangan perempuan. Pada 2013, ada 12 tokoh perempuan yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, namun per-2019, telah bertambah menjadi 15 tokoh, yaitu:
- Cut Nyan Dhien, ditetapkan pada 2 Mei 1964.
- Cut Meutia, ditetapkan pada 2 Mei 1964.
- RA Kartini, ditetapkan pada 2 Mei 1964.
- R. Dewi Sartika, ditetapkan pada 1 Desember 1966.
- Martha Christina Tiahahu, ditetapkan pada 20 Mei 1969.
- Maria Walanda Maramis, ditetapkan pada 20 Mei 1969.
- Nyai Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan, ditetapkan pada tahun 1971.
- Nyai Ageng Serang, ditetapkan pada 13 Desember 1974.
- Hj. Rangkayo Rasuna Said, ditetapkan pada 13 Desember 1974.
- Hj. Fatimah Siti Hartinah Seoharto, ditetapkan pada 1996.
- Hj. Fatmawati Soekarno, ditetapkan pada 4 Nopember 2000.
- Opu Daeng Risaju, ditetapkan pada 2006.
- Laksamanawati Malahayati, ditetapkan pada 2017.
- Andi Depu, ditetapkan pada 2018.
- Ruhana Kuddus, ditetapkan pada 2019.
Pada lajur keterangan para tokoh itu, Dewi Sartika diangkat menjadi pahlawan nasional karena telah berjasa dalam membangun institusi pendidikan modern untuk kaum perempuan. Ia mendirikan ‘Sakola Istri’ pada 16 Januari 1904, atau ketika berusia 20 tahun, dan menjadi sekolah pertama untuk kaum perempuan di Hindia belanda. Nama sekolah ini kelak berganti nama menjadi Sakola Kautamaan Istri. Pada tahun ke-25, Sakola Istri telah memiliki cabang hingga berdiri di 15 Kadipaten di seluruh Keresidenan Priangan.
*Penulis adalah Guru Sanggar SituSeni Mediatif