Potret Perempuan-Perempuan Malang
Oleh Sarah Monica*
Membaca novel “The Women Destroyed” (1967), karya Simone de Beauvoir (1908-1986), barangkali akan membuat banyak pembaca perempuan jengah dan tidak nyaman. Apalagi jika dibaca dalam kondisi psikologis perempuan yang sedang tertekan. Novel tersebut jelas bukan pilihan yang tepat untuk sebuah penghiburan sesaat atau pengalihan kemelut suasana hati.
Kegusaran, kecamuk pikiran, dan pertarungan batin adalah apa yang de Beauvoir hadirkan melalui tokoh-tokoh utama perempuan dalam novelnya. Masing-masing dari mereka digambarkan sebagai perempuan yang tengah mengalami kecemasan, keputusasaan, bahkan nyaris di ambang kegilaan. Saat mulai menelusuri jalinan cerita, para pembaca akan tiba-tiba menemukan dirinya terseret dalam gelombang pergulatan psikologis yang begitu intens, kompleks, terkadang terlalu bertele-tele, bahkan bisa melelahkan.
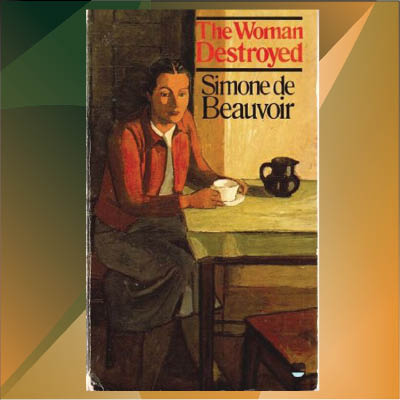
Sampul novel “The Women Destroyed” (Sumber Foto: https://www.abebooks.com)
Karya ”The Women Destroyed” yang diterjemahkan ke dalam versi berbahasa Indonesia menjadi “Perempuan yang Dihancurkan” terdiri dari tiga (3) novela. Pada cerita pertama dengan judul “Masa Penuh Pilihan”, seorang perempuan berusia senja telah mengabdikan sepanjang hidupnya untuk dunia pemikiran dan kepenulisan. Sang suami pun bekerja di ranah ilmu pengetahuan dan penelitian. Pilihan ideologi dan prinsip hidup yang mereka jalani merupakan konsekuensi dari kecintaan mereka pada semesta ilmu.
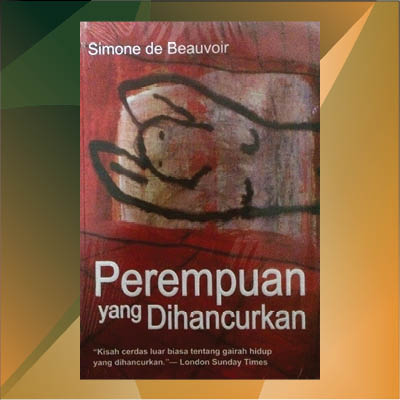
Sampul novel “Perempuan yang Dihancurkan” (Sumber Foto: https://mizanstore.com)
Percik konflik mulai terpantik ketika Philippe, anak laki-laki semata wayang mereka menikah, lalu memasuki fase kehidupan baru. Meleburnya sang anak ke dalam lingkungan keluarga yang berbeda, serta perjumpaannya dengan lingkaran sosial yang lebih beragam membuat mama sebagai tokoh utama, menyadari bahwa dirinya tak lagi memiliki kontrol atas pilihan dan keputusan hidup Philippe.
Selama ini sang mama tidak menyadari bahwa optimisme naif yang menjadi karakternya menyelubungi kekerasan ego dan kebutuhan akan dihormati-dituruti oleh anak satu-satunya. Perempuan tersebut memaksakan idealisme dirinya menjadi cara pandang dunia bagi Phillipe. Sehingga ketika Phillipe menikah dan secara tidak langsung membuat jarak dengan orangtuanya, hingga berkonfrontasi dengan mereka, dia dapat menilai diri dan keinginan-keinginannya secara lebih jujur. Meskipun keliru, menurut mama.
Pertengkaran dengan Philippe merembet ke hubungan pernikahannya dengan Andre. Pembelaan suaminya itu terhadap Philippe menjerumuskan mama ke lembah kesendirian. Dia jatuh dengan perasaan kalut sekaligus sakit hati atas pengkhianatan dari orang-orang yang selama ini ia percayai dan perjuangkan. Terlebih di saat yang sama buku terakhirnya, “Rousseau dan Montesquieu”, tidak memperoleh apresiasi publik sebagaimana yang ia harapkan. Kekecewaan, harga diri yang terluka, ditambah rasa minder karena usia tua bercampur aduk dalam gejolak batin sang mama.
——–
Kisah yang lebih rumit dipahami ialah novela kedua berjudul “Monolog”. Sebagaimana judulnya, de Beauvoir menciptakan karakter perempuan depresi yang mengoceh dengan dirinya sendiri. Namun banyaknya nama-nama tokoh yang diceritakan secara acak, dengan berbagai peristiwa yang terfragmentasi, akan menyebabkan para pembaca harus berusaha lebih keras untuk mengenal tiap tokoh dan memahami alur kronologi.

Foto Simone de Beauvoir. (Sumber Foto: https://www.tribunnewswiki.com)
Perempuan malang tersebut bernama Christine, berusia kira-kira setengah baya, telah menikah dua kali dan kandas. Ia mengalami keterguncangan mental tak berkesudahan karena Sylvie, anak remaja perempuannya yang lesbian memutuskan bunuh diri lima tahun lalu. Kematian Sylvie terus-menerus menghantui keseharian Christine hingga kini.
Kemanapun arah takdir berjalan, lingkungan masyarakat menjelma medan penghakiman bagi Christine. Atas tiap aspek dalam hidupnya, ia selalu dianggap melakukan kesalahan. Kematian Sylvie merupakan puncak kegagalannya. Semua orang, termasuk keluarga, menuduh Christine bertanggungjawab atas peristiwa bunuh diri tersebut. Ia pun ditinggalkan dan diabaikan dalam keterpurukan. Sendiri dalam larut amarah maupun penyesalan. Tak ada tempat berbagi, tak seorangpun mempercayai, Christine memandang diri dan hidupnya sebagai sebuah kegagalan besar.
Di malam tahun baru ketika semua orang bersukacita, Christine hanya mengurung diri dalam kamar dan bertengkar dengan dirinya sendiri. Dia mengutuk siapapun yang ada atau pernah ada dalam kehidupannya. Semua orang yang sudah membuatnya sengsara. Betapa ia merasa begitu disalahpahami. Betapa ia lalu tergoda untuk mengakhiri diri.
——–
“Perempuan yang Dihancurkan”, novela ketiga sekaligus juga yang menjadi judul buku fiksi Simone de Beauvoir ini menuturkan cerita tragedi kehidupan lainnya dari seorang tokoh perempuan. Narasi disajikan dengan model catatan harian (diary) yang ditulis oleh karakter utama, Monique. Ketika kedua anak perempuannya telah memasuki fase dewasa, Colette menikah di usia muda dengan seorang insinyur dan Lucienne melanjutkan sekolah di Amerika Serikat, Monique dan sang suami, Maurice, mengalami perubahan ritme kehidupan rumah tangga.

Foto Simone de Beauvoir. (Sumber Foto: https://andthekiosk.com)
Monique kemudian menemukan cara mengisi kesunyian waktunya dengan menulis di buku harian. Sedangkan Maurice, menenggelamkan diri dalam pekerjaannya sebagai dokter spesialis. Akan tetapi seiring waktu, ia semakin memperlihatkan tanda kesibukan yang tidak lazim. Hingga kemudian dirinya mengakui bahwa ada perempuan lain. Monique pada awalnya berusaha mengabaikan fakta perselingkuhan tersebut, dan terus memaksakan diri meyakini bahwa petualangan asmara sang suami hanya sesaat. Meskipun tak dapat dipungkiri, ia mengalami siksaan batin yang lambat laun menggerogoti kesehatan mentalnya.
Orang-orang di sekitar Monique memperlihatkan sikap dukungan dengan cara memperkecil masalah. Mereka mendorong Monique agar memaklumi bahwa pernikahan 15 tahun tanpa kasus perselingkuhan adalah mustahil. Lalu ia pun berupaya menerima Maurice yang tetap berselingkuh, serta mempercayai bahwa pada akhirnya sang suami akan bosan dan kembali padanya. Perempuan tersebut terus berpegang pada keyakinan semu bahwa cinta Maurice pada dirinya takkan terganti ataupun terkalahkan oleh perempuan lain manapun.
Namun demikian, ketika Maurice mulai menghabiskan waktu lebih banyak antara dia dan selingkuhannya Noellie, Monique mulai mempertanyakan banyak hal. Terutama, kualitas dirinya sebagai perempuan dan istri. Maurice sangat terlihat memperoleh semangat baru dengan kehadiran Noellie, perempuan dengan karir cemerlang sebagai pengacara. Noellie sebelumnya pernah menikah dengan seorang pengusaha yang mewariskan banyak harta saat mereka bercerai.
Independen secara ekonomi, mempunyai semangat intelektual, karir bagus, dan selera seni kontemporer, serta kelebihan-kelebihan lain yang menjadi daya tarik Noellie bagi Maurice, dipandang Monique yang cemburu sebagai penjelmaan perempuan muda yang penuh ambisi. Jenis perempuan yang dianggap akan melakukan segala cara demi memperoleh trofi kesuksesannya. Di sisi lain, Monique merupakan seorang ibu yang kecintaan dan daya hidupnya dicurahkan kepada keluarga. Perempuan yang sepenuhnya mengabdikan diri untuk kebutuhan suami dan anak-anak, serta berusaha menjaga kemapanan harmonis dalam berumah tangga.
Monique menderita dalam ketidakmampuannya melihat kebenaran bahwa perselingkuhan Maurice dan Noellie merupakan masalah serius. Bahwa tumbuhnya rasa cinta mereka itu nyata. Mereka menjadi semakin tak terpisahkan. Saat Maurice mengambil resiko berkata jujur bahwa dirinya bukan sekali ini melakukan perselingkuhan, melainkan sudah berlangsung 8 tahun dengan beberapa perempuan berbeda, Monique tersadar bahwa sebentar lagi ia akan kehilangan Maurice untuk selamanya. Akan tetapi, Monique belum berani menghadapi kemungkinan pahit itu. Ia memilih terus berjalan dalam fatamorgana yang menghancurkan kewarasan, hati, dan harga diri.
——–
Simone de Beauvoir menulis dengan cara yang sangat personal. Begitu detail menguliti persoalan gejolak batin perempuan. Seolah-olah ia menulis dari dalam, sebagai seorang korban yang tengah mengisahkan pengalamannya sendiri. Dalam sebuah wawancara di The Paris Review, de Beauvoir menyatakan bahwa ia memang bercita-cita agar tulisannya dapat menggerakan perasaan pembaca. Bagi saya, karya The Women Destroyed ini berhasil menggapai keinginannya tersebut. Dibutuhkan ketenangan dan kesiapan mental untuk berlayar dalam badai kata-kata di novel de Beauvoir yang satu itu.

Foto Simone de Beauvoir. (Sumber Foto: https://www.gabrielledubois.net)
Hanya saja, apa yang tertulis dalam karya fiksi de Beauvoir tidaklah seluruhnya berasal dari pengalaman dia sendiri. De Beauvoir menyuarakan pengalaman-pengalaman dari orang-orang di sekitarnya. Selain itu, ia pun tidak secara eksplisit menunjukkan posisi dirinya dalam kisah yang tertulis. Meskipun jika merujuk pada spektrum pemikirannya sebagai seorang feminis, de Beauvoir jelas menyindir fenomena masyarakat patriarki yang melanggengkan subordinasi terhadap perempuan. Persis sebagaimana pesan filosofis yang termaktub dalam “The Second Sex” (1949), buku legendaris de Beauvoir yang melejitkan namanya sebagai pelopor gerakan feminisme gelombang kedua.
Sama halnya dengan pasangan intelektual de Beauvoir, yakni Jean-Paul Sartre (1905-1980), mereka berdua merupakan filsuf sekaligus novelis. Keduanya saling menginspirasi, sehingga tema serta gagasan filsafat yang diangkat pun sewarna, di antaranya perihal eksistensialisme. Meskipun, dalam beberapa hal de Beauvoir dan Sartre juga bertentangan pandang mengenai konsep freedom (kebebasan) dan humanity (kemanusiaan). Akan tetapi, renungan atas hidup, waktu, dan kematian yang tersirat dalam karya-karya de Beauvoir, salah satunya dalam The Women Destroyed, menggolongkan dirinya ke dalam aliran pemikir eksistensialis.
Menggaungkan konsep ‘The Eye that Sees’ atau subjek yang mengguratkan sejarahnya sendiri, bukan hasil objektifikasi laki-laki adalah perjuangan de Beauvoir. Baginya, perempuan jangan lagi sebagai pihak yang melulu didikte, didefinisikan, maupun dikonstruksi oleh kaum laki-laki. Perempuan berhak memperoleh kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana laki-laki, atau pernyataan sejenis lainnya yang lahir dari prinsip-prinsip gerakan feminisme yang sudah sering kita dengar di masa kini.
——–
Bahkan setelah lebih dari setengah abad berlalu de Beauvoir menyuarakan “One is not born, but rather becomes, a woman”, ‘Menjadi Perempuan’ tetaplah bukan perkara mudah. Setelah perempuan telah memperoleh hak pilih, hak bekerja di publik, hak bersekolah dan berkarir setinggi-tingginya, hak menjadi pemimpin, hak berkarya sesuai dengan passion and interest, penilaian maupun perlakuan terhadap perempuan tetap menyisakan praktik stigma dan pelecehan. Tidak hanya dari laki-laki kepada perempuan, melainkan juga dari sesama perempuan.

Foto Simone de Beauvoir. (Sumber Foto: ://www.femmeactuelle.fr
Perempuan yang sukses dalam karir, bidang apapun itu, biasanya dipandang secara stereotipikal karena ia mengandung faktor “X”. Faktor X tersebut adalah kekurangan yang memungkinkan ia memperoleh keberhasilan tertentu. Misal, perempuan itu sukses karena ia berasal dari keluarga kaya; perempuan itu sukses karena ia cantik; perempuan itu sukses karena bergaul dengan kelompok yang memegang kekuasaan; perempuan itu sukses karena ia belum menikah; perempuan itu sukses karena mau jadi istri kedua atau ketiga; perempuan itu sukses karena ia tidak punya anak; perempuan itu sukses karena ia telah bercerai; perempuan itu sukses karena ia dicurigai rela melemparkan tubuhnya ke siapapun yang dapat meloloskan ambisinya; dan seterusnya bisa ditambahkan sendiri daftar panjang stereotip tersebut.
Dengan demikian, ketika seorang perempuan berhasil di ranah tertentu, dia akan tetap dianggap kurang atau gagal pada ranah lainnya. Persoalan ini tidak semata-mata mengacu pada jenis keberhasilan di wilayah publik, melainkan juga di wilayah domestik. Ketika feminisme telah secara masif menjadi sebuah gerakan dan ideologi yang mengubah secara radikal gagasan perempuan mengenai dirinya sendiri, mereka berbondong-bondong keluar rumah dan menghambakan diri kepada kerja pabrik maupun korporasi. Menjadi perempuan rumah tangga semakin mengalami peyorasi, seakan-akan status itu melabelkan kehinaan dan kesia-siaan hidup pada diri perempuan.
Dalam The Women Destroyed, de Beauvoir secara tersirat menampilkan bahwasanya perempuan rumah tangga pun perlu diapresiasi keberhasilannya dalam merawat keluarga, menanamkan nilai, dan menumbuhkembangkan anak, tanpa terbatasi untuk berkiprah di bidang pekerjaan lainnya. Perempuan harus dilihat secara menyeluruh dalam peran apapun yang dilakukan dan diperjuangkan. Menjadi perempuan, bukan semata-mata bebas dan mengejar kesamaan-kesamaan hak atas laki-laki, melainkan sadar sekaligus memahami kapasitas serta kualitas diri untuk menjadi apa dan bermanfaat bagi siapa. Pendidikan kesadaran ini juga penting bagi segenap laki-laki dan seluruh perempuan lainnya, agar setiap kali melihat fenomena keberhasilan seorang perempuan, ia tidak lagi dilecehkan sejak dalam pikiran.
*Penulis esai dan puisi, mahasiswa pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia.













