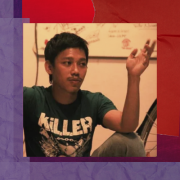Kreativitas Olah Budaya
Oleh: Mudji Sutrisno SJ*
Kreativitas kebudayaan merupakan misteri dari tetap tumbuhnya kemanusiaan ketika peradaban dihadapkan pada ujian-ujian sejarah. Ujian itu, misalnya, kekejaman politik; penindasan hak asasi; pemasungan alam pikiran merdeka; pengontrolan dan penghapusan pikiran-pikiran kritis dan perbedaan pendapat; dan humanisasi proses-proses bermasyarakat. Tapi, mengapa merupakan misteri?
Pertama: karena ruang lingkup kemampuan-kemampuan manusia berada pada sebuah cakrawala ruang batin yang mahaluas. Ruang itu tidak pernah bisa ditundukkan secara fisik maupun secara teror oleh kekuasaan fisik, penjara, senjata, atau apa pun. Kedua, potensi-potensi kreatif kebudayaan – yang oleh pelaku-pelakunya baik seniman, budayawan, serta cendikiawan dihayati dan diekspresikan untuk menjaga tetap cerah dan heningnya peradaban sumber mendasarnya – memang ada pada tataran nurani jernih kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang.
Ketika krisis dan ujian-ujian mau mengoyak kemanusiaan dan mau memperlakukan sesama secara kejam bahkan secara biadab, sejarah peradaban humanis memiliki enak cara untuk bertahan – termasuk di dalamnya bahasa budaya bisu, ordo nurani, atau pun bahasa pasif buat resistensi.
Yang pertama, ia muncul dalam resistensi budaya komedi atau kelucuan yang tidak hanya mau menertawakan rezim yang ada tapi juga mau menertawakan diri sendiri. Inilah otokritik untuk sebuah proses transformasi budaya ketika kelaliman harus dilawan dan ketika kekuasaan mau menghabisi segala kreativitas yang kritis dari manusia. Pada saat itu, kita mengenal komedi-komedi macam Don Kisot, atau Mati ketawa ala Daripada, atau bentuk-bentuk satire yang intinya memperolok kekuasaan yang memonopoli kebenaran sendiri dan memaksakan kehendak kepada rakyat. Itulah cara bertahan dengan gaya lawak. Komedi semacam ini dihayati ketika bersuara bebas yang kritis dan merdeka dipasung – tidak hanya dengan kekuasaan represif, tetapi dengan menghabiskan semua musuh-musuh yang berbeda pendapat demi kelangsungan rezim yang totaliter, otoriter, dan fasis.
Yang kedua, ia muncul dalam resistensi bungkus-bungkus utopia dan cita-cita masa depan sebagai cara melarikan diri dari ketidakmampuan menghayati realitas masa kini yang keras dan represif. Dalam hal ini, jangan heran kalau ada tokoh atau penguasa yang mengatakan “Mari kita songsong era baru, masa baru” manakala keadaan riil di depan mata penuh krisis – tidak hanya krisis-krisis kelaparan, lebih-lebih lagi krisis kesemrawutan dalam tidak adanya saling percaya dan krisis kepemimpinan.
Raja-raja Mataram
Yang ketiga, ia muncul dalam bentuk pelarian dari ke masa lalu. Artinya, orang berkisah dan melarikan ketidakberanian menghadapi krisis yang ada secara kebudayaan dalam bentuk nostalgia yang mengacu ke kisah sukses zaman lalu atau sejarah lalu yang sudah tidak aktual lagi.
Keempat, dalam situasi krisis resistensi budaya, muncul bentuk pengkristalan impian-impian dan cita-cita yang tidak kesampaian dalam wujud-wujud simbmolisasi dan ritualisasi. Simbolisasi adalah pemadatan frustrasi, kebosanan, impian-impian dalam bentuk lambang-lambang, retorika simbol-simbol berupa kata-kata manis atau janji-janji pidato, dan retorika pernyataan, yang ketika diuji wujud pelaksanaan atau aksinya ternyata hanya kosong belaka. Saat ini, modal semacam ini banyak terjadi: janji-janji dilontarkan amat banyak, tetapi wujud pelaksanaan di lapangan tidak terjadi. Misalnya, janji kebebasan berbicara, kenyataannya, tindakan riilnya adalah pembatasan hak bersuara yang diberi label atas nama kebebasan yang bertanggungjawab dalam peraturan pengganti undang-undang atau perpu.
Ritualisasi adalah wujud kebudayaan yang berintisari upacara dengan seluruh kesemarakannya. Namun, esensi nilainya hanya fisik, formal, dan kulit belaka. Contoh: ekspresi negara gebyar teater yang dilakukan raja-raja Mataram Jawa dalam ritual-ritual yang semarak sebagai pengganti kenyataan bahwa raja-raja tersebut tidak punya kekuasaan fisik teritorial lagi karena sudah dikuasai VOC sejak Perjanjian Giyanti. Inilah cara bertahan nomor lima.
Yang keenam: bentuk resistensi budaya dalam situasi sulit represif yang sesungguhnya amat kreatif. Yaitu bentuk-bentuk mini kata, ekspresi pantomim kreatif yang mengkritik penuh dinamika kritis namun terbentur politik represi kebebasan berpikir. Serta, setiap wujud ungkapan budaya-budaya bisu dan kontestasi-kontestasi (pemberontakan) budaya yang secara danai berunjuk rasa dalam ekspresi drama, seni konstelasi-konstelasi (pemberontakan) budaya yang secara damai berunjuk rasa dalam ekspresi drama, seni konstelasi, film, serta karikatur-karikatur yang intinya mengkritik situasi yang tidak bebas dan otoriter. Wujud resistensi ini amat subur manakala monopoli penafsiran makna dan sentralisasi pengontrolan pikiran rakyat oleh pemerintah dengan perangkat birokratik dan kekuasaan militernya demikian ketat. Iia seakan mencari celah-celah tembok-tembok baja penjara otoriter dan kegelapan-kegelapan dinding penyekapan untuk tetap percaya dan mengajak percaya setiap orang bahwa cahaya matahari kebebasan pada suatu saat akan dua puluh empat jam dirasakan.
Enam bentuk resistensi di atas membuktikan bahwa potensi-potensi kreatif kebudayaan – yang ketika diproses baik oleh bangsa yang bersangkutan sebagai pribadi-pribadi merdeka, maupun yang dihambat oleh struktur sistem politik kekuasaan yang mau membelenggu untuk pemenhangan status quo kemapanan kursi kepentingan sendiri – tiap kali disadari bersumber lebih pada ruang batin.
Keenam bentuk resistensi kebudayaan ini bisa membuktikan kuat-tidaknya peradaban sebuah bangsa. Dengan enam bentuk itulah, misalnya, sebuah bangsa ditentukan lulus-tidaknya dalam serat-serat budayanya ketika bangsa tersebut harus mengolah sejarah pengalaman traumatis, semacam tahun 1965-1966 dengan matinya 600-an ribu orang tanpa proses pengadilan; trauma penjarahan; penculikan dan pemerkosaan 13-15 Mei 1998; politik kekerasan yang dipakai untuk memaksakan kehendak politik ego sendiri atau ego kelompok dengan tega membunuh sesama saudara sebangsa dalam Peristiwa 27 Juli 1996. Bila kita tidak lulus, jangan kaget bila separo wajah kita, paling tidak, bisa saja dibilang wajah biadab.
Hati Nurani
Sejarah pengalaman traumatis bisa diolah – oleh masing-masing kita sendiri maupun sebagai bangsa – bila kita dalam ordo (tarekat) hati nurani melakukan pengakuan dengan rendah hati; memang kenyataan bahwa sebagian wajah kita sadistis.
Tapi, tentu tak cuma berhenti di pengakuan. Diperlukan pengolahan dalam proses rekonsiliasi, yang secara kebudayaan menuntut seluruh potensi kreasi budaya untuk menegaskan diri menolak pembunuhan, penculikan, atau pemerkosaan dengan memberi tidak hanya bahasa moralitas rekonsiliasi tetapi bahasa struktural politis, hukum, sosial, ekonomi. Dan, secara keseluruhan, itu semua mengekspresikan tekad untuk bilang tegas-tegas: No more again violence and dehumanization toa our brothers and sisters.
Berikutnya, proses pengolahan trauma hanya mungkin dihayati dari dua pihak. Berpihak pada posisi korban untuk memproses secara hukum pelaku pidana pemerkosaan secara hukum pelaku pidana pemerkosaan dan pembunuhan. Dan, di pihak penanggung-jawab keamanan, warga dan rakyat harus berani jujur mengakui kesalahan dan membuka proses seterang mungkin terhadap trauma-trauma yang ada hingga kredibilitas pemerintah kembali pulih.
Ini berarti tidak boleh ada diskriminasi dalam pembebasan tahanan-tahanan yang tidak bersalah; tidak boleh diskriminatif pada yang terlibat karena pangkat; serta harus mau secara pahit membongkar memori kolektif, yang memang kemanusiaannya dilukai. Ini berarti segala bentuk dan usaha untuk menghapuskan sejarah politik kekerasan, seperti 27 Juli 1996, harus dihentkan dan diproses dalam keterbukaan, dan mengadili yang terlibat meskipun banyak yangt masih berada dalam kursi-kursi, pemerintahan. Di sini tuntutan reformasi budaya secara total yang secara gemilang disejarahkan oleh mahasiswa dan generasi muda dengan tuntutan pembersihan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) merupakan pisau tajam untuk proses rekonsiliasi yang sebenarnya. Artinya, selama tntutan KKN belum radikal dilaksanakan, terutama di basis-basis birokrasi pemerintah yang sekarang ada, di situ cita-cita untuk rekonsiliasi dan olahan trauma tidak akan berhasil.
Berikutnya, olah sejarah menuntut kearifan memberi ruang baru bagi publik rakyat dengan dikembalikannya potensi daulat rakyat secara konkret. Artinya, kekayaan-kekayaan kemajemukan dihormati dan berkembangnya sistem politik ketika setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dikembangkan secara struktural. Juga, tiap konflik yang terjadi diselesaikan secara beradab dalam proses pengadilan dan hukum dalam sistem politik demokratis. Hingga ekspresi “bertanggungjawab” bukan diputuskan sepihak, oleh presiden atau pemerintah, tapi merupakan hasil godokan bersama yang terus menerus.
Mau tak mau potensi-potensi kreatif budaya akan menjadi peradaban. Kemudian, humanisasi diberi bahasa-bahasa strukturalnya dan menghasilkan peradaban humanis. Maka, ada dua pekerjaan rumah yang saat ini menantang kita dalam reformasi kebudayaan.
Pertama, kita butuh memberi lagi nafas hidup yang segar agar potensi-potensi kreatif bangsa untuk merajut cita-cita para pendiri bangsa berkembang. Cita-cita itu, kalau Anda belum lupa: masyarakat yang beradab, majemuk, terbuka, dan manusiawi maju.
Kedua, kita butuh – dalam menghadapi krisis desintegrasi saat ini – usaha-usaha mengolah trauma-trauma sejarah dalam rekonsiliasi kebudayaan dan penegasan untuk menolak setiap politik kekuasaan dan kekerasan yang menghalalkan kebiadaban. Dan, ini hanya mungkin apabila kita memulihkan saling percaya untuk meletakkan kembali format peradaban kita dengan titik-tolak hormat pada harkat tiap sesama kita. Kemajemukan suku, agama, dan golongan harus dijadikan sumber pengikat bangsa dalam satu cita-cita yang sama: humanisasi dalam setiap ikhtiar peradaban kita.
———–
*Mudji Sutrisno Sj, budayawan.