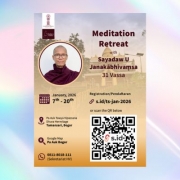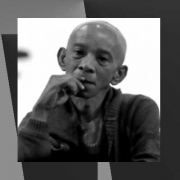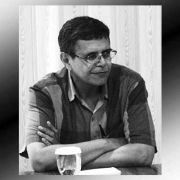Dewi Sri, Pergelaran Subkultur, dan Politik Kebudayaan
Oleh Purnawan Andra*
Nusantara sejak awal bukanlah ruang homogen. Ia adalah pertemuan berlapis dari ratusan bahasa, sistem kepercayaan, adat, dan praktik estetik yang terus bergerak. Clifford Geertz dalam Religion of Java menyebut Jawa sebagai “mosaic of cultural streams,” dan istilah itu tampak hidup di Jawa Timur.
Dalam hal ini, Ayu Sutarto (2004) mengidentifikasi sepuluh subkultur di Jawa Timur. Empat kebudayaan besar di Jawa Timur adalah Mataraman, Arek, Madura Pulau dan Pandalungan. Kebudayaan kecil terdiri dari Jawa Panoragan, Osing, Tengger, Madura Bawean, Madura Kangean dan Samin.
Kultur Arekan meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Malang. Kultur Madura Pulau meliputi Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan. Kultur Pandalungan meliputi Bondowoso, Jember, Lumajang, Situbondo, Probolinggo (kabupaten/kota), Pasuruan.
Sementara kultur Mataraman Timur mencakup daerah seperti Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, sedangkan Mataraman Barat meliputi Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Pacitan. Masing-masing daerah memiliki karakteristik budaya yang khas, baik dari segi bahasa, ekspresi seni, sistem kepercayaan, hingga tata ruang dan lanskap budaya.
Itulah mengapa, dari Surabaya hingga Pacitan, dari Ngawi hingga Banyuwangi, bentang ini dihuni subkultur dengan logika berbeda: Arekan dengan egalitarianisme kota pelabuhan, Tapal Kuda dengan religiositas santri, Madura dengan vitalitas perantau, dan Mataraman dengan tata krama keratonik yang lentur. Masing-masing punya gaya bahasa, ekspresi seni, hingga cara menyelesaikan konflik.
Menjaga Keragaman
Keragaman budaya ini tentu saja bukan merupakan sebuah beban, melainkan sumber daya. Ia mengajarkan bahwa identitas bukan monolit, melainkan proses dialogis antar kultur yang dinamis. Itulah mengapa ketika Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI menggelar kegiatan Rawat Budaya Mataraman di GOR Bung Karno Nganjuk 22-23 Agustus 2025 lalu, konteksnya tidak sekadar “pelestarian” dalam arti menyimpan masa lalu.
Dalam pemberitaannya, kegiatan ini merupakan langkah dalam merawat keberagaman budaya di wilayah subkultur Mataraman. Melalui pendekatan yang kolaboratif, edukatif, dan partisipatif, diharapkan budaya lokal dapat terus hidup, berkembang, dan diwariskan sebagai bagian dari peradaban yang luhur dan berkelanjutan. Kegiatan ini sendiri mengangkat tema “Ngleluri Budaya, Memulya Trapsila” yang dimaksudkan bukan hanya slogan, melainkan spirit yang ingin ditegakkan dalam menjaga keragaman budaya bangsa.
Pada titik ini, dalam kontekstualisasinya dengan masa kini, kita perlu berharap dari kegiatan ini yang lebih penting adalah menunjukkan bagaimana satu subkultur bernegosiasi dengan modernitas, lalu membuka kemungkinan dialog dengan subkultur lain.
Dialektika Kebudayaan
Dalam hal ini, sendratari Dewi Sri “Merti Bumi Ngreksa Pakarti” garapan Irwan Riyadi yang tampil di acara Rawat Budaya Mataraman (Jumat, 22/8/2025) bisa dibaca sebagai contoh pembahasan tentang dialektika kebudayaan. Pada karya ini, tokoh mitologis yang dulu bersemayam dalam ritus agraris di sawah dan lumbung dipanggil kembali ke panggung modern.
Dewi padi itu hadir dengan gestur tayub, dinamika reog, dan dramaturgi wayang, sebuah “kamus gerak” yang akrab bagi masyarakat Mataraman. Panggung ini bukan jadi museum, melainkan medium tafsir, yang menyambungkan memori agraris dengan isu kontemporer seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan renggangnya solidaritas desa yang makin urban.

Salah satu adegan sendratari Dewi Sri (Foto: Ardha – BPK XI)
Tentu Dewi Sri bukan milik Jawa Mataraman saja. Hampir semua masyarakat agraris Nusantara mengenal figur serupa. Kita mengenal Sangiang Sari di Kalimantan, Indung Pare di Sunda, hingga Lakshmi dalam tradisi Hindu Bali. Di Sulawesi Selatan, tradisi mappalili yang melibatkan doa dan ritual sebelum menanam padi memiliki tujuan menghormati alam dan mengikat komunitas lewat ritus pangan.
Ini membuktikan bahwa imajinasi tentang kesuburan, padi, dan siklus alam adalah basis kosmologi bersama. Namun ketika ia dipanggungkan dalam idiom Mataraman, kita melihat satu kemungkinan tafsir: harmoni berupa etetika Jawa berada dalam konteks dramaturgis dengan penekanan pada rasa syukur sebagai tata batin.

Salah satu adegan sendratari Dewi Sri (Foto: Ardha – BPK XI)
Lalu bagaimana bila subkultur lain, misalnya arek Malang, mementaskan Dewi Sri? Bedanya bisa sangat terasa. Tradisi ludruk dan remo mungkin membuat penyajiannya lebih cepat, komunikatif, bahkan satiris. Narasi bisa menghadirkan Dewi Sri berdialog dengan “tengkulak” atau “driver logistik,” menyinggung harga beras dan korupsi dengan humor khas arek.
Sementara dalam tangan seniman Tapal Kuda, logika panggung bisa ditautkan dengan nuansa religious seperti doa panen, lantunan shalawat, simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dan dalam energi Madura, Dewi Sri bisa tampil dengan ritme keras, vitalitas perantauan, menekankan sirkulasi pangan ke kota-kota pelabuhan.
Pergelaran
Perbedaan itu bukan ancaman. Justru di situlah konsep pergelaran menemukan maknanya. Pergelaran bukan hanya pertunjukan seni, melainkan peristiwa sosial di mana identitas dinegosiasikan di depan publik. Victor Turner dalam Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society (1974) menyebut ritual dan pergelaran sebagai social drama, yaitu ruang di mana konflik, nilai, dan solidaritas diuji.
Ketika Dewi Sri dipentaskan di Mataraman, ia berfungsi sebagai drama sosial yang mengikat kembali masyarakat pada memori agraris. Ketika ia dipentaskan di Malang, fungsi itu bisa bergeser menjadi satire kota. Jika dipentaskan bersama lintas subkultur, pergelaran berubah menjadi arena kolaborasi yang memperlihatkan logika kebudayaan Indonesia yang majemuk, cair, dan terus bergerak.

Salah satu adegan sendratari Dewi Sri (Foto: Ardha – BPK XI)
Dari sini, kita masuk pada ranah politik kebudayaan. Selama ini, program pelestarian sering terjebak pada logika administrasi berupa mendata, mendokumentasikan, memberi label warisan takbenda. Memang semua itu penting sebagai langkah-langkah mengelola produk budaya masyarakat.
Tapi seperti diingatkan Koentjaraningrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi (edisi revisi 1981), kebudayaan bukan hanya benda atau catatan, melainkan sistem makna yang hidup bila dijalankan. Dalam hal ini, UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebenarnya sudah memberi arahan bahwa yang perlu dipelihara bukan hanya bentuk, melainkan fungsi sosial budaya sebagai perekat bangsa.
Reduksi
Sayangnya, dalam praktiknya, politik kebudayaan kerap tereduksi jadi festival seremonial atau agenda pariwisata. Yang terjadi bukan pemajuan, melainkan komodifikasi. Kebudayaan jadi event, bukan proses.
Padahal, contoh dari Nganjuk memperlihatkan kemungkinan lain. Yaitu bagaiman menjadikan panggung sebagai forum sipil di mana persoalan pangan, air, dan kohesi sosial dibicarakan dengan bahasa estetik.
Di sini saya teringat pemikiran Benedict Anderson tentang imagined communities. Bangsa, katanya, terbentuk karena kita membayangkan diri terhubung dengan orang yang tak pernah kita jumpai, melalui media simbol.
Pergelaran Dewi Sri bisa dilihat sebagai salah satu media itu. Ia menyatukan masyarakat yang berbeda subkultur dalam imajinasi bersama: bahwa kita semua bergantung pada padi, air, tanah, dan ritme alam. Imajinasi kolektif semacam ini lebih kuat daripada jargon politik yang kering.
Maka ketika kita bicara tentang “strategi pemajuan kebudayaan,” kita bisa belajar pada praktik seperti ini. Bukan sekadar melindungi warisan, tapi menciptakan ruang pergelaran lintas subkultur. Bayangkan jika Dewi Sri digarap kolaboratif di mana koreografer Mataraman meramu struktur rasa, seniman arek menyuntikkan humor partisipatif, musisi Tapal Kuda membawa lantunan religius, seniman Madura menghadirkan energi mobilitas. Pergelaran semacam ini bukan hanya hiburan, melainkan bisa jadi strategi kebudayaan, untuk meneguhkan perbedaan sebagai kekuatan.

Salah satu adegan sendratari Dewi Sri (Foto: Ardha – BPK XI)
Politik kebudayaan yang sehat tidak menganggap subkultur sebagai arsip, tapi sebagai laboratorium. Jawa Timur bisa menjadi contoh di mana wilayah dengan keragaman kultural yang sering dianggap kontradiktif, ternyata menyimpan potensi kolaborasi yang memperlihatkan wajah Indonesia mini. Dari laboratorium inilah bisa lahir model kebudayaan nasional yang tidak seragam, tapi juga tidak tercerai-berai.
Dan Dewi Sri, yang dahulu menjaga lumbung padi desa, kini bisa menjaga “lumbung imajinasi” bangsa. Dari sawah hingga panggung, dari ritus desa hingga forum seni, ia menegaskan bahwa kebudayaan bukan sekadar memuja masa lalu, tapi cara masyarakat membicarakan masa depan. Ketika iklim berubah, ketika pangan terancam, ketika solidaritas sosial retak, justru panggung inilah yang memanggil kita untuk berkumpul, berdialog, dan membayangkan ulang Indonesia.
—-
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.