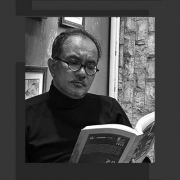Break the Language Barriers: Perjumpaan Sinekar, Fatamorgana, Splinter of an Age dan Sea of Silence
Oleh Sekar Tri Kusuma
Benang Merah antara Sinekar, Fatamorgana dan Splinter of an Age
Sepanjang tahun 2023 menjadi perjalanan yang sangat berarti bagi saya. Berawal dari kenekatan untuk menjalankan misi mengumpulkan video vertikal pose di berbagai tempat umum sebagai laboratorium gerak yang saya beri tajuk Laboratorium Sinekar. Tempat umum yang pertama kali saya kunjungi adalah Stasiun Jebres. Sejak awal, saya berniat untuk membebaskan diri dari rencana, artinya rencana bisa berubah kapan saja sesuai kehendak saya. Pada akhirnya, pengambilan video saya lakukan di dalam gerbong kereta yang hendak melaju dari Surakarta ke Jogja.
Tanpa ragu, saya menata perlengkapan berupa tripod sepanjang 1 meter. Tak ada satupun pose yang terlintas di pikiran, secara spontan saya mengatur kamera telepon seluler dan perlahan menyesuaikan posisi berdiam diri seolah-olah menggenggam handrail yang tak kasat mata. Kemudian perlahan menekuk kedua lutut demi menjaga keseimbangan di tengah goyangnya kereta. Aksi tersebut tidak begitu mendapat respon yang berlebihan dari penumpang, justru seluruh penumpang terlihat biasa saja. Video-video yang saya kumpulkan dapat disaksikan melalui akun Instagram @_sinekar. Dalam video yang telah saya unggah juga tersematkan beberapa data seperti lokasi; suhu tubuh; cuaca; jam; durasi video; makan; minum dan seri gawai. Seperti halnya yang terlihat pada bagian belakang bungkus mi instan, saya mengajak audiens dan pengguna telepon seluler pintar untuk mengintip apa saja bahan-bahan karya yang nantinya akan saya ‘masak’.
Laboratorium Sinekar saya kembangkan berdasarkan keingintahuan mengenai seberapa intens hubungan yang melekat antara tubuh, diam, pasca trauma, konsumerisme, kolonialisme, publik, dan perempuan. Tidak hanya saya kumpulkan, data-data berupa video tersebut juga saya olah. Kumpulan video tersebut menjadi pengarah dalam menarasikan karya Fatamorgana. Fatamorgana yang saya kerjakan merupakan karya tari kontemporer yang fokus membaca persoalan antara tubuh dan perempuan. Fatamorgana pertama kali dipentaskan di acara Tidak Sekedar Tari ke-82 dan bisa disaksikan di kanal Youtube Taman Budaya Jawa Tengah. Ide yang ditawarkan melalui karya ini adalah membicarakan tentang bagaimana perempuan selalu beradu dengan waktu. Berangkat dari banyaknya anggapan bahwa usia perempuan tergolong pendek dan tidak sepanjang masa kaum laki-laki, terlebih jika sudah menikah dan memiliki keturunan.
Persoalan ini mungkin sudah seringkali digaungkan, akan tetapi ada pelbagai hal yang lebih kompleks dan mendalam yang perlu diperhatikan kembali. Hal ini menyinggung soal dampak kolonialisme yang cenderung mendiskreditkan posisi kaum perempuan dan mungkin saja hingga hari ini masih kita rasakan imbasnya. Kolonial memang sudah tidak lagi beroperasi, namun peninggalannya masih setia bermukim hingga menyentuh ranah reyotnya budaya, mitologi, dan sejarah suatu bangsa. Misal, banyaknya mitos atau kearifan lokal yang terpinggirkan oleh zaman dan silam dengan menyisakan hanya secuil informasi. Padahal jika ditelusuri secara kritis, kearifan lokal milik leluhur kita adalah pengetahuan dasar yang akarnya kuat sekaligus visioner dan disalurkan dengan cara yang filosofis, manis meski tak jarang diberi bumbu hal-hal mistis. Persis seperti yang disampaikan oleh Titah AW dalam bukunya yang berjudul Parade Hantu Siang Bolong.
Hal ini juga saya amati pada beredarnya mitos uji keperawanan dan ruwatan atau penyucian yang menyelimuti sejarah di sekitaran Candi Sukuh. Mitos uji kesucian menjadi landasan pemikiran karya saya dalam format seni performans bertajuk Splinter of an Age berdurasi 120 menit. Sepanjang performans berlangsung, yang saya lakukan adalah berdiam diri di pojok ruang, duduk diantara daun pintu juga terlentang di tengah ruang. Splinter of an Age telah saya presentasikan di Tulang Bawang Barat (Tubaba, Lampung) pada acara Indonesia Bertutur 2023 yang diinisiasi oleh Melati Suryodarmo bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Secara garis besar, visi dan misi Indonesia Bertutur adalah menyelami masa lalu untuk menciptakan masa depan melalui mitos, sejarah dan pengetahuan lokal yang tersimpan pada cagar-cagar budaya di seluruh Indonesia. Mitos yang diduga menyimpan pengetahuan leluhur, dipercaya jauh lebih mutakhir daripada yang pernah kita bayangkan. Akan tetapi, pengetahuan-pengetahuan yang tersisihkan akibat kolonialisme, kini hanya menyisakan praduga-praduga. Praduga inilah yang menjadi sumber dari segala pincangnya interpretasi bahkan ikut menyeret posisi kaum perempuan. Kompleksitas yang terjadi pada perempuan dan kolonialisme, bersinggungan juga dengan penelitian yang dikerjakan oleh Tamara Cubas.
Tamara Cubas adalah seniman Uruguay yang selama 5 tahun terakhir mengerjakan proyek Sea of Silence. Proyek ini mengusung atensi Tamara terhadap migrasi perempuan dari berbagai wilayah terjajah dan hubungannya dengan kolonialisme. Dalam proyek Sea of Silence di tahun 2024, Tamara tidak hanya bekerja seorang diri. Ia menggaet beberapa nama seniman dari negara-negara yang juga memiliki sejarah kolonialisme. Seluruh seniman yang terlibat secara aktif turut mengerjakan karya Sea of Silence. Berikut deretan nama seniman yang terlibat: Karen Daneida (Meksiko), Dani Mara (Brasil), Hadeer Moustafa (Mesir), Ocheipeter Marie (Nigeria), Noelia Roxana Coñuenao (Chili), Alejandra Wolf (Uruguay) yang kini digantikan oleh Victoria Pereira (Uruguay), dan saya—Sekar Tri Kusuma (Indonesia)
Sementara itu, karya Sea of Silence telah ditampilkan di beberapa festival internasional. Diantaranya adalah Teatro Solis (Montevideo, Uruguay), Festival d’Avignon (Avignon, Perancis), Tanz im August (Berlin, Jerman), serta Teatro a Mil (Santiago, Chili) dan Teatro Bio Bio (Concepción, Chili)
Sea of Silence Project
Sea of Silence pada awalnya dikembangkan oleh Tamara dalam wujud pameran seni rupa, fotografi, instalasi dan film pendek. Akan tetapi, pada proyek Sea of Silence termutakhirnya, Tamara mencoba menyuguhkan sesuatu yang baru yakni mempersembahkan semacam kumpulan ritual berformat teater monolog dalam berbagai bahasa. Sedikit sulit saya jabarkan sebagai satu istilah yang spesifik, karena memang karya ini cukup kompleks untuk diidentifikasikan sebagai jenis tontonan tertentu.
Selama bertahun-tahun Tamara melakukan penelitian, menggali informasi dan membagikan kisah perjalanan migrasi perempuan dari berbagai benua. Ia meyakini bahwa migrasi telah ada sejak awal sejarah, dan tidak ada umat manusia yang tidak tersentuh olehnya. Profil karya-karya Tamara dapat disaksikan melalui kanal Youtube pribadinya. Berikut salinan tautannya : https://youtube.com/@tamaracubas_artworks?si=fHW27xJEqGO9-q-7
Awal Perjumpaan
Seiring berjalannya waktu, Tamara mencoba mengerucutkan idenya melalui realita yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, Ia berinisiatif untuk melibatkan seniman lain sebagai rekan kerja yang turut memperkaya temuan-temuannya menyoal migrasi perempuan. Baik terlibat sebagai aktris, asisten direktur maupun dramaturg.
Bagi saya, Tamara memiliki keberanian yang luar biasa besar. Pasalnya, Ia betul-betul mempercayakan rekomendasi rekan mancanegara yang bahkan beberapa diantaranya tidak begitu ia kenal. Termasuk saya, yang mendapat rekomendasi secara langsung oleh Direktur dan Kurator Indonesian Dance Festival yakni Ratri Anindyajati dan Nia Agustina. Proses keikutsertaan masing-masing dari kami pun sangat beragam, ada yang mengikuti audisi, ada yang mendaftarkan diri, ada yang mendapat rekomendasi hingga ada yang memang ‘di-lobby’ secara langsung oleh Tamara pribadi.
Kriteria yang Tamara cari kurang lebih seperti ini; seniman perempuan independen yang sedang melakukan penelitian, memiliki kemampuan menari, bernyanyi dan bermain peran alias akting. Untuk hal menari dan bernyanyi saya cukup memiliki kepercayaan diri, namun tidak dengan akting. Saya rasa, akting belum menjadi satu disiplin yang saya kuasai. Pada momen tersebut saya selalu saja merasa khawatir tak mampu mengimbangi performa seniman yang lain, namun siapa sangka bahwa justru Tamara mempercayakan secara penuh pada saya. Ia meminta saya untuk membawakan monolog secara jujur tanpa dibuat-buat sedikitpun dan tidak terbebani secara teknis. Ia percaya bahwa tubuh tiap individu punya andil dalam menyimpan sejarah dan dibekali daya yang kuat.
Residensi dan Latihan
Seluruh seniman dan tim, pertama kali dipertemukan di Campo Abierto yang bertempatan di Rivera, Uruguay —kawasan perbatasan antara Uruguay dan Brasil. Salah satu wilayah di Uruguay yang mempersilahkan matahari muncul di tengah pergantian musim dingin. Selama hampir satu bulan kami melakukan proses di Campo Abierto, yang mana merupakan galeri dan penginapan milik Tamara. Mungkin terkesan berlebihan, namun yang saya rasakan ketika tinggal di sana, saya merasa terlahir kembali. Seperti mengintip surga, udara disana seolah tak pernah bergumul dengan polusi, air tidak pernah tercemar dan kami bisa meminum langsung dari keran. Hewan ternak dibiarkan berkeliaran bebas, tanpa ada rasa takut diganggu olehnya. Campo Abierto tidak hanya menyediakan tempat untuk singgah dan galeri yang dapat dikunjungi setiap saat, tapi disana juga tersedia hutan yang masih asri.
Pada minggu pertama, kami fokus dengan residensi yang memperkenalkan masing-masing ritual kuna dan masih dilakukan di tiap daerah kami. Spesifiknya, kami memperkenalkan seni, budaya, dan tradisi masyarakat adat seperti Mapuche, Pataxó, Borun, Guarani, hingga Jawa. Kami juga saling membagikan kisah pribadi melalui metode cartography yang diperkenalkan oleh Tamara. Proses ini sangat intens dan intim. Satu pekan penuh kami habiskan dengan menitikkan air mata, bahkan beberapa diantara kami seringkali menghentikan cerita sebab tak mampu melanjutkan lewat kata-kata.
Kami juga mencoba mengilustrasikan kondisi terkini masing-masing negara, supaya tidak begitu hanyut dalam persoalan personal. Akan tetapi, saya rasa sama saja. Bukannya teralihkan, justru saya merasa cukup terbebani karena banyak kejadian yang bertubi-tubi menimpa negeri terutama sejak awal tahun 2024 hingga saat ini. Mulai dari isu politik dinasti, polarisasi antar partai politik, pemindahan ibukota, kesenjangan persepsi antar generasi, isu lingkungan, isu masyarakat adat, isu perempuan hingga korupsi besar-besaran dan terang-terangan.
Kebanyakan dari kami merasa kesulitan menerjemahkan capaian Tamara lewat residensinya. Setiap gebrakan yang ia tawarkan selalu menimbulkan tanda tanya besar, bahkan tanpa ada keterangan. Tamara menyebutnya ‘incertidumbre’ yang artinya kurang lebih adalah ketidakpastian. Segala hal yang kami lakukan pada waktu itu benar-benar mengandalkan ketidakpastian, di luar rangkaian jadwal, dan kadang diluar nalar. Setiap hari kami selalu menunggu “kira-kira apa lagi yang akan Tamara berikan pada kami?” Memang sulit sekali untuk memecahkan teka-teki Tamara, tapi hal ini justru menyadarkan saya bahwa ternyata metode Tamara telah berhasil menghipnotis kami untuk tidak pernah berhenti berpikir akan segala sesuatu yang telah, sedang dan akan terjadi. Sungguh berhasil membangun kesadaran kami secara penuh. Bagaimana tidak? Kami serasa berada di hutan sungguhan, yang musti siap siaga kalau-kalau ada binatang buas yang hendak memangsa ataupun malapetaka yang hendak menimpa.
Spirit ketidakpastian ini terproyeksikan lewat bagaimana tiba-tiba kami diminta menceritakan arti nama dan sejarah keluarga kami. Tiba-tiba seluruh seniman diajak foto bersama seolah-olah menciptakan memori keluarga. Tiba-tiba merangkai buku diary yang bisa kami kreasikan secara bebas, bahkan tiba-tiba di buang ke hutan. Sewaktu di hutan, kami diminta untuk mencari rute secara mandiri, tidak diperkenankan untuk berbicara satu sama lain, dan dibiarkan kalut dengan pikiran masing-masing. Tamara hanya memberi kami informasi soal lanskap, rute jalan setapak dan batas-batasnya. Tidak hanya itu, kami juga dibekali pertanyaan yang sukar. Siapa yang selalu bersamamu? Apa yang menghubungkanmu? Apa yang ada di belakang atau ujung? Dan masih banyak lagi.
Ternyata setiap dari keputusan Tamara menyimpan alasan yang kuat. Misal, adanya cartography membantu kami untuk lebih imajinatif dalam menceritakan segala hal. Buku diary yang menjadi notulensi kami selama ini dikumpulkan dan diinterpretasi oleh Vachi Gutierrez sebagai dramaturg. Setidaknya, pertanyaan-pertanyaan Tamara telah membantu menemukan benang merah yang putus antara kami dengan pengetahuan para leluhur. Vachi memiliki andil yang besar melalui diary tersebut, sebab sebagian besar naskah yang nantinya akan kami bawakan merupakan hasil dari tafsir dan rangkuman yang dikerjakan oleh Vachi. Akan tetapi, lagi-lagi disini kami diberikan keleluasaan. Tamara menyampaikan bahwa kami diperbolehkan mengubah naskah sesuai keinginan kami, pun diperbolehkan tetap mengikuti arahan dari Vachi.
Tentu hal ini kami lihat sebagai kesempatan besar untuk bebas berkreasi. Kebebasan yang diberikan Tamara pada kami menjadi ruang yang sangat aman untuk berkisah tanpa merasa disudutkan dan dihakimi.
Pergolakan Ego
Ada satu hari dimana kami bertujuh merasa kelelahan dan gagu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Hendak mengatakan A tapi justru yang terucap malah B. Belum genap satu bulan tinggal di satu atap yang sama, tiba-tiba kami mengalami menstrual synchrony. Siklus menstruasi kami terjadi secara berurutan dan bersamaan. Pengalaman ini menyadarkan saya, bahwa ternyata kekuatan hormon ini bukan main dampaknya. Tepat pada hari itu, kami bertengkar hebat dengan bahasa masing-masing. Rasanya kami sungguh muak dengan bahasa Inggris dan saya rindu ngomong leluasa dengan Bahasa Jawa. Saya hanya bisa menahan tangis dan sulit menghubungi orang rumah juga kerabat dekat, sebab kami dipisahkan bukan hanya oleh jarak tapi juga oleh waktu. Perbedaan waktu antara Indonesia dengan Uruguay hampir setara setengah hari, yakni 10 jam. Alhasil yang bisa saya lakukan hanya mengendapkan seluruh emosi dan yang kami lakukan di keesokan harinya adalah mencoba mengevaluasi. Masih terjerat rasa khawatir, sebab proses karya belum sepenuhnya selesai dan belum bisa diukur setara setengah jalan. Apa yang kira-kira bisa dilakukan setelahnya?
Pada akhirnya, kami mencoba mengendurkan intensitas latihan. Bahkan kami juga mencoba untuk tidak memaksakan berkomunikasi, kalau memang tidak berkenan berbicara pun tidak masalah. Kami juga mulai mewajarkan berkomunikasi lewat google translate dan membiasakan diri mengucapkan bahasa Inggris namun dengan logat masing-masing alias logat medok. Mungkin ini terdengar konyol, tapi cara tersebut justru membantu kami pulih dari kewalahan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Hingga pada akhirnya, karya Sea of Silence sedikit demi sedikit mulai terlihat wujudnya. Struktur karya ini kami susun dalam 4 bagian; The Calling, The Ask for Permission, The Offering dan The Circle.
Tur Montevideo, Avignon, Berlin, Santiago dan Concepción
Tur pertama dipentaskan pada festival Teatro Solis di Montevideo. Membutuhkan waktu selama kurang lebih 6 jam untuk berpindah dari Rivera ke Montevideo. Cuaca dingin yang ekstrem tidak menggetarkan upaya untuk mempersembahkan Sea of Silence secara totalitas. Kami mementaskannya selama dua hari, 25-26 Juni 2024. Tiket terjual habis, sementara itu mayoritas penonton perempuan memeluk kami dengan masih terisak-isak setelah selesai pementasan. Saya rasa, karya ini bukan hanya sedang membicarakan omong kosong belaka. Ada banyak hal besar dan magis dibalik hingar bingar Sea of Silence yang perlu kita kupas lagi bersama-sama.
Tur selanjutnya kami pentaskan pada acara Festival d’Avignon di Perancis. Kami tampil sebanyak lima kali, mulai dari tanggal 4,5,6,8 dan 9 Juli 2024. Cukup banyak kerabat yang mengelu-elukan festival tersebut yang usianya lebih tua dari usia kemerdekaan bangsa Indonesia. Bertolak belakang dengan pengalaman kami di Montevideo yang dibanjiri pujian, justru di Avignon kami mendapat banyak sindiran. Setiap selesai pentas, kami menyempatkan diri untuk membaca artikel mengenai Sea of Silence. Kebanyakan jurnalis menuliskan komentar pedas dan terkesan dingin. Kira-kira nukilannya seperti ini “Tujuh perempuan pemarah menyuarakan kisah tentang lautan yang diam, tapi sepanjang karya tak ada satupun yang betah diam. Lebih mirip seperti karya musikal ketimbang rangkaian ritual.” Bukannya merasa pundung, justru kritik tersebut berhasil menyulutkan kobaran semangat kami untuk tetap ngeyel menyuarakan kisah para perempuan.
Setelah berjibaku dan menikmati indahnya Kota Paus di Avignon, kami pulang ke negara masing-masing. Sembari masih mengerjakan penelitian, kami terus menggali informasi yang barangkali bisa menjadi tambahan data untuk bekal di tur selanjutnya. Dan benar saja, setiap kali pentas, Sea of Silence selalu mengalami perubahan. Meski masih menggunakan struktur yang sama, namun wujud karya kami selalu berubah. Mulai dari teks, nyanyian hingga gerakan. Ini menjadi semacam karya yang hidup bagi saya, karya ini ikut bertumbuh dan berkembangH bersamaan dengan cara berpikir kami.
Persinggahan berikutnya adalah festival Tanz im August di Jerman pada tanggal 16-17 Agustus 2024. Sedikit berbeda dengan tur-tur sebelumnya, festival ini khusus dihadiri oleh para penari dan koreografer dari seluruh dunia. Tidak hanya itu, yang membedakan dengan tur yang lain adalah saya memberikan kado berupa persembahan Tari Gambyong Pareanom setelah pementasan di hari kedua. Sejak awal, sebelum berangkat ke Berlin saya sengaja meminta izin pada Tamara dan Ricardo Carmona selaku Direktur Artistik untuk membawakan tari tersebut yang sering saya tarikan setiap malam tirakatan di desa tempat saya tinggal. Kado tersebut adalah keputusan politikal saya dalam menghadapi pergulatan tradisi dengan komoditi. Di sisi lain, ini adalah kebiasaan yang diturunkan oleh Bapak. Bapak saya selalu berpesan bahwa kemanapun saya menjelajah, sempatkan waktu membawa tradisi sebagai rumah. Tak ayal, orang tua saya adalah panutan dan inspirasi nomor satu bagi saya.
Panutan saya yang lain juga kebetulan berada di festival yang sama. Saya masih starstruck jika mengingat bahwa Meg Stuart, Mette Ingvartsen, dan Jérôme Bel juga mementaskan karyanya di Tanz im August. Sayangnya, saya tidak dapat berjumpa dan menyaksikan karya mereka sebab waktu pementasan kami jatuh di hari yang berbeda. Karya-karya Meg Stuart, Mette Ingvartsen, dan Jérôme Bel sangat berpengaruh dalam proses berkarya saya selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Itulah mengapa saya sedikit menyesal tidak mengambil resiko perpanjangan hari untuk singgah lebih lama, namun penyesalan saya tidak berarti jika dibandingkan dengan rasa syukur yang ada. Di Jerman, saya merasa diberi suntikan semangat lebih untuk bisa memaksimalkan peluang di masa yang akan datang. Terlebih lagi setelah bertemu dan mengenal banyak rekan dari mancanegara yang juga sedang berjuang bersama.
Tur terakhir kami terjadi berada di Chili, menghadiri festival di dua kota berbeda pada pertengahan bulan Januari 2025. Festival pertama yang kami hadiri digadang-gadang sebagai festival terbesar di Amerika Latin, yakni Teatro a Mil di Santiago. Sementara festival di kota yang lain adalah Teatro Blibli di Concepción. Pementasan di dua kota ini sungguh berkesan bagi saya. Ini adalah pertama kalinya perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), orang Indonesia menyaksikan Sea of Silence. Rizkita Murwani mengaku sangat tersentuh ketika saya membawakan monolog berbahasa Indonesia dan Jawa. Setelah cukup lama bertugas di manca, akhirnya Ia kembali mendengar lantunan Gugur Gunung yang sedikit digubah liriknya. Ia merasa dibawa pulang meski hanya sebentar. Merasa suaranya terwakilkan, meski dengungnya tak cukup menggema.
Perjuangan Masih Berlangsung
Debar jantung cukup intens selama tur terakhir. Dengar-dengar, Sea of Silence akan dipentaskan lagi di beberapa waktu yang akan datang. Itu artinya hingga hari ini kami masih terus melakukan riset, mengerjakan proyek masing-masing yang entah berkaitan ataupun tidak dengan karya Sea of Silence, dan terus berkomunikasi secara jarak jauh. Barangkali masing-masing dari kami menemukan sesuatu yang menarik dan dapat dibubuhkan sebagai data baru dalam karya.
Jika diperumpamakan, Sea of Silence mirip seperti kain yang berserat. Serat antar serat saling menyatu membentuk benang. Benang antar benang saling berkelindan hingga terjahit rapih. Antara teks kuna, mitos, legenda, nyanyian, tarian, seni peran, gestur, sejarah keluarga, mars kemerdekaan negara semua terjahit hingga menjadi busana yang kemudian turut membentuk identitas kami. Sea of Silence saya hayati sebagai lautan yang berusaha menceritakan kilatan jalinan kisah. Lautan yang menghubungkan benua lewat duka dan perjuangan, khususnya melalui perjuangan perempuan. Perjuangan yang harapannya di kemudian hari dapat meruntuhkan tebalnya dinding sekat bahasa dan diluluhkan melalui tutur bahasa rasa.

Dokumentasi profil akun Instagram Sinekar (2023)

Dokumentasi milik pribadi karya Fatamorgana (2023)

Dokumentasi milik Sekolah Seni Tubaba karya Splinter of an Age (2023)

Dokumentasi karya Sea of Silence di Festival d’Avignon (2024)

Dokumentasi karya Sea of Silence di Tanz im August (2024)

Dokumentasi karya Sea of Silence di Concepción
*Sekar Tri Kusumo bergabung dengan Studio Plesungan Dalam program tari & performance art. Dan peserta Ruang-Antara, program menuliskan ingatan dan pengalaman.