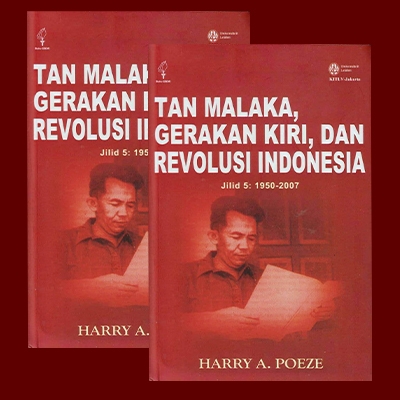“Rumput-Rumput Danau Bento”: Fakta Rawa, Fiksi Danau
Tiga Drama Kuntowijoyo (1)
Oleh : Seno Gumira Ajidarma
Naskah drama Kuntowijoyo yang terbenam sejarah, manuskripnya bermukim di PDS HB Jassin, TIM, Jakarta. Pertama dari tiga drama Kuntowijoyo yang dibaca ulang dan diperbincangkan kembali, dalam proyek mandiri, Susastra di Bawah Radar, untuk menggali gubahan tersembunyi. Dalam “Rumput-Rumput Danau Bento”, fiksi menjadi informasi praktis yang melengkapi fakta.
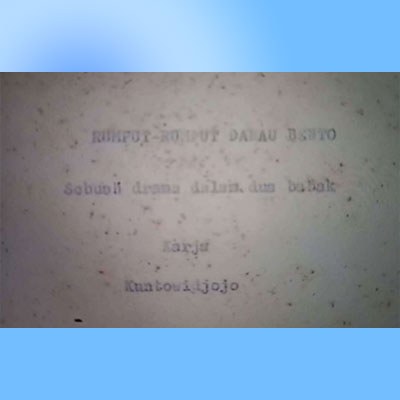
Ketikan kabur pada manuskrip asli “Rumput-Rumput Danau Bento” di PDS HB Jassin, TIM, Jakarta.
Catatan tentang drama Kuntowijoyo (1943-2005), “Rumput-Rumput Danau Bento”, yang naskahnya mendapatkan Hadiah Harapan dalam Sayembara Penulisan Lakon Badan Pembina Teater Nasional Indonesia pada 1969, saya coba untuk dimulai dengan pengenalan tentang Danau Bento itu sendiri, sebagai latar yang menentukan segenap peristiwa di dalamnya.
Rumput Bento, Rumput Air
Danau Bento bukanlah danau, melainkan rawa yang tertutup rerumput bento, karena merupakan rumput air atau semi-akuatik, dan bagian batang dapat mengapung di air. Air rawa ini tawar, dari dekat airnya hitam pekat, selain terdapat yang berwarna kuning dan merah. Airnya berbau lumpur, karena rumput bento tua yang mati akarnya membusuk, dan mengeluarkan bau tertentu. Endapan air tidak mengalir deras, membuat air mengendap bersamaan ke tanah yang akhirnya menjadi lumpur dan menghasilkan bau khas.
Sekarang ini Danau Bento lebih ditegaskan namanya sebagai Rawa Bento. Letaknya di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, di hadapan Gunung Kerinci. Nama “danau” itu didapat dari penduduk setempat, karena jika dipandang dari ketinggian Gunung Kerinci, tampak seperti danau yang diapit Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, dan Gunung Sangka. Selain disebut seperti mangkuk, tampak juga hutan basah dikelilingi rerumputan bento menghijau, ditengahnya terlihat jalur sungai tertutupi bento.
Disebutkan pula, Rawa Bento dulunya adalah danau sebelum pendangkalan mengubahnya jadi rawa. Terdapat dua danau lain, Danau Undan (undan = belibis; bahasa Siulak di Kerinci) dan Pusat Danau. Sekitar tahun 2010 kedua danau ini masih terlihat, tetapi rumput bento yang terus merambat membuat danau-danau ini tertutup oleh bento.
Rumput itu meluas ketika penduduk menebang pepohonan untuk membuat sawah, yang toh gagal karena kedalamannya menyulitkan tanam padi. Waktu hujan tanah menjadi cair, menghanyutkan padi, dan merusak panen. Kini anak-anak gembala membawa sapi dan kerbaunya ke situ.
Danau Bento disebut ‘mento berayun’ ketika tekstur tanah yang diinjak memberi kesan berjalan di atas air, karena Danau atau Rawa Bento sebetulnya merupakan air sungai yang terbentuk dari sungai-sungai kecil yang mengalir, berkumpul di sebuah titik dan membentuk danau yang mengalirkan air itu dari bawah, menjadi sungai bawah tanah. Maka ketika menginjak tanah di Rawa Bento, akan terasa berjalan di atas karpet yang di bawahnya air.
Itulah lapisan yang disebut bisa menahan berat pohon dan rerumputan bento, termasuk mampu menahan berat beban manusia. Kerbau juga bisa berjalan di atasnya. Terdapat empat lapisan di sana: (1) air dan lumpur; (2) lumpur dan tanah; (3) rerumputan bento; (4) hutan berbagai pepohonan (
https://www.kompasiana.com/meizizan1190/61c32c6b7a6d886264049423/danau-bento-serta-keunikannya & https://id.wikipedia.org/wiki/Rumput_banto).
Fiksi yang Melengkapi Fakta

(Z Creators/Taufiq Hippy) https://travel.indozone.id/news/951269888/aneh-banget-ada-rawa-berada-di-atas-ketinggian-view-nya-mirip-sungai-amazon- Danau atau Rawa Bento yang terlihat seperti aliran sungai, latar drama “Rumput-Rumput Danau Bento” Kuntowijoyo.
Gambar di atas adalah satu di antara banyak gambar dari yang silih berganti disebut Rawa Bento atau Danau Bento, tetapi saya pilih yang paling mendekati situasi misterius, seperti terungkap dari drama Kuntowijoyo. Gambar-gambar lain, yang cenderung menampilkan ‘keindahan turistik’ warna-warni, dapatlah saya katakan berpeluang besar membatalkan imajinasi yang mungkin terbangun saat membaca “Rumput-Rumput Danau Bento”. Naskah yang penulisannya berdata tempat dan tanggal: Jogjakarta 16-1-1966.
Dalam hal saya, beruntung naskahnya saya baca lebih dulu sebelum menengok berbagai penjelasan ensiklopedis, yang membantu pemahaman latar, dan menyaksikan foto-foto turistik, yang menggugurkan imajinasi, walau saya bisa mempertahankannya. Tentu tidak ada ketentuan, mana yang mesti diikuti: baca fiksi dulu, lantas baru faktanya; atau tengok dulu fakta, sebelum membaca bagaimana akan difiksikan.
Kuntowijoyo sendiri menuliskan catatan pada naskah: Danau Bento terletak di daerah Kerintji, sebelah utara Kota Sungai Penuh. Bento ialah sedjenis rumputan jang tumbuh di atas air.
Jadi terdapat suatu dasar faktual. Dalam dua babak, masing-masing tiga dan dua adegan, melalui Inah, mantu baru dalam keluarga suaminya, Ujang, yang tampaknya serumah dengan Ibu dan Ayah, dikisahkan kecelakaan berbalut mitos yang nantinya akan membunuh Ujang dan Ayah.
Itu satu keluarga. Keluarga lain yang suka muncul ke rumah itu adalah Maryamah, Abang Maryamah, Suami Maryamah. Setelah Ujang tewas, Abang Maryamah menjadi suami Inah. Di luar kedua keluarga ini ada Lelaki Tua, yang tampak seperti peran penting penggenggam rahasia masa lalu: bahwa anak-anak dan istrinya sendiri pun lenyap ditelan rumput-rumput Danau Bento, yang kemudian juga melenyapkan Ujang dan Ayah.
Pemburu I dan Pemburu II adalah peran-peran kecil yang bukan tidak penting (“Tidak ada peran kecil,” kata Stanislavsky, “yang ada hanyalah aktor bertubuh kecil.”), untuk memberi gambaran dari luar rumah tempat para peran ini melakukan cakapannya; serta Jubah Hitam, kawan bercakap di dalam dunia batin Inah–yang rupanya pencabut nyawa, tapi bukan malaikat, melainkan penculik ruh dari kerajaan gaib. Bersamanyalah terdapat peluang berpuisi. Mereka yang tanpa cakapan dinamakan Orang Banyak dari Bawah.
JUBAH HITAM
Aku datang lagi, Inah!
INAH
(tak bergerak)
Kenapa kau datang lagi, pedagang nyawa
Bukankah masih terlalu pagi?
Matahari sedang tenggelam
Daun pun tak bergoyang,
Bulan terbaring di balik awan hitam
Embun tergantung di puncak pohonan
Dengan apa kau berjalan kalau bukan dengan awan
Dengan apa kau terbang kalau matahari tak bersinar
Dengan apa kau hinggap kalau ranting pun masih terlelap
Dengan apa kau turun kalau belum tetes si embun
……………………………………………………….
JUBAH HITAM
Di mana-mana di bumi ini sama. Di bukit ini atau di mana saja.
Bila aku telah datang, seorang di antara kalian yang di sini
harus mengikuti aku pergi. Di sebuah kerajaan yang tak jauh
dari bukit ini, seorang menteri memerlukan bujang lelaki
untuk mengurus kudanya.
INAH
Tapi aku tak menjual suamiku.
JUBAH HITAM
Sama saja. Dia akan kutangkap dan kumasukkan dalam saku.
Lalu terbang mendekati langit pagi dan kembali.
INAH
Tidak, tidak.
(Tetapi Jubah Hitam terus saja hendak memasuki rumah itu, dan Inah berteriak, masih di atas kursi)
Pergi! Pergi!
(Terbangun. Jubah Hitam telah lenyap dalam gelap)
IBU
(Ke serambi)
Inah! Kau bilang apa?
INAH
Ibu. Dia datang lagi, Ibu.
IBU
Siapa yang datang?
INAH
(tersadar)
Oh, tak seorangpun Ibu.
IBU
Kau mimpi buruk lagi?
INAH
Ya
Dalam teori tentang mimpi, Freud menyebutkan bahwa mimpi adalah via regia atau jalan utama yang mengantarkan manusia ke ketaksadaran, sebagai fenomen psikis yang normal. Mimpi adalah produk psikis, dan bagi Freud hidup psikis adalah konflik antara daya-daya psikis, sehingga mimpi dimengerti sebagai perwujudan konflik. Maka, apabila mimpi dianggap realisasi keinginan, dirumuskan oleh Freud bahwa mimpi adalah cara berkedok untuk mewujudkan suatu keinginan yang direpresi. Inilah fungsi mimpi untuk melindungi tidur manusia.
Namun Inah bermimpi sampai terbangun (arousal-dreams). Ini berarti faktor-faktor dari luar, pengganggu mimpi terepresi yang semestinya terintegrasi, sudah terlalu kuat, lepas dari sensor Ego, menjadi mimpi cemas atawa mimpi buruk (Bertens 1979, xx-xxi). Dengan catatan bahwa mimpi adalah produk ketaksadaran, faktor-faktor dari luar macam apakah yang telah mengganggunya? Memang Inah bukanlah manusia-nyata, tetapi psikoanalisa sudah lama tersahihkan dalam kajian susastra, sebagai produk imajinasi yang terbandingkan dengan kerja mimpi (dreamworks).
Kini fakta-fakta geografis Danau Bento itu berguna, justru karena fiksi berformat lakon ini menyampaikan peristiwa yang berlawanan. Alih-alih lapisan rumput bento itu disebut mampu menahan kerbau dan pepohonan, justru di musim kering lumpur rawa menyedot manusia yang lewat di atasnya–ini menjadi fakta dalam fiksi, yang rupanya diperbincangkan sebagai mitos.
Kuntowijoyo mengungkapnya secara bertahap, yang dalam kategorisasi Netflix dapat tergolong sebagai slow burn: lambat tapi mencekam.
Mitos di Atas Kampung
Adegan Pertama dari Babak Pertama, selain Inah seperti yang sudah disebutkan, juga memperkenalkan Ujang, suami yang ternyata lebih lama tinggal di kota, yang ditunjuk sebagai berada di bawah; sementara danaunya tersebut berada di atas. Ujang rupanya termakan mitos kejantanan bahwa menjadi lelaki sejati kampung itu, berarti mampu menggunakan senapan untuk berburu rusa ke atas, ke hutan Danau Bento.
Mitos ini diperteguh Ayah, tapi dipersoalkan Ibu, karena bagi Ibu lelaki yang baik peduli ketakutan istrinya. Kekhawatiran Inah telah membuatnya bermimpi buruk, tetapi Inah sendiri siap melebur dengan kehidupan di gunung itu sepenuhnya. Maryamah mengajarinya untuk mengenal alam di kampung itu, yang eksotik, romantik, dan serba ideal, meski gelap jika malam; dalam penghadapannya dengan kota di bawah yang serba gemerlapan.
Aneka jenis burung, sangat banyak rusa, dan lingkungan alam muncul dalam cakapan para peran. Pada akhir Adegan Pertama, pergilah Ujang membawa senapan dan menghilang. Ayah masih terus menipu diri, bahwa Ujang akan kembali membawa rusa, karena Ujang adalah warga kampungnya. Dalam kenyataannya Ujang baru kembali dua minggu dari kota.
Dalam Adegan Dua, pada hari siang, dipercakapkan Ujang yang belum pulang. Dianggap wajar karena berburu rusa bisa lama, dan diyakinkan pasti pulang karena rusa ratusan banyaknya di sekitar danau di atas gunung itu. Hanya orang kampung itu yang tahu, karena kampung-kampung di bawah terlanjur menganggap danau itu keramat.
Dipercakapkan juga tentang Lelaki Tua, yang tinggal di tepi Danau Bento itu. Ia disebut berada di antara keramat dan gila, tetapi dihormati sebagai orang tua paling memahami dan setia berjaga. Saat semua orang meninggalkan kampung, karena banyaknya binatang yang turun mengganggu ketenangan, dengan senapan di tangan ia siap menembak harimau jika menerkam. Usianya lebih tua dari kampung itu, walau anak-anaknya tak mau tinggal di sana–meski sebetulnya ditelan danau itu sendiri.
Maryamah meyakinkan Inah bahwa lingkungan alam mereka jauh lebih aman dari kota. Namun Inah mengkhawatirkan Ujang yang belum pulang. Lantas muncul Lelaki Tua. Semestinya ada yang luar biasa jika dia turun gunung, tetapi dia hanya mau bicara dengan Ayah, yang disebutnya Ujang Tua. Ya, dia telah bertemu dengan Ujang yang bermaksud memburu rusa. Telah diperingatkannya agar tidak melampaui batu-batu penunjuk jalan yang telah diatur.
Lelaki Tua itu menjelaskan fakta Danau Bento, bahwa yang selama ini mungkin mereka kira daratan berumput dan berhutan, di bawahnya terdapat air, tempat binatang-binatang dan keluarganya terperosok tak bisa diselamatkan lagi. Ujang ternyata tak peduli, masuk hutan di luar batas batu-batu itu dan belum kembali lagi. Akhirnya Ibu, Maryamah, dan Inah yang serba khawatir terlibat juga perbincangan itu.
Semula Maryamah dan Ayah masih percaya, bahwa Ujang sebagai warga kampung mereka akan selamat. Semula tampak seseorang mendatang seperti Ujang, tetapi ternyata Suami Maryamah yang baru datang dari kota, yang asyik sendiri berkisah tentang menaikkan harga kopi hasil panen mereka. Namun kembalinya Pemburu I dan Pemburu II yang tak berhasil menembak apapun, dan juga berjumpa Ujang, membuat mereka gelisah juga. Lelaki Tua pun mengerahkan para pekerja kebun kopinya untuk mencari. Ayah menyerah pada kejujuran perasaannya, berteriak memanggil-manggil Ujang.
Kegelisahan Inah menjadi-jadi dan membuat ia berpuisi.
INAH
Ya. Di bukit itu mereka mencari,
antara semak dan pohon berduri.
Rumput-rumput melayu, mereka pun berlalu.
Kentong-kentong bertalu, mereka pun terus berlalu.
Pudarlah matahari, dan kita semua menanti.
Kembanglah melati, sebab kita semua menanti.
Mengalirlah air terus ke pematang.
Kericiknya menggema dalam petang,
mengantar matahari yang sedang tenggelam.
Ya. Matahari pun sedang tenggelam ketika merekapun datang,
bersama si Ujang (diam).
Dalam Adegan Ketiga, langit sudah merah ketika Maryamah dan Ibu berusaha meredam kegelisahan Inah yang sejak awal kedatangannya mendapat firasat buruk jika melihat burung-burung gagak, karena bisa terhubungkan secara kebetulan dengan apa saja. Termasuk banyak hal yang baik.
Namun Suami Maryamah datang, dan gelisah karena ragu apakah mesti menyampaikan kabar buruk. Lantas Lelaki Tua muncul diiringi Orang Banyak. Ia menyampaikan bahwa di hutan Danau Bento, di tempat rusa banyak sekali sedang minum, mereka temukan Ujang di bawah air saat angin bertiup kencang menyibakkan rumput. Ayah yang melihat Ujang segera masuk ke dalam air, dan saat itu pula rerumputan tersebut menutup kembali.
Ibu dan Inah menutup mukanya. Lelaki Tua dan Orang Banyak menghibur keduanya. Inah berjuang keras menerima kenyataan. Ibu pun akhirnya mencoba meredam kesedihan Inah, mereka berpelukan sebagai dua manusia yang kehilangan.
Mitos Memakan Anak Sendiri
Waktu sudah berlalu tiga tahun ketika memasuki Babak Kedua. Pada Adegan Kesatu diperlihatkan bagaimana kampung di atas perbukitan itu mengalami musim kering, melalui adegan Inah menadahkan ember di pancuran, dan hanya mendapatkan air seadanya. Dalam cakapan terlontar gagasan untuk pindah meninggalkan kampung, seandainya perbukitan itu benar-benar menjadi kering. Ibu mau pindah, tapi Maryamah dan Inah masih ingin bertahan. Dalam cakapan disebutkan pula anjuran agar Inah kembali menikah.
Lelaki Tua yang semakin tua datang dengan gagasan, bahwa jika kemarau panjang ini mengeringkan pula Danau Bento, ia bermaksud mencari, menggali, dan mengambil tulang-belulang orang-orang tercinta, anak-istrinya. Ia menganjurkan hal yang sama kepada siapapun yang kehilangan keluarganya di sana. Gagasan ini dilawan dengan pendapat, biarkanlah mereka yang hilang di danau tidur tenang selamanya di sana.
Sementara Maryamah dan Suami Maryamah tampak berusaha menjodohkan Inah dengan Abang Maryamah. Inah tidak ingin kehilangan Ibu, mertua yang bagai ibu sendiri, tetapi bersedia melakukan apapun yang akan membahagiakannya. Seperti mengharap kebahagiaan, orang-orang mengharap hujan turun minggu depan.
Adegan Kedua dalam Babak Kedua ini adalah seminggu kemudian, ketika hujan belum turun juga, dan hanya Inah yakin bahwa hujan tetap akan turun, bahkan mungkin hari ini. Maryam dan Suami Maryam sudah memantapkan keyakinan, bahwa masa depan mereka berada di kota. Ibu pun begitu, menganggap berkah kehidupan mereka di kampung itu sudah habis, padahal berkah Tuhan ada di mana-mana.
Adapun Lelaki Tua yang merasa tahu segalanya itu menganggap awan gelap bergulung di atas kampung adalah debu tanah kering yang akan mengubur mereka; katanya pula hujan tidak akan turun sebelum tulang-tulang itu diangkat, karena “Mereka yang terkubur di sana telah meminta itu.” Dianggapnya semua orang bodoh, dan mereka akan merasakan akibat seperti dialami Ujang yang tidak mau mendengar kata-katanya. Katanya mereka yang pergi memang tidak punya keberanian mengangkat tulang-tulang itu–tapi semua orang menentangnya.
Namun Abang Maryamah mengikuti Lelaki Tua ke atas, ke Danau Bento yang telah menjadi rawa kering, dan inilah kisahnya setelah muncul kembali, justru dalam keadaan basah kuyup.
SUAMI MARYAMAH
Hujan telah datang.
MARYAMAH
Abang telah pulang.
(Abang Maryamah masih terdiam)
IBU
Kenapa kau tak segera kemari. Berhenti di pagar?
ABANG MARYAMAH
Danau itu telah meminta seorang korban lagi Ibu.
SUAMI MARYAMAH
Ya, rusa yang kehausan telah kembali dan mandi di danau itu.
ABANG MARYAMAH
Tidak.
MARYAMAH
Apa?
ABANG MARYAMAH
Ketika itu hujan belum turun di puncak. Kami sudah sampai di tepi danau. Kulihat danau itu kering bagai jurang yang menganga. Di tangan Kakek tergenggam cangkul. Di muka kami, ya Tuhan. Berpuluh tulang berserakan. Binatang dan manusia. Betapa banyak mereka yang jadi korban danau itu, yang bening dan indah tapi seram dan menakutkan.Kakek mengajakku turun. Dan kami pun turun, ke danau itu. Tetapi awan di atas semakin tebal. Hujan mulai datang.
Hujan makin deras. Dan kami masih dalam danau itu. Kami mengumpulkan tulang. Kakek bekerja sangat keras. Baru sekali ini dalam hidupku kulihat seorang lelaki yang begitu keras dan bersemangat. Ia lebih keras dari gajah yang mabuk. Di wajahnya kulihat selembar kekerasan yang tak akan dapat dilunakkan. Dia bekerja dan bekerja. Tapi hujan makin deras. Dan air telah mulai masuk ke danau itu. “Air sudah mulai masuk, Kakek,” aku berkata. Tetapi dia di matanya terpancar kekerasan tak terkalahkan. Ia tak mendengarkan. Dan air pun mulai masuk lagi. Ia sudah tidak mau lagi mendengarkan aku. Dan, ya Tuhan. Dia mengancam akan membunuhku dengan cangkul itu kalau aku tak mau berhenti mengingatkan dia tentang hujan itu. Aku sudah mulai takut, sebab air sudah terasa di kaki. Sekali lagi kuperingatkan Kakek tentang hujan itu. Tapi ia menatapku dengan pandangan iblis, matanya menyala dalam air hujan itu. Tiba-tiba aku berniat untuk memukulnya dan kemudian membawanya naik. Kami bertengkar. Tetapi ia membawa senjata itu. Dan aku dikejarnya. Ya Tuhan, dalam matanya terpancar kebencian yang luar biasa. Baru sekali ini aku melihatnya. Hujan semakin deras. Air mulai naik. Dan aku ingat kalian yang di sini, yang sedang menantikan dengan kecemasan. Kakek itu tak ingat siapapun lagi, kecuali tulang-tulang itu. Dia mengatakan, tulang-tulang itu adalah keluarganya dan akan mengangkatnya kembali.
Tetapi kemudian terjadilah apa yang kutakutkan. Kami tak dapat berdamai lagi, aku ketakutan oleh Kakek yang mulai marah. Dia telah gila. Dan ketika air benar-benar telah masuk ke danau aku berusaha untuk menariknya. Tapi dia berkeras, dan aku berusaha untuk menyelamatkan diri. Ketika aku sudah sampai di atas tepi danau, aku memandang ke danau yang telah dibanjiri oleh air yang deras.
Aku menunggu Kakek di atas, tapi ia tak muncul. Rumput-rumput bento itu telah kembali menjadi kekuatan yang dahsyat. Kakek tak akan dapat muncul lagi.
(Semua tertunduk menyambut kesedihan itu. Air hujan mengalir dengan tenang. Berbisik dengan sepi mengiringi kesedihan mereka).
Sudah jelas para peran itu tidak pernah pindah ke kota, dan Ibu yang sebetulnya mertua Inah mengakhiri lakon dengan menyebut Abang Maryamah anak-menantu.
Fiksi Faktual di Ruang Drama
Membandingkan kembali fakta Rawa Bento, bahwa “ketika menginjak tanah di Rawa Bento, akan terasa berjalan di atas karpet yang di bawahnya air”, dengan fiksi yang berkisah tentang tulang-belulang orang-orang dan binatang di bawah rerumputan Danau Bento, dapatlah diperkirakan bagaimana tanpa fakta ilmiah Rawa Bento suatu ketika pernah diterima sebagai mitos danau keramat.
Deskripsi tentang keunikan Rawa Bento sebagai tujuan wisata tidak menyebutkan sama sekali kemungkinan terperosok ke dalam air, untuk kembali tertutup lapisan rumput. Selain karena bentuk wisatanya lebih tampak berperahu, data atas bahayanya, yang berkemungkinan mengurangi potensi kedatangan wisatawan, tentu tidak dipandang perlu.
Tanggal akhir penulisan Kuntowijoyo, 16 Januari 1966, mengandaikan proses kreatifnya (mendengar, melihat, membaca, memikirkan, membayangkan, mengolah, dan tentu juga mencatat-tuliskan) berlangsung sebelumnya, 1965, dan mungkin saja jauh sebelumnya. Saat cerita yang sampai kepadanya adalah bahan obrolan dari mulut ke mulut setengah mapan, berdasar fakta hilangnya orang, yang berkemungkinan telah menjadi susastra lisan, dengan bumbu mitos kekeramatan bagi gejala-gejala alam.
Cara Inah berkisah tentang burung-burung gagak yang membawa firasat buruk, atau bual Lelaki Tua tentang hubungan benar dan salahnya manusia dengan gejala alam, dapat dibaca sebagai prosedur yang dilalui kreasi susastra lisan kolektif, sebelum menjadi semacam mitos.
Namun berdasarkan fakta sifat alamiah rumput bento dan fakta terdapatnya mitos, fiksi Kuntowijoyo tidak mengukuhkan mitos itu melainkan menggugurkannya, tanpa melepaskan peluang menghadirkan mitos itu sebagai besutan (peng-gaya-an, stilistika) susastra, dalam hal ini naskah drama.
Sebagai naskah drama, Kuntowijoyo menuliskan LAYAR dalam pergantian babak, tetapi sepanjang naskah ini tidak terdapat didaskalia (teks apapun dalam naskah yang tidak diucapkan peran), seperti tata lampu atau bentuk rumah, sehingga keterbacaan naskah ini lebih seperti film, karena realisme tekstual prosaik yang menyeruak seni pentas seperti pembuka Adegan Satu Babak Kedua berikut:
Fajar kemerahan di timur, di rumah yang dulu juga. Tapi rumah itu sudah sangat tak terpelihara. Rumput-rumput tinggi dan lumut tampak di tempat yang mungkin. Tapi semuanya tidak hijau. Musim kemarau yang panjang. Inah, yang bertambah kurus, keluar dari rumah dan menatap fajar. Suara lambat dari adzan di kampung bawah terdengar. Ia berhenti untuk menikmati. Pagi itu, sudah tiga tahun ia tinggal di bukit. Di pancuran, air tidak mengalir. Musim yang kelewat kering.
Satu-satunya petunjuk yang mengikatnya ke panggung–meski tanpa petunjuk spesifik–adalah semua adegan bermain di halaman rumah Ibu, tempat setiap peran lewat atau mampir ke sana. Lokasinya memang tersebutkan, berada di antara “danau di atas” dan “kampung di bawah sana”, yang terhubung ke Kota Sungai Penuh dengan oplet.
Dalam konteks tahun penulisan yang berakhir pada awal 1966, drama “Rumput-Rumput Danau Bento”, melalui cakapan segenap peran, dapat diikuti suatu situasi yang dibentuk oleh lokasi, atau lebih tepat ruang tempat mereka berada.
Ujang memang dilahirkan di sana, tetapi masa tinggalnya yang lama di kota telah membuatnya tak mampu berburu rusa, bahkan pengabaiannya atas petunjuk Lelaki Tua berakibat fatal.
Lelaki Tua yang juga kehilangan anak-anak dan istri di danau, menjadi personifikasi keterbentukan mitos, yang begitu rapuh berhadapan dengan gejala alam faktual, sehingga mitosnya disesuaikan ketika gejala alam berubah–tetapi justru dirinya secara ironis menjadi korban gejala alam yang berubah-ubah itu.
Inah bukan dari kampung itu, bahkan dari kota, berjuang mengakrabkan diri ke dalam hidup baru, dengan segenap daya yang dimilikinya. Dalam segenap kelemahannya, ketulusan dan kesetiaan kepada kampung barunya tetap berlandaskan nalar, yang sangat dibutuhkan pada saat kritis menghadapi mitos.
Ayah, Ibu, Maryamah, Suami Maryamah, dan Abang Maryamah adalah mereka yang dengan caranya masing-masing berjuang menghadapi kuasa mitos.
Ayah menjadi korban, setelah membiarkan Ujang berburu di danau, hanya berdasarkan mitos.
Ibu, yang semula dikuasai mitos disadarkan gejala alam faktual, bahwa manusia boleh berubah dan pindah.
Keluarga Maryamah, walau juga mengetahui mitos danau dan tenteram hidup di kampung, sebagai pekebun kopi selalu siap untuk pindah, walau gejala alam akhirnya memberi alasan untuk tetap tinggal dan bahagia di sana.
Lakon ini jelas merupakan representasi modernisme dalam penempatan mitos, yang ditunjukkan kedudukannya dalam keberhadapan dengan gejala-gejala alam faktual, sebagai konstruksi pemikiran yang sudah selesai. Dalam panggung cerita antara danau mitologis dan kota sekuler, diperlihatkan dilema manusia di antara kedua kutub tersebut.
Hubungan antarmanusia di dalamnya membentuk drama, dengan kausalitas yang didorong keberadaan Danau Bento, kini Rawa Bento, ketika rumput-rumput bento dapat menjebak siapapun yang tak waspada, untuk terperosok ke dalamnya.
Susunan dialog sebagai naskah yang dibaca, sebagaimana susastra, mengungkap kesunyian sebuah dunia berkabut, dengan jalan setapak di kejauhan yang mendaki ke arah danau keramat, dalam suara cakapan berlagu, diseling bunyi pancuran, timba di sumur, angin dingin, alunan azan, dengan monolog puitik sesekali.
Itulah suasana “Rumput-Rumput Danau Bento”, gubahan Kuntowijoyo ketika masih berusia 22 tahun.
————
SENO GUMIRA AJIDARMA
Partikelir