Senirupa Kita yang Tidak ke Mana-mana
Oleh: Syakieb Sungkar
Tentang 4 Artikel Seni Rupa di Kompas
Esai ini ingin merespon 4 artikel di Kompas Minggu yang saling berbalas-balasan satu sama lain. Pada mulanya adalah tulisan Aminudin TH Siregar yang berjudul “Takjub Ajoeb: Kepada Bung Hendro Wiyanto”. Pada prinsipnya Aminudin mengemukakan bahwa infrastruktur senirupa kita tidak mengalami perkembangan yang berarti. Orang Indonesia gagal paham tentang senirupa, debat senirupa tanpa ujung soal definisi dan mabuk pengakuan internasional tetapi jago kandang. Kita kurang sejarahwan, kritikus dan teks kuratorialnya jelek. Menurut Aminudin kita membutuhkan suatu “historiografi penyadaran”, yaitu penulisan sejarah yang lebih progresif yang menganalisis arsip secara baik sehingga memahami senirupa bangsa sendiri. Aminudin mengingatkan tentang tulisan Joebar Ajoeb yang mengatakan senirupa Indonesia cenderung menggerhana, yang telah melupakan Soekarno, sebagai seorang kolektor senirupa terkemuka. Setelah Soekarno, pembangunan infrastruktur senirupa tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur lainnya.
Kemudian Aminudin ingin memperkuat argumen Joebar Ajoeb itu dengan mengedepankan lukisan “Maka Lahirlah Angkatan 66” karya S. Sudjojono dan “Mentari Setelah September 1965” karya AD Pirous, yang masing-masing dibuat tahun 1966 dan 1968. Lukisan itu kemudian diberi komentar oleh Aminudin bahwa nampaknya Sudjojono sedang memberi pesan bahwa “ada yang nggak beres dalam proses kelahiran Angkatan ‘66”. Sementara untuk lukisan Pirous itu, Aminudin mengutip Astri Wright bahwa lukisan ini adalah reaksi atas iklim keheningan dan ketakutan terkait ingatan menyakitkan tentang pembantaian. Lukisan ini “mempersoalkan situasi di masa itu”. Namun pada penutup tulisan, Aminudin mengutipkan tafsir Kenneth M George yang berbeda atas lukisan Pirous itu. Menurutnya lukisan itu justru mensyukuri kemerdekaan individu dan menyambut era keterbukaan seni.

Lukisan Sudjojono “Maka Lahirlah Angkatan 66”
Seminggu sesudahnya, muncul tulisan Hendro Wiyanto yang menanggapi tulisan Aminudin itu. Menurut Hendro, Aminudin itu gemar membuat daftar masalah yang sudah berulang-ulang disemburkan orang di mana-mana. Hendro menyarankan untuk Aminudin “berhenti ngedumel melulu”. Kalau Aminudin mengatakan – melalui Ajoeb – bahwa senirupa Indonesia telah melupakan Soekarno, maka menurut Hendro selera estetik Soekarno berhenti hanya sampai lukisan-lukisan Basoeki Abdullah. Soekarno bahkan tidak paham corat-coret lukisan Affandi yang makin ruwet sesudah 1950-an. Seharusnya kita mewarisi wawasan estetik dan politik Soekarno dengan cara yang lebih pintar. Ketimbang Soekarno, Hendro lebih tertarik kepada Affandi yang merupakan “manusia baru Indonesia”. Dan Hendro menuduh Aminudin telah melakukan ankronisme sejarah yang menjadi penyebab ia melihat senirupa Indonesia mengalami gerhana.
Kalau Ajoeb berasyik-ma’syuk dengan Soekarno dan karya-karya seniman-seniman di zaman Orde Lama, serta merendahkan “prestasi” seniman Orde Baru yang katanya “belum memadai”. Maka Hendro mengingatkan ada Semsar Siahaan yang mengecam keras guru-gurunya sendiri dan melawan otoritarian Orde Baru. Ada yang kurang lurus antara peminjaman Aminudin atas pemikiran Ajoeb yang mengecam estetisme Orde Baru sehingga timbul gerhana, dan upaya memajukan sebuah lukisan Pirous yang juga produk Orde Baru. Di mana menurut Wijaya Herlambang justru karya-karya seperti itu mengafirmasi kekerasan. Menurut Hendro, tidak akan ada kurator yang berhasrat menulis “historiografi penyadaran” dalam pengantar pameran di galeri orang berduit. Lagi pula “historiografi penyadaran” bukan satu-satunya jalan dalam penulisan teks sejarah. Dalam penutup tulisan Hendro itu, ia menambahkan bahwa Aminudin bukan hanya telah melakukan anakronisme tetapi juga gagal paham sejarah.
Selanjutnya Yuswantoro Adi ikut nimbrung menanggapi pada minggu berikutnya. Berbeda dengan Aminudin, Yuswantoro melihat infrastruktur seni kita tidak sebegitu menyedihkan. Selain Soekarno, Suharto ternyata seorang kolektor yang membangun Graha Lukisan TMII. Dan SBY memesan lukisan kepada beberapa pelukis serta memajangnya pada Balai Kirti di Istana Bogor. Demikian pula Jokowi suka membeli lukisan, salah satunya adalah lukisan Djoko Pekik yang nantinya akan dipajang di ibu kota baru. Museum-museum swasta juga dibangun seperti Museum Pelita Harapan, Macan, OHD, Dedi Kusumah, dan Tumurun.¹ Nasirun pun ternyata membangun museum juga. Menurut Yuswantoro, para perupa Jogja tetap optimis, pameran jalan terus. Masih ada pameran reguler Artjog dan Yogyakarta Annual Art (YAA). Peristiwa seni terselenggara di banyak tempat yang didirikan para perupa, seperti Sarang, Sangkring, Studio Kalahan dan Cemeti. Dan di tempat-tempat pameran itu banyak karya terjual, artinya disambut baik oleh pasar. Pasar senirupa kita itu “baik-baik saja, sehat, segar, dan waras”. Setelah gerhana, senirupa kita akan terus terang benderang.
Kompas menutup ‘polemik gerhana’ ini dengan tulisan Asmudjo J. Irianto yang mengatakan Senirupa Kontemporer Indonesia masih gerhana. Tanggapan Asmudjo ditujukan kepada Aminudin dengan mempertanyakan seberapa penting pemahaman atas sejarah senirupa bagi para seniman kontemporer. Karena toh senirupa Barat itu sendiri telah berkali-kali menganulir sejarah senirupanya. Bahkan mereka juga bilang sejarah senirupa telah berakhir. Menurut Asmudjo, kita tidak punya sejarah yang menjadi rujukan, sehingga kita kerap merujuk sumber sejarah senirupa Barat untuk memahami praktik senirupa di sini. Praktik senirupa modern/kontemporer Indonesia merupakan adopsi dari Barat. Prinsip multikulturalisme dan pluralisme dalam senirupa di Pusat (Barat) menjadi berkah bagi senirupa kontemporer di Pinggiran (Indonesia) untuk dilibatkan dan diberi suara.
Selanjutnya Asmudjo membahas senirupa otonom yang disederhanakan dengan gerakan seni untuk seni. Seni otonom membutuhkan kelembagaan untuk melindungi kemurniannya dengan membangun museum, teoritikus, kritikus dan kurator senirupa modern. Strategi otonom ini melanggengkan posisi sentral seniman yang sangat berjarak dengan persoalan masyarakat. Senirupa modern kemudian menjebak dirinya sendiri sampai pada kebuntuan. Setelah prinsip modernisme bangkrut, ruang-ruang otonom – museum dan galeri terus dimanfaatkan, dan menjadi ujung tombak komodifikasi seni, yaitu dengan berkembangnya art fair dan balai lelang.² Dalam komodifikasi, karya seni berlaku sebagai modal simbolik bagi pemiliknya, kelas sosial dan aset untuk berinvestasi. Dengan itu kritik dan wacana seni tidak lagi dianggap penting. Kritik digantikan dengan berita sensasi harga karya seni. Namun Asmudjo juga memaparkan adanya gerak perlawanan kepada seni otonom ini, yaitu kolektif seni, karena senirupa otonom terlalu berorientasi pada uang. Asmudjo memberi contoh Documenta sebagai kolektif seni yang mengembalikan praktik senirupa ke dalam masyarakat.³Pada bagian akhir Asmudjo menyalahkan praktik senirupa kita yang tidak bersungguh-sungguh menjalankan konsekuensi adopsi senirupa dalam konteks masyarakat moderrn. Juga Asmudjo menyalahkan Pemerintah yang tidak pernah menganggap penting senirupa. Sehingga wacana, pemikiran dan praktik senirupa kita sesungguhnya masih dalam gerhana.
Sejarah senirupa itu penting atau tidak?
Asmudjo meragukan pentingnya pemahaman atas sejarah senirupa bagi para seniman kontemporer. Karena toh senirupa Barat itu sendiri telah berkali-kali menganulir sejarah senirupanya. Bahkan mereka juga bilang sejarah senirupa telah berakhir. Barangkali Asmudjo dalam menyampaikan pendapatnya ini terinspirasi oleh essay Francis Fukuyama, “The End of History?” (1989), yang mengacu pada Hegel bahwa sejarah manusia sebagai perkembangan linear dari satu zaman ke zaman lainnya. Fukuyama pesimistis tentang masa depan kemanusiaan karena selalu dikontrol teknologi. Berakhirnya sejarah berarti demokrasi liberal sebagai pemenang dan menjadi bentuk final dari pemerintahan seluruh negara di dunia. Tidak ada lagi sistem alternatif. Karena sejak Revolusi Perancis, sejarah membuktikan bahwa sistem demokrasi liberal beserta ikutannya, kapitalisme, adalah yang terbaik ketimbang sistem lain.4 Tentu saja pemikiran Fukuyama ini mendapat kritik dari banyak pemikir dunia, Jacques Derrida di antaranya. Derrida mengatakan Fukuyama baru pinter belakangan dan ia merupakan antek sayap kanan yang merayakan hegemoni ekonomi serta budaya liberalisme Barat. Dari Barat manusia merasakan penaklukan, kelaparan dan pemusnahan yang begitu besar yang belum ada sebelumnya.5
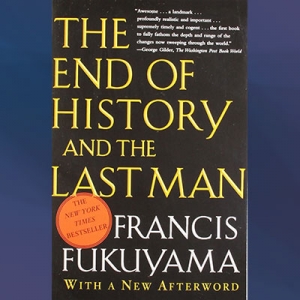
Francis Fukuyama “The End of History?” (1989)
Kemenangan kapitalisme ini memang suatu yang niscaya, karena kapitalisme sudah sesuai dengan fitrah manusia yang pada dasarnya egois, rakus dan mau menang sendiri. Upaya untuk menaklukan kapitalisme selalu kandas karena kapitalisme dapat bersalin rupa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bahkan perlawanan Madzhab Frankfurt – diwakili oleh Max Horkheimer dan Adorno – sejak tahun 1940-an mereka terus menentang komodifikasi seni yang dilakukan oleh kapitalisme,6menjadi sia-sia. Kita harus mengapresiasi tujuan Adorno dalam memberikan teori estetikanya, bahwa karya seni itu bukanlah alat untuk dipertukarkan, apalagi diperdagangkan untuk mencari keuntungan. Karena kalau demikian yang terjadi, maka kita sedang melakukan reifikasi (pembendaan) terhadap seni. Seni itu harus dialami, dinikmati, dihayati ketimbang dianalisis melalui konsep-konsep yang sistematis. Karena perbuatan seperti itu berarti sedang memberikan identitas kepada karya seni. Dan pemberian identitas merupakan langkah awal dari pembuatan kategorisasi dalam rasionalitas ilmiah sehingga memberi jalan manusia akan menundukkan dan mengatur seni. Itulah jalan kapitalisme, di mana manusia nantinya akan dininabobokan oleh kesadaran palsu. Dan seni kemudian dijadikan alat atau instrumen untuk tujuan tersebut.
Namun kita tahu bahwa sistem kapitalisme mempunyai kecerdasannya sendiri untuk dapat bertahan. Sehingga produk budaya yang banyak mendapatkan kritik akan cepat digantikan dengan versi barunya yang lebih baik dan lebih diterima masyarakat. Dengan itu kita dapat merasakan bahwa estetika, daya kritis dan komodifikasi dapat berjalan seiring. Kembali ke pertanyaan apakah sejarah itu penting, dalam pengamatan penulis, sejarah senirupa itu hanya dijadikan bumbu dalam mengulas suatu karya seni yang sedang dipasarkan oleh Balai Lelang Sotheby’s dan Christie’s. Kalau kita rajin mengamati katalog senirupa buatan mereka, terasa sejarah menjadi unsur pemanis dari karya-karya yang akan dilelang demi menarik minat kolektor dan meningkatkan harga jual. Sekali lagi, sejarah pun hanyalah sebuah elemen pemasaran yang tunduk pada kapitalisme.

Balai Lelang Sotheby’s
Senirupa dan peristiwa ekonomi
Kita menyadari bahwa kemajuan senirupa di suatu negara selalu berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, bukan oleh pemahaman sejarah para seniman dan kuratornya. Pasar senirupa China sebagai contoh, tumbuh beriringan dengan meningkatnya GDP. Dengan itu pertumbuhan ekonomi telah memunculkan banyak filantropi yang mau menyumbangkan uangnya untuk kegiatan seni.7 Selanjutnya para orang kaya baru China bermunculan untuk memasuki gaya hidup kontemporer yaitu mengoleksi karya seni. Sehingga pasar senirupa tumbuh dan berkembang yang diikuti dengan peningkatan aktivitas Balai Lelang dan munculnya galeri-galeri baru.
Indonesia juga pernah mengalami masa-masa seperti itu. Perluasan pasar lukisan dicatat pertama kali sekitar awal 70-an. Tahun itu sedang terjadi limpahan minyak, situasi yang melahirkan banyak orang kaya baru dan selanjutnya terjadi pembangunan perumahan, lengkap dengan interiornya. Lukisan dengan gaya dekoratif dan abstrak sebagai pengisi interior rumah orang berpunya, nampaknya cocok dengan semangat zaman itu. Zaman depolitisasi, di mana Orde Baru lebih menyukai karya-karya non politis ketimbang corak realisme sosialis ala Orde Lama. Dalam konteks itu, karya-karya produk Bandung School, dan beberapa pelukis lain dari Jogja juga mulai digemari, seperti Sadali, Pirous, Apin, Srihadi, Popo Iskandar, Widajat, Fadjar Sidik, Abas Alibasjah dan Nasjah Djamin.
Masih ada lagi perluasan pasar setelah itu yaitu tahun 1999-2000, di mana ada peristiwa ekonomi di sana. Sekelompok lapisan elit yang tipis telah menangguk keuntungan dari perubahan kurs dolar yang semula Rp 2000,- menjadi Rp 20.000,-. Motif investasi dan keuntungan finansial lebih mendasari munculnya booming kali ini. Krisis moneter saat itu membuat sebagian orang melarikan dananya ke lukisan, karena bidang ini menjanjikan margin yang lebih besar.
Kemudian tahun 2007 menjadi tahun kejayaan seni rupa kontemporer Indonesia, setelah di bulan April 2007 Balai Lelang Sotheby’s bisa menjual lukisan Putu Sutawijaya seharga 70,000 US$. Angka yang fantastis ketika itu. Rupanya booming kali ini merupakan imbas dari pertumbuhan ekonomi di China yang memicu pertumbuhan ekonomi seni di kawasan Asia. Keberhasilan ini menarik karya seniman-seniman lain seperti Masriadi, Agus Suwage, Handiwirman, Galam Zulkifli, Dipo Andy, Ugo Untoro, Jumaldi Alfi dan Budi Kustarto, sehingga harga lukisannya yang semula masih di bawah Rp 30 juta menjadi terangkat naik dalam kisaran Rp 300 – 700 juta,- Booming lukisan tahun 2007 membawa perubahan dalam sejarah lukisan kontemporer Indonesia. Harga lukisan yang pada tahun 2004-2005 masih dalam kisaran Rp 10-30 juta,- bergeser harganya ke orde ratusan juta sampai tembus satu milyar rupiah. Mengoleksi kemudian tidak lagi menjadi hobi yang terjangkau dalam kantong kelas menengah-bawah Indonesia.

Acara Lelang Lukisan
Booming tersebut juga membuat bergairahnya dunia senirupa Indonesia, terutama marketnya. Ada 7 Balai Lelang yang aktif di Indonesia pada saat itu, yaitu Masterpiece, Borobudur, Cempaka, Larasati, Sidharta, Maestro dan 33 Auction. Khusus untuk Masterpiece, balai lelang tersebut memecah lelangnya menjadi tiga edisi: Treasure untuk lukisan affordable, Heritage untuk lukisan kontemporer dan Masterpiece sendiri untuk lukisan para maestro. Sementara ada empat majalah senirupa yang pernah berjaya, yaitu Visual Art, Contemporary Art, Arti dan Saraswati. Demikian pula pertumbuhan Galeri baru juga marak di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Magelang, Surabaya, Malang dan Bali. Galeri juga berdiri di Plaza Indonesia dan Grand Indonesia. Bahkan di Grand Indonesia ada section khusus yang disebut Art District, berisi 10 Galeri yang aktif dan melaunching pameran setiap minggu.
Dari segi skills melukis, pelukis-pelukis baru mempunyai pencapaian artistik yang lebih baik dari pelukis hiperrealis generasi sebelumnya seperti Dede Eri Supria dan Ivan Sagito. Demikian pula dari segi idea, banyak hal segar yang ditampilkan, dari yang serius sampai dengan gagasan yang bermain-main. Booming 2007 juga membuat pelukis-pelukis senior turun gelanggang dengan kualitas karya yang lebih baik, seperti Ronald Manullang, Chusin Setiadikara dan FX Harsono. Demikian pula, karya-karya dengan media alternatif seperti Yudi Sulistiyo dengan karya instalasi melalui media karton, Wimo Ambalang dan Jim Abel (fotografi), Tromarama dan Prilla Tania (video), serta karya-karya instalasi lainnya mulai digemari dan dibeli.
Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan munculnya filantropi dan berimpak pada meluasnya pasar senirupa serta bertambahnya jumlah kolektor. Museum-museum pribadi juga bermunculan seperti yang sudah diulas oleh Yuswatoro Adi di atas. Namun pertumbuhan pasar senirupa Indonesia tahun 2007 itu tidak sustainable karena tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ada yang bilang bahwa senirupa Indonesia tetap memble setelah booming berakhir sementara China tetap jaya sampai sekarang, malah senirupa Thailand, Filipina dan Vietnam sekarang jauh lebih pesat pertumbuhannya ketimbang Indonesia. Hal itu bukan terjadi karena Thailand, Filipina dan Vietnam telah menerapkan “historiografi penyadaran” seperti yang diujarkan Aminudin, namun memang negeri-negeri itu ekonominya telah tumbuh dengan pesat melebihi Indonesia.

Sebuah acara lelang di Sotheby’s, London, 12 Oktober 2018, karya Banksy “Girl with Ballon” yang tercacah-cacah melalui mesin penghancur (vogue.com)
Belajar dari Vietnam yang sekarang karya-karyanya jadi primadona di Sotheby’s dan Christie’s, hal itu saya rasa terjadi karena negeri Vietnam baru membentuk kelas elite baru dalam struktur strata sosialnya. Ekonomi Vietnam tumbuh luar biasa akhir-akhir ini. Hal yang sama terjadi pada China yang ekonominya tumbuh luar biasa pada tahun 2000-an. Sementara Indonesia itu growthnya cuma berkisar pada 5% per tahun. Kejar-kejaran dengan rate pertumbuhan penduduk dan rate inflasi. Pertumbuhan yang cuma 5% itu tidak cukup untuk memperluas kelas elite yang baru. Dalam riset yang dilakuan penulis 5 tahun lalu, berdasarkan data base kolektor yang dimiliki beberapa galeri dan dikomparasi serta dikomentari oleh satu Balai Lelang, jumlah kolektor Indonesia hanya berkisar 1000 orang dan yang aktif membeli (dan juga menjual) cuma 300 kolektor saja. Chris Dharmawan dari galeri Semarang, mempertajam bahwa dari 300 itu hanya 100 yang mengumpulkan senirupa kontemporer, sisanya mengumpulkan modern art yang lebih jelas nilai aset dan investasinya serta kestabilan harganya di masa depan.

Balai Lelang Christie’s
Angka yang cuma 300 kolektor itu terjadi karena kelas elite Indonesia yang lama sudah punya banyak koleksi, sehingga mereka tidak berminat menambah koleksinya lagi. Kecuali jika muncul suatu karya di Balai Lelang yg benar-benar luar biasa dari segi kelangkaan dan keindahannya. Jadi, kalau ekonomi Indonesia cuma begini-begini saja, maka antusiasme market Indonesia juga mengalami stagnasi. Dan memang Balai Lelang luar negeri sudah meninggalkan kita.
Jalan Keluar
Untuk itu perlu dicarikan alternatif market yg lain di luar Balai Lelang. Apakah itu melalui art fair seperti yg dilakukan oleh Heri Pemad, Art Jakarta seperti yang dilakukan Tom Tandio, Art Moment seperti yang dilakuan Leo Silitonga, dan keaktifan galeri yang tersisa untuk mendapatkan niche market. Jadi biang keladinya bukan hanya soal infrastruktur senirupa yang tidak dibangun, tetapi ekonomi Indonesia memang memble. Dengan ekonomi yang memble itu akan membuat pembangunan infrastruktur seni menjadi tidak penting atau tidak prioritas dalam pandangan Pemerintah. Akan sia-sia menyalahkan Pemerintah, seperti yang dilakukan Asmudjo, karena urusan seni di Indonesia adalah urusan swasta mandiri, yang telah diusahakan para filantropi yang segelintir itu sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan yang dilakukan Soekarno pun adalah termasuk dalam inisiatif filantropi, bukan suatu kebijakan sistemik Pemerintah Orde Lama.
Jalan keluar yang lain adalah mengusahakan sistem perpajakan kita lebih manis terhadap senirupa misalnya artwork diberi pajak 0%, termasuk kemudahan bea masuk untuk ekspor dan impor barang seni. Pemberian kejelasan untuk penggunaan dana CSR dalam bidang seni akan banyak menolong, sehingga hal itu akan membuat para korporasi leluasa menyumbang dana CSR nya ke senirupa. Seandainya (hanya seandainya) Pemerintah masih menyisihkan dana untuk Bekraf, barangkali dana itu dapat difokuskan untuk menyelenggarakan satu dua kegiatan saja yang besar, misalnya event Biennale yang spektakuler dengan mengundang perupa dari luar dan melibatkan kepanitiaan yang profesional. Apabila hal-hal itu sudah dilakukan, senirupa Indonesia masih terjamin untuk tetap ‘ada’, walaupun tidak akan ke mana-mana, jika ekonomi kita tumbuhnya biasa-biasa saja.
——–
1Yuswantoro Adi lupa menyebutkan Museum Orion di Surakarta dan Pacifica di Bali yang sangat articulate dalam menampilkan karya-karya modern art.
2Theodor Adorno justru melihat seni otonom itu yang akan melawan komodifikasi seni (The Culture Industry, Routlegde, New York, 1991).
3Nampaknya Asmudjo mendasarkan istilah Kolektif Seni mengacu pada praktik yang sedang dilakukan Ade Dermawan (Ruang Rupa), ketika terpilih menjadi Direktur Artistik Documenta ke 15 (2022). Lihat Dylan Amirio & Stevie Emilia. Indonesian Art Collective Choosen to Curate World Renowned Documenta. The Jakarta Post, 24 Februari 2019.
4Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. The Free Press, 1992.
5Derrida, Jacques (1994). Specters of Marx: State of Debt, the Work of Mourning and the New International. Routledge
6Horkheimer, Max dan Adorno, Theodor. Dialectic of Enlightment, Philosophical Fragments. terj. Edmund Jephcott. California: Standford University Press, 2002 [1944].
7Lee, Rawon, dkk (2020). Economic Growth and the Arts: a Macroeconomic Studies. Cogent Business & Management, volume 7 – Issue 1.
Referensi
[1] Adorno, Theodor (1991). The Culture Industry. Routlegde, New York.
[2] Amirio, Dylan & Emilia, Stevie (24 Februari 2019). Indonesian Art Collective Choosen to Curate World Renowned Documenta. The Jakarta Post.
[3] Derrida, Jacques (1994). Specters of Marx: State of Debt, the Work of Mourning and the New International. Routledge.
[4] Fukuyama, Francis (1992). The End of History and the Last Man. The Free Press.
[5] Horkheimer, Max dan Adorno, Theodor (2002 [1944]). Dialectic of Enlightment, Philosophical Fragments. terj. Edmund Jephcott. California: Standford University Press.
[6] Harian Kompas 30 Mei, 6 Juni, 27 Juni, 4 Juli 2021.
[7] Lee, Rawon, dkk (2020). Economic Growth and the Arts: a Macroeconomic Studies. Cogent Business & Management, volume 7 – Issue 1.
*Penulis adalah kolektor.












