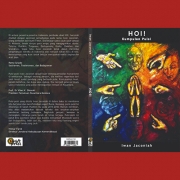Membaca “Garis Merah” Lukisan I Ketut Suwidiarta
Oleh I Made Kridalaksana*
Karya seni, apa pun bentuknya, kalau sudah disuguhkan ke ranah publik hak interpretasinya sudah menjadi milik publik. Dominasi pemaknaan sudah bukan mutlak berada pada senimannya lagi. Hal ini disadari betul oleh I Ketut Suwidiarta terkait karya-karyanya pada pameran tunggal yang bertajuk “Crossing the Red Line” di Komaneka Gallery-Ubud, dari tanggal 4 sampai 30 April 2022 yang lalu. Apakah garis serta obyek-obyek merah boleh dimaknai sebagai figur maupun partai tertentu? “Boleh saja,” katanya saat kami berbincang santai seusai pameran digelar.

Foto I Ketut Suwidiarta (Sumber Foto: Arsip Penulis)
Penempatan obyek-obyek lukisan—termasuk garis merah—di tengah-tengah bidang kanvas yang menyisakan ruang-ruang kosong di sekelilingnya semakin mewakili sikap demokratisasi pelukisnya dalam memberikan kemerdekaan pemaknaan bagi khalayak penikmatnya. Karya-karya I Ketut Suwidiarta pada pameran “Crossing the Red Lines” banyak menghadiran ruang-ruang hampa agak berbeda dengan beberapa karya sebelumnya dengan obyek yang justru sangat ramai hingga memenuhi kanvas—nyaris tanpa bidang yang tersisa.
Merah adalah warna yang secara alami telah ada sebelum manusia ada. Tetapi manusialah yang menyepakati ‘merah’ itu sebagai apa. Kesepakatan yang paling umum tentang merah adalah stop, larangan, berhenti, danger, zona merah, batas, dan sejenisnya. Batas bisa diterjemahkan bermacam-macam. Tidak boleh dilewati atau boleh dilewati dengan konsekuensi. Kalau pun merah tersebut berhasil dilewati maka akan menimbulkan suatu nilai yang baru—termasuk menjadi sesuatu yang paradoksal. Kurang-lebih demikian intisari pemaknaan I Ketut Suwidiarta terkait keberadaan garis merah menjawab pertanyaan saya tentang konsep yang melatari pemilihan warna yang identik dengan darah tersebut.
Lukisan berjudul “Basic Instinct” menyuguhkan gambaran naluri dasar manusia untuk mempertahankan hidup. Manusia dengan pisang yang sudah siap dimakan seperti membuka ruang permenungan kita bahwa hidup bukan hanya hari ini. Lukisan ini lebih mengajak untuk lebih bijak mengatur apa yang sudah ada di depan kita dengan tidak lupa memperhitungkan apa yang belum terjadi. Dalam realitasnya, ketika harta sudah dalam genggaman tidak jarang kita larut dalam kesenangan yang berlebihan sehingga tidak bisa membedakan kebutuhan dengan keiniginan. Saat seperti ini kita “melintasi garis merah” dengan perilaku konsumtif dan cenderung hedonistik. Tapi, begitu bencana datang, saat cadangan harta juga makanan mulai menipis bahkan habis maka kita akan menjadi kelimpungan. Jika ini terjadi, kita akan kembali mundur ke kondisi nol lagi, yang dalam lukisan ini digambarkan dengan ekor di belakang garis “merah”.

Foto lukisan “Basic Instinct” (Sumber Foto: Arsip Penulis)
Pesan serupa dihadirkan pada lukisan berjudul “Sintesa” dengan kaktus dan akar pohon yang berada pada posisi seberang-menyeberangi garis merah. Ide lukisan ini barangkali lahir setelah I Ketut Suwidiarta mengamati femonena sosial yang terjadi di Bongkasa—tempat I Ketut Suwidiarta dilahirkan tahun 1976 dan menetap hingga kini. Pada satu sisi, akar pohon dihadirkan mewakili kesuburan alam desa serta potensi pariwisata—dengan Sungai Ayung sebagai episentrum magnetnya. Pada sisi lainnya, kaktus dihadirkan sebagai pengingat bagaimana mengelola keberadaan kesuburan yang telah disediakan alam tersebut sehingga bisa memberikan manfaat sepanjang hayat. Jika salah mengelola apalagi sampai “melanggar garis merah” seperti mengeksploitasi alam secara berlebihan, berperilaku konsumtif apalagi hedonistik dan sejenisnya, yang akan rasakan adalah penderitaan sebagaimana sakitnya tusukan duri-duri kaktus. Realitas ini terjadi pada saat Covid-19 melanda. Banyak orang yang sebelumnya “sebasah” akar pohon mendadak menjadi “sekering” duri pohon kaktus.

Foto lukisan “Sintesa” (Sumber Foto: Arsip Penulis)
Kelahiran di dunia bagi manusia tidak sekadar mempertahankan hidup. Popularitas, kekuasaan, kesejahteraan, dan sebagainya adalah hal-hal lainnya yang merupakan simbul “kemenangan” manusia pada kehidupan ini. Lukisan berjudul “V is Reaching the Star, the Moon and the Star” bisa menjadi perlambang “kemenangan atau victory” tersebut. Hanya saja, untuk mencapai puncak-puncak pencapaian seperti bintang, bulan dan matahari tersebut terkadang manusia “melanggar” garis merah sebagaimana pada lukisan ini digambarkan dengan huruf “V” yang kedua ujung atasnya ditransformasi menjadi semacam cheliped atau capit udang ini. “V—sebagai simbul perempuan—bisa jadi juga membawa makna bahwa perempuan kini yang tidak lagi hanya berada pada lingkaran kodratnya yang dulu hanya masak, macak dan manak sebagaimana istilah yang terkenal pada masyarakat Jawa. Perempuan kini sudah mampu melintasi “garis merah” yang dulu menjadi garis tegas pemisah dengan laki-laki yang mendominasi hal-hal penting yang dalam lukisan ini dilukiskan dengan “bintang”, “bulan” serta “matahari”.

Foto lukisan “V is Reaching the Star, the Moon and the Star” (Sumber Foto: Arsip Penulis)
Puncak-puncak pencapaian seperti bintang, bulan, serta matahari juga dikemas apik pada lukisan lainnya yang berjudul “Puisi Kursi”. Saya lebih melihat ini mengarah pada gambaran kecenderungan bagaimana cara manusia meraih capaian tertinggi tersebut termasuk bagaimana mempertahankannya. Lukisan ini sepertinya punya benang merah dengan fenomena yang sedang “viral” baik di dunia maya maupun dunia yang nyata belakangan ini. Lukisan ini bisa jadi adalah misteri terkait apa yang akan terjadi setelah sang pemilik kursi lengser keprabon nanti. Apakah akan melanggar garis merah seperti mempertahankan kembali kursi secara mati-matian? Apakah menyerahkan sesuai mekanisme yang ada? Siapa penggantinya? Apakah penggantinya adalah figur-figur yang mulai bermunculan di layar kaca serta media online selama ini? Semua itu adalah “puisi”—sesuatu yang masih misteri.

Foto lukisan “Puisi Kursi” (Sumber Foto: Arsip Penulis)
I Ketut Suwidiarta menjawab pertanyaan ini pada lukisan berjudul “Kuda Hitam”. Pada lukisan ini terlihat kuda hitam dengan tubuh serta bulu-bulu surinya berwarna nyentrik di atas garis merah. Semantara di bawah garis tersebut terlihat kepala manusia posisinya terbalik. Lagi-lagi, mengambil realitas politik yang menghangat belakangan ini, posisi terbalik ini sepertinya mengajak kita berpikir secara terbalik untuk tidak terburu-buru “melintasi garis merah’ yang dibentangkan pihak-pihak tertentu melalui promosi popularitas maupun elektabilitas nama-nama yang selama ini “dijual” untuk kepentingan mendaki kursi kekuasaan. Lukisan ini lebih menyiratkan pesan untuk menunggu “Kuda Hitam” yang bisa jadi sengaja disembunyikan oleh penunggangnya sebagai strategi mengecoh lawan. “Ojo kesusu, sik!” Begitu kira-kira.

Foto Lukisan “Kuda Hitam” (Sumber Foto: Arsip Penulis)
Narasi dualitas juga dihadirkan pada lukisan “Pertemuan Ganjil”. Kepala yang normalnya di atas malah dibuat sebaliknya. Bisa jadi ini sebagai perlambang terbaliknya pola pikir yang barangkali diakibatkan perbedaan sudut pandang dalam memaknai garis merah ini pada lukisan ini. Bila dihubungkan dengan konteks kekinian, bagi masyarakat awam, manuver politik yang marak dilakukan politsi, partai, maupun relawan dalam upaya menuju kursi kekuasaan yang dirasa terlalu dini adalah sesuatu yang melintasi garis merah. Sebaliknya, di mata politisi serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, hal seperti itu dianggap bersifat “normal”, tidak ada pelanggaran garis merah. Jika masyarakat memandang ini sebagai tindakan yang terburu-buru sebab kontestasi politik masih jauh sementara para politisi memandangnya sebagi sesuatu yang sebaliknya. Untuk itu, mereka mesti melakukan gerakan lebih awal untuk lebih mendapatkan “pasangan pengantin berkelamin sama” dalam artian kesamaan ideologi maupun kepentingan agar dapat melenggang mulus ke kursi pelaminan kekuasaan.

Foto lukisan “Pertemuan Ganjil” (Sumber Foto: Arsip Penulis)
Kursi-kursi pelaminan kekuasaan tidak selalu digapai dengah lurus-lurus saja. Tidak jarang pergantian kekuasaan dilakukan dengan peristiwa berdarah. Ketidaklurusan ini dilukiskan pada lukisan “Z in Red Diagonal”. Meskipun “Z” yang juga disematkan pada kendaraan militer Rusia ini merupakan singkatan dari frase “za pobedu” adalah untuk kemenangan, “za mir” untuk perdamaian, “za pravdu” untuk kebenaran serta sejumlah makna Z yang lainnya, tapi bagi Ukraina itu bukanlah perdamaian. Jika demikian, saya meyakini pelukis yang pernah mengikuti pameran bersama di Turki ini sangat mungkin melukiskan kecamannya terhadap peperangan. Tidak saja di kawasan Rusia-Ukraina yang sedang bergejolak akhir-akhir ini tetapi perdamaian di seluruh belahan dunia. Jika dunia aman tanpa perang maka tentara suatu negara tidak perlu lagi “melintasi garis merah” mengerahkan tentara beserta tang-tang maupun persenjataan mereka untuk mengibarkan perang. Kekuatan-kekuatan mereka ini justru mesti terus dipergunakan untuk melakukan kampanye anti-peperangan yang sebagaimana lukisan “Parade Damai”. Jika dunia aman, manusia akan hidup dengan tenang, indah, bahagia serta sebutan-sebutan positif lainnya sebagaimana diwakilkan dengan burung merpati serta bunga pada lukisan lainnya berjudul “Gun and Flower”.

Foto lukisan “Z in Red Diagonal” (Sumber Foto: Arsip Penulis)
Meski pada banyak hal garis merah identik sebagai simbol larangan untuk dilewati tapi pada sisi tertentu ada kalanya garis tersebut mesti dilintasi—dengan segala konsekuensinya—untuk bisa keluar dari kekeringan, kesulitan, penderitaan serta hal-hal sejenisnya. Keharusberanian tersebut diwujudkan pada lukisan “Staring Figure”. Melalui keberadaan orang-orang penting dengan mata melotot dan mulut “terkunci” masker ini I Ketut Suwidiarta sepertinya menyoroti tidak berjalannya peran para pemegang otoritas dalam menyampaikan suara (voice) serta menentukan pilihan (choice) dalam menyikapi peristiwa yang terjadi seperti kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng, bahan baku minyak goreng yang sempat dijual ke luar negeri, atau mungkin saja jiwanya sedang terusik oleh peristiwa kemanusiaan seperti serangan Rusia atas Ukraina, misalnya, atau kasus-kasus serupa lainnya. Dengan demikian harapan untuk mendiami dunia yang damai dan aman akan dapat diwujudkan sebagaimana ungkapan “May peaceful prevail on earth” dapat terwujud. Tidak hanya perdamaian dari sudut pandang fisik seperti peperangan, penindasan, serta sejenisnya tetapi juga perdamaian dalam pengertian psikis seperti ketenangan pikiran dari rasa takut, tekanan, intimidasi, dan sejenisnya.
Perdamaian juga terejawantah pada lukisan berjudul ‘Coincidence’. Meskipun judul ini berarti ‘kebetulan’, tetapi saya melihat bukan sebuah kebetulan ketika pelukis yang memperoleh gelar Master of Fine Art (MFA) pada Faculty of Fine Art Rabindra Bharati University, Kolkata-India ini menghadirkan garis merah di antara Unta dan Karang gajah. Lukisan ini sepertinya bukan dimaknai untuk saling mempertentangkan apalagi membentur-benturkan dua kebudayaan yang berbeda tetapi lebih sebagai peringatan untuk saling memahami dan menghormati batas-batas “merah” masing-masing sehingga tidak terjadi polarisasi dan disharmonisasi. Jika manusia mampu mewujudkan harmonisasi serta toleransi maka yang terjadi adalah roda kehidupan yang berjalan normal sebagaimana lukisan “Perputaran Energi”.

Foto lukisan “Coincidence” (Sumber Foto: Arsip Penulis)

Foto lukisan “Perputaran Energi” (Sumber Foto: Arsip Penulis)
Demikian kira-kira pesan I Ketut Suwidiarta yang saya tangkap dari 12 karya yang dihasilkan saat melakukan Living Residence selama 3 kali 24 jam ini.
* I Made Kridalaksana, penulis seni. Tulisannya pernah dimuat di Bali Post, Den Post, Radar Bali, Pos Bali serta beberapa media daring.