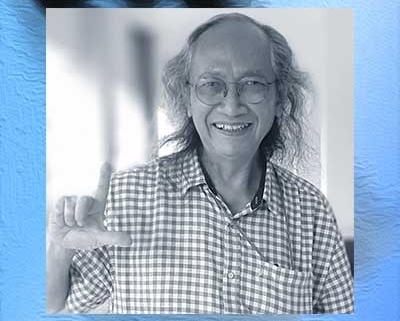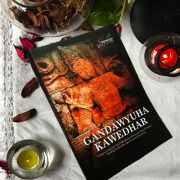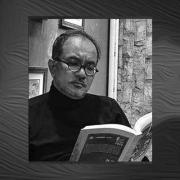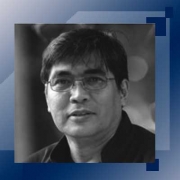Muatan Makna Dari Karya Seni
Oleh. Mudji Sutrisno SJ.*
Membaca karya seni entah itu sastra, seni rupa lukisan atau bangunan candi, mengandaikan si pembaca dalam mengapresiasi karya itu, belajar menangkap maksud pengarang atau senimannya. Di barat, sekolah ini sebagai isme, menyebut diri sebagai ‘intensionalisme’. Mereka berpendapat bahwa makna sebuah karya itu ada pada intensi, maksud atau apa yang ingin disampaikan (pesan) oleh senimannya. Konsekwensinya, membaca karya sebagai penafsiran mesti menangkap maknanya menurut pesan yang mau disampaikan senimannya. Sehingga seni dan karya seni merupakan bentuk komunikasi (antara seniman dengan maksudnya dalam berkarya) dan orang yang mengapresiasi, membaca karya seni itu.
Karya seni lalu merupakan ungkapan (komunikasi) dari senimannya ke khalayak publik. Karya seni sebagai ekspresi maksud senimannya inilah yang dikembangkan di Eropa oleh Tolstoy, Benedetto Croce dan Collingwood. Mereka inilah para intensionalis baku di dunia seni. Soalnya dalam sastra atau karya seni tulis, apakah intensi (maksud) pengarang tertulis sama dengan saat ia bicara sebagai seminaris di panggung? Ada kemungkinan terjadi kerancuan ‘semu’ maksud antara lisan dan tulis dari senimannya bila tidak teliti dahulu mendeskripsi jelas-jelas apa pesan pengarang di buku novelnya dan maksudnya itu berubahkah saat medianya lisan. Ini hanya rancu semu bila yang bicara sama dengan yang menulis atau si penulis. Namun bila berbeda pendapat antara yang menulis dan ceramah, maka metode interpretasi atau hermeneutikalah yang menentukan dengan kaidah-kaidahnya. Garis besar tafsir bisa dari teks (dari dalam) intrinsik dan bisa dari luar dengan ilmu di luar yang intrinsik misalnya sosiologi sastra, psikolog sastra.
Membuat interpretasi atau membaca karya seni dari maksud atau pesan senimannya terutama apa yang jadi ‘intensi’ nya bila dilakukan langkah demi langkah akan asyik untuk dilakukan. Pertama, kegiatan ini kreatif karena memakai budi yang menimbang dengan ukuran-ukuran yang mengatur cerapan langsung dari lukisan ‘ibu’ maestro Affandi misalnya. Rasa yang muncul dan bercakap-cakap di depan wajah perempuan bijaksana sepuh, namun mengundang menatap lebih dekat untuk melihat garis-garis kerut wajah sepuh yang jelas mengungkap warna lembut sekaligus menyapa untuk tanpa kata mengaguminya. Kegiatan menafsir ini pelan menaruh kepekaan pemahaman hati dan dialog hati dan budi untuk mencoba membuat pemahaman di depan lukisan. Syukurlah ada teman menemani yaitu katalog yang ikut bercakap-cakap dalam Bahasa tulisan dari kurator hingga sang ibu sebagai lukisan oleh putranya yaitu Affandi diperkaya paparan keterangan katalog yang seperti di depan menaruh komunikasi dalam senyap antara dang ibu lukisan sebagai teks dan katalog dengan narasi lukisan itu memuat intensi dan pesan apa dari Affandi sebagai ‘konteks’. Tajam saja seandainya katalog di bagian lukisan ‘ibu’ itu terluberi muntahan kopi yang menutupi narasi maka terpotonglah dialog teks dan konteks. Tidak hanya itu, kegiatan interpretasi kata menjadi terputus pula.
Yang kedua, tindakan tindakan menginterpretasi akan mensyaratkan kemampuan untuk memahami makna estetis lukisan sang ibu itu. Dari pengalaman, ditemukan bahwa ketiadaan kemampuan apresiasi karena tidak diinformasikan, dididik atau tidak tahu apresiasi akan mengakibatkan makna estetis lukisan itu tidak ditangkap. Contoh analoginya sebagai berikut: buah salak dengan kulit tajam atau buah manggis dengan kulit keras saat teman saya dari luar negeri ingin memakannya, harus saya beri tahu bagaimananya. Buka kulit salak, lalu buah putih di dalam juga harus diberitahukan ke teman bahwa di dalamnya ada biji, maka jangan dimakan. Pernah kejadian, karena tergesa-gesa mau makan buah salak, lalu cepat menggigitnya sehingga darah keluar lantaran kulit tajam salak belum dikelupas. Saudara kecil saya melakukan yang sama untuk buah manggis, ia langsung memakannya lalu berteriak katanya manggisnya manis, kok ini pahit! Tentu saja rasa kulit manggis pahit karena yang manis ya yang di dalam: buahnya.
Dengan menjelaskan cara makan buah-buah tersebut, terjadilah: ‘a disclosure of its meaning’. Nilai enak manis buah manggis dan salak menjadi terkuak terbuka, di lidah kita. Diperlukan pula kemampuan penguasaan dunia nilai estetis dari karya seni, kode-kode sastranya atau konteks saat proses karya itu dibuat senimannya, hal ini sering dikaitkan dengan semanat jaman karya itu diproses dan pesan seninya. Oleh karena itu pokok ketiga yang penting dalam interpretasi adalah pemahaman dalam pengetahuan mengenai apakah karya seni itu; proses cipta dan kasih akhirnya sebagai karya seni. Di sini mereka yangmenganut sekolahan / aliran ‘intensionalis’ = pesan atau maksud seniman itu penting sering sampai pada posisi monism yaitu: intensi atau maksud seniman itulah yang maha penting sebagai mono: satu-satunya kebenaran. Di sini pula jalan pikiran kritik seni sebagai tafsir terbagi dua antara membuat interpretasi dan hermenutika: kerja menafsirkan yang lebih menegaskan pluralisme: keragaman tafsir makna estetis karya seni. Maestro kita yaitu Ramadhan dari Soetardji Calzoum Bachri.
Sesedap sedapnya sajak
Di bulan Ramadhan
Lebih enak baca Quran
Kupinggirkan puisi
Ke tepi diri
Kubaca Quran
Tiap pagi dan malam
Tiap kubaca Quran
Selalu Quran
Membacaku
Mata Quran melahap abjad
Dan nama namaku
Terang Quran
Menyimak padat
Kalimat dan tamsil diriku
Gugup gagap aku dibuatnya
Di tepi diri
Sedih, geli, cemas dan kadang
Menahan tawa
Puisi menyaksikan aku
Gugup gagap dalam tatapan
14 Mei 2020
Ketika konteks karya seni dikonstruksi oleh kondisi structural masyarakat dan sistem politik yang ada semisal otoriternya sistem politik yang melarang karya seni yang berlawanan dengan garis politik negara, maka di sana kebebasan berkesenian praktis dibatasi bahkan harus hidup dibawah tanah. Ekstrimnya karya seni adalah karya yang segaris dan ditentukan oleh rejim kekuasaan dalam hal ini ideologi rejim itu bahwa tujuan berseni adalah demi revolusi sosialis perjuangan rakyat. Ideologi seni demi rakyat atau seni kontekstual berhadapan langsung dengan seni untuk seni, yang pada eksistensi berkesenian sendiri memunculkan manifesto seni itu mesti memihak perjuangan rakyat versus seni itu demi perkembangannya peradaban manusia yang dipadatkan dalam humanism untuk tidak dikotak-kotak oleh politik ideologi rejim tetapi kemanusiaan itu universal untuk diperjuangkan dalam humanism universal.
Untuk mengakhiri bahasan interpretasi ini, mari kita lakukan kerja interpretasi ini dalam puisi penyair Soetardji menulis puisi religius berjudul Ramadhan, dalam suasana puasa Ramadhan 2020 dengan intensi menggambarkan dirinya sebagai penyair sedang ‘membaca’ (baca) Quran. Dalam ranah pengalaman doa baca Quran itu pesan langsung yang kita rasakan adalah peralihan dari subyek pembaca sang penyair ke Quran yang justru membaca hidup Soetardji, dalam hal ini: dirinya. Ini berlangsung dalam proses laku batinnya setelah secara sadar, ia tepikan puisi. la ‘pinggirkan’ dirinya sebagai penyair yang karya-karya seninya adalah puisi. Ia menikmati membaca Quran dengan ‘enak’, tekun tanpa henti khusuk doa baca renung ini tiap pagi dan malam. Maha dahsyat Allah yang dijumpai Soetardji dalam Ramadhan: kini bukan lagi ia yang membaca Quran, tetapi Quran yang membaca Soetardji. Setiap membaca Quran, selalu Quran membacanya. Bahkan saat menafsir lebih ke dalam lagi, kita mendapatkan frasa mata Quran melahap abjad dan nama-namaku.
Kini puisi dan diri Soetardji sabagai penyair justru menyatu dalam pengalaman religius ‘sufi’ saat yang inti dari diri penyair yaitu kalimat, tamsil lalu ‘nama’ diri dijamah, dilahap oleh Allah hingga Yang Numinosum (meminjam Rudolf Otto) menyapa sebagai yang membuat Tardji ‘gugup gagap’, getar ‘termendum’, dirasakan: menakutkan sehingga sang penyair mengalami kehadiran Allah yang Fascinans: mengundang sekaligus membuat gugup dan gagap. Gagap ungkapan kelu dan habis kata tak mampu berkata-kata lagi dalam pengalaman baca Quran ini. Menyadari lagi si diri yang sudah ditepi, tafsiran saya, diambang kembali menyadari diri setelah pengalaman doa yang dahsyat itu, Soetardji memerikan pengalaman dirinya riil sebagai penyair dengan puisi yang menyaksikan dirinya: sebagai aku yang gugup dalam rasa sedih geli, cemas dan menahan tawa. Kini puisi sebagai semesta pengalaman baca Quran Tardji setelah mengalami diresapi oleh trasnformasi pengalaman religius doa selama Ramadhan ini membuahkan sapa Allah, Quran yang memberi tatapan Allah sendiri untuk menyaksikan laku hidup, cemas gembira sehari-hari lagi dalam hidup Soetardji.
Puisi sudah diresapi ruh baru, kata dan tamsil dalam puisinya sudah menjadi tatapan mataNya dalam tatapan mata Soetardji untuk melihat semesta dan kehidupannya nanti pasca Ramadhan dalam fitri yang sejatinya sebagai ‘kekasihNya’ (tulis Jallaudin Rumi, penyair Sufi).
—–
*Prof. Dr. Mudji Sutrisno SJ, Budayawan.