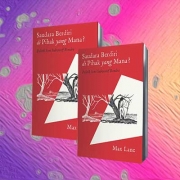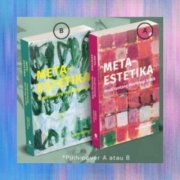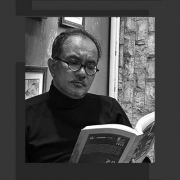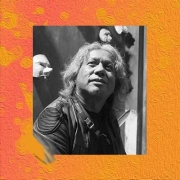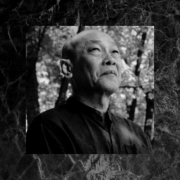Belanja Daerah untuk Berkebudayaan Sebuah Ironi
Oleh Pietra Widiadi*
Dalam pertemuan beberapa kawan di daerah, setingkat Kabupaten atau Kota dan juga Tingkat Provinsi yang aktif berkesenian, sering membicarakan soal dana, terutama soal alokasi dana untuk Dewan Kesenian Daerah dari APBD yang dianggap tidak cukup, dan dana cekak. Ada yang bilang alokasi dana yang tidak memanusia buat para budayawan (baca seniman), yang sering nombok. Atau bahkan beberapa waktu yang lalu, ada “sengketa soal” pembagian duit dari alokasi APBD itu. Seseorang yang terlibat dalam Dewan Kebudayaan Daerah, sampai menuliskan itu dengan sangat gamblang bahwa ada perebutan dalam sebuah media daring. Bahkan dalam satu peristiwa ada seniman yang meninggal karena kekerasan bersumber pada perdebatan alokasi dana dari Pemerintah, di Kota Malang beberapa waktu yang lalu.
Perebutan alokasi dana dari APBD yang dialokasikan pada suatu kegiatan dengan tujuan supaya berkelanjutan, tidak hanya dialami oleh sektor pertanian, perternakan, kelautan atau infrastruktur dan Pendidikan saja, tetapi juga dialami dalam bidang kesenian (baca juga kebudayaan). Bahwa bidang ini, masuk dalam nomenklatur yang bisa diberi alokasi dari Anggaran Belanja Daerah. Mari kita cermati, dengan merujuk pada UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menetapkan “seni” sebagai salah satu Objek Pemajuan Kebudayaan (Pasal 5 huruf g).
Dari sana sumber kekuatan yang mengakibatkan daerah harus mengalokasikan dana dari APBD untuk berkesenian. UU 5/2017 itu, memerintahkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan atau lebih enak kalau disebuut mengalokasikan dana serta sarana/prasarana. Dalam hal ini Pemerintah Daerah juga dituntut membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan (Pasal 44 huruf f–h; Pasal 46 huruf c), yang lazim dijadikan dasar legal untuk membentuk atau menguatkan DKD sebagai wadah pelibatan seniman/budayawan. Sehingga penggunaan alokasi dana dapat diukur kegunaannya.
Selain dari itu, dalam Perpres No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan Strategi Kebudayaan, mewajibkan Kepala Daerah menyusun PPKD dengan melibatkan masyarakat/ahli. Maka dalam hal ini PPKD menjadi rujukan untuk mengusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini artinya ada ruang dan peluang secara formal bagi Dewan Kesenian Daerah (DKD, bukan Dewan Kebudayaan Daerah) terlibat dalam perencanaan pembangunan kebudayaan daerah, atau dalam istilah praktisnya adalah DKD terlibat dalam pengusunan anggaran belanja daerah.
PP No. 87 Tahun 2021 (Peraturan Pelaksanaan UU 5/2017), mengatur lebih rinci perencanaan, pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, termasuk pendanaan dan fasilitas bagi pelaku/SDM kebudayaan. Ini memperkuat mandat daerah untuk menata kelembagaan/kemitraan kebudayaan (sering dioperasionalkan lewat DKD). Lalu Perpres No. 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, merupakan pedoman bagi Pemda dan Masyarakat untuk menetapkan strategi nasional 20-tahunan. Dokumen ini menegaskan pentingnya sinergi pemerintah–masyarakat dalam ekosistem kebudayaan, di mana DKD biasa berperan. Dalam terminology di sini, menekankan bisa bukan harus berperan jadi nampak, dalam penyusunan anggaran mereka tidak selalu harus dilibatkan.
Selain itu, Permendikbud No. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan PPKD, sebagaimana diubah dengan Permendikbudristek No. 6 Tahun 2023, memberi teknis pembentukan tim penyusun PPKD di kab/kota & provinsi; dasar yang kerap dipakai untuk melibatkan DKD/seniman sebagai unsur ahli/pemangku kepentingan. Dalam hal dilibatkan ini, memiliki makna abigu, sehingga perlu mendapatkan penjelasan yang utuh, sehingga pengertiannya bukan kalau diundang tapi keterlibatan. Maka menilik Permendikbud No. 45 Tahun 2018, lalu diubah dengan Permendikbudristek No. 6 Tahun 2023 menegaskan bahwa penyusunan PPKD wajib melibatkan unsur masyarakat, ahli, dan pemangku kepentingan.
Dari dasar itu lah, posisi Dewan Kesenian Daerah atau seniman-budayawan sering dipakai sebagai dasar formal untuk dilibatkan dalam Tim Penyusun. Hal ini karena mereka dianggap sebagai unsur ahli (memiliki kepakaran seni-budaya) sekaligus pemangku kepentingan (mewakili komunitas seni dan budaya yang akan terdampak oleh kebijakan). Dalam hal ini, masih ada terminilogi yang ambigu lagi, yaitu seni-budaya, karena pada dasarnya seni dan budaya bukan bangunan yang setara. Saya menjelaskan dalam tulisan saya belumnya “Berkesenian yang tidak berkebudayaan https://borobudurwriters.id/kronik-budaya-dan-sejarah/berkesenian-yang-tidak-berkebudayaan, 5 September 2025”.
Menyusun Anggaran untuk bekersenian
Kembali pada soal “rebut-ribut” di kalangan semiman terkait dengan pengelolaan dana dari alokasi APBD. Peran DKD sangat penting dan dalam pesepektif ini, mereka dianggap mewakili Masyarakat yang berkebudayana dan berkesenimaan. Seluruh konsideran regulasi yang saya paparkan di atas terkait dengan Gerakan berkebudayaan. Nampak dengan serta merta bahwa regulasi itu memberikan mandat kuat, bahwa DKD adalah wadah kelompok Masyarakat yang aktif berkesenian telah diwakili dalam Tata Kelola Pemerintahan di Daerah.
Kerangka ini jelas merujuk pada perspektif Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance). Di mana dalam menggerakkan roda Pemerintah tidak hanya ditentukan oleh Pemerintah, baca juga Pelayan Publik tetapi juga kelompok Masyarakat yang secara melembaga beraktivitas dalam kegiatan tertentu, dalam hal ini adalah berkesenian (jangan di baca berkebudayaan). Maka dalam menggerakkan Kepemintahan yang mengamanatkan dalam membangun berkesenian, maka kelompok-kelompok berkesenian harus terlibat. Meskipun di sini, kemudian wadah itu adalah DKD.
Kepentingan berkesenian, maka dalam hal ini menjadi sektor berkesenian dapat dibiayai oleh negara melalui konsideran regulasi dan DKD jelas menjadi wakilnya. Dalam hal ini, langsung merujuk pada keterlibatan mereka dalan proses penyusunan anggaran. Langkah ini merujuk pada konsep good governance, yang merupakan paradigma penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, termasuk di tingkat Daerah. UNDP (1997) mendefinisikan good governance sebagai “the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels,” dengan prinsip utama partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keadilan.
Dalam konteks ini, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar prosedur teknokratis, melainkan juga arena demokratis yang melibatkan masyarakat luas. Dalam hal ini, keterwakilan berkesenian tidak serta merta dimandatkan merupakan peran dari anggota DPRD, tetapi jelas peran dari DKP. Prinsip tersebut menjadi sangat relevan ketika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan manusia berkelanjutan.
Alokasi APBD bagi pemajuan kebudayaan adalah wujud tanggung jawab negara dalam memberikan ruang bagi kegiatan berkesenian masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 44 huruf f yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pendanaan Pemajuan Kebudayaan” (UU No. 5/2017). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa dukungan anggaran adalah bagian dari mandat hukum, bukan semata kebijakan politis. Dengan demikian, penganggaran kebudayaan berbasis strategi kebudayaan daerah mencerminkan implementasi prinsip responsiveness dalam good governance, di mana pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat seni-budaya secara sistematis (Sedarmayanti, 2003).
Keterlibatan Dewan Kesenian Daerah (DKD) dalam penyusunan kebijakan kebudayaan merupakan wujud konkret partisipasi publik. Permendikbud No. 45 Tahun 2018, kemudian diubah dalam No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan PPKD menegaskan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa “Tim Penyusun PPKD terdiri atas unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan.” Dengan dasar ini, DKD atau seniman-budayawan sering ditempatkan sebagai unsur ahli karena kepakaran seni-budaya, sekaligus sebagai pemangku kepentingan yang mewakili komunitas seni. Hal ini sejalan dengan prinsip participation dalam good governance (Dwiyanto, 2005).
Selain partisipasi, prinsip akuntabilitas dan transparansi juga diwujudkan melalui keterlibatan DKD dalam proses penyusunan APBD. Keterwakilan masyarakat seni memungkinkan Pemerintah Daerah memastikan bahwa program kebudayaan yang dianggarkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjawab kebutuhan nyata. Mardiasmo (2009) menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah “kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya kepada pihak yang memiliki kepentingan.” Kehadiran DKD dalam forum perencanaan seperti Musrenbang kebudayaan, yang merupakan musrenbang tematik memperkuat transparansi, karena setiap tahapan perencanaan terbuka terhadap masukan dan pengawasan publik.
Berdasarkan konsideran regulasi yang saya paparkan di atas, maka keterlibatan (bukan pelibatan) DKD dalam penyusunan anggaran daerah tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip good governance. Keterwakilan ini memastikan ruang dialog sejajar antara pemerintah dan masyarakat seni-budaya, sehingga kebijakan yang lahir lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dapat ditegaskan, bahwa good governance hanya dapat terwujud apabila ada “synergy between the state, private sector, and civil society.” Dalam kerangka ini, pemajuan kebudayaan daerah menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan melalui kolaborasi antara negara dan masyarakat seni.
Paparan di atas jelas memberikan Gambaran tentang kedudukan dari DKP. Meskipun dalam prakteknya peran DKP tidak seideal seperti dalam regulasi yang dapat doirujuk tersebut karena terdapat keraguan bahwa DKD bukan merupakan perangkat Daerah yang dapat secara langsung mengelola alokasi anggaran. Ini dapat dipahami karena konsideran regulasi utama, yaitu UU 5/2017 tidak menyebut “Dewan Kesenian” secara eksplisit, namun mewajibkan pelibatan masyarakat dan menugaskan Pemda menyiapkan pendanaan/kelembagaan kebudayaan. Itulah yang dipakai sebagai dasar pembentukan/penegasan DKD lewat produk hukum daerah.
Apakah DKD mewakili Masyarakat?
Partisipasi masyarakat menjadi prinsip pokok dalam good governance. Dwiyanto (2005) menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan berfungsi untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi mekanisme pengawasan sosial. Dalam konteks kebudayaan, partisipasi berarti melibatkan komunitas seni, budayawan, dan lembaga kebudayaan dalam perencanaan hingga evaluasi program. Hal ini memastikan bahwa arah pembangunan kebudayaan tidak didominasi oleh perspektif birokrasi semata, tetapi juga mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan.
Ditegaskan keterlibatan Masyarakat yang diwadahi dalam tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Di mana dalam penyusunan itu, tim harus terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan masyarakat berkompetensi di bidang kebudayaan. Ketentuan ini menjadi dasar legal formal pelibatan Dewan Kesenian Daerah (DKD) atau seniman sebagai unsur ahli dan pemangku kepentingan (baca stakeholder)
Dari ini, terdapat kontradiksi dalam proses penganggaran yang sering ketelibatan Masyarakat sangat marginal, tetapi dalam peran DKP seolah-olah mendapatkan kesempatan yang luas untuk terlibat. Padahal proses penentuan dilakukan sendiri oleh perangkat Pemerintah (baca Daerah). Meskipun dalam hal ini, DKD dianggap mewakili tetapi DKP merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi seniman dan budayawan. Maka pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan penguatan pemajuan kebudayaan melalui berkesenian dilaksanakan dinas atau OPD yang diberi mandat.
Dalam kerangka good governance, DKD dapat dilihat sebagai representasi masyarakat sipil yang berperan ganda, yaitu pertama, sebagai unsur ahli karena memiliki kepakaran dalam bidang seni-budaya; kedua, sebagai pemangku kepentingan karena mewakili komunitas seni yang terdampak langsung oleh kebijakan kebudayaan. Melalui keterlibatan dalam penyusunan PPKD, RPJMD, hingga RKPD, DKD memperkuat prinsip participation dan accountability dalam perencanaan anggaran daerah. Kerangka good governance dalam pemajuan kebudayaan memperlihatkan pentingnya sinergi antara negara dan masyarakat.
Partisipasi DKD bukan hanya aspek prosedural, melainkan bagian dari mekanisme tata kelola yang memastikan legitimasi kebijakan publik. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat seni dalam penyusunan APBD tidak sekadar memenuhi prinsip demokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas kebijakan kebudayaan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan adalah arena praksis good governance yang menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat.
Memang, secara hukum DKD biasanya dibentuk lewat SK/Perda/Perkada sehingga diakui negara. Namun, legitimasi formal belum tentu sama dengan legitimasi sosial di mata seniman/budayawan. Supaya DKD benar-benar diterima dan diakui sebagai representasi masyarakat seni dalam proses penyusunan anggaran daerah, ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi, yaitu pertama DKD sebaiknya tidak dibentuk hanya “top-down” lewat SK Kepala Daerah, tetapi melibatkan musyawarah komunitas seni di tingkat daerah. Dua, pemilihan anggota/pengurus dilakukan melalui forum seniman/budayawan lintas disiplin (musik, teater, tari, rupa, sastra, film, dll.), sehingga ada perasaan “kami memilih” bukan “ditunjuk pemerintah”. Maka Jika proses rekrutmen transparan dan akomodatif, maka DKD akan dianggap benar-benar mewakili aspirasi masyarakat seni, bukan sekadar kepanjangan tangan birokrasi.
Meskipun DKD secara sosiologis belum diakui oleh Masyarakat kelompoknya, maka perlu membuka akses informasi tentang program, peran, dan keterlibatannya dalam perencanaan anggaran. Masyarakat seni harus tahu bagaimana aspirasi dihimpun, disalurkan, dan diperjuangkan dalam forum OPD maupun Musrenbang. Misalnya, setiap usulan dari DKD bisa dipublikasikan lewat forum diskusi terbuka, laporan publik, atau media sosial resmi, sehingga ada akuntabilitas horizontal kepada komunitas seni. Dengan demikian maka DKP bukan lagi menyelenggarakan praktek-praktek berkesenian tetapi melakukan penguatan dan dororongan pada pelaku seni di daerahnya.
Berkaitan dengan itu, maka DKD harus mampu mengadvokasi kebutuhan seniman dalam bahasa kebijakan. Artinya, usulan harus diterjemahkan menjadi program yang sesuai logika perencanaan APBD (misalnya berbasis indikator kinerja, output, outcome). Kemampuan manajerial ini membuat DKD dipercaya oleh komunitas seni, karena mereka tahu aspirasinya tidak hanya “didengar”, tetapi juga “diperjuangkan secara efektif”. Sehingga kelembagaan DKD yang berbadan hukum (yayasan/perkumpulan) juga bisa memperkuat legalitas dalam mengakses program hibah/bantuan pemerintah, menambah kredibilitas di mata publik.
Lebih jauh maka DKD perlu menunjukkan bahwa ia mewakili beragam komunitas seni, bukan hanya kelompok tertentu. Ini bisa dilakukan dengan membentuk komisi-komisi bidang seni (misalnya Komisi Teater, Komisi Musik, Komisi Rupa, dsb.) atau forum komunikasi reguler dengan komunitas. Dengan mekanisme ini, DKD dipandang sebagai rumah bersama, bukan “klub eksklusif” yang hanya mengakomodasi segelintir orang.
Supaya legitimat secara sosiologis, DKD tidak cukup mengandalkan dasar hukum (SK/Perda), melainkan harus membangun legitimasi partisipatif yang dibentuk secara inklusif, bekerja transparan, punya kapasitas advokasi, dan akuntabel kepada komunitas seni. Jika hal ini dijalankan, maka masyarakat seni akan mengakui DKD sebagai representasi sah dalam penyusunan alokasi anggaran APBD. Dengan begitu, DKD dapat berfungsi sebagai jembatan kepercayaan antara negara (OPD/pemerintah daerah) dan masyarakat seni-budaya.
Kontradiksi peran DKD sebagai representasi masyarakat
Dewan Kesenian Daerah (DKD) memang bukan lembaga struktural pemerintahan, sehingga tidak bisa mengelola langsung anggaran. Mekanisme keuangan daerah diatur ketat dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebut hanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat mengelola APBD. Maka DKP bergantung pada struktur pemerintahan daerah, sehingga anggaran kebudayaan biasanya ditempatkan pada OPD yang dianggap dapat mewadahi, seperti Dinas Kebudayaan (bagi provinsi/kabupaten/kota yang memilikinya secara khusus). Atau bisa ditempatkan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (jika digabung dengan sektor pariwisata), atau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (jika urusan kebudayaan dilekatkan ke pendidikan) dan atau di Badan/Dinas yang membidangi ekonomi kreatif (pada daerah tertentu).
Di sini, OPD ini yang memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA), menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta mengeksekusi kegiatan yang dianggarkan di APBD. DKD biasanya berperan sebagai mitra strategis, bukan sebagai pengelola keuangan. Sehingga anggaran kegiatan seni-budaya dialokasikan ke program dan kegiatan OPD. Contoh: Festival Seni, Workshop Budaya, Pameran, dll. Dalam hal ini, DKD kemudian dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan melalui penugasan resmi oleh OPD, dalam kerjasama dalam bentuk hibah/bantuan ke lembaga DKD (jika berbadan hukum yayasan/perkumpulan). Atau DKD menjadi tenaga ahli/mitra pelaksana dalam program OPD.
Merujuk pada mekanisme Pengelolaan Anggaran (Alur Standar APBD), keterlibatan DKD adalah memberi masukan dalam forum Musrenbang atau penyusunan PPKD, atau dalam Forum OPD di mana di situ tema berkesenian dibicarakan dan proses pengalolasian anggaran. Masukan ini diintegrasikan OPD ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD. Dengan demikian maka rencana anggaran bisa masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibahas di DPRD kemudian ditetapkan dalam APBD.
Dalam proses pertanggungjawabab, maka OPD sebagai PA mengeksekusi kegiatan bukan DKD. Jika kegiatan melibatkan DKD, bisa melalui mekanisme Kerjasama kegiatan (pagu kegiatan dikelola OPD, DKD jadi pelaksana teknis/pendukung). Atau hibah/bansos (jika DKD berbadan hukum, sesuai Permendagri No. 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah). Maka pertanggungjawaban semua realisasi anggaran dipertanggungjawabkan oleh OPD melalui laporan keuangan Pemda. Dan jika hibah diberikan ke DKD, maka DKD wajib membuat laporan penggunaan hibah sesuai aturan (termasuk bukti-bukti pengeluaran).
Dari Gambaran di atas jelas bahwa DKD tidak punya kewenangan mengelola APBD secara langsung karena bukan OPD. Peran DKD lebih ke arah advokasi, konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan teknis kegiatan. Maka untuk mengakses dana, DKD perlu bekerjasama dengan OPD pengampu, atau Membentuk badan hukum (yayasan/perkumpulan) agar bisa menerima hibah resmi. Alokasi anggaran kesenian melalui APBD selalu dikelola oleh OPD terkait kebudayaan (baca berkesenian) DKD hanya dapat berperan melalui kemitraan dan pelibatan formal yang diatur oleh OPD. Mekanisme ini sesuai prinsip good governance, karena menjamin akuntabilitas pengelolaan dana publik tetap berada di tangan lembaga struktural pemerintah.
Kebudayaan tidak bisa parsial dalam bentuk Kriya
Kalau mencermati proses penganggaran dan kebutuhan akan perkembangan berkebudayaan maka seberapa besar biayanya tidak akan mencukupi. Maka berkebudayaan tidak bisa hanya dititipkan dalam alokasi satu atau dua OPD, bahkan kepada DKP yang lebih mengedepankan ekspresi berkesenia. Lebih=-lebih bila ini merujuk pada Koentjaraningrat (1985; 2009) yang mendefinisikan kebudayaan sebagai “keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat, yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.”
Dalam hal ini wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga, yaitu wujud ide/gagasan atau sistem nilai, pengetahuan, keyakinan, wujud aktivitas (tindakan) atau pola perilaku sosial, sistem interaksi, praktik hidup sehari-hari. Dan wujud artefak (benda hasil karya) atau hasil fisik seperti seni, teknologi, dan peralatan hidup. Dari definisi ini jelas bahwa kebudayaan adalah ruang hidup yang sangat luas dan tidak terbatas pada kesenian saja. Seni hanyalah salah satu bagian (wujud artefaktual/ekspresi estetis) dari keseluruhan kebudayaan.
Jika kebudayaan didefinisikan seluas itu, maka mustahil kebudayaan hanya “diwadahi” oleh DKD (Dewan Kesenian Daerah) atau DKP (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). Ada beberapa hal menjadi landasan terkait, yaitu bahwa cakupan terlalu luas, kebudayaan mencakup bahasa, sistem religi, sistem kekerabatan, hukum adat, sistem ekonomi tradisional, bahkan sistem pengetahuan lokal. Hal-hal ini tidak mungkin seluruhnya ditangani oleh lembaga kesenian saja. Sedang kesenian hanyalah bagian dari kebudayaan maka DKD secara fungsi lebih spesifik pada seni dan ekspresi budaya, sementara dimensi kebudayaan yang lain melampaui itu (nilai, norma, sistem sosial).
Jika seluruh kebudayaan diwadahi hanya oleh DKP (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), ada risiko kebijakan menjadi bias pariwisata atau festivalisasi seni, sehingga mengabaikan aspek nilai, etika, dan sistem sosial yang menjadi inti kebudayaan. Dengan demikian peran ideal DKD dalam bingkai kebudayaan adalah DKD sah dan penting sebagai representasi bidang seni dalam ekosistem kebudayaan. Namun, ia hanya salah satu unsur dalam pemajuan kebudayaan (UU 5/2017 menetapkan 10 objek pemajuan kebudayaan, termasuk bahasa, manuskrip, adat istiadat, permainan tradisional, dan lain-lain). DKD dapat memberi kontribusi signifikan pada dimensi seni (salah satu objek kebudayaan), tetapi tidak bisa mewakili seluruh dimensi kebudayaan sebagaimana didefinisikan oleh Koentjaraningrat.
Dengan merujuk pada Koentjaraningrat, dapat ditegaskan bahwa Kebudayaan tidak sama dengan (≠) Kesenian. Seni adalah bagian, bukan keseluruhan kebudayaan. Dalam hal ini karena wadah seperti DKD/DKP hanya bisa berfungsi untuk sebagian aspek (seni dan ekspresi budaya). Untuk mengelola kebudayaan secara komprehensif, diperlukan ekosistem kelembagaan yang lebih luas, yang meliputi lembaga adat, lembaga penelitian, komunitas bahasa, pendidikan, organisasi keagamaan, hingga OPD lintas sektor. Hal ini sesuai dengan semangat UU 5/2017 yang mengatur pemajuan kebudayaan melalui mekanisme partisipasi lintas pemangku kepentingan, bukan hanya satu lembaga formal.
Dengan demikian berdasar apa yang disampaikan Koentjaraningrat, kebudayaan mencakup gagasan, tindakan, dan karya manusia dalam arti luas. Oleh karena itu, kebudayaan tidak bisa diwadahi sepenuhnya oleh Dewan Kesenian Daerah (DKD) maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DKP), karena lembaga ini hanya menyentuh salah satu aspek, yaitu seni. Kebudayaan memerlukan wadah dan mekanisme partisipasi yang lebih holistik, melibatkan berbagai aktor sosial, agar pengelolaan kebudayaan tidak tereduksi menjadi sekadar pengelolaan seni atau pariwisata.
Akhiran
Berkesenian pada dasarnya hanyalah salah satu unsur kecil dari kebudayaan. Mengacu pada Koentjaraningrat, kebudayaan mencakup keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, penyusunan anggaran untuk kegiatan seni, betapapun pentingnya akan kehilangan makna strategis apabila Pemerintah Daerah tidak memiliki komitmen holistik dan komprehensif dalam membangun kebudayaan secara menyeluruh. Pemajuan seni seharusnya menjadi bagian dari rekayasa sosial yang lebih besar untuk menumbuhkan peradaban, bukan sekadar agenda teknis yang terfragmentasi.
Dalam kerangka ini muncul pertanyaan mendasar, apakah Dewan Kesenian Daerah (DKD) sungguh-sungguh mewakili masyarakat seni, ataukah hanya berfungsi sebagai mitra pelaksana salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD)? Ketika anggaran publik untuk seni dialokasikan melalui OPD dan DKD terlibat sebagai representasi masyarakat sekaligus bagian dari mekanisme belanja publik, muncullah kontradiksi peran. Di satu sisi, DKD diharapkan memperjuangkan aspirasi seniman dan di sisi lain, ia terikat pada logika birokrasi anggaran yang membatasi ruang geraknya.
Situasi ini kerap melahirkan persoalan tentang siapa yang berhak mengakses, menggunakan, dan mengawasi alokasi anggaran untuk kesenian. Perseteruan dalam penggunaan anggaran antara pemerintah, DKD, dan komunitas seni seringkali lebih menonjol dari pada usaha bersama membangun kebudayaan. Padahal, kebudayaan tidak bisa dipahami secara parsial hanya dalam bentuk kriya, pertunjukan, atau festival. Ia merupakan keseluruhan sistem hidup bermasyarakat yang mencakup nilai, norma, dan cara hidup sehari-hari. Jika anggaran hanya diarahkan pada sektor seni tertentu, maka dimensi kebudayaan yang lain akan terabaikan.
Dengan demikian, alokasi anggaran yang ditujukan semata-mata kepada DKD atau OPD pengampu tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang bijaksana dalam kerangka pembangunan kebudayaan. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan Masyarakat sebagai subjek utama kebudayaan memiliki ruang nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kebudayaan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah di manakah posisi masyarakat dalam membangun kebudayaan dan berkesenian? Tanpa keterlibatan masyarakat secara langsung dan substantif, setiap alokasi anggaran hanya akan menjadi instrumen administratif, bukan driver sejati bagi tumbuhnya peradaban yang berakar pada budaya lokal.
—–
*Penulis merupakan petani kopi yang tinggal di Desa Sumbersuko, lereng Timur Gunung Kawi, Kabupaten Malang mendalami Sosiologi dan kandidat PhD dalam Ilmu SosialBbudaya dari Unmer, Malang. Penggagas komunitas Petani Mandiri Lereng Kawi.