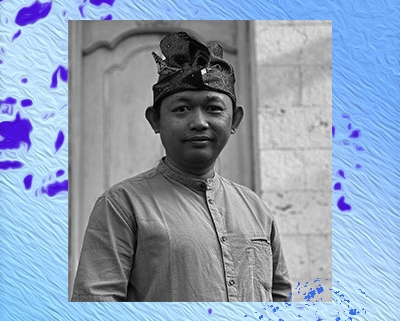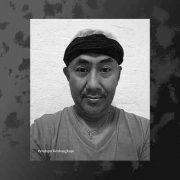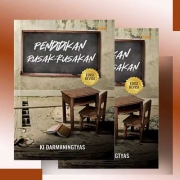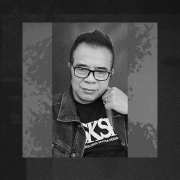Malam Jumat Kliwon sebagai Pengetahuan yang Menubuh dan Pergelaran Keyakinan
Oleh Purnawan Andra*
Di banyak wilayah Nusantara, terutama di Jawa, malam Jumat Kliwon memiliki posisi simbolik yang unik dan kompleks. Ia bukan sekadar penanda waktu dalam kalender Jawa yang memadukan sistem penanggalan Islam dan perhitungan pancawara-sapta wara, melainkan juga sebuah ruang simbolik yang sarat makna spiritual, sosial, dan kultural.
Secara antropologis, Jumat Kliwon adalah simpul dari dua sistem penanggalan: kalender Islam (Jumat) dan kalender Jawa (Kliwon). Dalam sistem pasaran Jawa, Kliwon merupakan salah satu dari lima hari siklus mingguan (Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon) yang membentuk sistem penanggalan weton. Perjumpaan Jumat dan Kliwon dianggap sebagai momentum dengan intensitas spiritual tinggi.
Dalam tradisi kejawen dan spiritualitas Nusantara, Jumat Kliwon adalah waktu terbaik untuk melakukan laku tapa, ritual penyucian batin, atau meditasi diri. Seturut pemikiran liminality-nya Victor Turner, malam Jumat Kliwon adalah ambang waktu yang mengguncang batas-batas antara yang profan dan sakral.
Namun, masyarakat modern, yang disetir oleh logika industrial dan media populer, malam ini kerap diasosiasikan dengan dunia gaib, praktik mistik, dan laku spiritual tertentu. Ia dijadikan medium untuk menjual rasa takut, bukan rasa tafakur. Tayangan televisi dan kanal YouTube menyajikan tontonan horor dan mitos hantu yang menggiring publik pada sensasi kengerian. Hal ini justru menyingkirkan dimensi reflektif dari hari tersebut.
Maka, pertanyaannya kemudian, jika malam Jumat Kliwon selama ini dicitrakan sebagai malam horor, malam ‘angker’, dan dikonstruksi lewat narasi media sebagai waktu makhluk halus, maka siapa yang membentuk narasi itu? Untuk kepentingan siapa ketakutan kolektif terhadap malam ini dilanggengkan? Siapa yang diuntungkan dari narasi menyeramkan soal Jumat Kliwon? Apakah ini juga merupakan bentuk produksi pengetahuan yang dimanfaatkan untuk mengatur tubuh dan perilaku masyarakat?
Mungkin kapital budaya populer yang beroleh keuntungan atas hal tersebut. Tapi ada logika pembangunan budaya warisan kolonial juga yang bekerja di sini, yaitu logika menjinakkan laku spiritual masyarakat lokal dengan membungkusnya sebagai sesuatu yang “mistik”, irasional, atau bahkan berbahaya. Perspektif postkolonial menyebutnya sebagai strategi epistemik untuk mendeligitimasi cara hidup dan spiritualitas lokal agar bisa diganti dengan sistem nilai Barat yang lebih “modern”, linear, dan produktif secara ekonomi.
Praktik Sosial
Namun pada kenyataannya, masyarakat lokal tidak pernah sepenuhnya tunduk pada logika ini. Kita bisa melihat, misalnya, bagaimana malam Jumat Kliwon dimaknai secara produktif oleh komunitas spiritual, seniman dan budayawan. Di beberapa daerah seperti Banyuwangi, Gunung Kidul, atau pedalaman Purbalingga dan tempat-tempat lainnya, Jumat Kliwon kerap dijadikan momen untuk menggelar pertunjukan wayang, ritual slametan, atau tirakat malam.
Dalam kajian antropologi Clifford Geertz, malam Jumat Kliwon merupakan bagian dari struktur simbolik masyarakat. bukan hanya sebagai tanda-tanda religiositas, tetapi sebagai sistem makna yang mereproduksi tatanan sosial dan struktur kekuasaan. Malam ini menjadi ruang alternatif ekspresi religiositas lokal, spiritualitas kritis, bahkan rekonsiliasi ekologis, sekaligus menjadi ruang negosiasi antara manusia, arwah leluhur, dan jagat raya.
Malam Jumat Kliwon menjadi cara masyarakat membangun relasi dengan waktu, ruang, dan kekuasaan—baik kekuasaan spiritual, sosial, maupun politik. Dengan kata lain, praktik-praktik yang melekat pada malam Jumat Kliwon adalah bagian dari performance of belief—pementasan keyakinan—yang memperkuat identitas komunal.
Praktik-praktik ini merupakan bentuk cultural performance yang menegosiasikan makna Jumat Kliwon secara aktif, bukan pasif. Inilah ruang yang dalam kajian performance studies disebut sebagai restored behavior, yaitu praktik sosial yang tidak hanya mereplikasi tradisi, tetapi juga mencipta dan mentransformasi makna dalam konteks kini.
Pergelaran
Peristiwa-peristiwa ritual semacam itu tak bisa dipisahkan dari dinamika pergelaran, seperti adanya elemen pertunjukan, struktur dramatik, transformasi identitas, dan efek liminal. Malam Jumat Kliwon adalah saat ketika batas-batas norma dan realitas dikaburkan, di mana ruang menjadi magis, waktu menjadi lindap, dan tubuh-tubuh warga menjadi medium antara yang kasat dan yang tidak kasat. Dalam fase liminal ini, seturut Victor Turner lagi, individu dan komunitas bisa mengalami transformasi simbolik yang memungkinkan negosiasi ulang atas struktur sosial—baik itu melalui ketakutan, penghayatan spiritual, maupun pembebasan personal.
Di satu sisi, kajian Lono Simatupang tentang pergelaran dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa pertunjukan atau ritual budaya bukan sekadar hiburan, tetapi juga “metafora sosial” yang merepresentasikan pergeseran, resistansi, atau reproduksi tatanan sosial. Dalam perspektif ini, malam Jumat Kliwon bisa dibaca sebagai cultural staging—pementasan budaya yang menyimpan potensi rekonstruksi narasi.
Ketika masyarakat menolak modernitas yang terlalu rasional dan tidak memberi ruang pada spiritualitas lokal, malam Jumat Kliwon menjadi ruang oposisi simbolik terhadap kapitalisme waktu dan kolonialisme kalender Barat. Malam ini bukan malam terkutuk, melainkan waktu yang penuh daya, penuh makna.
Dengan demikian, malam Jumat Kliwon bisa dibaca sebagai panggung kultural tempat terjadi negosiasi identitas, spiritualitas, dan resistensi terhadap hegemoni narasi tunggal modernitas. Apa yang terjadi dalam ritual malam itu bukan sekadar “acara mistik”, tetapi bentuk praksis budaya yang menyambungkan manusia dengan ruang batin, kosmos, dan sejarah. Bahkan, jika kita masuk lebih jauh ke wilayah semiotik, Jumat Kliwon bisa dimaknai sebagai simbol dari krisis dan kelahiran kembali, chaos dan keteraturan, gelap dan terang—sebuah dialektika yang selalu hidup dalam kebudayaan Jawa.
Pengetahuan yang Hidup
Sayangnya, dalam wacana pembangunan nasional, narasi-narasi lokal seperti malam Jumat Kliwon cenderung digeser, dipinggirkan, atau disimplifikasi. Logika pembangunan modern menganggap waktu harus linier, produktif, efisien. Tidak ada ruang bagi waktu yang “tak produktif” seperti malam Jumat Kliwon, yang dianggap pasif, hening, atau bahkan jadi sesuatu “yang lain”.
Di sinilah kita bisa membaca malam Jumat Kliwon sebagai bentuk perlawanan terhadap logika pembangunan yang terlalu teknokratis. Ia adalah ingatan budaya yang menolak dilupakan. Ia adalah bentuk pengetahuan lokal yang menolak dihilangkan.
Dalam kerangka ini, revitalisasi makna malam Jumat Kliwon bisa menjadi strategi kebudayaan yang penting untuk menghadirkan kembali embodied wisdom—pengetahuan yang hidup di tubuh, waktu, dan ruang masyarakat.
Namun revitalisasi semacam ini tidak bisa dilakukan dengan cara romantisasi semata. Kita tak bisa hanya menganggap malam Jumat Kliwon sebagai “warisan leluhur” tanpa memahami konteks sosial-politik dan epistemologinya.
Kita perlu membaca ulang simbol, memahami pergelarannya, dan mengintegrasikannya ke dalam praktik kebudayaan kontemporer yang kritis dan reflektif. Ini bisa menjadi bagian dari strategi dekolonisasi waktu: menolak narasi tunggal soal modernitas, dan mengakui keberagaman cara hidup dan cara memaknai waktu.
Narasi pemaknaan semacam ini penting untuk memberi tempat pada ruang-ruang spiritual dimaksud, terutama dalam konteks kebijakan pemajuan kebudayaan. Mengikuti kerangka pikir strategi kebudayaan, seperti yang didorong oleh kebijakan UNESCO tentang safeguarding intangible cultural heritage, praktik budaya seperti tirakat Jumat Kliwon seharusnya dilihat sebagai warisan takbenda yang hidup dan dinamis. Ia bisa menjadi medium refleksi ekologis, spiritual, dan sosial yang justru sangat dibutuhkan di tengah krisis modernitas hari ini.
Malam Jumat Kliwon adalah representasi dari perjuangan manusia dalam mencari makna hidup di tengah kekacauan zaman. Ini adalah waktu ketika tradisi dan ritual kembali memberi arti pada kehidupan, menekankan bahwa nilai spiritual tidak dapat dipisahkan dari identitas kultural dan pengalaman komunal. Dengan demikian, diskusi tentang waktu dalam tradisi ini tidak hanya menjadi topik yang terkomodifikasi, tetapi juga sebuah panggilan untuk refleksi diri yang mengembalikan keseimbangan antara nilai-nilai religiositas dan eksistensialisme.
Kita tidak harus menjadi mistikus atau penganut kejawen untuk bisa menghargai Jumat Kliwon. Cukup menjadi manusia yang mau menafsir ulang dunianya dengan jujur, jernih, dan penuh kasih. Karena mungkin, di balik gelap malam Jumat Kliwon, ada terang spiritual yang selama ini kita abaikan.
Bukankah pertanyaan paling penting yang bisa kita ajukan adalah beranikah kita memulihkan malam Jumat Kliwon dari kutukannya sebagai malam horor menjadi malam spiritual-politik yang merawat hubungan kita dengan yang tak kasat, dengan sejarah, dengan bumi dan dengan diri kita sendiri?
—-
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, Pamong Budaya di Kementerian Kebudayaan.