Gedebok Diganti Jerami (Kisah Mendalang Bahasa Jerman di Frankfurt)
Oleh Sigit Susanto
Gedebok Pisang Diganti Jerami Gandum
Jerami kering dari dahan gandum itu diikat dengan tali diletakkan memanjang di atas panggung sebanyak empat ikatan. Itulah alat penancap wayang kulit sebagai pengganti gedebok pisang.
Jerami kering mengganti gedebok pisang ini menjadi fokus di pikiran saya, karena saya belum yakin, apakah jika wayang ditancapkan, bisa berdiri dengan tegak, tidak mudah ambruk? Wayang Kumbokarno dan gunungan yang paling besar posturnya aku coba tancapkan, ternyata wayang tetap berdiri kokoh. Senyum saya meleleh. Di luar dugaan saya sebelumnya.
Hati saya langsung plong. Logikanya, kalau postur wayang berat dan besar saja bisa berdiri kokoh, apalagi wayang yang posturnya lebih kecil, seperti Shinta dan Kunti pasti aman.
Pada 20 Agustus 2022, Sabtu sore pukul 13.00 taman di belakang gedung tua Weltkultur Museum, Metzler Park, Schaumainkai 29-37 Frankfurt, Jerman masih sepi. Dua tenda besar mulai didirikan untuk pagelaran wayang kulit dan seperangkat gamelan. Enam tenda lain menyusul berdiri berderet menjajakan Indonesia food, seperti sate lontong, sate padang, asinan, tempe mendoan, nasi campur, es cendol, kue nagasari dan lainnya.
Seminggu sebelum acara dimulai, saya dikirimi foto jerami kering itu lewat Email oleh kurator Museum, Matthias dan Vanessa. Seketika saya pesimis sekaligus geli, maka foto itu saya kirimkan ke grup whatsapp teman-teman di Jawa. Mereka rata-rata berkomentar; oh lucu, kok aneh, apa gak ada pohon pisang?

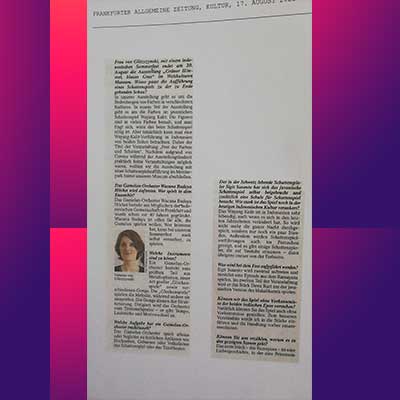

Pengumuman acara dalang di koran FAZ (Frankfurter Allgemeinen Zeitung). (Sumber: Penulis)
Memang di Swiss saya juga memakai Jerami gandum itu, tetapi tidak dalam bentuk gulungan seperti itu, melainkan saya ikat di rak kayu memanjang. Dan jerami itu cukup kuat, jika wayang ditancapkan, akan berdiri stabil. Sebab kiri dan kanan ada kayu. Lha, jerami kering di Frankfurt ini total jerami tebal dan padat diikat tali.
Merasa jeraminya aman, maka saya mulai menancapkan wayang-wayang lain yang lebih kecil, indah dan warna-warna di samping kanan dan kiri. Beruntung Pak Acep Soemantri, Konsul Jenderal RI untuk Frankfurt di Wisma Indonesia, tempat saya menginap menyodorkan titipan dari Ibu Annegret Haake, seorang nenek berusia 89 tahun sekoper berisi berbagai wayang dengan kualitas tinggi.

Mendalang dengan jerami – 1. (Sumber Foto: Weltkultur Museum Frankfurt)
Sepasang wayang dengan sosok Rama dan Shinta dengan ornamen beda dan halus. Belakangan setelah bertemu Ibu Annegret sendiri, ia sebut, itu wayang ukur. Biasa diikat dengan tali dan digantung di dinding ruangan. Perajin wayangnya masih keluarga seniman batik Winotosastro di Yogyakarta.
Sebagai catatan, Ibu Annegret itu pencinta wayang di Frankfurt dan lebih dari 400 koleksi wayangnya dihibahkan ke Weltkultur Museum. Saya sempat mengunjungi sebagian kecil koleksi wayangnya di Museum Weltkultur itu dan saya perkirakan wayang-wayang itu mempunyai nilai estetika tinggi. Ia menuturkan kepada saya, bahwa wayang yang ia miliki paling tua dibuat tahun 1940.
Setelah yakin jerami aman, saya mulai melafalkan secara pelan sambil jalan di taman dekat lokasi acara dan kadang saya duduk di bangku sambil komat-kamit sendiri. Di kereta api ICE Jerman yang membawa saya dari Swiss ke Frankfurt pun saya sering komat-kamit. Tapi tak ada orang curiga, karena setiap penumpang kereta masih diharuskan memakai masker. Masker punya arti ganda buat saya, selain menangkal virus, juga untuk menyembunyikan latihan menghafal cerita.

Mendalang dengan jerami – 2. (Sumber Foto: Weltkultur Museum Frankfurt)
Nah, di bangku taman itu saya sengaja menyepi dan menjauh dari kerumunan. Tentu saya menghindari, jika saya melafalkan, nanti kedengaran orang. Karena saya sering duduk sendiri di bangku dekat panggung pagelaran wayang itu, ada beberapa orang Indonesia mengira sang dalang sedang semadi minta izin yang bahurekso atau sedang mengusir setan yang hendak mengganggu. Lebih-lebih saya sudah pakaian lengkap dengan blangkon, jarit, baju surjan dan keris menempel di belakang. Orang-orang mengira saya sedang melakukan ritual sakral dalam pagelaran wayang.
Bercerita dalam bahasa Jerman tidaklah mudah, harus sesuai grammatik yang benar. Sejam menjelang acara, saya sudah tidak berlatih menghafal lagi. Saya percaya diri dan berdoa semoga tidak macet di tengah jalan. Petugas bagian sound system mendatangi saya untuk diberi mikrofon wireless yang melilit di belakang kepala saya. Saya mendadak merasa seperti penyanyi Rock yang segera harus bergoyang. Dengan petugas itu kami berjanji, jika saya akan mulai main, untuk memberi kode dengan ibu jari diacungkan tinggi, maka ia akan memutar musik gamelan jenis palaran dalam CD (Compact-Disc).
Pertengahan Juni 2022, telepon genggam saya kemasukan pesan dari Konsulat Jenderal di Frankfurt, Pak Acep Soemantri. Ia menanyakan, apakah ini Sigit dalang bahasa Jerman? Saya mengiyakan dan saya ditawari untuk mendalang di Frankfurt. Tak banyak berpikir saya iyakan saja. Dalam hati saya masih menimbang, bagaimana saya mencari pinjaman wayang yang asli? Tetapi Pak Konjen ini sangat baik hati, ada lima wayang kulit yang kurang dan ia langsung pesankan dari perajinnya di Yogyakarta. Wayang-wayang ini pada akhirnya saya minta dan diberikan untuk pertunjukkan saya di Swiss.
Bersyukur saya punya teman dalang Ki Sri Joko Wiyono, asal Solo sebagai pegawai PTRI (Perutusan Tetap Republik Indonesia) di Jenewa. Saya meminjam Bimo, Kumbokarno dan Gunungan. Dari KBRI Bern Swiss saya pinjam Rama, Kunti, Gatot Kaca dan yang lain.
Merasa wayang cukup untuk memainkan dua lakon: Ramayana dan Dewa Ruci yang masing-masing durasi tayang sekitar 20 menit, maka saya mulai menyusun ceritanya. Saya ambil dari berbagai sumber di Google dan youtube pada pagelaran Ki Mantep Soedarsono. Saya belajar dua suluk dari Ki Sugito HS dari Magetan lewat Whatsapp.
Setelah dua lakon saya tulis dalam bahasa Jerman, saya minta bantuan koreksi dari Mbak Lydia Kieven, perempuan Jerman yang menekuni budaya Jawa.
Sejak saya mendapat tugas mendalang ke Frankfurt itu saya setiap hari menghafalkan dua lakon itu. Terutama bangun pagi sampai siang saya hafalkan lakon: Ramayana dan Menjelang tidur saya hafalkan lakon Dewa Ruci. Sering saya dianggap orang sinting, karena saat naik sepeda menuju atau pulang kerja saya menghafalkan di perjalanan dan orang yang berpapasan dengan saya sering melihat saya begitu lama.
Kembali ke arena museum di Frankfurt itu, ada tenda sebelah kiri seperangkat gamelan sudah dipersiapkan dan disusul para penabuhnya berdatangan dari komunitas Wacana Budaya. Saya sebagai tamu uluk salam kepada mereka, saya salami mereka satu per satu.
Seorang bernama Pak Hari berasal dari Gunung Kidul. Ia memainkan kendang dan anaknya memainkan gong. Lebih jauh ia mengaku sudah 52 tahun berada di Frankfurt. Ia mulai aktif bergabung latihan kerawitan sejak sembilan tahun lalu. Lebih tepatnya setelah ia memasuki pensiun, sebab kalau masih bekerja sulit mencari waktu libur.
Sekitar 13 an penabuh gamelan ini memang rata-rata sudah berusia senja. Pak Acep Soemantri saat makan malam di Wisma Indonesia pernah bercerita, bahwa Jerman saat ini memerlukan 300 an perawat dari Indonesia. Sebelumnya Jerman tak mau mempekerjakan perawat Indonesia, alasannya berdasar data di WHO (World Health Orgnisation) Indonesia sendiri kekurangan perawat. Ternyata data di WHO itu tidak diupdate, yang terbaru bahwa Indonesia surplus tenaga perawat. Sejak data itu diperbaiki, maka perawat dari Indonesia diminati pemerintah Jerman. Para penabuh gamelan ini termasuk para perawat yang datang zaman dulu dan kini sudah sepuh-sepuh tetap setia dengan budayanya sendiri.
Waktu merangkak seiring berdatangannya warga Jerman setempat dari berbagai sudut taman yang terbuka. Ketika gamelan itu ditabuh, saya masih duduk di bangku dekat jalan raya dekat sungai Main. Cukup terharu secara optis mataku menatap landskap Eropa, tapi secara pendengaran seperti saya terbawa di pedesaan Jawa mendengarkan lantunan gamelan.
Matthias datang memberitahu, pertama dirinya akan bicara atas nama panitia dan menjelaskan susunan acara di atas panggung persis di belakang tempat saya akan mendalang, dilanjutkan Vanessa menjelaskan tema Pesta Warna dan Bayangan (Fest der Farben und Schatten) serta lakon cerita Ramayana secara singkat. Kemudian sambutan dari Pak Acep Soemantri sebagai Konsul Jenderal RI untuk Frankfurt. Secara ringkas sambutan berbahasa Inggris Pak Acep itu bahwa pesta musim panas ini untuk memperingati dua peristiwa, yakni HUT Kemerdekaan RI ke 77 tahun dan merayakan hubungan bilateral Indonesia-Jerman yang sudah berumur 70 tahun.
Tiga sambutan selesai dilanjutkan bertalunya gamelan secara live, disusul saya harus mendalang. Sebelumnya saya sudah menyiapkan para tokoh wayang yang akan saya pakai dalam lakon pertama yakni Ramayana, maka beberapa tokoh wayang untuk lakon berikutnya Dewa Ruci saya tancapkan di jerami sebagai hiasan.
Beruntung saya mengenal Mbak Etty Prihantini asal Salatiga yang domisili di Frankfurt. Ia mendadak saya beri tugas menjadi asisten saya, jika saya tiba-tiba memerlukan wayang yang hendak saya mainkan, mungkin tertindih wayang lain, maka ia harus membantu saya menyiapkannya. Wajahnya pucat, ketika saya minta membantu, tapi dengan senyumnya yang ragu, dia siap duduk di belakang saya persis, menjadi kernet saya. Ia lakukan dengan baik.
Momen menegangkan pertama tiba, saat saya dipersilakan mendalang. Saya maju diiringi tepuk tangan penonton dari depan yang sudah penuh dan ibu jari saya naikkan ke arah petugas sound system, gamelan palaran membuncah, kalimat pertama yang saya ucapkan suluk pendek melodius
Tontang Wening Samodra, Ngalangut Tanpa Pagut, O…
Saya lanjutkan pembuka narasi kisah Ramayana dalam bahasa Jerman;
Im Königreich Alengka gibt es eine hektische Diskussion. Der Dämon König Rahwana möchte unbedingt eine Hübsche Frau haben und Kala Marica hat ihm Empfohlen, Shinta zu heiraten.
(Di kerajaan Alengka sedang ada perdebatan sengit, raja raksasa Rahwana ingin punya istri cantik dan Kala Marica merekomendasikan untuk menyunting dewi Shinta)
Gunungan saya cabut dan gerakkan, lalu saya keluarkan Rahwana dengan tawa lebar. Disusul Kumbokarno, Indrajit dan Kala Marica. Di saat Kala Marica menyebut, bahwa Shinta ini sangat cantik, saya coba gerakan Rahwana salto dan syukurlah saltonya berhasil.
Sejujurnya saya belajar saltokan wayang ini berkat nonton youtubenya Sigid Ariyanto Channel dan akun youtube Dalang Kangko Vlog. Kesulitan saya, karena salto tanpa layar kelir yang bisa sebagai sandaran.
Peragaan kisah Ramayana selesai, nyaris tanpa ada musibah di perjalanan, misalnya lupa atau ada peristiwa yang terlompati. Tepuk tangan gemuruh dari penonton yang berada di depan, samping kanan dan belakang.
Saya undur diri ke belakang panggung dengan perasaan haru dan gembira. Wajah-wajah orang dekat saya seperti almarhumah ibu saya yang jaritnya saya pakai bermunculan. Sebelum memainkan Ramayana ini, saya beranggapan, jika lakon ini bisa dilalui dengan mulus, niscaya lakon kedua bisa mulus juga. Sebab saya akui cerita Ramayana ini cukup panjang dan banyak konflik dengan narasi dan dialog yang cukup rumit. Bersyukurlah ujian berat itu telah lewat.
Tak lama orang-orang Jerman maupun Indonesia mendekat. Orang Jerman lebih mendekat ke wayang baik yang ditancapkan di jerami depan maupun di panggung belakang yang juga disediakan wayang untuk hadirin. Sedang penonton dari Indonesia yang kebanyakan cewek sambil menggandeng pasangan bulenya, minta foto bersama saya.
“Boleh saya foto dengan Pak Dalang?” pintanya.
Dek, hati saya disebut dalang. Wajah-wajah perempuan Indonesia berbinar ceria, sambil sedikit menjelaskan kepada pasangan bulenya dengan bangga. Ada seorang perempuan muda berwajah ayu asal Majalengka, sambil menggandeng suaminya bule Jerman, mengaku sebagai guru TK (Taman Kanak-Kanak) dan hendak mengenalkan wayang kulit kepada murid-muridnya, sebab ia sudah pernah mengenalkan boneka kepada para muridnya.

Bersama penonton usai acara dalang. (Sumber Foto: Weltkultur Museum Frankfurt)
Beberapa anak kecil mendekat diantar ibu mereka memegang wayang dan mencoba menggerakkan. Saya ditanya oleh banyak penonton. Ada yang menanyakan tentang kisah Rahwana di Sri Lanka dan apakah ada hubungannya dengan Rangda di Bali?
Setelah istirahat sejenak dilanjutkan tetabuhan gamelan dan pagelaran wayang kulit kedua dengan lakon Dewa Ruci dimulai. Lagi-lagi suluk pendek saya mulai,
Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap katon, Lir Kincanging Alis O…
Dilanjutkan narasi pembuka:
Die Geschichte handelt von einem jungen Mann mit Namen Bima oder Broto Seno. (Kisahnya tentang seorang anak muda bernama Bima atau Broto Seno)
Saya sepintas menatap kerumunan penonton masih sama penuh sesak seperti pada lakon Ramayana. Bima mulai saya peragakan dengan gagah perkasa melawan dua raksasa Rukmuko dan Rukmokolo.
Cerita ini sebuah ujian bagi Bimo untuk mencari jati dirinya melewati pencarian kayu Gung Susuhing Angin dan Tirta Perwita Mahening Suci di tengah samodra.
Kisah diakhiri dengan bertemunya Bima dengan Dewa Kerdil bernama Dewa Ruci. Surealismenya terletak, ketika Bima yang besar itu disuruh masuk ke telinga Dewa Ruci dan bisa.
Ketika Bima ditolak hendak mendekam di dunia barunya, disuruh keluar lagi oleh Dewa Ruci dan Bima menuruti anjurannya. Sampai di sini sistem eksistensialis ala Jawa diperkenalkan dengan cara mengenali diri sendiri dan setia terhadap sang guru.
Untuk menutup cerita ini saya bilang,
“Die Geschichte ist beendet” (Ceritanya sudah tamat)
Tepuk tangan membahana. Beberapa penonton mendatangi panggung lagi. Ada yang menanyakan keris yang saya pakai, palu yang saya pakai bunyikan kotak tog dog dog dan kecrek yang terdengar lirih karena kalah dengan mikrofon yang hanya menempel di sudut mulut sebelah kiri.
Seorang ibu Jerman berpostur kurus menunjukkan Handynya dan memperlihatkan foto wayang dengan rambut api merah. Saya bilang itu raksasa Rambut Geni. Rupanya ibu itu menunjukkan foto-foto yang lain dari ponselnya. Tak disangka ada 70 an foto wayang. Ia jelaskan, di rumahnya ayahnya yang sudah meninggal mewariskan 70 an wayang kuno dari Jawa. Ibu itu bingung, hendak dibawa ke mana wayang-wayang itu. Saya sarankan, untuk terus disimpan dan dirawat.
Belakangan saya mendapatkan informasi, ibu itu hendak menghibahkan semua wayangnya ke Weltkultur Museum. Tapi Vanessa mengatakan, pihaknya sudah tak menerima hibah wayang lagi dari kolektor wayang, karena museumnya sudah penuh barang antik, dan wayang sendiri ada 400 an.
Perlahan kerumunan penonton berkurang dan saya sering gabung dengan teman-teman kerawitan untuk foto bersama dan mencicipi sate lontong. Ibu Annegret mendatangi saya untuk mengambil koleksi wayangnya yang kami pinjam sekopor. Ia memberi saya sebuah CD berisi semua koleksi wayangnya yang dihibahkan ke museum. Lelaki tua pasangan Annegret bercerita kepada saya, bahwa keluarga Winotosastro baru saja berkunjung ke Frankfurt dan Annegret cukup dekat dengan keluarganya. Lelaki itu menundukkan kepala untuk memperlihatkan baju batik cokelat yang dia pakai made in Winotosastro.

Foto bersama Konjen Acep Soemantri dan istri, Mathias, Vanessa dan Direktur Weltkultur Museum. (Sumber Foto: Weltkultur Museum Frankfurt))
Gelap memayungi kota Frankfurt dan saya bersama Krisna Diantha, wartawan Kompas untuk Swiss, kembali ke Wisma Indonesia bersama Bapak dan Ibu Konjen. Esoknya hari Minggu, kami kembali ke Swiss lagi dengan sejuta kenangan indah Frankfurt.
Petruk Lapor
Jika dirunut dari mana pertemuan saya dengan wayang kulit. Saya bisa mengingatnya, ketika masih usia sekitar lima tahun, sering menjelang subuh dibangunkan dan digendong ayah dibawa nonton goro-goro pada pagelaran wayang kulit di balai desa. Ketika masih di sekolah dasar, ayah saya punya teman seorang dalang dan wayang kulit satu kotak beserta gamelannya dititipkan di rumah saya. Sore hari ibu-ibu desa berlatih kerawitan dan secara iseng saya dan kakak saya membuka kotak wayang dan mengambil begitu saja. Saya mengambil tokoh Petruk dan saya pakai main-main. Tak disangka, esok harinya si dalang datang dan bilang ke ayah saya akan mengambil seluruh wayang sekotak, karena ia mimpi Petruknya tidak kerasan. Saya dimarahi ayah, karena lancang memainkan benda yang dianggap keramat.
Saya lahir di desa kecil Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya dengan anak-anak kampung biasa nonton wayang di hajatan orang sunatan, kawinan, sedekah desa dan acara lain. Tak hanya di desa saya saja, kadang juga di desa tetangga dan pulang pagi. Setidaknya setiap tahun ada dua kali pagelaran wayang kulit di desa saya. Pertama, sedekah desa di balai desa dan kedua di Makam Sunan Bromo di Depok juga ada pagelaran wayang kulit.
Ketika saya kuliah di Akademi Bahasa 17 Untag Semarang, saya pernah ikut kursus mendalang selama tiga bulan. Kursus wayang kulit yang berada di kompleks gedung Griss, timur gedung Wayang Orang Ngesti Pandowo, Semarang.
Sejak itu saya tak lagi bisa berinteraksi dengan wayang kulit, karena usai kuliah saya merantau ke Bali menjadi guide bahasa Jerman. Selama tujuh tahun menjadi pemandu keliling Bali mengantar turis-turis Jerman, Swiss dan Austria yang berbahasa Jerman. Akhirnya saya kecantol salah satu turis saya dari Swiss yang sekarang menjadi istri saya bernama Claudia Beck. Tahun 1996 saya meninggalkan Indonesia dan menetap di Swiss sampai sekarang sudah genap 27 tahun.
Rahwana di Dinding
Di Swiss saya dan beberapa teman perantau Indonesia mendirikan wadah ISC (Indonesia Swiss Club). Sekitar sembilan tahun silam wadah ini mengadakan acara Indonesien Abend (Malam Indonesia) di kotaku Zug. Berbagai atraksi budaya ditampilkan, seperti tarian Legong Bali, Demonstrasi Memahat Patung, Musik dan jual wayang kulit Bali.
Berawal dari melihat banyak wayang kulit Bali ditempel di dinding ruangan gedung, saya geregetan. Sebagai anak desa yang biasa melihat wayang itu live, kok di sini ditempel di tembok? Saya ingin memeragakan wayang-wayang itu. Usul saya diterima panitia, asal semua peralatan saya yang siapkan sendiri.
Mulailah saya membeli kayu, gergaji, kain, jerami, kotak dan cat. Saya membuat semacam rak kayu berkaki empat dengan lebar satu meter. Paling atas saya taruh jerami dan diikat kuat sebagai pengganti gedebok pisang. Kelir putih dan ujungnya merah saya jahit dengan tangan. Kecrek saya buat dari kaleng bekas yang saya potong-potong. Saat gladi resik di cafe d`Bauhütte seminggu sebelum berangkat ke Frankfurt, ada penonton Swiss yang khusus ingin tahu suara kecrek itu dari bahan apa dan bagaimana cara menabuhnya.
Wayang? Semua wayang yang saya pakai adalah jenis wayang suvenir yang saya beli di Malioboro, Yogyakarta. Lakon perdana adalah Ramayana, cerita yang paling mudah dan sudah di luar kepala, karena saat saya di Bali sering mengantar turis Jerman ke tarian kecak yang isinya cerita Ramayana. Cuma saya kekurangan dua tokoh wayang, Rahwana dan Hanoman.
Seorang teman asal Tulung Agung di Swiss mengontak saudaranya untuk segera kirim Hanoman dari sana. Harap-harap cemas, seminggu acara dimulai Hanoman belum tiba. Bersyukurlah tiga hari jelang acara, wayang Hanoman tiba. Untuk Rahwana, terpaksa saya akan memakai wayang Bali yang sedang dijual dan ditempel di dinding. Untungnya jelang atraksi mendalang dimulai, Rahwana tak ada yang membeli Rahwana, sehingga aman bisa saya pakai.
Celakanya, saat pagelaran dimulai dan tiba pertemuan Rahwana dengan Shinta, saya cari Rahwana tak ada di samping saya. Padahal saya sedang memainkan wayang, musik gamelan dari CD tetap bergema. Saya mulai sadar ternyata Rahwananya masih ditempel di dinding ruangan tempat saya dalang. Dengan sedikit berteriak-teriak di mikrofon, mohon bantuan diambilkan Rahwana di dinding, nyaris panitia sibuk sendiri.
Saya panggil “Mas Hari, Mas Hari, tulung jupukno wayang Rahwana aku lali ijik nempel ing tembok.”
Masih belum ada respon. Saya ulangi sampai empat kali tak ada yang membantu. Saya sadar ternyata Mas Hari si pemilik wayang Bali itu bukan orang Jawa, tapi orang Bali yang tentu tak paham bahasa Jawa. Setelah saya sambil menoleh ke belakang dan mengacung-acungkan tangan ke Budi yang sedang merekam di video, baru Rahwana dibawa ke depan dan selamatlah.
Usai acara beberapa orang Swiss yang membawa anak blasteran mengaku sengaja menunjukkan salah satu budaya Indonesia yang belum pernah dilihatnya. Di luar dugaanku, ada penonton Swiss tanya,
“Apakah ada tokoh wayang namanya Hari? Kok tadi sering disebut?”
Gedobraak!
Sejak pentas wayang perdana yang jenaka serba seadanya ini mulai tiap tahun saya pentas sambil memperbaiki koleksi wayang. Lagi-lagi saya hanya beli wayang jenis suvenir di Malioboro. Lakon pun meningkat lagi tambah Dewa Ruci.
Ketika saya beli wayang kulit di Malioboro dengan ditemani istri saya yang bule Swiss, saat saya tawar dengan bahasa Jawa, malah saya balik ditanya oleh penjualnya,
“Dari Suriname, toh Mas?”
Bajindol!
Saya pernah mendalang di perpustakaan kota Zug. Naskah dari cerpen saya sendiri berbahasa Jerman. Waktu itu teman-teman penulis asing yang tergabung dalam komunitas Writer Club hendak baca cerpen di perpustakaan kota, saya usulkan agar saya peragakan dengan wayang saja. Ternyata disambut hangat oleh panitia, dan giliran saya pada akhir acara mendalang. Suatu kali saya mendalang dengan hadirin yang kebanyakan orang perantau Pilipina. Ternyata guyonan lucu saya tak disambut.
Sampai kini saya sudah mendalang sekitar delapan kali; tujuh kali di Swiss dan satu kali di Jerman. Jika saya telusuri dari mana keberanian saya itu? Pertama, mungkin karena saya terbiasa bicara bahasa Jerman dengan orang-orang Jerman di Bali saat menjadi guide. Kedua, saya menyukai teks-teks sastra Jerman, terutama karya Franz Kafka yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti novel Proses, Metamorfosis, Surat untuk Ayah dan Percakapan dengan Kafka. Kisah Bima masuk ke telinga Dewa Ruci ini sangat surealis, seperti kisah Gregor Samsa bangun dari mimpi buruknya tiba-tiba dirinya sudah menjadi kecoak raksasa di tempat tidur. Ketiga, saat saya mudik dengan istri kami mendatangi rumah tukang ojek yang membuat wayang dari bahan kardus. Wayang-wayang itu saya mainkan sambil berdiri dalam adegan berperang sengit, membuat istri saya dan orang yang menonton itu tertawa terbahak-bahak. Dari tiga pengalaman itu menjadikan pupuk keberanian.
Kepada orang-orang yang saya sebutkan di atas, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bantuan teman-teman sangat berharga bagi saya. Matur Nuwun – Danke Vielmal.
Zug, 31 Agustus 2022
*Sigit Susanto, domisili di kota Zug, Switzerland sejak tahun 1996.













