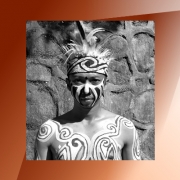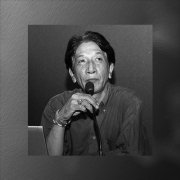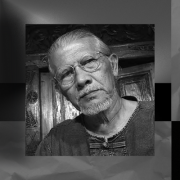Festival Muria Raya #5: Renungan tentang Desa, Gunung, dan Jantung Sebuah Festival
Oleh Hadi Aktsar*
Festival Muria Raya (FMR) #5, dengan tajuk “Wiwiting Werna Katresnan” (Permulaan Warna Cinta) yang diselenggarakan di Dukuh Duplak, Desa Tempur, Kabupaten Jepara, pada 16-17 Agustus 2025 lalu bukanlah sekadar perhelatan kebudayaan yang menyuguhkan kesenian sebagai tontonan. Lebih dari itu, ia menjadi ruang perjumpaan, sebuah lanskap sosial yang menegaskan kembali nilai-nilai dasar kehidupan: kebersamaan, kesahajaan, dan gotong royong. Sebagai seseorang yang telah lama bersinggungan dan terlibat dalam penyelenggaraan festival-festival di Jakarta dengan segala hingar-bingar metropolitan, saya merasa terdisrupsi. Saya seperti ditampar oleh kenyataan bahwa sebuah festival ternyata bisa tumbuh, mengakar, dan menyala justru dari kesederhanaan warga desa: dari tawa, senyum, dan hangatnya secangkir kopi beserta keramahan tulus yang tak mungkin direkayasa.
Di Dukuh Duplak, Desa Tempur, di kaki Gunung Muria, saya duduk bersama warga desa dan para tamu dari berbagai penjuru daerah, bahkan mancanegara. Selama beberapa hari, kami menyantap hidangan yang dimasak ibu-ibu dengan penuh kasih, menyeruput kopi dari tanah Tempur sembari bercakap tentang peradaban, warisan leluhur, dan kehidupan di Desa Tempur. Selepas kami bertamu dari rumah sebelumnya, kami selalu disambut lagi dengan kopi dan makan berat di rumah berikutnya, seolah perut tamu tidak boleh kosong. Rasanya, bukan hanya perut kami yang terisi, tetapi juga hati kami yang dipenuhi oleh hangatnya persaudaraan yang sulit saya jumpai di kota-kota besar. Tidak ada jarak antara tuan rumah dan tamu, antara “pelaku seni” dan “penonton”. Semua larut dalam satu lingkaran yang sama. Sesuatu yang selama ini nyaris mustahil saya temukan dalam festival di kota-kota besar, di mana relasi kerap dibatasi oleh sekat-sekat sosial dan simbolik.
Desa, Gunung, dan Kosmologi Nusantara
Salah satu momen reflektif datang dari perbincangan dengan Kang Pepep DW, penulis buku Manusia dan Gunung, yang dalam sesi Temu Cakap Desa mengulas konsep Reksi, Rama, dan Ratu. Tiga entitas ini, menurutnya, merupakan pembagian peran yang diwariskan leluhur Nusantara: gunung sebagai pusat spiritual (Reksi), pedalaman sebagai ruang penghidupan (Rama), dan pesisir sebagai pusat pemerintahan sekaligus gerbang dunia luar (Ratu). Sebuah struktur kosmologis yang terjalin harmonis sebelum kolonialisme merusaknya dan menggantinya dengan sistem modern yang mengedepankan kota metropolitan sebagai pusat tunggal kekuasaan.

Sesi ‘Temu Cakap Desa’ di malam pertama perhelatan FMR#5. Dari kiri: Mbah Jatmiko (sesepuh Dukuh Duplak); Dr. Barbara Titus; W. Sanavero; Pepep D.W.; Franki Raden; Brian Trinanda K. Adi. [Photo Credit: Roni]

Warga Dukuh Duplak, Desa Tempur berkumpul menyambut pembukaan FMR#5. [Photo Credit: Roni]
Simbolisme ini mengingatkan saya pada garis imajiner kosmologi Ngayogyakarta Hadiningrat yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Pantai Parangtritis. Sebuah poros kosmologis yang menegaskan keseimbangan antara spiritualitas, kekuasaan, dan alam. Dalam cara yang hampir serupa, Desa Tempur dengan FMR-nya menghadirkan kembali kesadaran akan pentingnya menyeimbangkan “gunung, desa, dan laut” dalam tubuh kebudayaan kita hari ini.
Secara topologi, saya melihat masyarakat Indonesia hari ini justru semakin terpecah-belah. Narasi “nenek moyangku seorang pelaut” yang sering kita dengungkan, sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat gunung yang sejak dahulu menjadi bagian kosmologis peradaban Nusantara. Perjalanan laut tidak akan mungkin berlangsung tanpa hulu yang mengalir dari gunung; demikian pula kebudayaan pesisir tidak pernah bisa lahir tanpa adanya keseimbangan ekosistem dari pelosok pedalaman. Rempah-rempah, kopi, teh, cengkeh, kayu manis, hingga hasil bumi lain dari kawasan pegunungan dibawa turun ke pesisir untuk diperdagangkan, lalu menyebar ke jalur perdagangan dunia. Pesisir memang menjadi “etalase” global, tetapi janganlah lupa bahwa produk yang dijual mayoritas berasal dari gunung dan pedalaman. Ironisnya, hari ini kita hidup dalam lanskap yang terfragmentasi oleh kepentingan post-kolonial dan kapitalisme: kota dijadikan pusat segalanya, sementara desa (terutama masyarakat gunung) ditempatkan sebagai “penyedia” semata. Padahal, bila kita renungkan lebih dalam, (mungkin saja) masyarakat desa bisa bertahan hidup tanpa masyarakat kota. Namun, sanggupkah masyarakat kota tetap bertahan hidup tanpa adanya desa yang berperan sebagai sumber pangan, air, dan pengetahuan ekologis yang menopang kehidupan?
Pertunjukan: Dari Doa, Bunyi, hingga Masa Depan
Kekaguman saya berlanjut pada pertunjukan-pertunjukan yang dihadirkan. Misalnya karya musik Rani Jambak berjudul Future Ancestor. Karya ini menggabungkan elemen musik elektronik dengan instrumen tradisional dan soundscape yang dekat dengan kehidupan masyarakat kita hari ini, seolah ingin menyambungkan masa depan dengan akar leluhur. Rani menyebut karyanya sebagai upaya “membayangkan bagaimana nenek moyang hadir dalam tubuh kita hari ini, dan bagaimana kita sebagai generasi mendatang dapat menjadi leluhur bagi masa depan.” Pesannya jelas: warisan budaya tidak boleh dilihat sebagai beban masa lalu, melainkan jembatan menuju kemungkinan baru di masa yang akan datang.
Begitu pula pertunjukan Membelah Kabut oleh Komunitas Mantra Gula Kelapa dari Solo. Lewat perpaduan tarian, tembang dan mantra, mereka mengungkap keresahan sosial masyarakat sekaligus mengangkat doa-doa untuk masa depan. Ada lapisan semiotik yang kuat: tubuh sebagai medium perlawanan, mantra sebagai suara kolektif, dan kabut sebagai metafora ketidakjelasan hidup.

Komunitas Mantra Gula Kelapa mempersembahkan pertunjukan bertajuk ‘Membelah Kabut’. [Photo credit: Roni]

Eksperimen musik batu di acara ‘Bluron Kali’ FMR#5. [Photo credit: Roni]

Pentas kolaborasi gamelan dari batu pada malam puncak FMR #5. [Photo credit: Roni]
Prosesi Sakral: Antara Etnografi dan Mitologi Baru
Puncak refleksi saya hadir dalam prosesi kirab Prasastu: prasasti batu yang dipadu dengan ritual penanaman pohon penjaga mata air di punden Mbah Robyong, Dukuh Duplak. Sebelum prosesi, Sabda Paseduluran mengumpulkan perwakilan komunitas, kolaborator, dan sesepuh desa. Mereka menyiramkan air dari berbagai sumber mata air yang dibawa dari tempat asal masing-masing ke prasasti batu. Air yang menyatu dalam batu (Prasastu) itu seolah meneguhkan ikrar persaudaraan lintas batas.

Prosesi Kirab ‘Prasastu’ pada malam puncak FMR #5. [Photo credit: Roni]

‘Prasastu’ diletakkan pada Punden Mbah Robyong di Dukuh Duplak, sebagai simbol ‘persaudaraan untuk selamanya’. [Photo credit: Roni]
Namun demikian, dibalik sakralitas prosesi Sabda Paseduluran dan Prasastu, saya melihat bagaimana warisan leluhur sebagai memori kolektif bisa dengan mudah terdistorsi oleh kepentingan politik praktis. Saya melihat bahwa pemuda-pemuda di Dukuh Duplak adalah aset Bangsa yang sangat kreatif dan terampil. Mereka bisa menjadikan ampas kopi menjadi lukisan yang estetik dan bernilai. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana potensi dan kreatifitas yang mereka miliki ini dapat diaktuliasikan dan didukung oleh suatu ekosistem yang tepat dan berkelanjutan?
Kampanye-kampanye politik yang datang ke desa seringkali membawa janji-janji kosong, kadang cukup dengan sekadar “membagi amplop” untuk menyenangkan warga, tanpa menghadirkan perubahan yang berarti. Di sisi lain, program-program “Desa Wisata” yang digulirkan oleh pemerintah pusat, sering kali dengan dukungan investor menawarkan pembangunan serba cepat: infrastruktur baru, spot wisata instan, dan festival dadakan yang diimpor dari luar. Tetapi, pembangunan yang serba tergesa itu sering kali gagal mengakar. Ia melahirkan estetika artifisial yang merombak tatanan desa, namun melupakan kualitas sumber daya manusianya, melupakan nilai-nilai yang selama ini diwariskan oleh para leluhur.
Dalam kacamata semiotik, fenomena ini menghadirkan paradoks. Desa yang semestinya menjadi ruang perawatan nilai justru diperlakukan sebagai “objek konsumsi”. Batu, air, dan pohon yang dalam prosesi Prasastu dimaknai sebagai sumber kehidupan, dalam logika kapitalisme kerap ditransformasikan menjadi “sumber devisa”. Desa diposisikan bukan sebagai subjek yang menentukan jalan hidupnya sendiri, tetapi sebagai latar belakang bagi kepentingan elit dan arus ekonomi global.
Maka dari itu, apa yang saya saksikan di FMR#5 di Dukuh Duplak menjadi sangat relevan. Festival ini hadir bukan untuk menjadikan desa sebagai objek eksotisme pariwisata, melainkan sebagai ruang perjumpaan yang justru menghidupkan kembali makna-makna yang hampir hilang dari ingatan generasi muda. Ketika air dari berbagai sumber mata air disatukan dalam prosesi Sabda Paseduluran, ia bukan sekadar ritual simbolik, tetapi juga sebuah pengingat bahwa kesatuan, gotong royong, dan relasi ekologis adalah warisan paling berharga yang dimiliki desa.
Dengan demikian, FMR#5 tidak hanya menciptakan “mitos baru” yang mengikat warga dengan tamu dalam narasi persaudaraan, tetapi juga mengingatkan generasi mudanya sendiri agar tidak silau oleh janji pembangunan yang serba cepat. Sebab, jika air, batu, dan pohon hanyalah simbol yang kita rayakan sekali dalam setahun tanpa dijaga dalam kehidupan sehari-hari, maka festival ini akan kehilangan makna terdalamnya.
Refleksi Kritis: Untuk Siapa Festival Ini?
Sebagai peneliti dan pegiat kebudayaan, saya juga merasa perlu mengajukan pertanyaan kritis: “Untuk siapa sebenarnya festival ini?” Para seniman, kolektif, dan kolaborator dari luar desa datang membawa karya dan ilmu dari luar yang (mungkin) kadang provokatif, eksperimental, bahkan membingungkan. Sementara warga Duplak mungkin saja memiliki gagasan berbeda tentang apa itu ekspresi budaya. Apakah FMR benar-benar memberi ruang bagi gagasan warga desa, atau justru memaksakan agenda kultural dari luar? Apakah kehadiran festival ini benar-benar menumbuhkan persaudaraan, atau justru berpotensi memicu konflik horizontal baru?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita tidak terjebak dalam romantisme semata. Niat baik tidak selalu identik dengan dampak yang baik pula. Agensi warga desa harus tetap menjadi jantung festival, bukan sekadar dekorasi atau latar eksotis. Jika tidak, festival akan kehilangan maknanya.
Bagi saya, FMR#5 adalah sebuah cermin. Ia memperlihatkan betapa desa dan gunung bukanlah “pinggiran” peradaban, melainkan pusat spiritual dan sosial yang memberi keseimbangan pada hidup kita. Ia mengingatkan bahwa gotong royong dan kesahajaan bukanlah konsep usang, melainkan energi yang mampu menggerakkan pertemuan lintas bangsa. Namun, ia juga menantang kita untuk terus kritis: memastikan bahwa festival bukan hanya milik seniman atau penyelenggara, tetapi sungguh menjadi milik warga desa: sumber air, batu, dan pohon yang selama ini menjaga kehidupan kita.
Malang, 24 Agustus 2025.
***
*Hadi Aktsar, peneliti dan pegiat kebudayaan. Lulusan Seni Teater dari Institut Kesenian Jakarta. Pada Agustus 2024, ia menyelesaikan studi Master of Arts di jurusan Arts, Policy, and Cultural Entrepreneurship dari University of Groningen, Belanda.