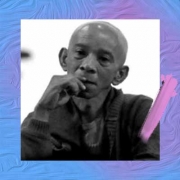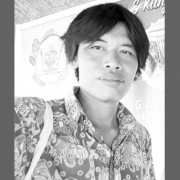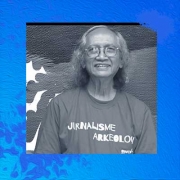Catatan Progam Pementasan Ryukyu Buyo Japan Foundation
Oleh Seno Joko Suyono*
Khazanah tari tradisi sering merupakan pintu masuk untuk menelusuri hubungan-hubungan lama antar kebudayaan yang tak terduga. Hal itulah yang memantik imaji saya saat mengikuti workshop tari Ryukyu Buyo di selasar Graha Bakti Budaya, Jumat tanggal 25 Juli lalu. Pengantar singkat yang diberikan oleh Mogi Hitoshi Ph.D, dari National Theatre Okinawa sebelum acara dimulai menarik perhatian saya. Dia mengatakan:
“Kerajaan Ryukyu,dari ujung selatan Jepang dalam sejarahnya sekitar abad 15 sampai 16 M memiliki hubungan luas dengan kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Melalui jalur perdagangan maritim orang-orang Ryukyu juga sampai ke Jawa dan membina kontak budaya. Budaya Jawa mungkin juga memberikan pengaruh kepada kebudayaan kami. Kostum yang digunakan penari-penari Ryukyu Buyo misalnya mirip batik Jawa,” katanya.
Pernyataan Mogi Hitoshi ini, segera menyadarkan saya akan makna pentingnya kedatangan rombongan penari Ryukyu Buyo berpentas di istana Mangkunegaraan Solo dan Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, pekan lalu. Kunjungan ini sesungguhnya bukan sekedar kunjungan tari, namun membuka kemungkinan untuk membaca kembali hubungan Kerajaan Ryukyu di masa lalu dengan Asia Tenggara.
Mengamati workshop dan pertunjukan tarinya secara umum memberikan saya kesan akan kehalusan dan kelembutan tari Okinawa. Warisan masyarakat dan kerajaan yang hidupnya di tepi laut itu secara sepintas saya tangkap memiliki khazanah tari dengan dasar-dasar gerak-gerak kaki dan dan ayunan tangan sederhana namun berbasis kuat kepada rasa sembah bakti yang mendalam terhadap kekuatan metafisik dewa-dewi. Sekali lagi kita bisa merasakan keaneragaman tradisi-tradisi seni pertunjukan Asia yang berbasiskan kepada penghormatan terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan gaib yang tak terlihat. Tentu dibalik gerakan-gerakan tari yang anggun itu terdapat lapisan-lapisan budaya yang lebih dalam.
Siapa yang terpikat menonton workshop dan pertunjukan Ryukyo minggu lalu itu, hampir bisa dipastikan ingin mengetahui sejarah dan alam rohani Kerajaan Ryukyu secara lebih kompleks. Tentang rumah-rumah ibadahnya, tentang dewa-dewi dan religinya – adakah sama dengan Shinto atau Buddhisme, atau sepenuhnya mengembangkan kepercayaan agama lokal, festival-festivalnya, foklor dan mitologi-mitologi lautnya dan khususnya dalam konteks hubungan dengan Indonesia – tentang diplomasi-diplomasi dan jalur-jalur maritim yang dilakukan oleh Kerajaan Ryukyu di masa lalu ke Asia Tenggara.
Kerajaan Ryukyu seperti kita ketahui adalah kerajaan yang berkuasa di kepulauan Ryukyu (Okinawa) antara abad 15 sampai 19 M . Kerajaan kuat ini mulanya tidak termasuk wilayah Jepang, baru kemudian masuk dan bergabung dengan imperium Jepang pada tahun 1879. Tentunya kita semua ingin tahu lebih jelas perihal Kerajaan Ryukyu ini, kekuatan dan kebudayaannya, dan komoditi apa yang dibawa orang-orang Ryukyu ke Asia Tenggaradi masa lalu dan sebaliknya barang-barang apa dari Asia Tenggara yang diminati oleh para pelaut Ryukyu. Tentunya kedatangan wakil-wakil Kerajaan Ryukyu atau saudagar-saudagar Ryukyu ke nusantara tidak sama dengan dengan kedatangan orang-orang Eropa yang ingin mengekploitasi rempah dan tendesinya bermaksud menguasai pasar.
Menonton workshop dan pertunjukan Ryukyu Buyo maka saya membayangkan sebuah progam lebih besar – atau lebih lengkap dari “sekedar” workshop dan pertunjukan tari sesungguhnya bisa diadakan Japan Foundation.
***
Rata-rata publik Indonesia mengenal Jepang hanya sebatas kota-kota besarnya semisal Tokyo, Yokohama, Osaka, Hiroshima, Nagasaki, Kyoto. Di tahun-tahun lampau saya ingat Japan Foundation selain mementaskan teater kontemporer seperti Black Tent dan Teater Seinendan pimpinan Oriza Hirata pernah mengirim pertunjukan tradisi Kyogen, Noh atau cuplikan (show case) Kabuki di Jakarta. Seingat saya penonton Jakarta antusias untuk memahami seni-seni rakyat dan seni-seni klasik Jepang.
Masih banyak khazanah kultural dan klasik Jepang yang penting-penting belum pernah dibawa Japan Foundation ke Jakarta. Tradisi arca kayu atau seni pertunjukan yang berkaitan dengan ritual Buddhisme Jepang dari Nara dan Kyoto yang penuh mantra-mantra Mahayana misalnya belum pernah dihadirkan dalam pameran atau dipentaskan di Jakarta. Padahal Buddhisme Jepang pada konsep-konsep teologi tertentu memiliki paralelitas dengan sejarah Buddhisme yang ada di percandian di Jawa. Di kuil Todai- Ji Nara dan kuil To-ji serta kuil Hoko-ji Kyoto sebagaimana pernah saya lihat misalnya terdapat arca kayu besar Dainichi Nyorai atau Vairocana. Vairocana adalah pantheon kuat dalam tradisi Buddhisme Mahayana. Ia selalu menduduki posisi sentral dalam mandala seperti Vajradhatu mandala.
Adalah menarik pantheon Vairocana juga dimuliakan di Jawa kuno. Termasuk Borobudur. Konsep teologi dan kosmologi Borobudur berdasar mandala Pancatathagata. Pancatathagata adalah sistem kosmologi dan ontologi dhyani Buddha dengan Vairocana pada posisi pancer atau di tengah dikelilingi empat dhyani Buddha lainnya lainnya antara lain Aksobhya (barat), Amoggasidhi (utara), Ratnasambhawa (Selatan), Amitabha (barat). Vairocana artinya adalah sebuah pantheon yang sangat utama karena letaknya di zenith. Dari Borobudur sampai ke percandian Jawa Timur dalam rentang berabad-abad, Vairocana tetap dimuliakan. Di Candi Jago Malang terdapat relief Vairocana. Juga di Kakawin Sutasoma, dewa tertinggi disebut adalah Vairocana. Adalah fakta bahwa Kuil Todai-Ji Nara dan kuil To-Ji Kyoto dibangun pada abad 8 M, sezaman dengan pembangunan Borobudur. Serta ketiganya sama-sama memuliakan Vairocana sebagai pantheon utama.
Banyak yang tidak tahu konsep-konsep keagamaan dalam pembangunan arsitektural Borobudur juga selaras dengan konsep konsep keagamaan tradisi Shingon, salah satu mazhab Buddhisme tertua di Jepang. Pendiri Shingon, Kukai atau Kobo Daishi dalam sejarahnya diketahui saat belajar mandala di Chang-an, ibu kota Cina zaman Tang memiliki seorang sahabat Bhikkhu asal Jawa yang di Cina dipanggil dengan nama Bianhong. Mereka sama-sama mempelajari satu jenis mandala yang baru di saman itu yaitu Vajradhatu mandala. Adakah kebetulan atau tidak, relief panjang Borobudur yang terpatri dari lorong dua sampai ke ke lorong empat adalah relief Gandawyuha yang menampilkan seorang anak muda bernama Sudhana melakukan perjalanan mencari pencerahan. Sementara teks utama dari Shingon Buddhisme adalah Avatasamka Sutra yang bagian akhirnya adalah sutra Gandawyuha. Shingon Buddhisme juga amat memuliakan Vairocana. Itulah sebabnya banyak Bikkhu dan agamawan Shingon menganggap Borobudur sesungguhnya senyawa dengan spirit ajaran religi mereka. Tiap tahun ada saja Bikkhu Shingon yang mengunjungi Borobudur dan melakukan pradaksina. Hubungan antara Jawa dan Jepang di masa-masa klasik begini belum pernah dieksplorasi Japan Foundation dan disajikan dalam pameran pemikiran.
Sejauh saya tahu ini kali pertama tari-tari istana dan rakyat Okinama disajikan Japan Foundation di Solo dan Jakarta. Secara umum nama Okinawa oleh banyak masyarakat yang mengenal Jepang selalu diasosiasikan dengan pangkalan militer Amerika. Memang pertempuran Sekutu dan Jepang pernah terjadi di sekitar Okinawa dan semenjak akhir PD 2 Amerika membangun pangkalan militer di sana. Dari film-film kita mendapat informasi bahwa keberadaan pangkalan militer ini kerap menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan dengan warga lokal Okinawa. Beberapa kelompok teater modern Jepang juga mengangkat isyu ini. Okinawa dengan kata lain lebih dikenal ke publik luar mengenai sejarah perang Dunia ke 2 termasuk keharusan mematuhi Amerika soal pangkalan militer. Sementara sejarah Kerajaan Ryukyu jarang disajikan.
Padahal kajian-kajian arkeologi mengenai Ryukyu berkembang. Dari jurnal-jurnal arkeologi Asia kita dapat membaca data-data sejarah dan arkeologi baru hasil penemuan para ahli mengenai Ryukyu. Misalnya tulisan Geoff Wade: Ryukyu in the Ming Reign Annal 1380s-1580s yang dimuat di Asian Research Institute Juli 2007. Tulisan ini penting karena memberikan informasi bahwa perdagangan maritim dari Ryukyu sudah dimulai sejak tahun 1300 an akhir atau abad 14-15 M bukan sejak abad 15-16 M. Menurut Wade di abad 14 M itu sudah terjalin hubungan baik antara Ryukyu dan dinasti Ming Cina. Kapal-kapal Cina yang hendak meunju berbagai destinasi di Asia kerap mampir lebih dulu di Ryukyu. Jalur-jalur maritim dinasti Ming ini juga dimanfaatkan oleh Ryukyu. Soal jalur maritim dinasti Ming ke Asia Tenggara dibahas Wade di tulisan lain: Ming China and Southeast Asia in the 15th Century, A Reappraisal (Asia Research Institute, 2004). Kaisar Hong Wu dari pemerintahan Ming yang berkuasa antara 1368-1398 menurut Wade memiliki politik luar negri untuk menjalin hubungan dengan Asia Tenggara yang kemudian diteruskan oleh penguasa-penguasa sesudahnya. Politik maritim Dinasti Ming Cina ke Asia Tenggara ini meliputi negara-negara: Annam, Champa, Kamboja, Siam, Cochin, San Fo-qi, Jawa, Jepang, Ryukyu, Brunei dan Korea.
Cina mengirimkan diplomat-diplomatnya ke Majapahit bahkan sampai paska pemerintahan Kaisar Hong Wu sepeti muhibah terkemuka Laksamana Cheng Ho. Sebaliknya penguasa Majapahit, Hayam Wuruk diketahui beberapa kali mengirim utusan diplomatik ke pemerintahan Ming di Cina. Melalui jaringan maritim Cina dan Asia Tenggara ini, kemungkinan misi-misi Kerajaan Ryukyu bisa mencapai Jawa. Menurut sejarawan Thailand, Priyada Chonlaworn yang menulis hubungan sejarah antara Ryukyu dan Kerajaan Ayutthaya Thailand pada Journal of The Siam Society, 2004, di Ryukyu terdapat dokumen berbahasa Cina berisi arsip-arsip surat menyurat resmi hubungan diplomatik dagang Ryukyu dengan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara antara tahun 1424-1867. Surat-surat korespodensi itu meliputi surat diplomatik resmi ke Ayutthaya, Palembang, Jawa, Malaka, Sumatra, Pattani, Anam dan Sunda. Himpunan dokumen penting itu bernama Rekidai Hoan.
Pada titik ini adalah masuk akal bila di masa sekarang ada temuan sisa-sisa barang-barang dari Ryukyu yang berada di Jawa atau sebaliknya, barang-barang dari Jawa di Ryukyu. Sebab pernah terjadi interaksi dagang resmi antara mereka. Pada tahun 2003 media Star on line Malaysia menurunkan berita bahwa para arkeolog Okinawa menemukan sebuah keris kuno berluk sembilan di dalam tanah kuil Enkakuji – kuil milik istana Ryukyu masa lampau yang lokasinya tidak jauh dari kastil Shurijo yang berdiri sejak abad 15 M. Keris kuno tanpa hulu dan warangka itu ditemukan bersama benda-benda kuno lain antara lain piring tanah liat dengan ukiran naga, pot berglasir, engsel pintu berbahan emas, lis dinding dari logam. Prof Dr Kurayoshi Takara, sejarawan dari University of Ryuku dan orang yang memimpin restorasi kastil Shurijo, memperkirakan keris itu berasal dari Malaka atau Jawa. Menurut Prof Dr Takara, kapal-kapal dari Ryukyu datang ke Malaka selama 49 kali berturut-turut tiap tahun antara tahun 1425-1570. Apakah keris itu berasal dari Malaka atau Jawa memang harus diadakan penelitian lebih lanjut. Betapapun demikian ini membuktikan bahwa hubungan diplomatik Ryukyu dengan Jawa atau Malaka itu benar-benar ada.
Di samping itu di kawasan Trowulan pernah ditemukan fragmen-fragmen pecahan keramik imori asal Jepang. Itu menandakan disamping mayoritas keramik Cina yang mendominasi perdagangan keramik di Majapahit juga ada keramik dari Jepang. Dan bukan tidak mungkin bila diteliti lebih jauh ada yang berasal dari wilayah Okinawa. Adalah menarik bahwa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bekerjasama dengan sekelompok pengusaha dari Jepang berkaitan dengan hal ini pernah mencoba merekonstruksi hubungan maritim antara dari Jawa dan Ryukyu. Mereka membuat proyek bernama Spirit of Majapahit dengan merekonstruksi perahu dagang yang terbuat dari kayu di zaman Majapahit dan melayarkannya dari Jawa menuju Ryukyu atau Okinawa. Meskipun secara arkeologis belum ada data-data bagaimana model perahu-perahu dagang besar di era Majapahit, pembuatan kapal itu dilakukan dengan menyadur model perahu yang ada di relief Borobudur. Kapal berhasil dirancang dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 4,5 meter. Semua terbuat dari kayu. Pelayaran itu berangkat dari Jakarta tanggal satu Mei 2016 dengan dipimpin nahkoda Muhammad Amin Azis yang saat itu telah berumur 70 tahun. Kapal itu meski dihajar gelombang setinggi 5 meter di perairan Jepang sampai dengan selamat di pelabuhan Naha, Okinawa pada 12 Juni 2016. Ekspedisi ini membuktikan bahwa rute Jawa-Ryukyu itu bisa dilaksanakan.
***
Spirit tari Ryukyu Buyo malam itu sendiri tidak asing, apalagi bagi penonton yang berasal dari Jawa. Geraknya tenang dan intens. Halus namun tidak gemulai. Pertunjukan Ryukyu Buyo mudah dipahami. Ornamen-ornamen dan vokabuler geraknya tidak serumit tari-tari dari kraton kita. Gerak leher, variasi ayunan dan tekukan tungkai kaki serta vokabuler gerak tangan dan putaran pergelangan tangan, pola jari-jemari dan koreografi belum mengalami stilisasi atau pencanggihan sebagaimana tari-tari kraton Yogya dan Solo. Namun kesamaannya saat menyaksikan nomor-nomor tari tunggal maupun berkelompok dari Okinawa itu – kita melihat adanya konsentrasi yang membuat tubuh luwes, lentur – tampak ringan tapi memiliki daya energi halus yang mengalir..
Dikemukakan oleh Mogi Hitoshi Ph.D, Ryukyu Buyo (tarian dari Ryukyu) bermula dari tari persembahan kepada dewa-dewa, dan kemudian berkembang menjadi bagian dari tari-tari dalam upacara istana yang hanya terbatas untuk penghuni istana. Termasuk tari untuk penyambutan tamu-tamu kerajaan, tari di acara-acara jamuan resmi negara, tari acara penobatan tahta dan acara kerajaan lainnya. Tari istana ini lambat laun keluar dari istana dan disajikan di teater-teater umum. Tatkala berasimilasi dengan masyarakat dan bersentuhan dengan lagu-lagu rakyat tarian ini kemudian berkembang meluas menjadi tari yang merefleksikan aneka kehidupan sehari-hari masyarakat di desa-desa.
Progam pertunjukan malam itu menyajikan tarian istana dan tarian rakyat dari berbagai pulau di Okinawa. Nomer pembuka: Yuchidaki adalah sebuah tarian sambutan. Tarian ini dimaksudkan sebagai tarian yang menyucikan tempat pertunjukan dan memohon kepada Ilahi agar memberikan penonton yang hadir suatu keberkahan. Menarik konsep tarian ini. Empat penari perempuan dengan mengenakan topi bunga dan jubah luar tradisional Ryukyu. Warna dasar jubah dan kostum adalah kuning tua. Ornamen bunga-bunganya meriah. Sebuah batik dengan warna- semarak. Tidak ada gerakan-gerakan yang mengasosiasikan dengan ritual secara verbal sebagaimana bila kita saksikan tarian-tarian rakyat kita yang berkenaaan dengan upacara-upacara pasti penuh gerakan sembah, sujud atau percikan tirta suci. Sama sekali tidak menguar nuansa Buddhisme atau Shinto. Yuchidaki lebih mengesankan suatu tarian selamat datang, menyambut hadirin namun dengan gerakan yang tidak menampilkan luapan-luapan ekspresi tubuh, seperti melonjak, menampilkan kegembiraan berlebihan. Tubuh terasa masih terikat kepada penghormatan kesucian ruang dan etiket istana. Ekspresi luapan kebahagian itu sering malah terlihat pada perubahan mimik muka.
Adalah menarik cara mengikatkan kimono yang dikenakan para penari bisa menjadi petunjuk apakah dalam imajinasi tarian itu disajikan di sebuah ruangan indoor atau di halaman out door. Bila seorang penari mengenakan kimono dengan membiarkan obi – ikat pinggang kimono menjuntai di depan, itu artinya bahwa tarian itu merepresentasikan adegan di luar ruangan. Menarik memang soal simbol-simbol kostum ini. Saya lihat juga dari tari satu ke tari lain para penari mengenakan berbagai ikat kepala yang berbeda. Warna-warna kimononya juga beragam. Adalah menarik bila kostum kimono “batik” Okinawa dan lambang-lambang gaya busana serta motif-motifnya, aneka ikat kepala dan type sanggul penari juga diuraikan di workshop. Namun karena keterbasan waktu, workshop tidak menyinggung hal tersebut.
Beberapa tarian, segera dapat kita lihat bahwa itu berkaitan dengan kehidupan penduduk desa– karena para penarinya membawa properti sehari-hari seperti bambu, bulir padi, dayung sampai benang tenun. Segera dapat kita raba tarian itu berkaitan dengan permohonan agar panen berlimpah, tentang nelayan dan harapannya akan tangkapan ikan-ikan berlimpah. Seperti saya ungkapkan di atas, betapapun tarian-tarian menyuguhkan kegembiraan -namun tetap, tidak begitu saja emosinya diloskan. Dinamika tubuhnya tetap perlahan dan gerak mobilisasinya tidak cepat atau tergesa-gesa. Seolah mereka sadar bahwa alam rohani Ilahi tetap mengawasi Gerak-gerik mereka dan itu harus diresapi di setiap inci tubuh. Pesta, Kegembiraan singkatnya saya lihat tidak dinyatakan verbal. Tidak ada ekspresi berlebihan dalam keriangan. Seolah selalu ada mawas diri dalam kesukariaan.
Saya melihat yang juga sangat kuat dari seni pertunjukan Okinawa ini adalah musik dan koor – vokal para pemusik. Saya merasa malah yang menghidupkan suasana adalah unsur musiknya dan tari hanya menyesuaikan dengan ritme musik. Pada beberapa momen terasa aspek musik lebih kuat daripada tarinya. Musik terdiri dari seorang yang memainkan Sou -semacam kecapi Okinawa, lalu tiga orang memetik gitar Okinawa bersenar tiga yang di Okinawa disebut Sanshin, dan kemudian seorang penabuh taiko – drum Jepang. Alat-alat musik tersebut muasalnya dari Cina, namun sama sekali kecinaanya tak muncul. Suara-suara yang keluar dari alat-alat itu seolah memgalami naturalisasi dan pribumisasi kultur Okinawa. Apalagi karakter warna dan melodi vokal yang dilantunkan tiga pemetik Sanshin. Tidak sedikitpun mengimajinasikan kita ke lagu-lagu Cina. Paduan vokal ini menghadirkan dialektika harmoni dan disonansi yang membuat kitab bisa membayangkan Okinawa adalah wilayah jauh yang nyanyian-nyanyian rakyatnya mengisahkan suka-duka tersendiri yang tak kita pahami.
Karakter folk baik lantunan suara maupun komposisinya sangat kuat. Sebagaimana musik-musik rakyat yang asli dan tak dipoles-poles – suasana ambang atau liminitas sangat terasa. Menurut saya – musik dan vokal pemusik seolah antara ratapan kasar dari akar rumput dan doa permohonan yang lembut kepada yang Ilahi. Kadang saya merasa koor menampilkan komposisi suara yang menimbulkan perasaan masygul.
Untuk vokal ini saya terkesan pada koreografi tari rakyat berjudul: Kurushima Kudoki. Kurushima dalam katalog buku progam disebut sebagai pulau terpencil yang terletak jauh di Selatan Okinawa. Pulau ini dikenal memiliki festival yang meriah hingga disebut “pulau nyanyian dan tarian”. Kurushima Kudoki menggambarkan kehidupan di pulau Kurushima yang penuh kehangatan. Saya tertarik bagaiman para penari wanita dengan suara lirih ikut bernyanyi meningkapi nyanyian vokal para pemetik Sanshin. Jarang dalam tarian-tarian klasik Jawa para penari perempuan ikut bersenandung bersama para penabuh gamelan. Pada tarian-tarian klasik Jawa yang menyanyikan adalah koor para niyaga gamelan yang terpisah dari penarinya. Sementara pada Kurushima Kudoki antara penari dan pemain musik saling bersahutan menciptakan lapis-lapisan nyanyian yang impresif .Suara-suara para penari perempuan cenderung halus dan tidak menyolok – seolah melapisi vokal para pria pemetik Sanshin, menimbulkan komposisi yang kadang syahdu, kadang magis. Tentunya lirik-lirik yang dinyanyikan mereka sangat bermakna. Seandainya lirik-lirik itu diterjemahkan dalam buku katalog akan dapat membuat penonton lebih menyelami apa yang ingin dikatakan oleh koreografi Kurushima Kudoki ini – serta bisa meraba lanskap alam pemikiran desa-desa pulau Kurushima Okinawa.
***
Penonton yang hadir malam itu di Graha Bakti Budaya cukup lumayan. Lantai satu hampir penuh terisi. Balkon di lantai tiga terisi separuh. Setelah pertunjukan saya lihat banyak penonton berebutan foto bersama dengan para penari di lobi Graha Bakti Budaya. Ini membuktikan tari klasik Jepang memikat publik. Tentunya saat dipertunjukan Ryukyu Bukyo disajikan di pendapa istana Mangkunegaran Solo aura dan atmosfernya lebih terasa rohnya, karena cocok. Apalagi progam juga diawali oleh tarian dari Mangkunegaran sebelum masuk ke Ryukyu Buyo.
Saya membayangkan di lobi Graha Bakti Budaya ada progam tambahan berupa pameran mengenai adat istiadat istana Ryukyu di masa lalu. Sehingga sehabis menonton pertunjukan, para penonton masih bisa mempedalam pengetahuan. Apalagi bila keesokannya ada semacam lecture-lecture dari para sejarawan atau arkeolog Jepang mengenai khazanah Kerajaan Ryukyu dan diplomasi-diplomasi perdagangan di Asia Tenggara yang dilakukannya di masa lalu, seperti saya kemukakan di atas. Pasti dahaga penonton akan terpenuhi.
Satu lagi yang terbersit di pikiran saya adalah Japan Foundation bisa memprakrasai semacam kolaborasi antara tarian klasik Jawa dan tarian klasik Okinawa .Mempertemukan dua budaya dalam sebuah pertunjukan – ini bukan tanpa preseden. Tahun lalu di Graha Bakti Budaya kita bisa menonton sebuah tarian kolaborasi Jepang-Jawa yang kualitasnya secara estetik luar biasa. Tarian berjudul Bedhaya Hagoromo itu mengolaborasikan antara maestro tari topeng Didik Nini Thowok dan maestro Noh Jepang. Di panggung, Bedhaya lanang- bedhaya yang ditarikan 9 penari pria disatukan dengan unsur-unsur topeng dan kipas tarian Noh. Musiknya juga berupa perpaduan antara gamelan dan musik-vokal tradisi Jepang. Saya menulis di majalah Tempo tahun lalu, bahwa karya ini merupakan pertunjukan terbaik di tahun 2024. Saya menyatakan pertemuan dua tari klasik yang berbeda itu berlangsung halus. Bedhaya dari kraton Yogja dan tari tua Noh dari Jepang melebur satu sama lain. Keduanya seolah saling menyerap. Energinya utuh. Sebuah osmosis yang menemukan esensi tunggal Sebuah kolaborasi yang tercipta dari “dunia dalam “, jiwa – bukan hanya sekedar perjumpaan tempelan-tempelan atau persenyawaan asesoris-asesoris.
Bila terobosan-terobosan semacam ini juga menjadi progam Japan Foundatiom tentu Japan Foundation memberikan kontribusi plus yang luar biasa dan out of the box.
—-
*Seno Joko Suyono, pernah kuliah di Fak Filsafat UGM, tinggal di Bekasi.