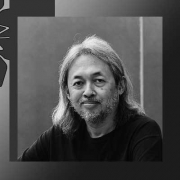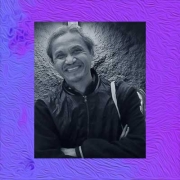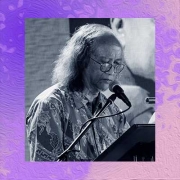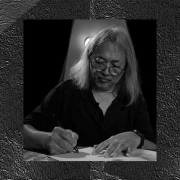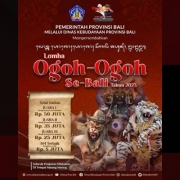Wali yang Tak Tampil di Panggung
Oleh: Hertasning Ichlas*
“Wali ada di sekitar kita. Tanpa panggung tanpa jubah dan pengeras suara.”
Saya menulis tentang sahabat sekaligus guru saya. Kami bersahabat sejak saya baru berusia awal dua puluhan. Namanya Musa Kadzhim Al Habsyi. Usianya hanya terpaut dua tahun lebih tua.
Sejak kecil Musa adalah santri. Ayahnya, Habib Husain, mendirikan pesantren di Jawa Timur. Ia belajar di berbagai negeri Timur Tengah sebelum kemudian merasakan kehidupan Barat di Australia. Bahasa Arab dan Parsi-nya crème de la crème — kelas terbaik.
Ia lama menjadi koresponden untuk beberapa televisi Arab di Indonesia, di antaranya Associated Press dan Al Jazeera. Ia pernah lama mengajar filsafat Islam di Universitas Paramadina dan Sadra serta menjadi penulis dan editor utama buku-buku filsafat dan tasawuf di Penerbit Mizan.
Kami bersahabat sehari-hari. Saya sering ke rumahnya, ia ke rumah saya. Teman-teman saya menjadi temannya; teman-temannya di kalangan jamaah keturunan Arab menjadi teman saya. Kami sama-sama gemar membaca, bergurau, dan berziarah — dari pelosok Indonesia hingga ke Timur Tengah.
Di tengah maraknya performativitas religius di kalangan keturunan Arab, Musa justru tampil sebaliknya. Ia sama sekali tak berpretensi menjadi habib atau ahli agama. Tapi justru karena itu, ia guru sejati: seorang habib yang menghayati sufisme—agama sebagai cinta.
Bacaan kitabnya luas. Tafsir Al-Qur’an, karya-karya klasik seperti Ibn ‘Arabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, Mulla Sadra—semuanya ia pahami dengan kedalaman yang memadai seperti ia membaca filsafat Barat. Ia habib yang sangat menghargai pendekatan ilmiah.
Tahun 2019 saya hijrah ke Belanda untuk melanjutkan sekolah. Tak lama, Musa menyusul. Ia melanjutkan studi doktoral di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
“Saya ingin meneliti bagaimana memadukan nash, kitab, dan studi etnografis untuk membumikan konsep kewalian,” katanya.
“Selama ini konsep itu tampak abstrak, bahkan kerap disalahpahami sebagai hal asing dan klenik.”
Suatu malam, ketika kami berkumpul, saya memintanya bercerita tentang risetnya. Ia bicara pelan tapi mengalir.
Menurut Musa, dalam literatur Al-Qur’an, hadis, dan kitab klasik, wali selalu muncul dari “belakang panggung”, dan berporos pada rumah. Wali tidak harus—dan sering kali tidak—terkenal.
Kita semua, katanya, punya potensi menjadi wali. Dengan menjadi kakak, abang, atau ayah dan ibu bukan hanya secara biologis, tetapi secara spiritual: penjaga, pelindung, pembawa kedamaian dan kasih sayang.
Fungsi-fungsi kewalian seperti ini kian memudar di zaman modern—di tengah fatherless, motherless, dan homelessness yang kian marak.
Bagi Musa, wali adalah sosok dengan kualitas akhlak yang lahir dari iman. Karena itu, sifat dasarnya pasti dermawan. Kata karamah sendiri berarti “kedermawanan”—bukan keajaiban. Dari kemurahan hati itulah kemuliaan lahir.
Musa menunjukkan bahwa para santo di abad pertengahan pun hidup berporos di rumah. Seperti Nabi Muhammad yang memulai dakwahnya bukan dari masjid, melainkan dari rumah. Dari ruang kasih sayang itulah akhlak menyebar dan rumah tumbuh menjadi Masjid Nabawi. Nabi menjadi wali lebih dulu—melalui akhlak sosial dan pengakuan masyarakat atas kebaikannya—bahkan sebelum menerima wahyu dan menjadi Nabi.
Rumah adalah pusat perlindungan, kasih sayang, dan pengajaran. Di situlah wali tumbuh. Wali adalah mereka yang waktunya, pikirannya, dan rumahnya dicurahkan untuk melayani orang lain, mulai dari keluarga hingga siapa pun yang datang mengetuk.
Saya pernah menggoda Musa: “Jadi apakah wali sesederhana itu?”
Ia tersenyum, “Kelihatannya sederhana, tapi tidak. Fungsi kewalian itu dijalankan bertahun-tahun—melayani orang tanpa perlu dalil, membantu tanpa pamrih.”
Bagi Musa, kewalian bukan tentang ritual pribadi, melainkan pengejawantahan akhlak sosial. Banyak wali, katanya, adalah orang-orang biasa: tanpa panggung, tanpa jubah, tanpa tasbih. Mereka menjadikan rumahnya pusat kedermawanan sosial.
Musa disiplin meneliti konsep ini. Hubungan antara tauhid dan kewalian ia lihat secara empiris. Meski fasih dalam metafisika Islam, ia lebih tertarik pada praksis. Wali, katanya, menunjukkan sifat Tuhan yang omnipresent melalui tindakan kecil: menjenguk orang sakit, menerima tamu, memberi makan, mendengarkan keluh kesah dengan tulus.
Hari ini, sosok seperti itu semakin langka. Keluarga hidup dalam tekanan ekonomi, keterputusan emosional, dan tumpukan aktivitas digital. Islam kian dikonsumsi sebagai tontonan—konten viral, ceramah singkat, poster motivasi. Kewalian bergeser dari pengasuhan menjadi pertunjukan. Iman menjadi simbol, bukan rasa yang dirawat.
Di tengah gelombang visualisasi religius yang makin dominan, algoritma memberi nilai lebih pada penampilan ketimbang keaslian, pada keaktifan ketimbang keintiman, pada penyebaran ketimbang pendalaman.
Hari-hari ini, Islam memang semakin tampak. Tapi semakin tampak pula, betapa ia makin tak terasa.
Kita semua sebenarnya wali—bila rumah dan waktu kita menjadi sumber kedermawanan. Dan tak terbantahkan, siapapun yang menjadikan rumah dan waktunya selalu terbuka bagi siapa pun mereka yang memerlukan perlindungan dan kasih sayang sebenarnya adalah pusat-pusat kewalian.[]
—-
*Hertasning Ichlas. Pelajar doktoral di Van Vollenhoven Institute, Leiden University.