Siti Munjiyah, Peran Perempuan dan Feminisme Jawa

Oleh Chubbi Syauqi
Persoalan mengenai perempuan, sekiranya sampai hari ini masih menyisakan perdebatan yang tak kunjung usai. Secara eksternal permasalahan perempuan yakni berupa budaya patriarki yang lestari, hingga menimbulkan ketimpangan gender. Adanya kegelisahan ini dipicu oleh gerakan feminisme yang mengklaim bahwa perempuan berada dalam bayang-bayang “hegemoni”, kekuasaaan, dan (maaf) “penjajahan” para lelaki. Seolah ada peran universialis, tepatnya eurosentris, yang ingin disodorkan: selama perempuan belum keluar dari wilayah domestiknya (alias rumahnya), selama itu pula ia terus dalam jaring “dominasi” dan “hegemoni” para lelaki.
Dalam konteks feminisme, peran domestifikasi inilah yang menguburkan semangat emansipasi perempuan dan melembekan progresifitas perempuan. Sekilas jika kita memakai perspektif feminisme, maka dengan serta merta kita akan mengamini hal tersebut. Apakah keterkaitan perempuan dalam ruang privat menjadikan tidak progresif? Atau lebih jauh lagi, sebagaimana paradigma khas feminisme, bila ingin lebih progresif dan mencapai ruang publik harus meninggalkan ruang privat?. Perlu diketahui bahwa feminisme lahir bukan dari khasanah nusantara, sehingga tidak dapat langsung digenaralisasikan. Hal ini dijelaskan dalam bukunya Risa Permanadeli “Dadi Wong Wadon” bahwa ruang privat bagi perempuan Jawa bukanlah ruang yang memenjarakan. Dalam penelaahanya, ia mendapati perempuan Jawa justru hidup dalam paradigma feminismenya sendiri yang harmonis bersandingan dengan tradisi.
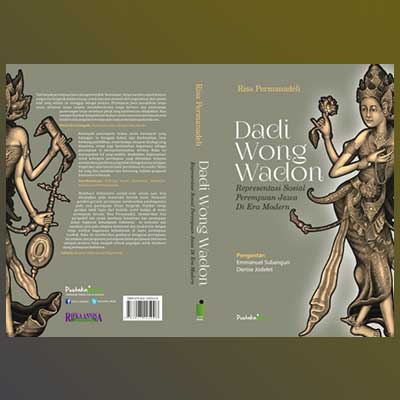
Sampul buku Dadi Wong Wadon karya Risa Permanadeli. (Sumber Foto: https://bentarabudayabali.wordpress.com)
Salah satu temuan yang bagi saya mencengangkan dari telaah Risa Permanadeli adalah ternyata paradigma feminisme yang dipahami secara “awam” oleh perempuan-perempuan di Timur justru mampu memediasi tegangan maknawi antara ruang privat dan ruang publik dari perempuan itu sendiri, dibandingkan dengan perspektif feminisme Barat yang kini menjadi tradisi mainstream (Risa, 2016). Paradigma tersebut bahkan mampu melahirkan nilai-nilai keperempuanan yang “otentik” dan harmonis bersanding dengan tradisi ketimurannya. Hal ini dapat kita telaah dari konsep rumah tangga Jawa yang menempatkan posisi perempuan menjadi peran yang sangat penting.
Dalam Perspektif Jawa, Rumah tangga tak ubahnya sebagai perpanjangan ruang sosial (publik), dan oleh karenanya, peran sebagai “kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga” menjadi tak apa-apa, asalkan itu berjangkar dalam konteks perluasan peran domestik sosial rumah tangga. Justru, sebagai pengatur keuangan keluarga, perempuan menempatkan dirinya dalam jaring sosial yang menautkan kehidupan sosial perempuan dalam dunia simbolik masyarakat Jawa secara umum. Peran sosial rumah tangga dianggap sukses justru terhubung secara positif dengan keberhasilan pengaturan keuangan keluarga, yang notabene ditentutan oleh peran perempuan. Perempuan menempatkan dirinya dalam jaring sosial yang menautkan kehidupan sosial perempuan dalam dunia simbolik masyarakat Jawa secara umum.
Sedangkan kesetaraan gender bagi perempuan dalam rumah tangga tidak berdasarkan dari sebuah kemandirian perempuan untuk memperoleh hasil pendapatan sendiri. Sehingga, apabila ada perempuan yang sudah berumah tangga kemudian bekerja, maka hal tersebut justru memperkukuh ruang sosial perempuan Jawa untuk memperkaya kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana dulu perempuan Jawa membuat batik, menari, menembang, maka sekarang ia melukis, menulis, bersekolah, bekerja, berdagang, ikut berpolitik, tetapi tempat dan perannya tetaplah berjangkar dalam rumah tangga sebagai perempuan Jawa. Tempat dan perannya tetaplah berjangkar dalam rumah tangga sebagai perempuan Jawa.
Gerak perempuan dalam rumah tangga (ibu rumah tangga), sejatinya bukan ketertutupan dan isolasi, melainkan sebentuk keterhubungan dengan dunia luar rumah tangga. Ungkapan “jangan sampai lupa dengan kodratnya” adalah sebentuk usaha menghormati tempat sendiri dimana setiap posisi mencerminkan fungsi dan perannya masing-masing, tidak hanya terkait perempuan laki-laki semata dalam usaha menjaga keseimbangan dunia (rukun/harmoni). Demi memperkuat narasi paradigma feminisme dan emansipasi yang “berkepribadian khas”, sosok Siti Munjiyah perlu dicuatkan.

Foto Siti Munjiyah. (Sumber Foto: Istimewa)
Siti Munjiyah merupakan salah satu tokoh perempuan di Muhammadiyah yang kebetulan merupakan saudari dari dua tokoh besar Muhammadiyah yakni H. Fachroddin dan Ki Bagus Hadikusumo (Suratmin: 1991). Ia merupakan sosok perempuan Jawa, anak dari seorang abdi dalem keraton di bagian keagamaan atau penghulu, serta memiliki latar belakang pendidikan tinggi hingga akrab dengan logika feminisme. Dalam sebuah Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928, Siti Munjiyah berujar, bahwa jangan menelan bulat-bulat emansipasi yang ada di Barat, sejatinya perempuan Indonesia memiliki “kepribadian yang “khas” yang tidak semestinya dirubah mengikuti pula Barat yang berkembang saat itu.
Dalam pidatonya, Siti munjiyah memaparkan alasan perlunya emansipasi yang “berkepribadian khas”. Ia tak mengingkari tradisi “lama” yang menindas perempuan. Akan tetapi Siti Munjiyah berasumsi bahwa ada gejala yang tidak sehat dari emansipasi di eropa (barat) saat itu. Yakni adanya upaya penanggalan identitas dan tradisi “lama” mereka (yang disimbolkan dengan rumah dan identitas feminin dan keibuannya) serta berupaya untuk membentuk “identitas baru” yang diklaim membebaskan. Emansipasi perempuan saat itu cenderung kebablasan hingga membentuk semacam “anti-perempuan” (baca: seperti laki-laki).
Berpijak dari pandangan tersebut, Siti Munjiyah mengutarakan pemikirannya mengenai pondasi emansipasi Indonesia yang seharusnya mampu “mensintesiskan” beraneka ragam nilai-nilai luhur, diantaranya: apa yang terjadi di Barat; kultur nusantara yang adiluhung (tidak mengoprasi tetapi justru membanggakan perempuan Indonesia); dan juga ajaran agama yang diimani oleh rakyat Indonesia (secara khusus Islam, karena Siti Munjiyah berasal dari organisasi Islam). Sosok Siti Munjiyah merupakan representasi dari emansipasi yang “berkepribadian khas”. Di “ruang privat” Munjiyah merupakan seorang ibu biasa, namun di “ruang publik” beliau adalah salah satu tokoh pendiri Aisyiah yang aktif. Dirinya juga rutin berinteraksi dengan banyak organisasi wanita saat itu (seperti Taman Siswa, Jong Java, dan Wanita Oetama) sebagai wakil dari Asiyiyah (Suratmin: 1991). Realitas ini menujukkan bahwa Siti Munjiyah dapat hidup dalam “dua ruang” yang berbeda dan juga tidak mengalami “masalah berarti” dengan tradisi yang melingkupinya. Karena, apa yang terus ia lakukan adalah melakukan “dialog” dengan realitas disekelilingnya.
Pemikiran emansipasi Siti Munjiyah bila dibaca dalam perspektif pasca-kolonial dapat dikategorikan sebagai pemikiran alternatif nan “otentik” yang disuarakan oleh perempuan lokal (non-barat). Ia juga tengah meruntuhkan gagasan feminisme yang selama ini berkembang di dunia. Darinya, kita tahu bahwa peran perempuan dalam “ruang privat dan ruang publik” tak sepatutnya di vis a vis kan. Kesadaran akan hal ini perlu meresap ke dalam pikiran perempuan agar tidak terjebak dalam gagasan feminisme barat. Lagi-lagi, kesadaran itu muncul bilamana perempuan mau menengok tradisi, pergulatan dan kebudayaan yang telah berjangkar di nusantara.
*Mahasiswa Jurusan Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta anggota Sekolah Kepenulisan Sastra Peradaban (SKSP) Purwokerto
—–
DAFTAR PUSTAKA
Suratmin, dkk. 1991. Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Risa Parmendeli. 2016 . Dadi Wong Wadon Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern. Yogyakarta: Pustaka Ifada













