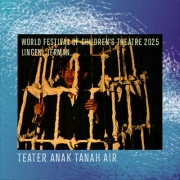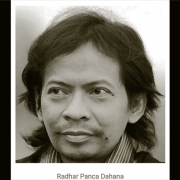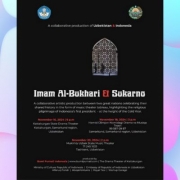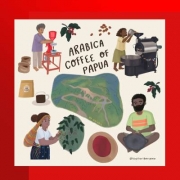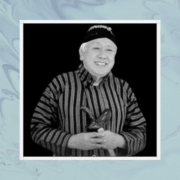Sastra sebagai Pendidikan Profetik: Refleksi atas Pemikiran Moh. Roqib dan Karya Ahmad Tohari
Oleh: Abdul Wachid B.S*
I. Pendahuluan
Sastra sejak lama tidak hanya dipandang sebagai seni untuk dinikmati secara estetik, tetapi juga sebagai medium untuk menanamkan nilai, moral, dan budaya dalam kehidupan manusia. Moh. Roqib dalam Pendidikan Sastra Profetik: dalam Karya Ahmad Tohari (Pesma An Najah Press, 2024:v-x) menegaskan bahwa sastra memiliki peran penting dalam membangun karakter dan kesadaran spiritual pembacanya. Bahasa dan gaya puitik bukan semata untuk keindahan, tetapi juga sarana edukatif yang menyampaikan pesan moral, religius, dan profetik secara halus namun mendalam.
Dalam konteks pendidikan profetik, sastra berfungsi sebagai media yang mendekatkan pembaca pada nilai-nilai luhur, seperti transendensi, humanisasi, dan liberasi. Roqib menekankan bahwa nilai-nilai ini harus diaktualisasikan melalui pengalaman membaca dan menghayati teks, bukan sekadar memahami teks secara formal. Pendidikan profetik, menurutnya, menuntut pembaca untuk menangkap ruh, makna, dan hikmah di balik simbol-simbol sastra, bukan sekadar bentuk atau kata-kata (2024: 9-15).
Pengalaman membaca karya Ahmad Tohari memperlihatkan hal ini secara konkret. Karya-karya Tohari, seperti novel Ronggeng Dukuh Paruk dan Kubah, menghadirkan realitas sosial dan religius yang akrab bagi masyarakat, tetapi dibingkai dengan pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan, moralitas, dan refleksi spiritual. Dengan demikian, sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau estetika, melainkan juga sebagai sarana pendidikan profetik yang membimbing pembaca untuk memahami kehidupan secara lebih utuh.
Esai ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sastra, khususnya karya Ahmad Tohari, dapat berperan sebagai pendidikan profetik, serta bagaimana pemikiran Moh. Roqib menjadi pijakan teoritis dalam memahami hubungan antara sastra dan pendidikan nilai. Argumen utama yang dikemukakan adalah bahwa sastra, melalui pengembangan karakter, narasi moral, dan penyampaian simbolik, mampu mendidik manusia dalam perspektif profetik, yakni mendekatkan mereka kepada nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab.
Lebih jauh, esai ini juga akan menyoroti refleksi pribadi penulis terkait relevansi pendidikan sastra profetik dalam konteks modern, khususnya bagi pengembangan creative writing berbasis komunitas. Dengan kata lain, sastra bukan hanya medium artistik, tetapi juga instrumen edukatif yang membentuk kesadaran moral, spiritual, dan sosial pembaca, sebagaimana diilustrasikan dalam karya Ahmad Tohari dan dianalisis melalui kerangka pemikiran Moh. Roqib.
II. Nilai Edukatif Sastra dalam Perspektif Profetik (Perluasan)
1. Bahasa dan Sastra sebagai Media Profetik
Dalam pandangan Moh. Roqib (dalam Pendidikan Sastra Profetik), bahasa dan sastra tidak sebatas sarana estetik, tetapi juga medium profetik yang dapat menginternalisasi nilai-nilai kenabian melalui simbol, analogi, dan metafora. Bahasa profetik menjadi jembatan antara tradisi religius dan konteks sosial kontemporer: memungkinkan pemaknaan mendalam sekaligus transformasi nilai.
Misalnya, praktik balaghah (retorika klasik) di lingkungan pesantren memperkaya cara menyampaikan ajaran moral atau spiritual. Menurut Roqib dalam tulisannya “Membangun Budaya Profetik”, simbol-simbol linguistik dapat dimaknai ulang agar mendukung pembebasan (liberasi) manusia dari struktur simbolik atau mitologis yang tidak lagi produktif. Dalam konteks ini, pendidikan sastra memiliki potensi besar karena ia tidak hanya menanamkan makna, tetapi juga membebaskan pemakna (2024: 1‑28).
Secara teoritis, perspektif ini sejalan dengan kerangka pendidikan profetik lainnya: nilai transendensi (hubungan dengan yang ilahi), humanisasi (menjunjung martabat manusia), dan liberasi (membebaskan dari keterikatan simbolik). Dalam praktik sastra, pesan profetik tidak selalu disampaikan secara literal, melainkan melalui “simbol kreatif” yang mengundang refleksi dan pemahaman batin. Dengan kata lain, sastra profetik mampu “menjadi guru bukan hanya melalui kata, tetapi melalui pengalaman simbolik”.
2. Sastra Pesantren dan Islam Nusantara
Sastra pesantren di Indonesia menunjukkan integrasi unik antara tradisi keislaman dan budaya lokal, yang sejalan dengan kerangka pendidikan profetik. Nilai-nilai profetik tidak hanya diinternalisasi melalui teks suci, tetapi juga melalui kehidupan sehari-hari santri; tembang, syair, syair puji-pujian, dan tradisi lisan pesantren menjadi media pengajaran karakter, moral, dan spiritual.
Roqib mencatat bahwa “komitmen pada tradisi yang positif (sunnah hasanah)” menjadi basis untuk mengembangkan pilar-pilar profetik seperti transendensi, humanisasi, dan liberasi. Tradisi lokal seperti mitologi, cerita wali, dan kearifan santri dapat direinterpretasikan agar melayani pendidikan profetik, bukan hanya mengulang adat, tetapi menghidupkan nilai (2024:2‑4).
Studi kontekstual terhadap karya Ahmad Tohari mendukung gagasan ini. Roqib menggambarkan bahwa Tohari menulis tidak hanya sebagai sastrawan, tetapi sebagai pendidik profetik yang menggunakan latar lokal (desa Banyumas) untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, ketakwaan, dan persaudaraan.
Sikap ini menunjukkan bahwa sastra pesantren bukanlah sesuatu yang kuno atau tertutup, tetapi sarana dinamis untuk menumbuhkan Islam Nusantara yang moderat dan berakar budaya. Nilai-nilai profetik ini tercermin dalam keseharian santri: toleransi, toleransi lintas kelompok, dan penghormatan terhadap warisan budaya lokal. Konsep pendidikan profetik ini tidak hanya teoritis, tetapi nyata: pesantren sebagai tempat penanaman moral dan estetika sekaligus.
3. Refleksi Pribadi
Sebagai penulis yang terlibat dalam pendidikan kreatif dan pengembangan karakter melalui sastra, pemahaman tentang sastra profetik membuka perspektif baru: menulis dan membaca tidak hanya sebagai aktivitas seni, tetapi sebagai proses transformasi moral dan rohani. Saya menyadari bahwa sastra, bila diposisikan dalam kerangka profetik, dapat menjadi media pembelajaran karakter yang sangat efektif.
Bagi komunitas penulis muda dan santri penulis, pendidikan sastra profetik berarti mendorong mereka untuk menulis bukan hanya untuk impresi estetika, tetapi untuk menyampaikan nilai: keadilan, empati, kemanusiaan, dan kesadaran spiritual. Dalam lokakarya menulis komunitas, misalnya, kita dapat menghadirkan teks-teks profetik sebagai bahan diskusi yang memancing refleksi tentang keadilan sosial, tanggung jawab, dan peran individu dalam masyarakat.
Di era modern dengan tantangan moral dan sosial yang kompleks (ketimpangan, polarisasi, materialisme), sastra profetik menjadi jembatan penting antara tradisi moral lama dan tuntutan kontemporer. Ia mengajarkan bahwa identitas lokal, tradisi, dan spiritualitas bukan beban masa lalu, tetapi modal untuk membangun masa depan yang lebih adil dan manusiawi.
III. Pendidikan Profetik menurut Moh. Roqib: Refleksi Argumentatif
1. Membangun Budaya Profetik
Moh. Roqib dalam Pendidikan Sastra Profetik menegaskan bahwa pembangunan budaya profetik berakar pada tiga pilar utama: transendensi, liberasi, dan humanisasi (2024: 9‑15). Pilar-pilar ini bukan sekadar teori, tetapi harus teraktualisasi dalam kehidupan nyata, termasuk melalui sastra.
Pilar Transendensi mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, yang dalam konteks sastra berarti teks dapat menuntun pembaca untuk merenungkan nilai spiritual. Roqib menjelaskan bahwa teks sastra profetik memiliki kemampuan untuk mempresentasikan simbol-simbol ilahi melalui cerita, tembang, atau syair sehingga pembaca dapat memahami pesan ketuhanan tanpa bersandar pada bentuk ritual formal semata.
Pilar Liberasi menekankan pembebasan individu dari ketergantungan simbolik, tekanan sosial, dan ketidakadilan. Sastra profetik menampilkan tokoh, konflik, dan narasi yang mengajak pembaca memahami kesadaran kebebasan manusia. Misalnya, dalam penggambaran karakter yang menolak ketidakadilan, pembaca diajak menginternalisasi nilai kebebasan secara moral dan spiritual.
Pilar Humanisasi menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Sastra yang menanamkan nilai ini menumbuhkan empati, solidaritas, dan kepedulian sosial. Roqib menekankan bahwa tanpa humanisasi, pendidikan profetik akan kehilangan relevansi praktisnya bagi kehidupan masyarakat.
Dari perspektif reflektif, ketiga pilar ini dapat diterapkan dalam pendidikan karakter melalui sastra: pembaca belajar menghayati Tuhan (transendensi), mengasah kesadaran kritis terhadap ketidakadilan (liberasi), dan menumbuhkan empati serta tanggung jawab sosial (humanisasi).
2. Implementasi Budaya Profetik
Roqib menegaskan bahwa pilar-pilar profetik harus diaktualisasikan melalui praktik nyata yang mendukung pembentukan karakter dan moral. Salah satu implementasinya adalah mitologi positif, yaitu reinterpretasi mitos atau cerita lokal sebagai sarana pembelajaran moral. Mitologi positif ini menumbuhkan kesadaran nilai-nilai etis dan spiritual dalam konteks budaya yang akrab dengan pembaca (2024: 21‑22).
Selain itu, tradisi dan milieu yang sehat menjadi kerangka pendidikan profetik. Tradisi pesantren, tembang, dan syair yang sarat nilai moral, jika dikemas secara edukatif, memungkinkan santri memahami ajaran keislaman secara holistik. Roqib menekankan bahwa lingkungan yang sehat secara fisik, sosial, dan spiritual memperkuat internalisasi nilai-nilai profetik (2024: 24).
Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan langkah strategis lain, di mana pendidikan profetik bertujuan membentuk individu yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab sosial. Sastra profetik dapat menjadi sarana pelatihan empati dan refleksi moral bagi pembaca.
Peneguhan keberagaman inklusif juga mendapat perhatian. Pendidikan profetik, melalui teks sastra yang menghargai perbedaan, menumbuhkan sikap toleransi dan pengakuan terhadap pluralitas masyarakat. Roqib mengaitkan hal ini dengan Islam Nusantara yang moderat dan adaptif terhadap konteks lokal (2024: 26).
Terakhir, musik edukatif dianggap sebagai medium tambahan untuk memperkuat pesan moral dan spiritual, selaras dengan praktik tradisi pesantren. Musik, tembang, dan syair tidak hanya hiburan, tetapi menjadi media internalisasi nilai transendensi, humanisasi, dan liberasi (2024: 28).
Pendidikan profetik yang dirancang Moh. Roqib memberikan kerangka holistik di mana sastra bukan sekadar estetika, melainkan sarana pembentukan karakter. Relevansinya terhadap pendidikan modern sangat tinggi, terutama dalam konteks pembelajaran berbasis komunitas atau creative writing, karena sastra memungkinkan pembaca untuk menginternalisasi nilai-nilai etis dan spiritual melalui pengalaman simbolik, bukan hanya dogma atau teori.
IV. Pemikiran dan Karya Ahmad Tohari dalam Pendidikan Profetik
1. Sketsa Kehidupan dan Background Sosio-Historis
Ahmad Tohari, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Roqib dalam Pendidikan Sastra Profetik, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan Muslim tradisional pesantren yang akrab dengan budaya agraris Jawa (2024: 30‑31). Pendidikan pesantren tidak hanya menekankan hafalan kitab kuning, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran sosial yang kuat. Interaksi Tohari dengan tokoh-tokoh Islam kultural seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Emha Ainun Nadjib memperkaya wawasan religiusnya, terutama terkait integrasi nilai spiritual dan budaya lokal.
Dari latar belakang ini, Tohari menginternalisasi perspektif bahwa agama harus dihayati sampai ke maknanya, bukan sekadar bentuk formalitas ritual. Roqib menekankan bahwa pendidikan pesantren membekali Tohari dengan kemampuan memahami kehidupan manusia secara komprehensif, yang menjadi dasar bagi sastra profetiknya (2024: 32‑33). Refleksi ini menunjukkan bahwa pengalaman sosio-historis seorang pengarang sangat menentukan kemampuan sastra untuk menanamkan nilai profetik.
2. Transformasi Nilai Profetik ke dalam Sastra
Dalam karya Tohari, nilai-nilai profetik ditransformasikan melalui narasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, novel Kubah menggambarkan perjuangan seorang santri menghadapi dinamika sosial-politik setelah kemerdekaan Indonesia, menekankan integritas, tanggung jawab moral, dan pengorbanan untuk kebaikan bersama. Nilai transendensi tampak ketika karakter utama menempatkan Tuhan sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan (Roqib, 2024: 34).
Ronggeng Dukuh Paruk menghadirkan realitas desa Jawa yang sarat dengan tradisi lokal, di mana konflik sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan dihadapi melalui ketekunan, solidaritas, dan kesadaran moral. Roqib menekankan bahwa dalam konteks pendidikan profetik, karya ini mengajarkan pembaca untuk menginternalisasi kebebasan moral (liberasi) dan penghormatan terhadap sesama manusia (humanisasi) melalui pengalaman estetis yang terhubung dengan budaya lokal (2024: 36‑38).
Cerpen “Anak Ini Mau Mengencingi Jakarta” menampilkan kritik sosial terhadap kesenjangan urban, ketidakadilan, dan pola perilaku manusia yang menyimpang. Dengan cara naratif yang reflektif, Tohari mendorong pembaca menyadari kondisi sosial, sekaligus menumbuhkan empati dan kesadaran akan tanggung jawab moral. Dalam konteks pendidikan profetik, narasi ini berfungsi sebagai medium liberasi dan humanisasi, di mana pembaca belajar memahami dan menilai realitas sosial secara etis.
3. Indikator Pendidikan Profetik dalam Karya Tohari
Roqib mengidentifikasi indikator pendidikan profetik dalam karya Tohari melalui implementasi pilar transendensi, liberasi, dan humanisasi. Pilar transendensi tercermin pada karakter yang senantiasa menempatkan nilai Tuhan sebagai acuan moral, baik dalam Kubah maupun Ronggeng Dukuh Paruk. Pilar liberasi tampak dalam penggambaran perjuangan melawan ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan penindasan, di mana tokoh-tokohnya tidak pasif tetapi aktif membebaskan diri dan masyarakat dari tekanan sosial. Pilar humanisasi hadir dalam cara Tohari menekankan empati, toleransi, dan solidaritas antarmanusia, terutama melalui relasi antartokoh dalam novel dan cerpennya (2024: 41‑43).
Dalam Ronggeng Dukuh Paruk, tokoh Srintil menghadapi dilema moral yang memerlukan pengorbanan demi kebaikan orang lain. Narasi ini mendidik pembaca untuk merenungkan nilai kemanusiaan dan keadilan secara mendalam, sehingga sastra berfungsi sebagai medium pendidikan profetik yang efektif. Refleksi ini memperlihatkan bahwa sastra, ketika dipahami melalui lensa profetik, dapat menanamkan kesadaran sosial, moral, dan spiritual secara bersamaan.
Pendidikan profetik dalam karya Tohari bukan sekadar penyampaian pesan moral, tetapi integrasi nilai-nilai ketuhanan, kebebasan, dan kemanusiaan ke dalam narasi yang hidup. Dengan membaca dan merefleksikan karya-karya ini, pembaca tidak hanya menikmati estetika sastra, tetapi juga belajar menilai realitas sosial, menginternalisasi nilai moral, dan menguatkan kesadaran spiritual. Sastra profetik, oleh karena itu, menjadi wahana pendidikan karakter yang mampu menjembatani pengalaman lokal dan nilai universal.
V. Karakteristik Pesan Profetik Ahmad Tohari
1. Pesan dan Karakteristik Karya
Karya-karya Ahmad Tohari, baik novel maupun cerpennya, menampilkan integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai profetik, yang menjadi ciri khas pendidikan sastra dalam perspektif Moh. Roqib (2024: 70-72). Misalnya, trilogi Ronggeng Dukuh Paruk menempatkan kehidupan masyarakat pedesaan sebagai panggung narasi, di mana konflik sosial, ketimpangan ekonomi, dan ketahanan spiritual tokoh-tokohnya dipaparkan secara nyata. Pesan moral dan spiritual dalam karya Tohari tidak hadir sebagai retorika normatif semata, tetapi menyatu dalam realitas sosial yang dialami tokoh dan pembaca. Dengan cara ini, sastra menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran etis, spiritual, dan sosial, sehingga pembaca tidak hanya mengapresiasi estetika, tetapi juga mengambil pelajaran hidup yang aplikatif.
Roqib menekankan bahwa dalam pendidikan profetik, nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan spiritual harus menyatu dalam praktik nyata, bukan sekadar teori atau simbol kosong. Dalam konteks karya Tohari, pesan profetik ini hadir melalui kisah tokoh-tokoh yang menghadapi ketidakadilan, kemiskinan, atau godaan moral, yang pada akhirnya memberikan pembelajaran bagaimana berperilaku adil, penuh empati, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.
2. Pemaknaan Budaya Lokal
Sastra Tohari secara konsisten memanfaatkan budaya lokal sebagai medium pemaknaan nilai profetik. Misalnya, tembang-tembang, syair, dan tradisi agraris Jawa menjadi elemen naratif yang tidak hanya memperkaya estetika, tetapi juga memperjelas makna moral dan spiritual. Budaya lokal ini memungkinkan pembaca merasakan konvergensi antara nilai tradisi dan ajaran profetik, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih hidup dan relevan dengan konteks kehidupan nyata (Roqib, 2024: 75).
Dalam perspektif pembelajaran sastra profetik, penggunaan budaya lokal tidak semata-mata untuk nostalgik atau identitas sempit, tetapi sebagai jembatan pemahaman yang memungkinkan nilai transendensi, kebebasan, dan kemanusiaan dihayati secara kontekstual. Contohnya, penghormatan terhadap orang tua, gotong-royong, dan kearifan lokal dalam karya Tohari menegaskan bahwa nilai moral dan spiritual dapat ditransformasikan melalui medium sastra tanpa kehilangan akar budaya.
3. Refleksi Argumentatif
Melalui karakteristik karya Ahmad Tohari, kita dapat melihat bahwa sastra bukan hanya seni, tetapi juga praktik pendidikan profetik. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya-karyanya (transendensi, liberasi, dan humanisasi) dapat mentransformasikan moral, karakter, dan kesadaran sosial pembaca. Hal ini sesuai dengan pandangan Roqib bahwa pendidikan profetik harus menyatukan pembelajaran nilai, pengalaman sosial, dan praktik spiritual sehingga pembaca atau peserta didik mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (2024: 81).
Dengan demikian, membaca karya Tohari bukan sekadar aktivitas estetik atau hiburan, tetapi proses edukatif yang menumbuhkan kesadaran profetik. Pembaca yang mampu menangkap pesan ini secara reflektif akan memperoleh pelajaran moral dan spiritual yang tidak hanya teoritis, tetapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sosial dan kultural mereka sendiri. Sastra, dalam kerangka ini, menjadi instrumen transformasi karakter yang efektif dan berkelanjutan.
VI. Signifikansi Buku Pendidikan Sastra Profetik bagi Pendidikan dan Sastra Indonesia
Buku Pendidikan Sastra Profetik karya Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. merupakan salah satu terobosan penting dalam kajian pendidikan sastra Indonesia karena menempatkan sastra bukan sekadar sebagai teks estetis, tetapi sebagai wahana transformasi spiritual, moral, dan sosial. Buku ini menyatukan tiga ranah yang selama ini sering dipisahkan: pendidikan, sastra, dan nilai profetik. Dengan demikian, karya ini dapat dibaca sebagai usaha membangun paradigma baru: bahwa sastra tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi juga tentang misi kenabian dalam membimbing manusia menuju bentuk kemanusiaan yang lebih paripurna.
1. Perspektif Pendidikan Sastra
Dari sudut pendidikan sastra, buku Roqib memperluas pengertian sastra sebagai media pembelajaran. Ia tidak berhenti pada pendekatan struktural, stilistika, atau semiotika, melainkan menegaskan dimensi etis dan pedagogis dari teks sastra. Menurut Burhan Nurgiyantoro dalam Teori Pengkajian Fiksi, sastra dapat menjadi sarana pendidikan karakter karena ia bekerja melalui penghayatan nilai, bukan melalui ceramah moral (2003: 1). Gagasan ini sejalan dengan penekanan Roqib bahwa sastra mampu mengajak pembaca memasuki ruang permenungan yang lebih dalam melalui simbol, imaji, dan dialog batin.
Roqib menyoroti bagaimana analogi balaghah, tradisi pesantren, serta praksis Islam Nusantara memainkan peran penting dalam pembentukan karakter masyarakat. Ia menegaskan bahwa sastra sering kali menjadi jembatan antara pesan moral dan konteks sosial pembacanya. Dalam hal ini, ia mengikuti pandangan Wolfgang Iser dalam The Act of Reading yang menyatakan bahwa teks sastra bekerja melalui “ruang kosong” yang diisi oleh pengalaman dan kesadaran pembacanya (1978: 50). Maka, ketika pembaca menafsirkan teks, ia sedang melakukan proses pendidikan diri yang bersifat batiniah.
Melalui analisis tersebut, Roqib memperlihatkan bahwa pendidikan sastra bukan sekadar mengajarkan apresiasi, tetapi membentuk kemampuan reflektif, empati, dan kepekaan etis—sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan karakter kontemporer.
2. Perspektif Sastra Profetik
Buku ini juga penting dalam konteks sastra profetik. Roqib menegaskan tiga pilar profetik (transendensi, liberasi, dan humanisasi) sebagai pendekatan untuk membaca karya-karya sastra Indonesia. Pendekatan ini dekat dengan konsep yang diperkenalkan oleh Kuntowijoyo dalam Identitas Politik Umat Islam, yang memaknai profetik sebagai usaha mentransformasikan nilai kenabian ke dalam realitas sosial, yakni penyatuan antara kesadaran ketuhanan, kesadaran pembebasan, dan kesadaran kemanusiaan (1997: 74).
Ketika Roqib membedah karya Ahmad Tohari (Kubah, Ronggeng Dukuh Paruk, dan sejumlah cerpen) ia menegaskan bahwa nilai profetik bukanlah tambahan eksternal yang ditempelkan pada karya, melainkan sudah inheren dalam struktur naratif dan psikologi tokoh-tokohnya. Misalnya, Kubah menampilkan perjalanan tobat dan transformasi spiritual seorang tokoh yang kembali kepada Tuhan setelah tersesat oleh ideologi politik; ini adalah ekspresi transendensi sekaligus liberasi batin.
Demikian pula Ronggeng Dukuh Paruk memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan, tradisi lokal, dan kekerasan politik dirajut menjadi narasi yang memanggil pembaca pada kesadaran humanisasi paling mendasar: bahwa manusia harus dimuliakan, bukan diperalat. Pendekatan Roqib ini berbeda dari kritik sastra konvensional yang berhenti pada dimensi sosial atau estetis; ia mendorong pembacanya untuk melihat sastra sebagai ruang etika profetik yang menggerakkan kesadaran.
3. Perspektif Pendidikan Sastra Profetik di Indonesia
Signifikansi buku ini menjadi semakin besar ketika ditempatkan dalam konteks pendidikan Indonesia. Setidaknya ada tiga kontribusi penting.
Pertama, buku ini menawarkan kerangka teoritis yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan estetika dan spiritualitas. Selama ini pendidikan karakter sering dianggap sebagai seperangkat nilai normatif yang diajarkan secara verbal, padahal sastra (melalui penghayatan) lebih efektif dalam membentuk kepribadian. Dalam hal ini, pendekatan Roqib menegaskan kembali gagasan D.S. Lichfield dalam The Humanities and Social Change bahwa karya sastra memiliki “kemampuan moral untuk menstrukturkan kesadaran manusia” (1980: 29).
Kedua, buku ini relevan bagi guru, dosen, komunitas sastra, dan pesantren karena menjembatani antara tradisi lokal (tembang Jawa, syair, balaghah, tradisi santri) dengan pendidikan modern. Sastra profetik dalam kerangka Roqib bukanlah konsep yang mengambang, tetapi berakar pada tradisi Nusantara dan praktik kultural masyarakat Indonesia.
Ketiga, buku ini memperkukuh posisi sastra sebagai ruang dialog antara religiusitas dan kemanusiaan, antara budaya lokal dan nilai universal. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, pendekatan ini sangat strategis sebagai dasar pembentukan etika publik yang sehat dan inklusif.
Secara reflektif-argumentatif, dapat ditegaskan bahwa buku Pendidikan Sastra Profetik memiliki posisi penting dalam perkembangan wacana pendidikan dan sastra di Indonesia. Roqib berhasil memperlihatkan bahwa sastra tidak hanya menghibur dan mengajar, tetapi juga “membimbing”, menggerakkan jiwa menuju bentuk kemanusiaan yang lebih utuh. Dengan demikian, buku ini bukan hanya kontribusi akademik, tetapi juga tawaran kultural dan spiritual bagi masa depan pendidikan sastra di Indonesia.
VII. Kesimpulan
Esai ini menegaskan bahwa sastra memiliki fungsi yang melampaui hiburan atau ekspresi estetis. Sastra, sebagaimana dijelaskan secara mendalam oleh Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. dalam Pendidikan Sastra Profetik, merupakan medium yang mampu menggerakkan perkembangan spiritual, moral, dan sosial manusia. Melalui tiga pilar profetik (transendensi, liberasi, dan humanisasi) Roqib menunjukkan bahwa sastra dapat membentuk karakter pembacanya dengan cara yang subtil tetapi mendalam, yakni melalui pengalaman batin, penghayatan simbol, dan permenungan etis yang lahir dari kontak dengan teks.
Dalam ruang praktis sastra Indonesia, karya-karya Ahmad Tohari memperlihatkan bagaimana nilai profetik tersebut bekerja secara konkret. Melalui Kubah, Ronggeng Dukuh Paruk, dan cerpen “Anak Ini Mau Mengencingi Jakarta”, Tohari menghadirkan perjalanan spiritual manusia, kritik sosial, dan pembelaan terhadap martabat kaum kecil. Tohari memperlihatkan bahwa sastra dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai keagamaan dan realitas sosial yang keras; antara pengalaman lokal dan pesan-pesan universal tentang kemanusiaan. Dengan demikian, teori pendidikan sastra profetik Roqib mendapatkan pijakan aplikatif dalam estetika dan representasi naratif Tohari.
Di tengah dunia modern yang ditandai oleh fragmentasi nilai, informasi berlebih, dan meningkatnya individualisme, pendidikan sastra profetik memberikan alternatif yang relevan dan signifikan. Sastra profetik mengingatkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga kedalaman batin; tidak hanya kecerdasan rasional, tetapi juga kecerdasan moral dan spiritual. Pendekatan ini memperkuat kembali fungsi sastra sebagai pembentuk empati, kepekaan sosial, dan keberanian moral: unsur penting yang semakin mendesak dalam pendidikan karakter.
Integrasi sastra dan nilai profetik sebagaimana diusulkan Roqib merupakan tawaran yang tidak bersifat indoktrinatif, melainkan transformatif. Ia menempatkan pendidikan karakter sebagai proses reflektif, bukan sekadar pengulangan norma. Di sisi lain, karya Tohari menunjukkan bahwa nilai profetik dapat dihadirkan secara alami dalam cerita, bukan sebagai pesan moral yang didaktis. Sinergi keduanya membuka potensi besar bagi pendidikan sastra profetik sebagai model pembelajaran yang menggabungkan estetika, etika, spiritualitas, dan kesadaran sosial.
Bagi praktik creative writing berbasis komunitas, pendekatan profetik menawarkan arah baru yang memperkaya. Komunitas sastra dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk membentuk penulis yang tidak hanya terampil secara estetis, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis dan sosial. Penulis pemula dapat belajar dari cara Tohari mengolah realitas lokal menjadi narasi universal, serta dari Roqib tentang bagaimana nilai profetik bekerja sebagai prinsip pedagogis. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi kekuatan budaya yang mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang membumi, visioner, dan bermakna.
Akhirnya, esai ini menegaskan bahwa sastra profetik memiliki peran strategis dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter, arif, dan empatik. Melalui perpaduan antara pemikiran Roqib dan praksis estetik Tohari, pendidikan sastra profetik bukan hanya wacana teoretis, tetapi juga model praksis kebudayaan yang dapat memperkaya kehidupan intelektual, spiritual, dan sosial masyarakat. Sastra, dengan demikian, kembali ke hakikatnya sebagai jalan menuju kemanusiaan yang lebih utuh.***
Daftar Pustaka
Kuntowijoyo. 1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan.
Lichfield, D. S. 1980. The Humanities and Social Change. New York: Harper & Row.
Nurgiyantoro, Burhan. 2003. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Roqib, Moh. 2024. Pendidikan Sastra Profetik. Purwokerto: Pesma An Najah Press.
Tohari, Ahmad. 1980. Kubah. Jakarta: Pustaka Jaya.
Tohari, Ahmad. 1982. Ronggeng Dukuh Paruk. Jakarta: Gramedia.
Tohari, Ahmad. 2015. “Anak Ini Mau Mengencingi Jakarta.” Dalam Cerpen Pilihan Kompas 2015. Jakarta: Penerbit Kompas.
—–
*Abdul Wachid B.S., Penyair, Guru Besar Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.