Pelajaran dari Mooi Indië dan Produksi Pengetahuannya
(Tanggapan untuk Syarif Maulana, Dwihandono Ahmad, dan Nurman Hakim)
Oleh Chabib Duta Hapsoro
Kita tahu bahwa Auguste Antoine Joseph Payen (1792-1853) adalah guru melukis Raden Saleh (1811-1880). Eksistensi dia yang lain adalah sebagai pelukis Kerajaan Belanda untuk menemani ekspedisi sains di Hindia Belanda pada dekade pertama abad 20. Payen beserta dua bersaudara Adrianus Johanes Bik (1790-1872) dan Jannes Theodoor Bik (1796-1875) menemani botanis Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854) selaku kepala ekspedisi sains ini. Payen ditugaskan untuk menghadirkan gambar-gambar pemandangan Pulau Jawa seakurat mungkin. Payen tercatat mengikuti Reinwardt di Priangan dan banyak bagian Jawa pada kurun waktu 1817 hingga 1820. Setelah itu, ia kemudian menjelajahi Sulawesi dan Maluku tanpa Reinwardt. Payen memang menyelesaikan beberapa lukisannya di Hindia Belanda. Tapi, menurut Marie-Odette Scalliet dalam buku Pictures from the tropics: Paintings by western artists during the dutch colonial period in Indonesia (1999) sebagian besar lukisannya ia selesaikan di Belgia, negara asalnya, bertahun-tahun kemudian (hal. 57). Penggambaran Hindia Belanda bertahun-tahun setelah Payen pergi dari Hindia Belanda tentu melewatkan banyak hal yang terjadi di Hindia Belanda, misalnya kuasa kolonial yang semakin sarat. Di Eropa, Payen menggambarkan Hindia Belanda bertumpu pada sketsa-sketsa dan ingatan-ingatan yang bercampur dengan imajinasinya. Sementara Hindia Belanda berubah di luar sana. Kita melihat bagaimana orientalisme sedang bekerja.
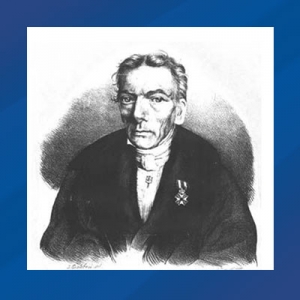
Potret Caspar Georg Carl Reinwardt dari buku biografinya yang ditulis oleh Peter van Mensch (Unknown author, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons)
Sebagai pelukis kerajaan Payen melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang perlu kita cermati adalah institusi kerajaan yang memberi tugas kepadanya. Singkat cerita, pemerintah kolonial kemudian meneruskan proyek ekspedisi pengetahuan itu yang kemudian menemukan beragam sumber daya alam dan kemungkinan-kemungkinan lain untuk mengeksploitasi koloni.
Bertahun-tahun kemudian banyak pelukis-pelukis amatir yang mengikuti jejak Payen untuk melukis pemandangan. Mereka antara lain adalah pegawai negara atau saudagar perkebunan, seperti Abraham Salm. Susie Protchsky dalam bukunya Images of the tropics: Environment and visual culture in colonial Indonesia (2011), menyebut bahwa lukisan-lukisan pemandangan karya Abraham Salm (1857-1915) mereduksi dan mengaburkan penampakan monokultur perkebunan, sehingga menunjukkan alam Indonesia yang seolah-olah masih alami (hal. 86-87).

Auguste Antoine Joseph Payen, The Great Postal Route near Rejapolah, cat minyak di atas kanvas, 167 × 140 cm, 1828. Koleksi Rijksmuseum Amsterdam (Public domain)
Inilah yang kemudian dikritik Sudjojono dalam beberapa tulisannya pada pertengahan abad 20, menyoal terus lestarinya lukisan pemandangan di koloni tanpa alternatif. Ia lantas menahbiskan secara sinis lukisan pemandangan sebagai Mooi Indië. Maka kritik Sudjojono tidak bisa dinilai sebagai reduktif melalui kacamata sekarang. Kritik Sudjojono harus dinilai secara proporsional kapan dan di mana ia merespon situasi itu. Sudjojono, dibandingkan pelukis-pelukis lain seperti Abdullah Suriosubroto (1878-1941), Sudjono Abdullah (1911-1993) dan Basuki Abdullah (1915-1993) yang memiliki privilese melimpah sebagai kelas menengah, meyakini pandangan yang berbeda. Sudjojono mengetahui ada yang salah dari Mooi Indië sebagai bagian dari masyarakat kolonial. Mooi Indië bukanlah produk yang baik untuk masyarakat terjajah. Membaca kritik-kritik Sudjojono terhadap Mooi Indië pada zaman itu kita akan melihat seorang intelejensia seni yang berusaha lepas dari “benak yang tertawan” (captive mind), sebuah konsep yang diciptakan oleh Syed Hussein Alatas. Ia ingin lepas dari perilaku yang imitatif dan tidak kritis. Sudjojono saat itu menunjukkan intelejensia yang otonom. Ia memakai pengaruh apa pun, dari Barat maupun Timur, untuk keluar dari situasi yang mengekang.

Abraham Salm, Een landschap in Bantam (Pemandangan di Bantam), litografi, 1865-1872, Koleksi Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)
Saya membaca Mooi Indië dengan melihat konteks penciptaan, apresiasi dan konsumsinya di tengah masyarakat kolonial. Kita seharusnya menilai siapa yang paling diuntungkan dan dirugikan oleh Mooi Indië. saat itu. Setiap hasil produksi pengetahuan seharusnya bisa dibaca kepentingannya, ideologi apa yang didukungnya dan ideologi apa yang sedang ia bungkam. Apakah menggambarkan pemandangan pedesaan berarti mendukung kepentingan masyarakat desa? Atau justru menempatkan desa sebagai entitas yang ajeg, yang harus terus menerus dirawat representasinya sebagai desa yang tradisional dan tidak bisa (atau boleh) berubah?
Kita bisa mengurai lagi gagasan orientalis yang dimanifestasikan oleh lukisan Mooi Indië dalam masyarakat kolonial. Gagasan orientalis juga menubuh dalam kompetisi imperialisme di antara negara-negara penjajah. Mereka berlomba untuk membawa eksplorasi pengetahuan dan budaya tempatan di koloni. Penemuan-penemuan kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat Eropa di negara induk. Sebagai produk pengetahuan yang bersumber dari negeri koloni, apakah lukisan Mooi Indië punya penonton dari penduduk pribumi jajahan?
Sekali lagi tentang Otonomi Seni Rupa Indonesia
Elaborasi karakter-karakter sosiologis Mooi Indië menunjukkan bahwa seni lukis ini merupakan hasil produksi pengetahuan orientalis yang mendukung kepentingan kuasa kolonial. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa manerisme seni lukis Mooi Indië dalam masyarakat kolonial menunjukkan sebuah medan seni rupa yang tidak berkembang. Ia adalah salah satu gejala yang menampakkan bahwa seni rupa tidak diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Secara lebih makro ia membuktikan pula bagaimana produksi pengetahuan secara umum di koloni yang memang dikembangkan dalam kepentingan ekstraksi dan eksploitasi koloni, demi kemaslahatan negara induk. Dengan argumentasi seperti ini kita bisa tegas menyebut bahwa Mooi Indië, dengan segala keindahan yang ia tawarkan, adalah warisan semenjana untuk seni rupa Indonesia. Namun, kita tetap perlu mempelajarinya agar kita tidak mengulangi kesalahan produksi pengetahuannya. Praktik ini acapkali disebut sebagai “unlearning” yakni melucuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari telah merugikan kita dan berusaha meninggalkannya. Unlearning sering menjadi terma kunci dalam diskursus dekolonisasi, sebuah upaya mempertanyakan, menolak dan membongkar pemahaman kita yang masih terbelenggu sebagai akibat dari penjajahan. Dekolonisasi sering dianggap sebagai upaya yang utopis karena masih perkasanya kooptasi warisan kolonialisme di banyak struktur kehidupan hari-hari ini.
Belajar untuk meninggalkan produksi pengetahuan dari seni lukis Mooi Indië amat penting untuk otonomi seni rupa Indonesia. Dalam konteks ini, kita akan memahami bahwa kesadaran dan laku otonomi tidak bisa kita bebankan kepada satu pihak saja. Otonomi seni rupa Indonesia yang saya maksudkan di sini adalah menyadari bahwa seni rupa beserta produksi pengetahuannya seharusnya dilakukan di bawah kepentingan kita sendiri. Maka dari itu ia punya tradisi pengetahuan yang mandiri dan khas, yang hasilnya bisa diakses siapa pun demi kemaslahatan publik. Ia tidak tunduk atau diperdaya oleh kepentingan-kepentingan golongan, baik dari dalam maupun luar. Ia juga tidak dipakai sebagai instrumen pendukung kekuasaan, lebih-lebih yang represif.
Menyadari bahwa produksi pengetahuan Mooi Indië yang hanya menguntungkan satu golongan saja, maka otonomi seni rupa Indonesia memerlukan praktik pengarusutamaan. Sanento Yuliman dalam tulisannya di harian Kompas berjudul Menuju Pengasingan Seni (4): Usaha Diagnosis dan Terapi (1969) menyatakan peran ekosistem seni rupa pada zaman modern adalah menjamin “terselenggaranya kesempatan yang terbuka bagi setiap orang dari setiap lapisan masyarakat untuk berhubungan dengan seni, baik hubungan penikmatan (apresiasi), penerangan, pendidikan, maupun penciptaan” (dalam Sanento Yuliman, Estetika yang Merabunkan (2020), hal. 157). Untuk memenuhi peran-peran itu, diperlukan ketersediaan ekosistem dan sumber daya yang lengkap, yakni seniman, kurator, kritikus, sekolah seni, galeri, museum dan seterusnya. Jika hal ini hanya lengkap dan berfungsi di pusat seni rupa saja, yakni Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, bagaimana kita bisa meyakini seni rupa kontemporer dan penikmatnya eksis di kota-kota lain di Jawa, seperti Semarang, Solo atau Surabaya? Atau bahkan kota-kota lain di luar Jawa?
Inisiatif-inisiatif partikelir telah kerapkali melakukan usaha-usaha untuk mengarustamakan seni rupa kontemporer Indonesia di luar tiga pusat itu, dengan beragam wacana dan pendekatan. Tak jarang mereka juga mendapatkan pendanaan dari institusi-institusi seni luar negeri. Globalisasi dan internet memungkinkan faktor-faktor luar juga memberikan dukungan terhadap pengembangan kebudayaan di Indonesia.
Di sisi lain, negara akhirnya memiliki paket kebijakan yang konkret untuk mendukung dan melindungi kebudayaan ketika Undang-Undang Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan. Dengan dasar hukum itu, di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, negara menunjukkan dukungan terhadap produksi dan dokumentasi untuk seluruh bidang seni. Program-program tersebut juga terlihat berprinsip berkeadilan, merangkul pelaku-pelaku seni rupa dengan beragam privilese, latar belakang dan asal. Meskipun pelaksanaannya masih berantakan, landasan hukum ini menjawab perhatian Yuliman terhadap kebutuhan sosialisasi seni yang menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk mengalami seni rupa. Problem pusat dan luar pusat seharusnya makin bisa teratasi. Kota-kota di luar Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta lebih punya peluang untuk mengembangkan seni rupanya sendiri. Jika pengarusutamaan sudah dilakukan, maka kita bisa berbicara tentang apresiasi dan lebih lanjut mengenai produksi pengetahuan yang mampu mencerahkan publik.

Gustave Coubet, The Stonebreakers (Para Pemecah Batu), cat minyak di atas kanvas, 165 x 257 cm, 1849, koleksi Gemäldegalerie Alte Meister (musnah pada 1945 karena Perang Dunia II) (Gustave Courbet, Public domain, via Wikimedia Commons)
Kita bisa membicarakan manifestasi otonomi seni rupa Indonesia dalam konteks yang lain, misalnya internasionalisasi. Medan seni rupa Hindia Belanda, menurut Aminudin TH Siregar adalah medan transnasional (Kisah Kritik Seni—sebagai esai pengantar buku Keindonesiaan, Kerakyatan dan Modernisme dalam Kritik Seni Lukis di Indonesia, 2019) (hal. xix). Ia adalah medan yang beberapa kali menjalin kontak, dengan medan seni rupa mancanegara, misalnya memamerkan beberapa karya maestro seni rupa modern dunia. Namun medan transnasional itu hampir tak punya pengaruh kepada perkembangan praktik pelukis-pelukis Eropa di Hindia Belanda, karena seni lukis Mooi Indië terus menjadi arus utama. Hanya sedikit genre-genre lain yang ditekuni seniman-seniman Eropa di Hindia Belanda. Sampai sekarang pun kita tidak mengetahui, adakah pelukis Eropa di Hindia Belanda yang menekuni realisme ala Gustave Courbet misalnya.
Memang seni rupa kontemporer Indonesia mendapat banyak manfaat melalui kontak-kontak dengan medan seni rupa mancanegara. Sudah banyak sekali perupa Indonesia yang berpartisipasi dalam sejumlah pameran dan proyek-proyek seni penting di luar negeri. Karya-karya mereka juga sudah banyak dikoleksi oleh museum-museum penting mancanegara. Keduanya merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan. Ini membuktikan bahwa seniman-seniman kita mampu berkontestasi di tengah medan kebudayaan global, menyumbangkan gagasan-gagasan khas tentang kemanusiaan, kesetaraan dan perdamaian.
Namun itu tidak banyak artinya jika kita belum memiliki kesadaran perihal otonomi. Kebergantungan yang berlebihan hanya menempatkan kita sebagai objek. Hingga sekarang, situasi ini masih berlangsung ketika seni rupa Indonesia masih menjadi subordinat dari inisiatif-inisiatif dari luar yang kaya akan sumber daya. Sumber-sumber pengetahuan terbaik kita, baik karya seni maupun arsip, dengan cepat diakses oleh mereka untuk audiens di negara-negara mereka. Akhirnya sumber-sumber terbaik kita belum mencerahkan untuk masyarakat kita sendiri.
Mendiskusikan relasi antara Mooi Indië dan kapitalisme kolonial dapat menyediakan kita peranti yang diagnostik untuk memeriksa otonomi seni rupa Indonesia di tengah neoliberalisme. Ini adalah hal yang menantang dan melelahkan karena rumitnya struktur kuasa dalam sistem neoliberal. Struktur kuasa ini beroperasi melalui cara-cara eksploitasi yang subtil dalam medan seni rupa sejagat. Namun, saya menolak untuk menyebut bahwa otonomi seni rupa Indonesia hanyalah sebuah utopia.
*Penulis seni rupa, tinggal di Singapura













