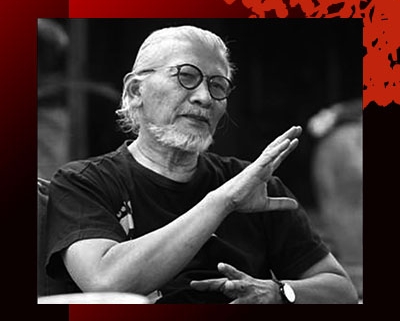Romo Mangun
Oleh Riwanto Tirtosudarmo
Seingat saya, saya sempat bertemu beliau dua kali. Yang pertama ketika dengan beberapa teman mengunjungi tempat tinggal beliau di perkampungan padat di bantaran kali Code, di tengah kota Yogyakarta. Pertemuan kedua ketika diajak Mohamad Sobary, saat itu kami sama-sama bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, menemui beliau yang sedang dalam sebuah acara di gedung Kompas Gramedia di Palmerah, Jakarta Selatan.

Foto Romo Mangun. (Sumber: Istimewa)
Pada pertemuan pertama, kami ingin mendengarkan cerita beliau tentang kegiatannya membantu penduduk merapikan rumah-rumah mereka yang tadinya kumuh menjadi pemukiman yang tidak saja rapi dan bersih tapi juga artistik. Untuk kegiatannya ini Romo Mangun mendapatkan Aga Khan Award yang sangat prestisius. Pada pertemuan kedua, saya menemani Kang Sobary, untuk meminta beliau menjadi salah satu pembicara dalam sebuah acara yang kami gagas, semacam refleksi intelektual, di akhir tahun, di LIPI. Acara itu selain menampilkan Romo Mangun juga menampilkan Asrul Sani, Goenawan Mohamad, Emha Ainun Najib, Todung Mulya Lubis, Mochtar Pabottingi dan sejumlah tokoh lain. Sebuah acara yang menurut kami sangat sukses karena berhasil mendiskusikan persoalan kemasyarakatan dan kebudayaan secara serius ditengah ketakutan berpendapat zaman itu.
Jika sekarang saya menulis tentang Romo Mangun, maka jelas tulisan saya itu lebih banyak didasarkan pada bahan bacaan, baik yang ditulis oleh beliau sendiri, maupun oleh orang lain yang mengenal beliau. Romo Mangun lahir di Ambarawa pada tanggal 6 Mei 1929 dan wafat, secara meakjubkan dalam pelukan sahabatnya, yang juga sahabat baik saya, Mohamad Sobary, tanggal 10 Februari1999 setelah memberikan ceramah dalam seminar Meningkatkan Peran Buku dalam Upaya Membentuk Masyarakat Indonesia Baru di Hotel Le Meridien, Jakarta. Beliau meninggal ketika Indonesia memasuki babak baru sejarahnya setelah Suharto lengser keprabon pada tanggal 21 Mei 1998. Eforia reformasi politik memenuhi udara dengan harapan akan munculnya tatanan sosial-politik baru yang lebih adil seperti yang dicita-citakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945.
Dalam pengetahuan saya yang terbatas tentang Romo Mangun, saya menemukan sosok yang menurut pandangan saya sulit dicari padanannya. Ketika buku saya, Mencari Indonesia 4: Dari Raden Saleh sampai Ayu Utami, terbit (2022), seorang teman mengingatkan, tokoh dengan nama mulai dengan huruf awal Y, belum ada, dan teman ini menyebutkan nama YB Mangunwijaya. Saat itu saya juga baru menyadari, mengapa tokoh sepenting Romo Mangun terlewat untuk saya tuliskan sosoknya? Tapi sambil merenung saya juga menyadari betapa banyak sosok-sosok penting di negeri ini, betapa kaya sesungguhnya Indonesia dengan tokoh-tokoh teladan. Tapi mengapa Indonesia masih sering dilihat sebagai negeri yang bergerak mundur, kalau tidak stagnan?
Sebagai seorang Romo Katolik, Romo Mangun jelas telah memilih jalan pengabdian kepada Tuhannya dan kemanusiaan secara total. Sebuah pilihan, menggunakan istilah dalam ajaran spiritual Sumarah, “menjadi orang biasa tapi tidak seperti biasanya orang”. Dalam jalan pengabdiannya itulah kita melihat bagaimana Romo Mangun mengembangkan dan melibatkan diri dalam berbagai bentuk kegiatan, tidak saja bersifat pemikiran tetapi juga kiprah langsung di masyarakat. Pendampingannya yang total terhadap warga masyarakat pinggiran, terutama di Code dan Kedung Ombo, tidak saja untuk memperbaiki taraf kesejahteraan namun yang tampaknya lebih ditekankan adalah mengangkat harga diri mereka sebagai warganegara. Karya-karya pemikirannya, bisa ditemui dalam berbagai buku yang ditulisnya, baik yang berupa esai perenungan, karya ilmiahnya sebagai seorang arsitek, maupun dalam karya sastra, baik cerpen maupun novel.

Foto Kali Code yang penataannya diinisiasi oleh Romo Mangun. (Sumber: Istimewa)
Tidak semua bukunya yang banyak itu saya baca. Buku kumpulan esai perenungan yang berjudul Sastra dan Religiositas yang saya dapat dari Romo Kirjito belum lama ini membuka mata saya bahwa justru melalui sastra-lah perenungan manusia tentang agama dan relijiusitas berhasil disampaikan dari pada melalui teks-teks agama atau religi yang resmi. Bagi saya juga menarik esai perenungan tentang relijiusitas yang lebih ditemukan dalam sastra ini disampaikan oleh seorang Romo Katolik yang sudah pasti lebih terbiasa dengan teks-teks agama dan religi yang resmi. Romo Mangun jelas memang bukan Romo biasa. Saya ingat membaca buku yang berjudul Menumbuhkan Sikap Religius Anak-anak (1986) yang diberi kata pengantar oleh Gus Dur, kawan dekatnya, menunjukkan perhatiannya bahwa menyemai gagasan haruslah sudah dilakukan sejak anak-anak.
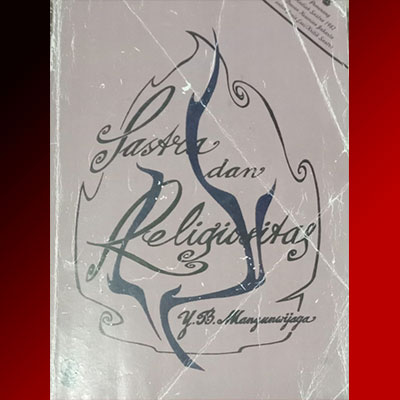
Foto buku Sastra dan Religiositas (Sumber: Istimewa)
Saya kira menjadi keyakinan beliau bahwa melalui pendikan dasar perbahan masyarakat harus dimulai. Itulah yang kemudian mendorongnya mendirikan lembaga edukasi dasar di Yogyakarta yang sampai hari ini masih diteruskan oleh murid-muridnya. Buku novelnya yang tuntas saya baca, Burung-burung Manyar (1981) memperlihatkan perhatiannya yang kuat tentang sejarah perjuangan bangsanya dalam merebut dan mengisi kemerdekaannya. Dalam buku itu, seperti saya kira selalu muncul dalam buku-buku fiksinya, pertentangan batin dan ketegangan antara tokoh-tokohnya diberi porsi yang besar olehnya. Selalu kita diajak untuk merenungkan kembali apa itu makna kehidupan.
Sebagai seorang peneliti sosial jika ada hal yang menarik yang lain dari Romo Mangunwijaya adalah pemikirannya tentang bentuk negara yang seharusnya dipilih oleh Indonesia jika ingin mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaannya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pada tahun 1998 ketika rezim Suharto dengan Orde Baru-nya tumbang, ibarat panci yang berisi air mendidih, ketika tutupnya dibuka, air panas meluap kemana-mana. Sebuah masa yang bisa dibilang sebagai “An Indonesian Spring” periode 1998-1999 mendorong lahirnya berbagai gagasan tentang bagaimana mengarahkan kembali politik Indonesia kedepan. Masa ini juga ditandai oleh apa yang kemudian dekenal sebagai periode reformasi. Paling tidak ada dua perubahan besar yang kemudian terjadi. Pertama, reformasi sistim kepartaian yang membebaskan siapapun bisa mendirikan partai politik dan berlakunya sistim multi partai. Kedua, reformasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Otonomi daerah.
Mungkin diluar dugaan banyak orang bahwa Romo Mangunwijaya ternyata memiliki perhatian yang sangat dalam terhadap bentuk negara Indonesia kedepan. Saya menduga, kedekatan, paling tidak dari sudut pemikiran dan gagasan antara dirinya dengan Sutan Syahrir dan Hatta; mendorongnya untuk mengusulkan bahwa bentuk yang tepat bagi negara kepulauan dan multi-etnik seperti Indonesia adalah federalisme, Republik Indonesia Serikat. Gagasan tentang federalisme ini memang sempat menjadi pembicaraan secara terbuka, meskipun kemudian padam. Pasca lengsernya Suharto, muncul gerakan dari berbagai daerah untuk merdeka dari Republik Indonesia. Kita tahu, provinsi Timor Timur, Aceh, Papua, juga Riau; saat itu muncul paling keras untuk merdeka. Periode 1999-2000 juga merupakan periode ketika konflik komunal pecah di berbagai tempat, yang terbesar di Sambas, Sampit, Poso dan Ambon. Dalam konflik komunal ini sentimen etnis dan keagamaan sering kental didalamnya, meskipun jika dianalisis faktor ekonomi dan politik barangkali yang paling kuat mendasarinya.

Foto buku Menuju Republik Indonesia Serikat (Sumber: Istimewa)
Dalam menyampaikan gagasan tentang perlunya Indonesia mulai memikirkan bentuk negara federal, Romo Mangun tidak tanggung-tanggung dalam mengekspresikannya. Selain dalam bentuk artikel-artikel pendeknya, Romo Mangun juga menerbitkan buku yang berjudul Menuju Republik Indonesia Serikat, dengan warna sampul depan merah menyala, dan diterbitkan oleh Penerbit Gramedia tahun 1998. Dalam kaitan ini, Romo Mangun tidak sendiri, intelektual seperti Daniel Dhakidae yang saat itu dekat dengan Penerbit Kompas-Gramedia saya kira adalah pemikir yang juga melihat bahwa federalisme adalah bentuk negara yang tepat bagi Indonesia. Selain buku Romo Mangun ini, sebuah buku lain juga diterbitkan oleh grup Kompas tahun 1999,berjudul Federalisme untuk Indonesia, penulisnya antara lain Adnan Buyung Nasution, sekapur sirih ditulis oleh Jacob Oetama, pendahuluan oleh Daniel Dhakidae; dan buku ini secara keseluruhan disunting oleh St. Sularto, T. Jakob Koekerits.
“An Indonesian Spring”, memang berlangsung dalam waktu yang pendek, gagasan tentang federalisme yang juga kemudian juga disuarakan oleh Amin Rais dan Faisal Basri yang baru saja membentuk PAN (Partai Amanat Nasional) segera mendapatkan reaksi keras, konon terutama dari pihak Angkatan Darat yang tetap menginginkan bentuk negara kesatuan. Harus secara jujur kita akui bahwa gagasan tentang federalisme, seperti pernah ditulis oleh Romo Mangun, tidak pernah secara serius didiskusikan dengan kepala dingin. Ide federalisme telah menjadi tabu politik yang tanpa tahu seperti apa sebetulnya substansi dan esensinya begitu saja kita tolak untuk menyentuhnya.
Proses penggodokan Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Ryaas Rasyid dengan Tim 7-nya pun harus mengakui kenyataan bahwa gagasan awal untuk memberikan otonomi daerah kepada pemerintahan tingkat provinsi-pun harus menghadap tantangan, konon juga dari pihak Angkatan Darat. Jadilah kemudian otonomi cukup diberikan kepada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten, sebuah keputusan yang kita tahu implikasinya belakangan, yaitu pemekaran jumlah kota dan kabupaten secara masif..
Romo Mangun ditakdirkan wafat sebelum melihat bagaimana reformasi politik kemudian berlangsung di negeri yang sangat dicintainya. Sebagai generasi yang masih harus meneruskan gagasan, pemikiran dan perenungannya; karya-karya arsitekturnya, kisah-kisah perjuangannya membela yang terpinggirkan, dan buku-bukunya; saya kira tetap menjadi inspirasi dan tauladan. Indonesia masa depan tidak mungkin hanya diserahkan pada para politisi maupun mereka yang merasa paling patriotik di negeri ini, dan Romo Mangun menjadi contoh yang sangat kuat; sebagai Romo, sebagai agamawan, kiprahnya menjangkau banyak bidang diluar jubah resminya, dan sampai akhir hayatnya beliau terbukti tidak pernah berhenti berjuang.
Jalan Tembok, Kampung Ambon, 30 Maret 2023.
*Riwanto Tirtosudarmo adalah peneliti.