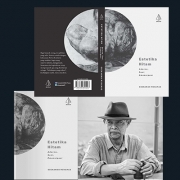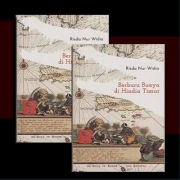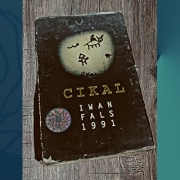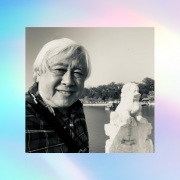Revolusi Linguistik Menjelang Kiamat Bahasa
Oleh Gus Nas Jogya*
Prolog
Dasein, Struktur, dan Angin Topan Digital
Dalam setiap tarikan napas peradaban, bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi; ia adalah keberadaan itu sendiri, Dasein (eksistensi) yang membentuk kesadaran dan realitas kolektif kita. Dari prasasti purba yang diukir di batu hingga aksara digital yang berkelebat di layar, bahasa adalah arsitektur yang menopang pemikiran, ingatan, dan identitas. Namun, kita kini berada di persimpangan jalan yang maha penting, sebuah era yang ditandai oleh disrupsi dan badai digital, di mana revolusi linguistik mengancam sebuah Kiamat Bahasa. Kiamat ini bukanlah akhir fisik di mana bahasa-bahasa akan punah, melainkan sebuah transformasi struktural yang fundamental, sebuah keruntuhan epistemologis yang mengubah esensi dan fungsi bahasa itu sendiri.
Esai ini berikhtiar untuk menganalisis fenomena ini dari dua pilar filosofis: eksistensialisme, untuk memahami makna dan keberadaan bahasa; dan strukturalisme, untuk mengurai sistem yang kini porak-poranda. Dengan berbekal Literasi Peradaban, kita mencoba membaca lanskap ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai sebuah tantangan radikal bagi kemanusiaan.
Eksistensi Bahasa di Era Pasca-Aksara
Filsafat eksistensial, dari Heidegger hingga Sartre, menempatkan bahasa sebagai pondasi di mana kesadaran dan dunia saling terhubung. Bagi Heidegger, bahasa adalah “rumah keberadaan” (Haus des Seins). Manusia adalah makhluk yang berbahasa, dan melalui bahasa, kita membentuk dunia kita, memberikan makna pada setiap entitas dan pengalaman. Namun, di era disrupsi digital, rumah ini kini dihadapkan pada badai. Penggunaan bahasa yang semakin terkompresi, visual, dan instan—dari emoji, GIF, hingga meme—menciptakan sebuah kondisi di mana makna diproduksi di luar ranah sintaksis yang mapan.
Ini adalah sebuah krisis eksistensial bagi bahasa. Makna tidak lagi terukir melalui narasi yang panjang dan rinci, tetapi dilontarkan dalam bentuk semiotika yang instan dan sering kali ambigu. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah bahasa masih menjadi “rumah keberadaan” jika ia tidak lagi mampu menampung kompleksitas pemikiran? Apakah kita, sebagai manusia yang berbahasa, masih eksis secara penuh ketika alat utama kita untuk berpikir mengalami fragmentasi? Kiamat Bahasa, dalam konteks ini, adalah hilangnya kedalaman eksistensial bahasa. Makna tidak lagi digali, melainkan dikonsumsi dan dibuang. Ini adalah sebuah kekosongan yang perlahan menggerogoti kemampuan kita untuk berpikir kritis, berempati, dan membangun argumen yang koheren.
Secara reflektif, krisis ini adalah sebuah ujian spiritual. Jika bahasa adalah “pakaian jiwa,” maka di era ini, jiwa kita berisiko telanjang, hanya mampu bergetar dalam resonansi dangkal. Kita telah melepaskan jubah narasi, alih-alih merajut makna yang rumit dan berlapis, kita memilih potongan-potongan tekstual yang mudah dipakai dan dibuang. Penggunaan emoji, misalnya, adalah sebuah manifestasi dari kemalasan eksistensial. Ia menawarkan shortcut emosional yang memuaskan secara instan, namun pada saat yang sama, ia mematikan otot-otot batin yang diperlukan untuk merasakan dan mengungkapkan nuansa-nuansa yang lebih halus dari penderitaan, sukacita, atau keraguan. Makna pun menjadi biner, antara ‘like’ dan ‘dislike’, ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’, meninggalkan ruang bagi ambivalensi dan kontemplasi. Ini adalah tragedi di mana kita kehilangan kemampuan untuk duduk bersama dalam keheningan yang penuh makna, karena keheningan kini dianggap sebagai ketiadaan pesan. Bahasa menjadi sebuah komoditas, dan seperti semua komoditas, ia diukur berdasarkan kecepatan dan efisiensi, bukan pada kedalaman dan kebenaran. Kita tidak lagi menulis untuk mengabadikan, melainkan untuk disajikan di beranda.
Struktur yang Terdisrupsi: Dari Sintaksis ke Semiotika Genggam
Di sisi lain, strukturalisme, sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, memandang bahasa sebagai sebuah sistem tanda yang terdiri dari signifier (penanda, bentuk) dan signified (petanda, makna). Sistem ini beroperasi melalui hubungan diferensial antara elemen-elemennya. Grammar, atau sintaksis, adalah arsitektur yang mengikat sistem ini menjadi satu kesatuan yang koheren. Namun, revolusi linguistik digital telah mendisrupsi struktur ini secara radikal.
Alih-alih linear dan kausal, komunikasi digital menjadi multi-modal dan terputus-putus. Penggunaan singkatan (brb, lol), ketiadaan tanda baca yang benar, dan penciptaan neologisme yang viral, semuanya mengikis aturan-aturan sintaksis. Penggantian kata-kata dengan emoji atau stiker adalah manifestasi paling jelas dari pergeseran ini. Studi komparatif terhadap manuskrip Abad Pertengahan yang berfokus pada transisi dari tradisi lisan ke tulisan—misalnya, 1 —menunjukkan bahwa setiap perubahan media komunikasi akan memengaruhi struktur bahasa. Namun, laju perubahan saat ini jauh lebih cepat. Kiamat bahasa, dari perspektif struktural, adalah keruntuhan sistem. Ia adalah saat di mana signifier dan signified menjadi cair dan tidak terikat, di mana konteks yang sama menghasilkan tafsiran yang berbeda. Hilangnya struktur ini menyebabkan ambiguitas yang tak terkendali, yang pada gilirannya memicu polarisasi dan kesalahpahaman. Bahasa tidak lagi berfungsi sebagai jembatan yang kokoh, melainkan sebagai jaring yang penuh lubang.
Secara struktural, kita sedang menyaksikan pembangunan kembali Menara Babel. Dahulu, bahasa yang berbeda memisahkan suku-suku. Kini, bahasa yang sama—misalnya, Bahasa Inggris, atau bahkan Bahasa Indonesia—dipecah-pecah menjadi dialek digital yang hanya dapat dipahami oleh subkultur tertentu. Neologisme internet yang tak terhitung jumlahnya, penggunaan akronim yang membingungkan, dan meme yang hanya memiliki makna di dalam konteks kelompok, semuanya menciptakan kantung-kantung linguistik yang terisolasi. Bahasa, yang seharusnya menjadi alat untuk menemukan kesamaan, kini menjadi alat untuk menegaskan perbedaan dan memblokir akses.2 Struktur naratif yang terfragmentasi—melalui cuitan singkat, cerita kilat, dan klip video pendek—menciptakan generasi yang tidak mampu lagi mengikuti alur argumen yang kompleks. Kita telah beralih dari narasi epik yang berkelanjutan, seperti yang ditemukan dalam manuskrip-manuskrip kuno, ke serangkaian narasi mikro yang saling terputus. Ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara kita berpikir. Pikiran kita menjadi terpotong-potong, kurang mampu membangun hubungan kausal yang logis, dan lebih rentan terhadap informasi yang menyederhanakan realitas. Ini adalah kiamat bagi struktur rasionalitas.
Literasi Peradaban sebagai Mercusuar
Menghadapi badai ini, kita membutuhkan sebuah kompas baru: Literasi Peradaban. Ini bukanlah sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan sebuah pemahaman holistik akan peran bahasa dalam membentuk sejarah dan identitas manusia. Literasi ini menuntut kita untuk:
1. Memahami Sejarah Bahasa: Menyadari bahwa bahasa yang kita gunakan sekarang adalah hasil dari ribuan tahun evolusi, sebuah warisan yang kaya akan makna dan konteks. Manuskrip kuno, seperti Kitab Jataka atau kronik-kronik Nusantara, adalah bukti dari kedalaman ini. Mereka menunjukkan bagaimana narasi dan pemikiran yang kompleks hanya bisa diungkapkan melalui struktur bahasa yang cermat. Secara spiritual, ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi arkeolog jiwa, menggali lapisan-lapisan bahasa untuk menemukan kebenaran yang tertimbun. Ini bukan sekadar studi akademis, melainkan sebuah praktik perenungan, sebuah ziarah kembali ke akar-akar eksistensi kita. Dengan membaca manuskrip kuno, kita tidak hanya membaca kata-kata, kita membaca pikiran para pendahulu kita, merasakan ritme waktu yang berbeda, dan membangun kembali jembatan yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan yang nyaris terlupakan.3
2. Mengkritik Media: Memiliki kesadaran kritis terhadap bagaimana media digital mengubah cara kita berkomunikasi dan berpikir. Literasi Peradaban mengajarkan kita untuk bertanya: apa yang hilang ketika kita mengganti kata dengan gambar? Apa konsekuensi dari komunikasi yang hanya membutuhkan perhatian singkat? Secara reflektif, ini adalah bentuk asketisme modern. Kita harus melatih diri untuk menahan godaan instan, untuk menolak logika algoritma yang mendorong kita untuk mengonsumsi informasi tanpa merenungkannya. Ini adalah sebuah meditasi terhadap ruang gema digital, sebuah upaya untuk melihat melampaui pantulan diri kita sendiri dan mendengarkan suara yang berbeda. Ini adalah latihan spiritual untuk menaklukkan ego digital kita, yang terus-menerus menuntut validasi dan afirmasi.4
3. Mempertahankan Nilai-nilai Humanis: Menyadari bahwa tujuan akhir dari bahasa adalah untuk membangun jembatan antar manusia, bukan untuk membangun tembok. Ini adalah tentang menggunakan bahasa untuk menumbuhkan empati, mendiskusikan perbedaan, dan mencari kebenaran, bukan hanya untuk menyebarkan informasi atau menyuarakan identitas kelompok. Ini adalah inti dari panggilan spiritual. Bahasa adalah anugerah ilahi yang memungkinkan kita untuk terhubung, untuk berbagi penderitaan, dan untuk menemukan makna bersama. Kiamat Bahasa adalah saat kita melupakan anugerah ini dan menggunakannya sebagai senjata. Literasi Peradaban adalah pengingat bahwa bahasa, pada intinya, adalah tentang cinta dan pemahaman. Ia adalah sebuah ajakan untuk kembali pada percakapan yang tulus, pada dialog yang jujur, dan pada pengakuan bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Tanpa literasi ini, kita berisiko menjadi generasi yang berbicara banyak namun tidak mengatakan apa-apa.5
Penutup:
Mengikat Kembali Makna
Revolusi linguistik yang kita saksikan saat ini bukanlah fenomena yang terlepas dari sejarah. Ia adalah babak baru dalam evolusi bahasa, sama pentingnya dengan penemuan tulisan atau mesin cetak. Namun, bahaya Kiamat Bahasa yang mengintai—baik dalam dimensi eksistensial maupun struktural—adalah tantangan terbesar yang pernah dihadapi manusia sebagai makhluk yang berbahasa. Jika kita gagal memegang kendali atas revolusi ini, kita akan kehilangan lebih dari sekadar aturan tata bahasa; kita akan kehilangan kemampuan untuk berbagi makna yang kompleks, membangun komunitas yang utuh, dan memahami diri kita sendiri.
Literasi Peradaban adalah satu-satunya jalan keluar. Ia adalah sebuah ajakan untuk kembali pada makna yang mendalam, pada kebijaksanaan yang terukir dalam manuskrip-manuskrip kuno, dan pada pengakuan bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki beban sejarah dan konsekuensi moral. Kiamat Bahasa dapat kita hindari, bukan dengan menolak teknologi, melainkan dengan mengintegrasikan kebijaksanaan masa lalu ke dalam praksis masa kini. Pada akhirnya, nasib bahasa berada di tangan kita—apakah kita akan membiarkannya terkikis oleh badai digital, atau akankah kita menggunakannya sebagai jangkar untuk mengikat kembali makna dalam dunia yang kian tercerai berai.
—–
Catatan Kaki
1 R.M. Driyarkara, “Transformasi Aksara: Dari Prasasti hingga Mesin Ketik,” Jurnal Linguistik Sejarah, vol. 18, no. 2, pp. 45-62, 2012.
2 N. Soemanto, Ketika Teks Menjadi Gema: Studi Etnografi Komunikasi Lisan, Jakarta: Pustaka Manggala, 2018.
3 K.J. Purbaya, Menjelajah Manuskrip dan Kosmologi Jawa, Yogyakarta: Sansekerta Press, 2020.
4 D. R. Wijaya, Filsafat Komunikasi Digital, Surabaya: Pustaka Metafora, 2021.
5 A. Budiarto, “Arkeologi Aksara Digital: Studi Kasus Emotikon dan Pola Komunikasi Gen-Z,” Linguistics Review, vol. 45, no. 1, pp. 78-90, 2022.
Rujukan Ilmiah
Budiarto, A. (2022). Arkeologi Aksara Digital: Studi Kasus Emotikon dan Pola Komunikasi Gen-Z. Linguistics Review, 45(1), 78-90.
De Saussure, F. (1916). Course in General Linguistics. Edisi Inggris, 1959.
Driyarkara, R.M. (2012). Transformasi Aksara: Dari Prasasti hingga Mesin Ketik. Jurnal Linguistik Sejarah, 18(2), 45-62.
Heidegger, M. (1947). Letter on Humanism. Edisi Jerman, 1947.
Purbaya, K.J. (2020). Menjelajah Manuskrip dan Kosmologi Jawa. Yogyakarta: Sansekerta Press.
Soemanto, N. (2018). Ketika Teks Menjadi Gema: Studi Etnografi Komunikasi Lisan. Jakarta: Pustaka Manggala.
Wijaya, D.R. (2021). Filsafat Komunikasi Digital. Surabaya: Pustaka Metafora.
———-
*Gus Nas Jogya, Budayawan.