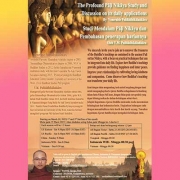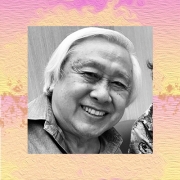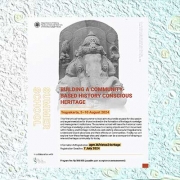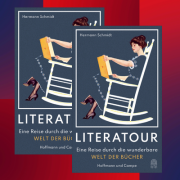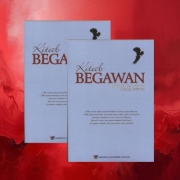Panggung Drama Sosial Politik Indonesia
Oleh Purnawan Andra*
Belakangan ini, kita menyaksikan dinamika sosial-politik Indonesia yang penuh gejolak. Mulai dari demo buruh, protes mahasiswa, maraknya aksi solidaritas setelah kematian seorang pengemudi ojek online, hingga perdebatan di ruang digital yang tak pernah berhenti.
Peristiwa-peristiwa ini sering kita tanggapi dengan cara sederhana, seperti tentang siapa salah, siapa benar, siapa yang patut disalahkan, dan siapa yang mesti dipuji. Tetapi jika kita tarik sedikit jarak, kita bisa membacanya dengan perspektif lain, dengan melihat seluruh rangkaian dinamika itu sebagai sebuah drama sosial.
Mengapa drama? Karena politik di Indonesia, seperti juga di banyak negara lain, sering tampil tidak hanya sebagai soal kebijakan dan hukum, tetapi sebagai sebuah pergelaran. Ada panggung, ada naskah, ada aktor, ada penonton, bahkan ada sutradara yang berusaha mengatur alur cerita.
Clifford Geertz (2017), antropolog yang meneliti Bali, pernah menyebut konsep negara teater yang menyebut kekuasaan tidak hanya dijalankan lewat administrasi, tapi juga lewat pertunjukan simbolik, seperti upacara, ritual, parade, atau pidato yang sarat dramatisasi. Jika kita gunakan kacamata itu untuk membaca politik Indonesia kini, kita bisa melihat betapa banyak peristiwa sosial tak ubahnya pertunjukan yang dimainkan di depan publik.
Drama Sosial
Antropolog Victor Turner dalam bukunya From Ritual to Theatre (1982) menawarkan kerangka tentang drama sosial yang terdiri dari empat tahap: breach (pelanggaran), crisis (krisis terbuka), redressive action (tindakan pemulihan), dan reintegration atau schism (kembali normal atau pecah permanen). Mari kita coba lihat peristiwa kematian seorang ojol yang memicu gelombang demo lebih lanjut.
Pelanggaran (breach) terjadi saat ada ketidakadilan yang dirasakan publik, ketika seorang warga kecil meninggal dalam situasi yang dianggap tidak wajar, bahkan menyinggung rasa keadilan sosial. Hal itu memuncak menjadi crisis ketika ribuan ojol turun ke jalan, publik ramai di media sosial, dan suasana politik memanas.
Negara lalu melakukan redressive action, dengan polisi memberi keterangan pers, pejabat membuat janji penyelidikan, lalu ada kompensasi yang diberikan. Lalu apa akhirnya? Apakah masyarakat merasa puas dan kembali normal (reintegration), atau justru retakan semakin lebar (schism) karena dianggap hanya janji kosong? Kerangka pemikiran ini membantu kita membaca konflik bukan sekadar sebagai insiden, melainkan sebagai drama yang berulang, dengan pola tertentu.
Politik Sebagai Pertunjukan
Dalam setiap drama, ada panggung yang dirancang. Erving Goffman, sosiolog Kanada yang menulis tentang kehidupan sehari-hari sebagai pertunjukan, menyebut adanya frontstage dan backstage. Dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1958), ia menjelaskan frontstage adalah bagian yang ditampilkan untuk publik: konferensi pers dengan latar belakang rapi, pejabat dengan bahasa formal, aparat berbaris dengan seragam lengkap. Sementara backstage adalah bagian yang tersembunyi, seperti negosiasi, kompromi, atau bahkan kesalahan yang berusaha ditutupi.
Politik Indonesia penuh dengan frontstage ini. Pidato kenegaraan, sidang yang disiarkan televisi, bahkan jumpa pers pasca-tragedi, semua adalah bagian dari pertunjukan yang dirancang untuk mengatur kesan publik.
Namun dalam era digital, backstage sering bocor. Warga merekam video amatir, meme beredar tanpa kendali, dan komentar netizen muncul seketika. Retakan kecil ini justru sering lebih dipercaya publik ketimbang deklarasi resmi, karena terasa lebih otentik. Inilah yang membuat politik sebagai pertunjukan selalu rapuh karena ada celah di mana naskah bisa diinterupsi oleh improvisasi tak terduga.
Pergelaran politik hari ini mempertemukan dua drama besar. Pertama, drama negara seperti upacara resmi, sidang parlemen, pernyataan aparat, dan semua yang dirancang dengan tata cahaya “resmi”. Kedua, drama rakyat berupa demo di jalan, mural di tembok kota, musik protes, hingga meme politik yang viral.
Kedua drama ini sering saling bertabrakan di ruang yang sama. Negara berusaha mempertahankan naskah dan panggungnya, sementara rakyat mencoba membuat panggung tandingan. Dalam perspektif cultural studies kedua drama ini menjadi teks budaya, yang bukan hanya peristiwa, tapi representasi yang sarat makna.
Stuart Hall dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997) mengatakan “Representation is the production of meaning through language”. Bahwa cara peristiwa dikisahkan menentukan makna yang lahir. Negara mungkin menyebut tragedi ojol sebagai kasus biasa, tapi rakyat menafsirnya sebagai simbol ketidakadilan struktural. Perbedaan representasi ini yang membuat konflik terus hidup.
Terlebih filsuf Prancis Jacques Rancière, dalam The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible (2004) memberi kita bahasa yang tajam dengan menyebut bahwa politik adalah soal “distribution of the sensible”, atau pembagian tentang siapa yang boleh tampak, siapa yang didengar, dan apa yang dianggap penting. Demo, mural, atau meme yang viral adalah cara rakyat membelah batas distribusi itu. Dengan cara itu, mereka memaksa negara mengakui pengalaman yang selama ini tak dianggap penting.
Kekuasaan atas Hidup dan Mati
Bahkan, berkaca pada dinamika sosial politik yang terjadi hingga kini, ada dimensi lain yang lebih gelap, yaitu tentang siapa yang berhak hidup dan siapa yang dibiarkan mati. Salah satu tokoh penting kajian poskolonial dan teori politik kontemporer Kamerun, Achille Mbembe menyebut ini sebagai necropolitik (2019). Ia menulis bahwa bentuk tertinggi kedaulatan adalah kekuasaan untuk memutuskan siapa boleh hidup dan siapa harus mati.
Dalam konteks pekerja seperti ojol, kita memang tidak melihat negara secara langsung “membunuh”, tetapi absennya perlindungan, lemahnya jaminan, dan kondisi sosial politik yang rawan adalah bentuk lain dari politik yang membiarkan kerentanan. Kematian seorang ojol lalu menjadi simbol betapa murahnya nyawa rakyat kecil di hadapan sistem yang tidak berpihak.
Dengannya, membaca dinamika sosial-politik Indonesia sebagai drama sosial dan negara teater membantu kita melihat lapisan-lapisan yang sering tersembunyi. Politik bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal panggung, naskah, dan representasi. Negara menampilkan pertunjukan kekuasaan, rakyat menampilkan pertunjukan tandingan. Dan media massa dan media sosial menjadi ruang perebutan makna.
Pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi sekadar “siapa salah, siapa benar,” melainkan: siapa yang menulis naskah? siapa yang mengatur tata cahaya? siapa yang dipaksa menjadi penonton, dan siapa yang berhak bersuara?
Jika politik adalah pergelaran, maka kualitas demokrasi ditentukan bukan oleh megahnya panggung penguasa, melainkan oleh kemampuan kita bersama untuk mengubah ruang tontonan menjadi ruang partisipasi. Kita perlu kunci, yang mengingatkan bahwa rakyat tidak ditakdirkan sebagai penonton pasif, melainkan bisa naik ke panggung, menulis naskah sendiri, dan menuntut akhir cerita yang lebih adil.
——
* Purnawan Andra, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.