Nagasasra Sabukinten: Membaca Romantisme Silat Jawa

Oleh Ika Anggraeni
Saya adalah seorang penikmat buku. Dari masa kanak hingga sekarang, membaca berbagai cerita dalam lembaran-lembaran kertas, sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri. Adakalanya bahkan ada beberapa buku yang mengandung untaian kisah yang sungguh-sungguh berkesan di hati. Salah satunya adalah buku yang berjudul Nagasasra dan Sabukinten.
Saya pertama kali membaca buku tersebut semasa masih duduk di bangku SMP, sekitar pertengahan tahun 90an. Saya menemukannya di tempat persewaan buku di kota Semarang, saat menghabiskan liburan kenaikan kelas. Kalau dari hasil “googling” toko-toko online yang menjual buku bekas dan membandingkan sampul mukanya dengan ingatan samar saya, maka sepertinya versi buku Nagasasra yang dulu saya baca adalah cetakan ke -2 (1982), yang terdiri dari 16 jilid buku.
Tahun berganti, belakangan saya baru mengetahui bahwa cerita tersebut aslinya adalah cerita bersambung yang dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, di tahun 1964. Lalu diterbitkan pertama kali oleh surat kabar yang sama di tahun 1966. Penulisnya adalah Singgih Hadi Mintardja atau yang lebih dikenal dengan sebutan SH Mintardja (1933-1999). Beliau ternyata juga menulis banyak buku bertema serupa dengan Nagasasra, yakni tema fiksi historis berbalut dunia persilatan di tanah Jawa. Beberapa karyanya antara lain: Bunga di Batu Karang, Suramnya Bayang-Bayang, Sayap-Sayap Terkembang, Istana yang Suram, Pelangi di Langit Singasari dan yang juga saya sempat baca: Api di Bukit Menoreh.

Foto SH Mintardja atau Singgih Hadi Mintardja (1933-1999)
Tertarik untuk membaca ulang, saya mencoba untuk melacak tempat persewaan buku tempat dulu saya meminjam Nagasasra. Sayangnya, tempat itu sudah raib. Sempat mencoba menghubungi penerbit Kedaulalatan Rakyat, untuk mendapatkan eksemplar dari cetakan terakhir mereka (cetakan tahun 2005), tapi ternyata kehabisan juga. Akhirnya saya berhasil mendapatkannya dari sebuah toko buku online di daerah Malang, dalam bentuk 2 jilid tebal. Terdiri dari total 1773 halaman, yang sayangnya tanpa ilustrasi sedikitpun di dalamnya. Berbeda dengan cetakan lebih awal, yang di tiap beberapa halaman dihiasi 1 halaman ilustrasi.
Tetapi, cerita Nagasasra dan Sabukitnten ternyata masih memiliki daya pikat yang sama seperti saat lebih dari 20 tahun yang lalu saya membacanya.
Benang merah cerita ini adalah kisah Mahesa Jenar, yang dikenal juga dengan nama Rangga Tohjaya, seorang perwira kesultanan Demak yang mengembara mencari sepasang keris pusaka yang hilang, Kyai Nagasasra dan Sabukinten.
Mengambil setting waktu pada saat periode pemerintahan Sultan Trenggana di kesultanan Demak, SH Mintardja memadupadankan cerita dengan tokoh-tokoh sejarah beserta mitos-mitos yang melingkupinya. Sebagai contoh, Mahesa Jenar diceritakan adalah murid dari perguruan Pengging yang bersumber dari Ki Ageng Pengging Sepuh. Disebut juga walau sekilas mengenai Syekh Siti Jenar. Di ujung cerita, juga sempat muncul sekejap sosok Arya Penangsang. Bahkan, Mas Karebet, yang kerap disebut Jaka Tingkir, juga menjadi salah satu karakter penting di cerita ini.
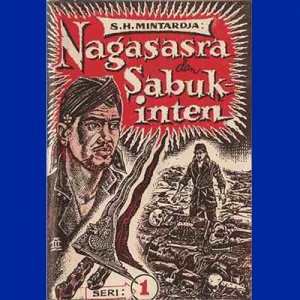
Buku Nagasasra dan Sabukinten karya S.H. Mintardja
Adapun daerah-daerah yang menjadi latar tempat berlangsungnya kisah ini juga tidak luput menjadi perhatian. Bagi yang sering bepergian di daerah-daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, tentu sangat bisa memvisualisasikannya. Misalkan daerah perdikan Banyu Biru, yang merupakan lokasi utama cerita, dikisahkan tidak jauh dari Rawa Pening. Lalu daerah asal masing-masing tokoh juga menarik, baik tokoh baik maupun jahat. Di antaranya Lawa Ijo dari Alas Mentaok, Sima Rodra dari Gunung Tidar, Sepasang Uling dari Rawa Pening, Bugel Kaliki dari Gunung Cerme, Jaka Soka dari Nusakambangan, Ki Ageng Pandan Alas dari Gunung Kidul, dan Titis Anganten dari Banyuwangi.
Alur cerita pun sederhana, tapi tidak pernah membosankan. Satu kisah bertaut dengan kisah selanjutnya dengan mulus, tanpa bertele-tele. Ada bumbu romansa percintaan, drama kisah kasih konflik hubungan keluarga. Ada juga warna senda gurau. Ada pula nuansa kengerian dan kelicikan. Semua pada porsi yang sesuai, tanpa berlebihan. Semua dibingkai dengan nuansa sepak terjang dunia persilatan Jawa.
Kemudian, berbicara tentang penokohan. Semua karakter dalam cerita ini sungguh kuat. Hampir semua tokoh mempunyai ciri khas. Baik itu watak, ciri ‘berkelahi’ (gaya persilatannya), gaya bicara, sampai ciri fisiknya. SH Mintardja bisa dikatakan sangat deskriptif dalam menuliskannya.
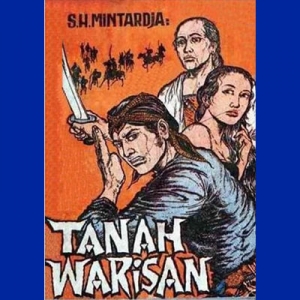
Buku Tanah Warisan karya SH Mintardja
Mulai dari sang tokoh utama, Mahesa Jenar, yang identik dengan ikat kepala wulung, baju dari kain lurik warna gadung melati dan setangkai kembang disisipkan di salah satu telinganya. Dan tentunya Sasrabirawa sebagai ilmu andalannya. Lalu sang murid sekaligus pewaris tanah Banyu Biru, Arya Salaka, dengan usia mudanya, watak yang masih mudah menggelegak. Kemudian ada Rara Wilis, sang kekasih Mahesa Jenar, sekaligus murid Ki Ageng Pandan Alas, yang mahir memainkan ilmu pedang khas perguruannya. Ki Ageng Pandan Alas sendiri selalu menandai kedatangannya di tengah lawannya dengan mendendangkan tembang Dhandanggula. Ada pula tokoh bernama Pasingsingan, yang selain identik dengan jubah panjang dan topeng buruk rupa, juga dengan ajian dahsyat, Gelap Ngampar. Aji ini dikisahkan bisa merontokkan rongga dada dengan suara tawa. Ada pula gadis kecil, Endang Widuri, yang fasih memainkan kalung rantai berpangkal cakra. Lalu, Jaka Tingkir dengan aji Lembu Sekilan dan Rog Rog Asem-nya. Dan, masih banyak yang lainnya.
Maka, tidak heran jika membaca kisah Nagasasra dan Sabuk Inten ini, sungguh merupakan pengalaman mengasyikkan. Ramuan antara ketegangan perang tanding, sejarah tanah Mataram, hiruk pikuk hubungan saudara perguruan maupun kandung, dan lokasi dengan beraneka ragam bentang alam, sungguh sangat menyihir.
Dan, setelah sampai di penghujung cerita, terasalah jika watak sepasang keris yang diperebutkan itu ditemui pada keluhuran budi tokoh-tokoh di kisah ini. Pada semangat perjuangan tanpa pamrih Mahesa Jenar, Arya Salaka, Rara Wilis, Kebo Kanigara, Gajah Sora, dan lain-lainnya.

Buku Api di Bukit Menoreh karya SH Mintardja
Mengutip gambaran sepasang keris tersebut di sampul belakang salah satu edisi cetak buku ini :
“Kyai Nagasasra mempunyai watak disuyudi oleh kawula, dicintai dan disegani oleh rakyat. Dengan demikian ia akan memiliki segala unsur sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat yang demikian memang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin. Pancaran dari cinta kasih Tuhan, peri kemanusiaan, memberi perlindungan kepada orang yang kehujanan dan kepanasan, memberi makanan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi tuntunan bagi yang kehilangan jalan.
Kyai Sabuk Inten memberi watak seperti lautan. Luas tanpa tepi. Menampung segala arus sungai dari manapun datangnya. Mampu menerima banjir yang bagaimanapun besarnya namun gelombangnya dapat menunjukan kedahsyatan dan kesediaan bergerak dan bahkan selalu bergerak. Watak yang demikianlah yang memungkinkan seseorang dapat menemukan yang belum pernah diketemukan. Dan karenanyalah kesejahteraan rakyat dapat dijamin. Kesejahteraan lahir dan batin.”
*Penulis adalah penikmat buku dan pecinta seni tradisi.













