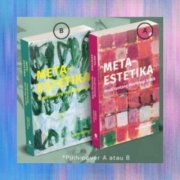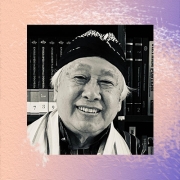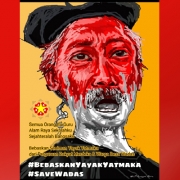Minta Maaf: Esensi Kultural, Formulasi Retoris dan Problem Sosio-Komunal Bangsa
Oleh Purnawan Andra
Dalam budaya Indonesia, terutama pada saat Lebaran, minta maaf merupakan ritual yang sarat makna. Tidak hanya bermakna religi dan berfungsi sebagai bentuk perbaikan hubungan interpersonal, tapi juga sebagai cermin nilai-nilai kebersamaan, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap norma sosial.
Secara antropologis, minta maaf pada saat Lebaran merupakan ritual sosial yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat Indonesia. Lebaran, yang identik dengan silaturahmi dan perbaikan hubungan, menjadi momen di mana masyarakat secara ritual menghapuskan kesalahan, memadamkan dendam serta memperbarui ikatan sosial. Praktik minta maaf di hari-hari Lebaran tidak hanya melibatkan individu yang berkumpul dalam lingkaran keluarga, melainkan juga mencerminkan mekanisme sosial yang berfungsi sebagai perekat komunitas.
Dalam kerangka antropologi simbolik, minta maaf dinilai sebagai tindakan yang memaknai kembalinya keadaan ‘bersih’, menyembuhkan luka-luka emosional, dan memperkuat kohesi sosial. Tindakan ini mengungkapkan bahwa nilai kesucian dan pemurnian telah menjadi bagian integral dari budaya perayaan, di mana proses ritual memperbaiki hubungan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari pembentukan identitas kolektif.
Lebih dari sekadar ritual sosial, esensi minta maaf juga memiliki dimensi filsafat yang mendalam. Dalam cerita sufi, dikisahkan orang yang memberi lebih mulia daripada meminta. Namun ada permintaan yang mulia, yaitu permintaan maaf. Meminta maaf menjadi sebuah kesadaran, keyakinan, kognisi, persepsi, dan perasaan (sedih, cinta, harapan, kecewa, resah dan gelisah) sebagai ungkapan kejiwaan yang jadi stimulan dari dalam kalbu atas realitas. Esensi permintaan maaf adalah pengakuan keikhlasan, kejujuran dan kerelaan seseorang atas sebuah fakta yang tidak pas dan tidak sepantasnya kepada orang lain.
Dalam tradisi filsafat, minta maaf sering dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap kesalahan dan sebagai langkah awal menuju perbaikan eksistensial. Filsuf eksistensialis menyatakan bahwa pengakuan atas ketidaklengkapan diri merupakan langkah penting untuk mencapai keotentikan. Dengan mengakui kesalahan, individu membuka ruang bagi transformasi batin yang tidak hanya membebaskan dari beban dosa, tetapi juga memungkinkan munculnya potensi pembaruan.
Modal Budaya bagi Tatanan Sosial
Dalam konteks budaya Nusantara, minta maaf telah menjadi bagian dari tata krama yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, kesalahan tidak hanya dihadapi secara personal tetapi juga dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap tatanan sosial dan alam roh. Ritual pengampunan, seperti dalam upacara adat, seringkali melibatkan simbol-simbol kesucian dan penebusan, yang menandai pemulihan harmoni antara individu dan komunitas. Nilai gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan sikap rendah hati merupakan inti dari praktik minta maaf yang telah mengakar dalam budaya lokal.
Dalam konteks ini, minta maaf berfungsi sebagai pengakuan atas keterbatasan manusia dan sebagai panggilan untuk berbenah, sehingga hubungan antarmanusia dapat berjalan dengan integritas dan kejujuran. Lebih jauh, tindakan minta maaf dapat dilihat sebagai upaya membangun kepercayaan baru—suatu proses yang mengandung kedalaman eksistensial, di mana proses pemulihan hubungan menyangkut dimensi etika dan moral yang mendasar.
Maka, minta maaf diartikan sebagai bentuk pemulihan tatanan sosial dan sebagai modal budaya untuk mempertahankan hubungan harmonis dalam konteks kekeluargaan dan komunitas. Praktik ini tidak hanya mengandung nilai moral, melainkan juga merupakan strategi adaptif yang memungkinkan masyarakat mengatasi konflik dan perpecahan dengan cara yang lembut namun tegas.
Namun, dalam konteks kehidupan kebudayaan kontemporer, esensi minta maaf mengalami pergeseran makna yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial-politik. Pertanyaan muncul ketika kita menengok kondisi saat ini: apakah minta maaf harus diadopsi oleh institusi publik—termasuk pemerintah—sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan kebijakan yang terjadi?
Mulai dari polemik kebijakan yang terkesan lebih berdasar trial and error atau “cek ombak” seperti kenaikan tarif PPN 12 persen, eceran elpiji dan RUU TNI; makin banyaknya kasus korupsi terungkap; efisiensi multi-program hingga yang mendasar, masalah komunikasi publik pemerintah, mulai dari para wakil rakyat, pembantu Presiden hingga pemimpin tertingginya sendiri. Semua itu menjadikan kondisi masyarakat terombang-ambing dalam ketidakpastian.
Presiden Joko Widodo pernah meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia pada Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, Jumat (16/8/2024). Sebelumnya Jokowi juga menyampaikan permintaan maaf pada acara Zikir Kebangsaan di Istana Merdeka, 1 Agustus 2024. Ia menyebut, sebagai manusia biasa masih banyak kekurangannya dalam memimpin Indonesia sehingga tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak.
Namun, permintaan maaf Jokowi pada praktiknya jauh dari kebutuhan publik, bahasanya retoris tidak berefek pada konteks hukum dan kebijakan serta kehadirannya dalam konteks acara kenegaraan (baca: birokratis) menghadirkan (meminjam logika Gramsci) kuasa tafsir yang terselubung didalam sebuah mekanisme sosial untuk mereproduksi kekuasaan. Dengannya, kekuasaan cenderung melakukan hegemoni makna terhadap kenyataan sosial.
Goenawan Mohamad (2016) menambahkan dengan mengutip Derrida yang menyebut bila maaf diberlakukan sebagai proyek politik, ketika maaf disertai syarat, memaafkan secara bersyarat jadi menghadirkan sebuah hierarki. Yang memberi maaf dan menetapkan syarat meletakkan diri di atas pihak yang diberi syarat dan akan diberi maaf. Maaf bahkan bisa dibatalkan jika syarat tak dipenuhi. Dengannya, faktor kekuasaan jadi menonjol. Menurut Marx, “Negara” hanya merupakan alat kekuasaan kelas tertentu di ruang dan waktu tertentu.
Sepertinya di Indonesia meminta maaf tidak ditempatkan sebagai implikasi kegagalan pelayanan, tapi mempunyai bobot yang lebih besar pada kalkulasi politik. Pertimbangan harga diri dan kuatnya politik transaksional lebih kerap jadi faktor utama untuk tidak meminta maaf. Seakan-akan minta maaf membuat wibawa penguasa melemah.
Padahal permintaan maaf Presiden atau pemimpin bisa berorientasi edukatif-persuasif dan reflektif karena jangkauan (emosional)nya menyangkut waktu lalu dan kini (masa pemerintahannya) dan nanti (pemerintah selanjutnya). Dengannya, pemerintah lalu segera menyelesaikan segala permasalahan yang bisa membuat harapan rakyat kembali tumbuh. Seperti menstabilkan kondisi sosial ekonomi, mensinergikan dinamika politik, hingga meningkatkan kualitas hukum yang menurun drastis.
Kesadaran Kritis
Ketika masyarakat dihadapkan pada krisis kepercayaan, konflik identitas, dan ketidakpastian ekonomi, sikap minta maaf menawarkan jalan untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak antara penguasa dan rakyat. Namun, pendekatan ini harus ditempuh dengan kesadaran kritis bahwa minta maaf bukanlah sekadar formalitas retoris atau langkah simbolis yang kosong makna, melainkan harus menyertai komitmen nyata terhadap perbaikan dan keadilan.
Dalam tradisi kritis, sikap minta maaf yang autentik adalah upaya untuk mengakui kesalahan, mengungkapkan empati, serta membuka ruang bagi dialog yang jujur tanpa terjebak dalam logika pembenaran kekuasaan. Dalam hal ini, minta maaf berpotensi menjadi alat pembongkaran struktur kekuasaan yang represif, asalkan disertai dengan transformasi kebijakan dan reformasi struktural yang menegakkan nilai keadilan sosial.
Dengannya, seturut Gramsci, praktik simbolik citra, bahasa dan juga wacana permintaan maaf tersebut tidak menjadi hegemoni makna (dan pengingkaran) terhadap fakta sosial. Pandangan, sikap dan pikiran yang narsis, egois, mau menang sendiri dan anti sosial seperti itu harus dihindari. Karena, seturut Hannah Arendt, maaf seperti hukuman. Ia dimaksudkan untuk mengakhiri sebuah kejahatan. Maaf adalah bagian dari proses hidup bersama.
Dalam tataran intelektual, kita dipanggil untuk memaknai minta maaf tidak hanya sebagai ritual domestik, melainkan sebagai strategi untuk mengembalikan kepercayaan dan membangun kembali hubungan sosial yang telah terkoyak. Esensi ini menantang paradigma norma kekuasaan yang selama ini menolak untuk mengakui kesalahan dan berupaya membungkam aspirasi rakyat.
Sebuah sikap minta maaf yang autentik dapat menyulut semangat perbaikan kolektif, memvalidasi penderitaan rakyat, dan merumuskan jalan menuju transformasi sosial. Dengannya, minta maaf tidak lagi menjadi alat konformitas semata, melainkan sebagai dasar untuk memperjuangkan perubahan yang berkeadilan.
Karena yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah permintaan maaf pemimpin yang mengubah realitas politik, hukum, dan sosial ekonomi, dalam wujud regulasi dan kebijakan nyata mengedepankan kepentingan bersama/masyarakat.
Jangan sampai justru rakyat yang kecewa dan merasa ditipu selama ini mendahului meminta maaf dengan mengatakan “maaf, Anda tak bisa dipercaya lagi” atau bahkan berkata “tiada maaf bagimu!”
—
*Purnawan Andra, bekerja di Direktorat Bina SDM, Lembaga & Pranata Kebudayaan, Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan & Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan.