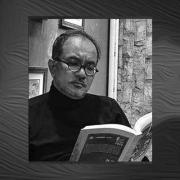Kota dan Budaya: Ruang Publik, Titik Temunya?
Oleh: Mudji Sutrisno SJ*
1. Pendahuluan
Ketika sebuah lapangan alun-alun kota Surakarta yang berdampingan bahkan menjadi perluasan tata kerajaan berperan sebagai tempat masyarakat bertemu bersama dan kadang protes halus dengan menjemur diri (pépé) dihadapan raja, di sana penghayatan ruang bersama dilaksanakan dalam makna budaya atau kultural.
Penghayatan itu bermakna budaya karena maksud temu di ruang bersama merupakan ungkapan saling bertemu dengan artian nilai agar harmoni hidup bersama bisa dilangsungkan terus dalam perayaan-perayaan kerakyatan sekatenan, perayaan pasar malam, lebaran, acara seni panggung bahkan menjelang peralihan abad ekonomis (dengan dikenalnya uang sebagai nilai tukar dan nilai pakai sekaligus), ruang bersama alun-alun masih menyatu dengan peran “ruang dalam” istana (nDaleman), lalu luar “benteng” dan rekatan istana, religi dan tempat kumpul masyarakat untuk oasis kebudayaan dan kesenian mereka.
Ada sebuah rekatan tata nilai yang saling mengutuhkan antara pusat jagat kuasa raja, religi (yang ketika Islam masuk lalu ada masjid kerajaan) serta lapangan alun-alun untuk segala keperluan ungkapan perayaan hidup bersama dalam seni dan kebudayaan.
Sejak kapan ruang bersama bergeser fungsi dan berubah posisinya?
Pertama, sejak permaknaan ruang bersama digeser dari bingkai nilai kultural dan fungsi temu bersama merayakan kebersamaan menjadi hanya berbingkai lapangan tempat panggung pameran dagang dengan kepentingan ekonomis dan nilai ekonomis industri menggusurnya menjadi pasar dagang jual beli.
Apakah itu fenomena modernitas, dalam arti, rasionalitas (pola pikir kalkulasi untung rugi dalam ekonomi modern mengganti bahkan menggusur ekonomi tradisional yang tukar menukar kebutuhan hidup lewat bahan-bahan tanaman, buah yang disaling tukarkan untuk kebutuhan hidup hari demi hari, sebelum uang dengan nilai tukarnya mengganti ini semua?
Bila itu gejala modernitas, maka akibat-akibat apa yang mengenai perilaku orang-orang dalam menghayati ruang bersamanya?
Pertanyaan-pertanyaan ini melanjutkan refleksi kedua dari paparan ini yaitu soal penghayatan ruang bersama yang bergeser dari makna kultural menjadi ekonomis serta apa yang berebut dan siapa yang memperebutkan ruang bersama itu: kekuatan-kekuatan manakah hingga orang-orang pemilik awal yang semula aktif kini menjadi penonton pasif?
Atau lebih tandas lagi, kini penonton-penonton ini sudah dijadikan obyek konsumsi atau sekedar konsumen oleh dominasinya penguasaan ruang bersama ditangan pemodal?
Dalam 3 bukunya berturut-turut, Jurgen Habermas, yaitu“The Structural Transformation of the public Sphere: An inquiry into a Category of Bourgeois Society” (Cambridge, 1989); lalu “Knowledge and Human Interest” (1988) dan “The Theory of Communicative Action” (1987) bisa membantu kita mengkonsep-teorikan fenomena persoalan ruang bersama dalam benturan antara dunia nilai-nilai dan kepentingan lalu ruang bersama manakah yang secara modern (bila proyek modernitas mau dikritisi agar dehumanisnya dan instrumentalis-nya (berciri memperalat, mengobyekkan) bisa dikurangi.
II. PIAZZA
Ketika penghuni-penghuni kota (citta dinanza) butuh tempat untuk mengekspresi-kan diri, mereka lalu berkumpul di alun-alun yang disebut “piazza” atau “square”. Ekspresi kemauan dan kritik yang mau diungkapkan, dicetuskan di lapangan kecil itu hingga lamakelamaan lalu disebut sebagai ruang publik. Artinya, sebuah tempat dengan keluasan untuk berekspresi, berpendapat dan saling menghargai pendapat warga kota dalam sistem pemerintahan kota yang demokratis.
Ketika ruang publik dihayati sebagai tempat berkumpul, di sana berkembang pula tradisi ekspresi bersama dalam “manifestazione”: ungkapan unjuk pendapat dan debat publik di mana hati boleh panas namun akal budi dingin dan argumentasi rasional harus tetap menjadi pemimpin polemik atau debat publik itu.
Mengapa “piazza” atau “plaza” yang arti harafiah sederhananya cuma berarti tempat lalu menjadi simbol ada atau tidaknya penghargaan terhadap suara publik dalam ruang publik? Mengapa pula, dalam sejarah peradaban berdialog dan berdebat ketika konflik kepentingan muncul akhirnya menjadi indikator ada dan tidaknya hak warga untuk mengritik, untuk bersuara?
Pertanyaan-pertanyaan di atas terjawab dalam proses berkembangnya apa yang disebut “polis” (kota dengan politik kesejahteraan untuk warga) lalu materi pokok yang dibahas dalam ruang publik yang lalu dikenal oleh sejarah pemikiran sebagai ‘res publica’ (republika dalam arti awal yaitu pokok-pokok hal kehidupan publik rakyat atau warga di mana penanganannya ada dalam otonomi warga itu). Sejak “res publica” menjadi kata kunci untuk sebuah proses perjuangan hak-hak publik yang otonom dan harus dihormati oleh sistem kota atau sistem negara (state) atau (lo stato); maka di sana republika akhirnya diidentifikasi sama dengan gerakan masyarakat (societas) untuk tetap berdaulat. Dan sejak itu pulalah “res publica” menyatu dalalm langkah gerak serempak yang sama dengan perjuangan berdaulatnya rakyat atau demokratisasi.
Penghayatan sadar mengenai ruang publik oleh warga untuk politik kesejahteraan bersama (communitas publica) lalu menjadi ciri otentik dari perjuangan riil warga masyarakat untuk menolak mati-matian setiap usaha negara yang mau membelenggu; campur tangan atau membatasi hak-hak sipil publik seperti hak berkumpul; berserikat, mengeluarkan pendapat dengan merdeka serta hak publik mengontrol kekuasaan dalam mekanisme kritik.
Ruang publik yang semula bermakna luas sebagai wahana hidup bersama untuk berekspresi kreatif merdeka sebagai warga, di mana bermain-main, bercengkarama; ngobrol dan menghirup udara segar serta rekreasi dan relaksasi untuk hidup lebih lanjut lagi pelanpelan mendapatkan makna khususnya sebagai ruang publik politik perjuangan hak-hak publik untuk demokrasi.
Yang membuat ruang bersama berubah dari tempat temu sebagai piazza, atau plaza menjadi fungsi ekonomis pasar adalah masuknya kepentingan kelas-kelas ekonomis yang berubah sejak kapitalisme menjadi penentu hidup manusia.
III. Iklan dan Konsumsi Gaya Hidup
Lifestyle atau gaya hidup merupakan salah satu cara bersikap yang dipakai oleh orang tertentu ketika ia mau tampil layak dan aktual di hadapan orang-orang lain.
Seharusnya, gaya hidup merupakan rentetan pengolahan sikap menghayati hidup dengan pertimbangan akal budi mengenai cocok tidak dengan “posture” (bentuk fisik); tingkat pendidikan’ keadaan sosial (strata) di masyarakat serta pula cita-cita ke depan mengenai makna atau arti hidup misalnya sebagai orang Indonesia yang kelas menengah sosial serta mau tampil modern dan rapi cerdas sebagai cita-cita.
Yang seharusnya ini lalu ditampilkan sebagai gaya hidup dalam cara berpakaian; pilihan selera makan; pilihan bacaan koran, majalah atau buku; pilihan lagu-lagu lalu kesemuanya ditampilkan secara fisik dengan mode dan “gaya” tertentu atau “trend” tertentu.
Di sini ada 3 sikap mengolah gaya hidup seseorang. Yang pertama, sikap seleksi dalam gaya hidup, artinya, orang itu berpendirian terhadap arus mode yang ada dan hanya memilih yang baik, cocok dengan kepribadiannya. Seleksi pertimbangannya adalah pribadinya yang cerdas dan nuraninya dalam tampil terhormat dan berharkat.
Yang kedua, sikap adaptasi yang berarti menyesuaikan terus menerus dengan tawarantawaran ide dan citra modis dan pria tampan atau perempuan cantik yang sebagian disesuaikan kondisi diri orang itu, keluarganya dalam kondisi ekonomi, sosial dan kultural. Adaptasi merupakan sikap tengah-tengah antara seleksi dan nanti yang ketiga adalah imitasi. Bandingkan pokok-pokok ini dengan perilaku sosial.[1] Yang ketiga adalah sikap imitasi dalam gaya hidup. Inilah gaya hidup menirukan, membuat citra diri seseorang tiap kali diimitasikan dengan tokoh publik, bintang atau arus mode dan gaya paling mutakhir lalu dilahap dan ditirulah setotal-totalnya.
Pada sikap ketiga yaitu imitasi inilah kebanyakan orang dengan meniru gaya hidup idolanya atau kelas glamor idola dengan kesamaan makanan, gaya pakaian, gaya rambut bahkan segi-segi yang secara sengaja ditawarkan oleh pasar iklan sebagai pencipta citra atau “trend setter” diambil dan dipakai sebagai cara hidup dan bergaya dalam hidup.
Ketika penentu gaya hidup yang dominan adalah pasar dengan iklan dan nilai konsumsi yang dipompa terus untuk terus membeli yang baru; terus tampil modern, berakibat konsumtifnya gaya hidup karena penampilan dibayar amat mahal dengan membeli terus mode pakaian terbaru, peralatan kecantikan terbaru, mobil dan asesori-asesori untuk tampil elegan pada hal jati diri penampilan yang sebenarnya tetaplah dari jiwa yang dewasa dan kecantikan dari dalam kepribadian seseorang.[2]
Ketika orang tidak merasa berharga dan tidak merasa percaya diri sebelum makan Mc Donald; minum coca-cola; merokok Dunhil hijau berfilter, berparfum Dior; berbedak paling mutakhir; di situlah gaya hidup yang dicitrakan oleh pasar konsumsi produk iklan benar–benar dihayati dalam sikap imitasi yang mengikuti gaya hidup tanpa sikap seleksi yang cerdas.
Mengapa imitasi gaya hidup kelas selebriti dan idola yang dijual pasar menjadi identitas populer bersama dengan cepat? Sebab, pencipta jualan gaya hidup dalam citra/idolaidola iklan sengaja merangsang nafsu terus membeli dan keinginan tampil baru yang naluriah dimiliki manusia?
Dengan menghujani terus lewat pelipatgandaan bertubi-tubi pada nafsu ini, maka tidak sempat lagi akal menyeleksi dan terburailah (terangsanglah) nafsu konsumsi yang kemudian sebagai gaya hidup dikatakan: saya baru bermakna dan ada artinya keberadaan saya bila saya membelinya!
“I buy therefore I exist”: saya hanya berarti bila ada bila aku membelinya!
Gaya hidup konsumtif hasil pasar iklan ini paling banyak menghujani generasi remaja dan anak ketika pendidikan kepribadian dewasa untuk sikap seleksi tidak ditanam dalam proses lama sejak dini. Sebab, ketika teman-teman si anak di SD dalam gaya kelas menengah hampir semua memakai gaya tas Tweety atau sepatu Nike, maka salah satu anak yang belum memakainya akan merasa belum berarti di hadapan teman-temannya.
Gejala seperti inilah yang menunjukkan bahwa sikap imitasi dalam gaya hidup sudah menuju ke lampu merah peringatan akan pentingnya penanaman sikap percaya diri melakukan seleksi dengan budi untuk tampil diri dari kecantikan “dalam” atau jiwa pribadi.
Tantangan adaptasi buta dan imitasi buta terhadap gaya hidup konsumtif yang merajalela di saat pasar terus berlomba menawarkan idola, gaya hidup yang dijual mahal seharusnya membuat orang tua dalam keluarga; sekolah atau instansi pendidikan bersatu duduk bersama untuk menyikapinya agar bukan gaya hidup konsumtif, fisik tampan dan ayu yang nomer satu tetapi gaya hidup dari kecantikan batin pribadi-pribadi matang menyeleksi pilihanpilihanlah yang sejak dini diproses jauh-jauh.
IV. Konsumsi
Konsumsi (sebagai hegemoni gaya hidup Amerika) menurut George Ritzer (lihat G. Ritzer, Mc Donaldizetion: The reader, 2006 hal 240 dst) masuk dan menyerambah lewat ‘media presence’ yaitu Teve, Film, Internet yang menerobos ruang imaji lebih cepat dan lebih telak dari “material Reality Presences atau physical presences”.
Ada 3 mediumnya sebagai serbuan ruang publik. Pertama, kehadiran restoran-restoran cepat saji; kedua, kartu kredit atau ATM dan “katedral” konsumsi sebagai simbol eksistensi gaya hidup dan tampil anggun apabila sudah memakai dan membeli gaya hidup dan mengkonsumsi yang ditawarkan dalam (Iconsume Therefore I Exist”
Fenomena pertama, dalam tahun-tahun terakhir kehadiran restoran-restoran cepat saji. Amerika langsung mendorong negara-negara lain meniru cara-cara manajemen bisnis Amerika soal makanan cepat saji. Tidak hanya terjadi paradoks dimana pesona masak memasak manusiawi untuk “kuliner” dilenyapkan diganti pesona baru kerja cepat terhidang, pelayanpelayan berseragam yang terampil dan dimisteriuskannya proses ramuan saji cepat dalam eksotisme baru yang menyedot konsumsi generasi muda untuk menyandang gaya hidup gaul bila sudah nongkrong disana.
Yang kedua, ATM atau kartu kredit menjadi simbol internasionalisasi bukti pembayaran yang ‘gagah’, penuh pesona bahkan “irasional” bila didalamnya penuh hutang yang terus menerus boros habis baru sadar bila ditagih oleh ‘debt collector’. ATM adalah kartu ‘hutang’ secara riel dalam transaksi namun terselubung dalam simbol eksotis gaya hidup dan gaya membeli sebagai yang beruang (tapi berhutang!).
Yang ketiga, “katedral-katedral” konsumsi tempat merayakan konsumsi sebagai ritual gaya dan penghayatan mengkonsumsi sebagai simbol ‘agama’ baru yaitu konsumerisme dalam kapitalisme.
Mal, dengan pemusatan toko hiburan, pemenuhan hasrat makan, hasrat menonton dengan nikmat dan hasrat tampil bergaya dengan melenggang ceria bahkan ‘show’ apa yang sedang dipakai di ruang publik menjadikan mal sebuah panggung “cat walk” kelas tengah ke atas dan punya penikmatan gaya hidup minum kafe, makanan “junk food” simbol kemajuan dan pergaulan urban/kota.
Belanja atau keliling mal dengan melihat etalase-etalase berjam-jam telah menyita waktu kreatif. Jalan-jalan di taman kebun, museum budaya atau seni yang kultural diganti ekonomi kapital di “shopping centers”.
Yang keempat, pusat-pusat perbelanjaan dalam mal dan maraknya model “discount” di mal-mal itu telah menggusur ruang publik belanja di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional kalah bersaing tidak hanya oleh kepastian standard barang yang dijual; kualifikasi kadaluwarsa tidaknya dengan stiker jelas bisa dipakai sampai tanggal berapa tetapi pula rasa psikologis aman berbelanja jenis makanan dari pembeli karena jelas tidak usah tawar-menawar harga.
Ruang publik taman kota, kebun binatang atau museum terkurangi dikunjungi karena pusat belanja mal dilengkapi dengan pusat-pusat “teater bioskop, “entertainment places”; boostore serta menjadi wahana jalan-jalan dari sarana berbelanja menjadi tujuan.
Mengisi waktu di hari Minggu atau hari senggang seluruhnya. Jadilah jalan-jalan sambil konsumi dan menikmati hari libur menjadi satu proses. Gaya hidup konsumsi yang dipenuhi semuanya (oleh pusat-pusat). Oleh pusat-pusat, belanja ini dari ‘pemenuhan hasrat konsumsi; kebutuhan mata inderawi cuci mata; sampai intelektual bacaan serta hasrat makan dan minum yang semuanya dikemas menjadi kebutuhan routine setiap ‘akhir pekan’ tanpa terasa, tanpa sadar mereduksi ruang-ruang batin sadar mereduksi ruang-ruang batin dan publik manusia hanya melulu satu dimensi yaitu “konsumsi”, (bdk. Herbert yaitu Marcuse,”One dimensional Man”, 1981).
V. Daya Sihir Mal
Jon Goss dalam tulisannya berjudul: “The Magic of the Mall”: an analysis of form, function and meaning in the contemporary retail built environment (Nicholas R. Fyfe and Judith T. Kenny, ed., ‘The urban geography reader’, Routledge, London, N.Y, 2005, hal. 293303). Diberi pengantar editor sbb:
“Para pengiklan berusaha menyatukan komoditas dengan simbol-simbol budaya yang umum dipahami dengan harapan tidak Cuma memenuhi kebutuhan konsumer mengenai komoditasnya tetapi agar konsumer mengidentifikasi diri dengannya. Maka “you are what you buy”: identitasmu melekat tampil pada apa yang kau beli harus ditambah langsung dengan “Anda membelinya dimana”? maka bangunan mal, letaknya, dirancang untuk mendorong pembeli mengejarnya dan merasa bergengsi di tempat mal “belanjaannya”.
Mal adalah mesin ajaib untuk belanja yang dimanipulasi hasratnya dengan arsitektur, setting lokasi, lanskap simbolik hingga sekaligus mengalami fantasi belanja di mal yang menggabungkan rasa belanja di ruang-ruang yang bersejarah tapi sudah dikemas eksotis memenuhi hasrat belanja, jalan-jalan, nonton dan tampil diri sebagai identitas dengan menaruh mal di lanskap budaya pop yang menyatukan kepuasan pemenuhan hasrat ruang privat dan ekspresi citra ruang publik sebagai ‘gaul’, mampu beli gaya hidup ‘modern’.
Dari sisi politik ekonomi: tempat seperti mal merupakan ‘political fact’, artinya, tempatnya ditangan kontrol kelas yang sedang berkuasa secara birokratis dan pemilik modal. Untuk membangun tempat eksotis buat pusat belanja pengembang memanipulasi nostalgia kaum modernis maju yang damba akan komunitas otentik yang khas sesuai stratifikasi sosial dan pemilikan.
Menstransformasi kenangan lalu pasar-pasar tradisional sebagai “centrum” komunitas, kini dicipta lanskap dengan nostalgia ekologis hijau dalam misalnya “Country Club Plaza” di kota Kansas. Maka “Shopping Towns” would be not only pleasant places to shop, but also centers of cultural enrichment, education and relaxation, a suburban alternative to the decaying downtown” (Gruen and Smith, 1960, “Shopping Towns USA”: New York).
Ingatlah langsung China Town di Cibubur; American Cities dan Imaji-imaji Eropah yang dibangun disana! Sebuah ruang imaji acuan kota-kota wisata Eropah yang diwujudkan di Cibubur serta Suburban Jakarta.
Ruang publik yang diwujudkan oleh ideologi nostalgia kenangan kunjungan-kunjungan kota-kota anggun eropah atau pusat-pusat dunia dipadukan dengan jalan setapak yang hilang karena di Jakarta selalu bermobil!
Goss menunjuk ciri-ciri ruang baru yang dikonstruksi di sekitar mal dan tempat relaksasi sbb:
a). “Shopping Center” sebagai “Civic Space” (Goss, ibid, hal. 298), artinya ditampilkannya mal dan pusat belanja sebagai ruang-ruang publik yang aman, enak, sehat dengan pesona nyaman terjaga di sana dengan bercengkerama dan jalan-jalan Anda akan menatap, melihat dan dilihat oleh yang lain dengan ‘gaya pakaian’, gaya jalan dan gaya hidup.
Di sana pula visi konsumsi diratakan dalam rasa kesamaan derajat sesama pemakai alat tanda bayar (credit card). Yang terlalu miskin tidak akan masuk ke ruang elit eksklusif bila tidak mau malu!
b). Pasar modern atau pusat belanja mal menjadi pula ruang liminal (menurut Victor Turner dalam ritus 1982) dimana mal tepat berada diantara eksotisme yang suci dan yang sekular; antara yang lokal dan global; antara yang resmi berjenjang dan bebas spontan. Ruang liminal ini memungkinkan Anda jadi diri Anda. Coba yang aneh-aneh, lucu-lucu termasuk yang mengatasi penilaian baik buruk tanpa resiko disensor secara moral dan bebas dari pengawasan institusional.
c). The Shoping Center juga sebagai ruang transaksi dimana kompetisi dan discount saling berlomba dan kita memilih untuk terus memuasi hasrat mengkonsumsi.
d). Ruang-ruang di mal dirancang menjadi taman firdaus dengan air mancur instrumental dan mini alami yang oleh pengembang menjadi ruang-ruang instrumentalisasi “seakan-akan alami dan surgawi ekologis namun seemingley, make believe hanya di situ saja lantaran begitu pulang ke rumah, rasa dan imaji ini tersadar lagi!
VI. Epilog
Ruang bersama yang awalnya dihayati secara kultural kemudian oleh rejim penentu makna ditambah rejim kelas pemenang kepentingan yang mengalahkan kelas-kelas bawah dengan modal dan kapital akhirnya tidak hanya mengubah peran temu bersama penghayatan ruang bersama dari kultural menjadi fungsional, instrumental untuk kepentingan kelas bermodal tetapi juga dalam istilah Antonia Gramsci telah menguasai dalam hegemoni sistem simbol dan makna hingga menundukkan kelas-kelas yang tak berpunya modal dan telah dihegemoni dalam menafsirkan hidup karena kesadaran kritisnya telah ditundukkan lewat pendidikan, tafsir realitas dengan cara non “Coercive” (tak memaksa namun yang dilumpuhkan adalah kesadaran kritisnya), menjadi segalanya dimaterialkan; dibendakan dalam proses reifikasi.
Maka pertanyaan dasarnya, mengapa itu terjadi, bukankah kesadaran manusia itu kritis dan mampu mengetahui serta menghimpun informasi menjadi pengetahuan?
Justru di tahapan rangkuman pengetahuan (dari proses berkepentingan ingin tahu untuk “cognitive interest” untuk informasi dan memakai pengetahuan), manusia memiliki berlapislapis kepentingan. Mulai dari mengiyakan informasi dan pengetahuan realitas seperti adanya (affirmative) sampai memakai pengetahuan secara kritis dengan kesadarannya untuk perubahan (transformatif kritis), “pergulatan atau perang kepentingan itulah yang menentukan akhir laga menang kalahnya.
Ketika pengetahuan dengan rasionalitas instrumental tidak digunakan untuk transformasi bertujuan peradaban bersama maka yang terjadi di ruang bersama adalah perang kepentingan dari anggota-anggotanya yang dimenangkan oleh mereka yang bermodal; mereka yang mampu menyatukan pengetahuan dengan kuasa kapital untuk kepentingan ekonomis serta oleh mereka yang menguasai dunia-dunia simbolik dalam mengartikan makna kehidupan ini.
Karena itu untuk menyelamatkan ruang bersama agar tetap demokratis dalam arti tiap orang secara fair menghayati hidup bersama dengan menghormatai harkat dan ruang-ruang pribadinya dalam temu bersama dibutuhkan syarat utamanya yaitu pertama, dialog terbuka buat membuka kepentingannya secara komunikasi yang demokratis diantara peserta ruang bersama. Syarat utama berikutnya adalah dialog komunikasi yang mencari terus menerus titik temu konsensus ketika perbedaan kepentingan bertemu untuk kepentingan umum yang didahulukan demi kelangsungan hidup bersama dalam ruang bersama.
Konsensus-konsensus ini, dalam bacaan saya, sebenarnya menjadikan ruang bersama tempat terbuka dialog untuk tulus membuka kepentingan masing-masing dan membuka pula nilai-nilai penghayatan hidup dari ruang personal ke ruang bersama dan diambil titik-titik temu konsensus untuk nilai dan kepentingan bersama atau yang dalam bahasa politis, ekonomis, kultural: kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama (bonum commune). Sebuah cita-cita utopiskah?***
Pustaka:
1. Jürgen Habermas,”The Public sphere: an encyclopedia article” dalam bukunya: “Critical
Theory and Society: A Reader”, ed. Stephen Eric Bronner and Douglas M. Kellner, translated by Sara Lennox and Frank Lennon (Routledge, 1989), terutama hal. 136 – 142.
2. Antonio Gramsci,”Selections from the Prison Notebooks”, ed. And Transl. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, New York, 1971, hal. 50 – 60.
3. Raymond Williams, “Culture and Society”, Penguin, 1960.
4. Paul Helas, Scott LASH, Paul MORRIS, ed.,Detraditionalization”, Blackwell, 1966.
5. Titi Surti Nastiti,”Pasar di Jawa: masa Mataram Kuno, abad VIII – XI”, Pustaka Jaya, 2003.
6. Ritzer,”MacDonaldization: The Reader, Pine Forge Press, London, 2006.
7. Nicholas R. Fyfe and Judith T. Kenny, “The Urban Geography”: The Reader, Routledge, London, N.Y, 2005.
[1] John W. Berry dkk., Psikologi lintas budaya,. Jakarta: Gramedia, 1999, hlm. 84-136.
[2] Lih. Ann Brydon dan Sandra Niessen (ed.), Consuming Fashion, Oxford: Berg., 1998, hlm. 60-70.
———-
*Mudji Sutrisno SJ, budayawan.