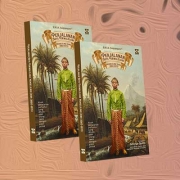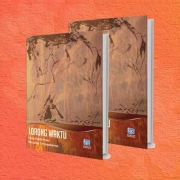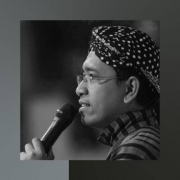Hujan Mikroplastik dalam Perspektif Kultural
Oleh: Purnawan Andra*
Ekopoetika Hujan
Hujan, yang dulu menjadi lambang kesuburan dan berkah dalam banyak tradisi Nusantara, kini turun membawa mikroplastik. Data penelitian BRIN sejak tahun 2022 menunjukkan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik yang berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah dan limbah plastik di udara (Kompas.id, 18/10/2025).
Artinya, udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan bahkan hujan yang kita sambut telah menjadi residu peradaban yang mencemari dirinya sendiri. Sebuah ironi yang menandai betapa dalamnya keterputusan manusia modern dari ekosistemnya sendiri.
Namun di luar aspek ekologisnya, peristiwa ini perlu dibaca sebagai gejala kebudayaan, sebagai tanda dari krisis kesadaran modern yang lebih dalam.
Peristiwa Simbolik
Dalam kerangka antropologis, hujan bukan hanya fenomena alam, tetapi juga peristiwa simbolik yang menandai relasi antara manusia dan kosmos. Claude Lévi-Strauss pernah menyebut mitos sebagai “bahasa yang digunakan manusia untuk menata kekacauan realitas.”
Dalam konteks masyarakat agraris Nusantara, hujan selalu dihadirkan dalam sistem makna yang penuh nilai. Ia tidak hanya memberi kesuburan, tetapi juga menuntut keseimbangan. Upacara seperti hajat bumi atau wiwitan merupakan bentuk penghormatan terhadap siklus ekologis, sebuah pengakuan bahwa manusia hanyalah bagian dari jaringan kehidupan, bukan penguasanya.
Namun modernitas, seperti dikritik sosiolog Prancis Bruno Latour dalam We Have Never Been Modern (1993), memisahkan manusia dari alam melalui dikotomi palsu: subjek dan objek, budaya dan alam, manusia dan bukan-manusia. Hasilnya adalah kesadaran yang timpang—kita memperlakukan bumi sebagai bahan, bukan mitra.
Dalam kebudayaan modern, “kemajuan” sering diukur dari sejauh mana kita mampu mengendalikan alam. Relasi spiritual yang dulunya penuh rasa takzim berubah menjadi relasi teknologis yang penuh klaim efisiensi. Hujan yang dulu disambut dengan doa, kini dibaca melalui sensor meteorologi dan radar. Modernitas menjadikan alam sebagai data.
Seperti diingatkan sosiolog Polandia Zygmunt Bauman dalam Liquid Modernity (2000), masyarakat modern hidup dalam keadaan cair—segala hal mengalir, berubah cepat, tanpa fondasi yang stabil. Tapi ironi besarnya adalah dalam kelimpahan informasi, kita kehilangan kebijaksanaan ekologis.
Dalam kecepatan mobilitas, kita kehilangan arah spiritual. Dan ketika hujan turun membawa mikroplastik, itu bukan sekadar persoalan limbah, melainkan simbol kembalinya akibat dari keterputusan yang kita bangun sendiri.
Krisis Kesadaran
Krisis ekologis ini pada dasarnya adalah krisis kesadaran. Antropolog Inggris Tim Ingold(2000) menyebut bahwa cara modern memandang lingkungan cenderung “terpisah,” bukan “terhubung.” Kita hidup dalam paradigma “environment as background”—lingkungan sebagai latar aktivitas manusia, bukan ruang hidup bersama.
Vandana Shiva menegaskan dalam Staying Alive (1988) bahwa logika kapitalisme patriarkal telah menyingkirkan prinsip prana—daya hidup kosmik yang menjiwai segala hal—dan menggantinya dengan logika produksi dan eksploitasi. Bagi aktivis lingkungan India ini, keadilan ekologis berarti mengembalikan kesadaran akan keterhubungan itu: bahwa bumi bukan sumber daya, melainkan sumber kehidupan; bukan obyek, melainkan ibu.
Dalam pandangan Nusantara, kesadaran ekologis seperti itu telah lama hidup. Konsep mamayu hayuning bawana dalam filsafat Jawa berarti “merawat keindahan dunia,” tetapi secara lebih dalam mengandung etika kosmik: bahwa manusia hidup untuk menjaga keseimbangan semesta.
Begitu pula dengan pandangan Bali tentang Tri Hita Karana—tiga harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Keduanya berangkat dari kesadaran bahwa kehancuran dunia luar selalu berakar pada keretakan dunia batin. Dengan demikian, krisis ekologis modern sejatinya adalah krisis spiritual: bukan karena kita kekurangan teknologi, tetapi karena kita kehilangan cara memaknai hubungan dengan yang hidup.
Penanda Dekonstruktif
Maka, hujan mikroplastik bukanlah “keajaiban sains,” melainkan penanda dekonstruktif atas mitos kemajuan modern. Jacques Derrida mengajarkan bahwa setiap oposisi biner menyembunyikan hierarki makna yang tak seimbang. Dalam hal ini, modernitas telah menempatkan “bersih” di atas “kotor,” “teknologis” di atas “alami.”
Padahal kini, justru yang tampak bersih seperti kemasan plastik steril, deterjen, pakaian sintetis, justru menjadi sumber kekotoran ekologis yang halus dan tak kasatmata. Kita hidup dalam paradoks kebersihan: semakin steril citra peradaban modern, semakin tercemar hakikat ekologisnya.
Pandangan ini diperkuat oleh Timothy Morton dalam Hyperobjects (2013), yang menyebut bahwa fenomena seperti perubahan iklim atau mikroplastik adalah “obyek-obyek hiper” —terlalu besar, kompleks, dan menyebar untuk sepenuhnya dipahami oleh persepsi manusia.
Hujan mikroplastik adalah salah satu “hyperobject” itu: sesuatu yang hadir di mana-mana, tak terlihat, tapi mempengaruhi segalanya. Ia memaksa kita untuk mengubah cara berpikir, dari kesadaran antroposentris menuju kesadaran ekologis. Seperti kata filsuf ekologi kontemporer Inggris itu, “the ecological thought begins when we realize that everything is interconnected.”
Ecopoetic
Kita membutuhkan cara berpikir yang lebih berbudaya, lebih puitis tentang bumi—ecopoetic baru yang menyatukan ekologi dan estetika. Ecopoetics sendiri berkembang dalam kritik sastra, filsafat ekologi, dan teori budaya sejak akhir 1980-an oleh pemikir seperti Jonathan Bate (2000), Timothy Morton (2007, 2018), hingga Scott Knickerbocker (2012).
Ecopoetika bukan sebagai gaya sastra, melainkan etika dan epistemologi, spiritualitas dan politik. Bukan lagi kampanye daur ulang, melainkan perubahan cara pandang terhadap kehidupan itu sendiri. Hujan mikroplastik yang terjadi hari ini adalah cara alam memanggil kembali kesadaran kita, agar manusia berhenti merasa sebagai pusat, dan mulai merasa sebagai bagian.
Dalam spiritualitas Nusantara, manusia selalu sadar bahwa ia adalah bagian dari makrokosmos. Kini kesadaran itu perlu dihidupkan kembali. Bukan dalam bentuk mistisisme yang romantik, melainkan dalam bentuk sikap politik ekologis yang rendah hati, penuh empati, dan sadar batas. Karena kini hujan tidak identik dengan puisi-puisi romantik, tapi dengan perenungan tentang bagaimana kita sampai di titik di mana langit pun ikut kotor oleh tangan kita sendiri.
Sebagaimana ditulis filsuf Prancis Michel Serres dalam The Natural Contract (1990), umat manusia harus menandatangani “kontrak baru” dengan alam—sebuah perjanjian yang berbasis pada kesalingan, bukan eksploitasi. Karena hujan mikroplastik bukan sekadar fenomena cuaca, tetapi pernyataan politis dari alam, bahwa kehidupan modern sedang menenggelamkan dirinya sendiri dalam limbah yang dihasilkannya.
Bila air kehidupan telah ternoda, yang perlu dimurnikan bukan sekadar sungai atau udara, melainkan cara kita berpikir, berbudaya, dan beriman. Sebab spiritualitas sejati tidak berhenti di altar atau tempat ibadah. Ia menetes dalam setiap hujan yang jatuh di bumi dan di hati kita sendiri.
—
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Governance & Management of Culture di Daegu Catholic University Korea Selatan.