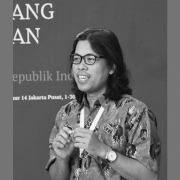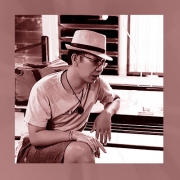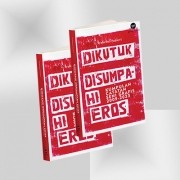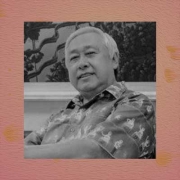Estetika Diam, Etika Ketabahan, dan Eksistensialisme Banowati
Oleh Purnawan Andra*
Dalam jagat Mahabharata yang penuh dengan heroisme, intrik kekuasaan, dan peperangan, nama Banowati sering kali luput dari pusat perhatian. Padahal, tokoh perempuan yang dalam versi India dikenal sebagai Bhanumati ini justru menyimpan lapisan makna reflektif sekaligus relevan bagi kehidupan kita hari ini.
Ia bukan sekadar permaisuri Duryodana, raja Astina, melainkan sebuah simpul simbolik yang mempertemukan cinta, pengorbanan, dan ketegangan eksistensial perempuan dalam sejarah yang ditulis oleh para lelaki.
Banowati adalah putri Raja Salya dari Mandaraka. Dalam banyak versi, ia dikisahkan diculik oleh Duryodana dengan bantuan Karna karena sang putri menolak pinangannya. Episode penculikan ini menandai satu hal: tubuh dan kehendak perempuan kerap menjadi medan perebutan dalam narasi kekuasaan, yang acap disamarkan sebagai “kisah cinta”.
Namun dalam versi pedalangan Jawa, kisah Banowati mengalami pengembangan—mulai dari Banowati Duta, Banowati Larung, hingga Gugur Banowati. Lakon-lakon ini tak selalu ditemukan dalam Mahabharata versi Sanskerta, tapi tumbuh sebagai narasi rakyat yang menyiratkan tafsir kultural dan refleksi nilai yang lebih luas. Banowati dalam dunia pewayangan bukan hanya tokoh, tetapi suara: lembut, tertahan, tetapi dalam dan tegas.
Menariknya, ia kerap diasosiasikan mencintai Arjuna—musuh suaminya sendiri. Lakon carangan Banowati Larung mengisahkan tentang dirinya yang dilarung (dibuang) oleh Duryodana karena difitnah berselingkuh dan membocorkan rahasia Kurawa. Dalam kebudayaan Jawa, kisah ini jadi metafora kesetiaan batin yang tak selalu sejalan dengan ikatan struktural. Bukan soal perselingkuhan, tetapi tentang ruang sunyi yang dimiliki manusia untuk tetap setia pada kebenaran perasaan.
Dalam konteks hari ini, kita melihat banyak perempuan yang mengalami dilema serupa: mencintai secara diam-diam, bertahan dalam hubungan demi status sosial, atau memilih jalan diam dalam sistem yang membungkam keberanian untuk menentukan hidup sendiri.
Estetika Ketabahan dan Laku Diam
Estetika Banowati adalah estetika ketabahan. Larik-larik pedalangan menyebut ia sebagai perempuan yang tak banyak bicara, tapi kehadirannya membawa terang—sesuai namanya, “Bhanu-mati”, sang bercahaya. Dalam lakon Banowati Duta, ia menjadi utusan diplomatik. Dalam versi Njajah Desa Milang Kori: Banowati Janji, ia memainkan peran strategis dalam pencarian remong, aksesoris tari yang sarat makna simbolik.
Ia bukan pahlawan konvensional, tapi keputusannya tak menyeret anaknya ke perang dan menyelamatkan Burisrawa dari kematian menyiratkan moralitas yang sunyi namun kuat. Banowati mencontohkan kebaikan yang tidak bising—kebajikan yang tidak haus tepuk tangan.
Dalam dunia yang bising oleh performativitas citra dan ekspresi sosial, Banowati justru hadir sebagai antitesis. Ia seperti puisi Sapardi: “tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni.” Kesetiaannya pada Arjuna yang tak pernah terucap adalah bentuk kesetiaan eksistensial. Diamnya bukan kekalahan, melainkan pilihan sadar untuk menjaga kebenaran batin.
Banowati semacam menjalani laku diam sebagai bentuk ngalap berkah. Dalam tradisi Jawa, ngalap berkah berarti memohon atau meraih berkah dari sesuatu yang dianggap sakral—biasanya melalui ziarah, laku tapa, atau tirakat. Ketika dikaitkan dengan diam, ini bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi menjadi bentuk kontemplasi eksistensial. Diam yang bukan pasif, tapi aktif menyerap, menimbang, dan memilih.
Eksistensialisme dan Perempuan Nusantara
Filsafat eksistensialisme yang diperkenalkan tokoh-tokoh seperti Kierkegaard, Sartre, dan Simone de Beauvoir menekankan kebebasan individu, otentisitas, dan pilihan eksistensial dalam situasi keterbatasan. Dalam kerangka ini, Banowati adalah representasi perempuan yang mengolah keterbatasan menjadi kebebasan batin.
Simone de Beauvoir pernah mengatakan bahwa perempuan bukan dilahirkan, melainkan menjadi. Banowati menjadi perempuan melalui jalan berliku: diculik, dituduh, dibuang, dan akhirnya dibunuh. Namun ia tetap menyimpan utuh ruang batinnya, memilih untuk mencintai dalam senyap, memaafkan tanpa perlu pengakuan publik, dan menghadapi nasib tanpa menyerah pada dendam.
Estetika dan filsafat Nusantara pun mendukung bentuk kehadiran semacam ini. Banyak tokoh perempuan dalam mitologi Jawa dan Bali tampil sebagai penjaga keseimbangan kosmis: Dewi Sri, Durga, dan Ratu Kidul, misalnya, adalah figur yang tak melulu agresif, tetapi memiliki kekuatan dalam kelembutan, keteguhan dalam diam. Konsep “ayu” dalam estetika Jawa bukan sekadar cantik, melainkan keseimbangan antara raga dan rasa.
Banowati pun begitu: keayuannya bukan hanya visual, tetapi spiritual. Daya tariknya bukan pada sensualitas tubuh, melainkan pada aura batin dan laku sabar yang memancarkan keteguhan. Ketika tubuh perempuan hari ini makin dieksploitasi sebagai komoditas visual dan moralitas patriarkis, Banowati menjadi pengingat bahwa ada bentuk lain dari daya tarik: kedalaman, kemurnian niat, dan integritas batin.
Dunia Setelah Perang
Kisah gugurnya Banowati—dibunuh Aswatama setelah perang Baratayuda—menegaskan bahwa bahkan setelah perang selesai, perempuan tetap menjadi korban. Kekerasan tak selesai di medan laga. Ia berlanjut dalam tubuh dan ingatan perempuan. Dalam banyak konflik modern, dari perang literal hingga kekerasan domestik, perempuan masih menjadi titik akhir dari dendam yang tak tuntas.
Namun versi lain dari kisah ini di India Selatan menyebut bahwa Banowati akhirnya menikah dengan Sahadeva (Sadewa), si bungsu Pandawa. Ini bukan semata penyelesaian romantik, tapi simbol rekonsiliasi: perempuan sebagai jembatan dua kutub besar yang saling memusuhi. Dalam dunia yang makin terbelah oleh identitas politik, agama, dan algoritma digital, kita butuh lebih banyak sosok semacam ini—yang mampu mengolah luka jadi jembatan, bukan jurang.
Banowati mengajarkan bahwa perempuan Nusantara tidak harus meniru model perempuan Barat yang berteriak untuk kebebasan. Perempuan Nusantara memiliki jalannya sendiri: dengan estetika ketabahan, dengan eksistensialisme diam, dengan laku yang justru melahirkan kebijaksanaan.
Banowati adalah pengingat bahwa kita tak selalu harus membentuk diri dari kerangka Barat. Dalam dirinya, filsafat, seni, dan spiritualitas lokal telah menyatu dalam satu tarikan napas yang membumi dan membebaskan. Ia bukan untuk ditiru, tetapi untuk direnungi.
Karena hari ini, dalam dunia yang semakin gaduh oleh simbol, kompetisi, dan kewajiban tampil, Banowati menawari jalan lain: diam, reflektif, tetapi sadar dan teguh. Sebuah bentuk ngalap berkah batiniah yang layak jadi teladan di tengah kebisingan zaman.
—-
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, bekerja di Kementerian Kebudayaan.