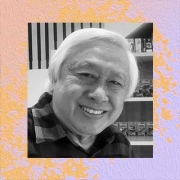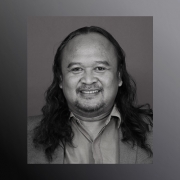Demo: Membaca Teks, Membedah Konteks
Oleh: Gus Nas Jogja*
Di bawah terik matahari Jakarta yang pekat oleh polusi dan emosi tanpa kendali, di persimpangan jalanan yang padat, sebuah teater absurd digelar pada tanggal 28 Agustus 2025 lalu. Panggungnya adalah aspal yang panas, aktornya adalah ribuan wajah yang sama-sama lelah, dan naskahnya adalah ketidakpuasan yang sudah lama membeku. Ini adalah sebuah demonstrasi. Kita seringkali melihatnya sebagai sebuah drama politik yang serius, namun jika kita mau sedikit menengok dari balik tirai, ia juga sebuah komedi tragis yang jenaka sekaligus getir.
Seorang filsuf mungkin akan bertanya, “Bagaimana bisa manusia, makhluk yang konon rasional, berubah menjadi gerombolan yang digerakkan oleh emosi?”
Di sinilah letak ironi terbesar. Aksi massa, di satu sisi, adalah manifestasi tertinggi dari akal budi yang memberontak. Di sisi lain, ia adalah contoh paling purba dari naluri kawanan yang kembali berkuasa. Untuk memahami kontradiksi ini, kita harus membedah demonstrasi dari tiga lensa kritis: logika, psikologi, dan budaya. Tiga lensa yang saling tumpang tindih, membentuk sebuah kacamata multifokal untuk melihat esensi dari kritik kekuasaan.
1. Silogisme: Logika sebagai Senjata Paling Tajam
Di jantung setiap demonstrasi, ada sebuah argumen yang begitu sederhana, begitu murni, sehingga terkadang kita melupakannya. Argumen ini adalah sebuah silogisme, sebuah struktur deduktif yang lurus dan tak terbantahkan. Premis mayornya adalah sebuah keyakinan yang fundamental, bahkan nyaris religius, tentang apa yang seharusnya.
Premis Mayornya mengatakan: “Sebuah pemerintahan yang beradab dan berpihak pada rakyat adalah pemerintahan yang mendengarkan suara publik, menjunjung tinggi keadilan, dan menjamin kesejahteraan dasar.”
Premis ini, pada dasarnya, adalah sebuah idealisme. Ini adalah impian yang kita pelajari dari buku-buku sejarah dan teori politik. Ini adalah sebuah narasi yang diwariskan dari para pemikir besar.
Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, “Semua manusia secara alamiah memiliki keinginan untuk mengetahui.” Premis mayor ini adalah manifestasi dari keinginan itu—keinginan kita untuk mengetahui dan hidup dalam sebuah sistem yang rasional dan adil. Namun, realitas seringkali tidak seideal teori. Di sinilah premis minor memasuki panggung, sebuah fakta yang mengganggu dan tak bisa diabaikan.
Premis Minor akan membuat narasi berikut: “Pemerintahan saat ini telah menunjukkan serangkaian tindakan yang tidak mencerminkan idealisme tersebut. Mereka telah mengabaikan aspirasi rakyat, membuat kebijakan yang merugikan, dan membiarkan ketidakadilan merajalela.”
Ini adalah bagian yang paling menyakitkan dari silogisme ini, karena ia memaksa kita untuk mengakui adanya ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan dan apa yang kita alami.
Dan dari kedua premis ini, lahirlah sebuah konklusi yang tak terhindarkan: “Oleh karena itu, pemerintahan ini harus dipertanyakan, dikritik, dan dipaksa untuk berubah.”
Ini adalah logika di balik setiap teriakan, setiap spanduk, dan setiap langkah kaki. Namun, yang menarik, seringkali dalam demonstrasi, logika ini tidak diucapkan secara utuh. Kita tidak mendengar orasi yang panjang dan rinci tentang premis mayor dan minor. Kita hanya mendengar sebuah entimem, sebuah singkatan yang padat dan emosional, seperti “Turunkan Harga!” atau “Hidup Rakyat!” Ini adalah sebuah “rahasia” yang hanya dipahami oleh mereka yang berada di dalam kerumunan, karena mereka semua berbagi premis mayor dan minor yang sama.
2. Psikologi Massa: Ketika Rasionalitas Mendapat Cuti
Begitu logika dasar tercipta, ia segera terhempas ke dalam lautan psikologi massa. Di sini, aturan logika murni seolah-olah ditangguhkan, digantikan oleh hukum-hukum emosi, sugesti, dan identitas. Gustave Le Bon, dalam studinya yang seminal, menjelaskan bagaimana individu yang berkerumun dapat kehilangan rasionalitasnya dan menjadi bagian dari sebuah entitas kolektif yang irasional.
“Seorang individu yang tenggelam dalam kerumunan akan segera menemukan dirinya—entah sebagai akibat dari pengaruh magnetis yang dipancarkan oleh kerumunan atau karena sebab lain yang kita tidak ketahui—dalam keadaan khusus, yang sangat mirip dengan keadaan terpesona dari individu yang terhipnotis,” tulis Le Bon.
Ini adalah penjelasan yang mengerikan sekaligus akurat. Di tengah kerumunan, kita merasa anonim, yang melenyapkan rasa tanggung jawab pribadi. Kita berteriak dengan suara yang tidak kita kenali, dan kita merasa berani melakukan hal-hal yang tidak akan kita lakukan sendirian.
Kemudian, ada fenomena sugesti dan penularan. Emosi, baik itu amarah, frustrasi, maupun euforia, menyebar di antara massa seperti api yang menyala di ladang kering. Satu orang meneriakkan kata-kata provokatif, dan ribuan orang mengikutinya tanpa berpikir panjang. Ini adalah sisi gelap dari solidaritas, di mana emosi kolektif dapat memicu tindakan destruktif.
Plato, jauh sebelum Le Bon, telah membagi jiwa manusia menjadi tiga bagian: rasio, roh, dan nafsu. Bagian “roh” inilah, yang mengandung amarah dan keberanian, yang seringkali mengambil alih kendali di tengah demonstrasi. Ketika massa merasa tertindas dan amarahnya memuncak, bagian “roh” inilah yang mendorong mereka untuk bertindak, terkadang tanpa bimbingan rasio.
Namun, tidak semua psikologi massa itu negatif. Identitas sosial, misalnya, memainkan peran yang sangat penting. Demonstrasi buruh, mahasiswa, atau petani terbentuk dari sebuah ikatan batin yang kuat. Mereka tidak hanya berdemonstrasi untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sebuah identitas kolektif yang merasa menjadi korban dari ketidakadilan. Ikatan ini memberi mereka kekuatan untuk bertahan, bahkan di hadapan kekerasan.
3. Literasi Kebudayaan: Membaca dan Menulis Ulang Narasi
Demonstrasi tidak hanya terjadi di jalanan; ia juga terjadi di ranah budaya. Di sini, pertempuran sesungguhnya adalah perebutan narasi. Literasi kebudayaan adalah kemampuan untuk membaca dan mengkritik teks, simbol, dan ritual yang membentuk realitas kita.
Pemerintah seringkali menggunakan narasi-narasi yang manis untuk mempertahankan hegemoni mereka. Narasi “pembangunan untuk kesejahteraan rakyat” atau “demokrasi yang stabil” adalah contoh-contoh narasi yang kuat. Namun, para demonstran, yang memiliki literasi kebudayaan yang tajam, mampu mendekonstruksi narasi ini. Mereka melihat bahwa di balik “pembangunan” ada penggusuran, dan di balik “stabilitas” ada penindasan.
Simbol-simbol perlawanan yang dibawa oleh demonstran adalah sebuah bentuk puisi visual. Spanduk yang berisi kutipan satir adalah sebuah anekdot jenaka yang menusuk kekuasaan. Yel-yel yang disuarakan adalah sebuah puisi yang diucapkan bersama, menciptakan melodi perlawanan.
Kahlil Gibran, seorang penyair yang tahu betul tentang penderitaan dan keindahan, berkata, “Penderitaanmu adalah cangkang yang pecah dari pemahamanmu.”
Demonstrasi adalah “cangkang yang pecah” ini. Ia adalah ekspresi dari rasa sakit yang begitu dalam sehingga tidak bisa lagi ditampung oleh narasi resmi. Aksi massa adalah sebuah karya seni kolektif yang mengubah penderitaan menjadi sebuah ekspresi yang kuat dan membebaskan.
Di sisi lain, kekuasaan juga menggunakan budaya untuk mengontrol. Mereka mungkin mengadakan konser musik, acara olahraga, atau festival budaya sebagai “roti dan sirkus” untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang mendesak. Ini adalah sebuah upaya untuk menulis ulang narasi, untuk membuat masyarakat melupakan premis minor dari silogisme mereka. Pertempuran antara demonstran dan penguasa, pada akhirnya, adalah pertempuran antara narasi yang jujur dan narasi yang dibuat-buat.
Kekuasaan dalam Echo Chamber
Kita telah melihat bagaimana demonstrasi adalah perpaduan antara logika, psikologi, dan budaya. Namun, di era digital, pertempuran ini memasuki medan baru yang lebih kompleks dan berbahaya: ruang gema atau echo chamber.
Ruang gema adalah sebuah fenomena di mana kita hanya mendengarkan suara-suara yang mengonfirmasi keyakinan kita sendiri, sementara pandangan yang berlawanan diabaikan, atau bahkan dianggap sebagai musuh. Di sini, narasi kekuasaan mendapatkan ruang yang subur untuk tumbuh. Pemerintah dapat menciptakan “ruang gema” mereka sendiri melalui media sosial yang terkontrol, algoritma yang bias, dan pasukan pendengung (buzzer) yang secara konsisten menyebarkan narasi positif dan membungkam kritik. Kritik, yang seharusnya menjadi premis minor dari silogisme kita, dengan mudah disaring keluar atau dituduh sebagai “hoaks” atau “berita negatif.”
Narasi tandingan yang dibangun oleh demonstran juga dapat terjebak dalam ruang gema mereka sendiri. Para aktivis dan pendukung mereka berbicara satu sama lain di platform yang sama, memvalidasi amarah dan frustrasi mereka, tetapi gagal menjangkau mereka yang berada di luar lingkaran mereka. Logika yang begitu jelas bagi mereka menjadi tidak terdengar oleh telinga yang sudah terbiasa dengan gema narasi kekuasaan.
Di ruang gema ini, demokrasi menjadi sebuah ilusi. Kekuasaan tidak lagi harus menindas secara fisik; mereka hanya perlu mengontrol informasi dan algoritma. Kritik kekuasaan, yang dulunya bergaung di jalanan, kini berisiko hanya menjadi bisikan di antara orang-orang yang sudah sepaham. Tantangan terbesar bagi demonstrasi di era modern bukanlah lagi perlawanan fisik, tetapi perlawanan terhadap fragmentasi narasi.
Maka, ketika kita melihat demonstrasi, kita tidak hanya menyaksikan perjuangan melawan ketidakadilan, tetapi juga perjuangan melawan tembok tak terlihat dari ruang gema. Ini adalah pertempuran untuk membuat suara kritik menembus gema kekuasaan, untuk memastikan bahwa premis minor yang jujur dapat mencapai hati dan pikiran setiap orang, bukan hanya mereka yang sudah sepaham. Dan mungkin, inilah mengapa, di panggung komedi tragis yang disebut demonstrasi, kita tidak boleh berhenti berbicara. Karena di sinilah perjuangan untuk kebenaran yang sesungguhnya berlangsung. Begitulah!
***
*Gus Nas Jogja, Budayawan.