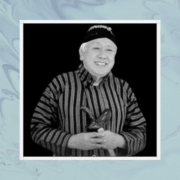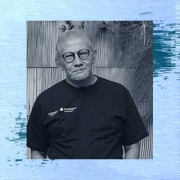Api Revolusi dengan Sumbu Kembar: Dialektika Injustisi dan Pilihan Etis Pergerakan Kaum Muda
Oleh: Gus Nas Jogja*
Abstrak
Esai ini mengeksplorasi kondisi paradoks pergerakan kaum muda dalam menghadapi krisis moral dan institusional: Dilema Sumbu Kembar. Sumbu pertama adalah Kejahatan Institusional, yang bermanifestasi sebagai keserakahan (pleonexia) para penguasa, korupsi, dan banalitas politik, yang meruntuhkan dasar-dasar keadilan dan merampas harapan kolektif. Sumbu kedua adalah Reaksi Destruktif Anarkisme, sebuah manifestasi nihilistik yang, dalam upayanya menolak tirani, justru mengancam sendi-sendi sosial-ekonomi masyarakat dan menciptakan kekacauan yang lebih buruk dari tatanan yang ditentangnya. Melalui lensa Epistemologi, tulisan ini fokus mengkaji kegagalan kognitif dalam mencari Kebenaran (Episteme) dan perannya dalam menciptakan kebobrokan. Sementara itu, Filsafat Moral berfungsi sebagai kompas untuk membedakan perjuangan yang berdasarkan Phronesis (kebijaksanaan praktis) dari amarah yang buta. Esai ini berargumen bahwa jalan pembebasan kaum muda terletak pada sintesis spiritual dan filosofis: sebuah Api Revolusi yang dipandu oleh nalar etis yang teguh, bukan sekadar emosi reaktif.
Senja Kala Nalar dan Keresahan Kolektif
Dalam bentangan sejarah peradaban, kaum muda seringkali menjadi mercusuar yang menyala di tengah kegelapan institusional, suara yang mendobrak keheningan moral. Namun, di era ini, nyala obor idealisme mereka terancam terbelah, digariskan oleh sebuah dilema eksistensial yang membingungkan: Api Revolusi dengan Sumbu Kembar.
Realitas yang mereka hadapi adalah cerminan dari diskursus filsafat abadi tentang keadilan (dikaiosyne) dan kejahatan. Di satu sisi, tegak berdiri struktur kekuasaan yang dipagari oleh Keserakahan dan Korupsi. Ini bukan hanya tentang pencurian materi, melainkan erosi sistematis terhadap nilai dan integritas, yang oleh Hannah Arendt disinyalir sebagai Banalitas Kejahatan — kejahatan yang dilakukan tanpa hasrat jahat, melainkan karena kegagalan berpikir, rutinitas, dan kepatuhan buta terhadap sistem yang bobrok.¹ Sumbu ini, yang bersifat opresif dan dingin, adalah racun yang membunuh nalar etis publik.
Di sisi lain, reaksi terhadap tirani ini seringkali mengambil bentuk yang ekstrem, terwujud sebagai Anarkisme Destruktif. Reaksi ini, yang lahir dari kekecewaan mendalam dan nihilisme politik, berupaya meruntuhkan segala bentuk tatanan, institusi, dan bahkan sendi sosial-ekonomi yang menopang kehidupan bersama. Jika Sumbu Pertama merusak melalui stagnasi dan pengkhianatan, Sumbu Kedua merusak melalui ledakan dan kehancuran.
Maka, pergerakan kaum muda modern berdiri di persimpangan. Untuk bergerak maju, mereka harus mampu mendefinisikan perjuangan mereka melalui kerangka yang kokoh. Tugas ini memerlukan instrumen ganda: Epistemologi untuk menemukan dan menegakkan Kebenaran (Alethéia) di tengah lautan manipulasi, dan Filsafat Moral untuk memilih jalan tindakan yang membebaskan, bukan sekadar membalas. Tanpa fondasi ini, Api Revolusi, alih-alih menyinari, justru akan membakar habis dirinya sendiri dan medan juangnya.
Keserakahan, Korupsi, dan Kekosongan Epistemik
Keserakahan para penguasa bukanlah fenomena baru; ia adalah manifestasi dari pleonexia, hasrat berlebihan untuk memiliki lebih dari yang seharusnya, yang telah dikecam oleh Aristoteles sebagai pelanggaran terhadap keadilan distributif.² Namun, pada era modern, pleonexia ini berkelindan dengan birokrasi, menciptakan korupsi yang terstruktur dan, yang lebih berbahaya, menciptakan Banalitas Kekuasaan.
Banalitas Kejahatan dalam Timbangan Epistemologi
Arendt mengajarkan bahwa kejahatan terbesar mungkin tidak berasal dari iblis, melainkan dari thoughtlessness — ketiadaan pemikiran. Korupsi dan keserakahan institusional bekerja dalam keheningan yang seragam, di mana etika digantikan oleh prosedur dan hukum. Para pelaku, dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan, melakukan kejahatan bukan karena mereka ingin menghancurkan, melainkan karena mereka gagal untuk berpikir secara moral dan mempertanyakan tujuan dari tindakan mereka.
Dalam kerangka Epistemologi, ini adalah kekalahan Kebenaran (Episteme) oleh Opini (Doxa). Para penguasa, hidup di dalam gua Platonik yang penuh bayangan kekuasaan dan fatamorgana kekayaan, telah menganggap bayangan itu sebagai realitas. Kebenaran, yang seharusnya menjadi cahaya yang membimbing negara (sebagaimana dipahami dalam konsep Philosopher King), telah direduksi menjadi alat retorika untuk mempertahankan kekuasaan.
“The trouble with Eichmann was precisely that so many others were like him, and that the many were neither perverted nor sadistic, that they were, and still are, terribly and terrifyingly normal.” ³
— Hannah Arendt
Kutipan Arendt ini menegaskan bahwa bahaya terbesar Sumbu Pertama adalah normalisasi ketidakadilan. Ini adalah krisis epistemik: sebuah negara di mana kebohongan dan korupsi menjadi status quo yang tidak lagi dipertanyakan secara serius, bahkan oleh kaum terpelajar. Kaum muda yang bergerak wajib memahami bahwa pertempuran melawan korupsi adalah, pada hakikatnya, pertempuran untuk mengembalikan validitas Kebenaran dan Integritas Nalar dalam diskursus publik.
Krisis Moralitas Institusional dan Keterasingan
Kegagalan epistemik di atas secara langsung menghasilkan krisis Moralitas. Sumbu Pertama menciptakan sebuah dunia di mana nilai kemanusiaan tergerus di bawah mekanisme pasar dan politik yang dingin.
Filsafat Moral Immanuel Kant memberikan alat yang tajam untuk mengkritik Sumbu Pertama. Kant menegaskan bahwa prinsip moral tertinggi adalah Imperatif Kategoris, yang salah satu formulasinya berbunyi: “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda selalu memperlakukan kemanusiaan, baik dalam diri Anda sendiri maupun dalam diri orang lain, tidak pernah semata-mata sebagai sarana, tetapi selalu pada saat yang sama sebagai tujuan.”⁴
Korupsi dan keserakahan adalah pelanggaran telanjang terhadap imperatif ini. Ketika seorang penguasa mencuri dari kas negara atau mengambil keputusan yang menguntungkan kelompoknya sendiri, mereka secara fundamental memperlakukan rakyat jelata—yang menderita akibat kekurangan fasilitas, pendidikan, atau kesehatan—sebagai sarana untuk memperkaya diri mereka, bukan sebagai tujuan yang memiliki nilai intrinsik dan martabat.
Implikasinya adalah Keterasingan (Entfremdung) ala Hegel dan Marx. Kaum muda merasa asing dari negara mereka, dari pekerjaan mereka, bahkan dari nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemimpin mereka. Keterasingan ini bukan lagi sekadar kondisi ekonomi, melainkan kondisi spiritual dan filosofis. Rasa hilang ini memicu kemarahan, yang menjadi bahan bakar utama bagi Sumbu Kedua.
Sumbu Kedua, Anarkisme Destruktif, muncul sebagai respon histeris terhadap Sumbu Pertama. Ia adalah penolakan mutlak terhadap otoritas yang telah mengkhianati kepercayaan. Namun, di balik seruan pembebasan, tersembunyi jurang nihilisme.
Kehendak untuk Menghancurkan: Kritik Nietzschean
Nietzsche, dengan kritik kerasnya terhadap moralitas budak, mengajarkan kita untuk melihat melampaui motif yang diucapkan. Anarkisme yang destruktif, yang hanya berfokus pada penghancuran tanpa menawarkan visi pembangunan yang koheren dan etis, dapat dilihat sebagai manifestasi dari Nihilisme Pasif—pengakuan bahwa nilai-nilai tertinggi telah kehilangan nilainya, diikuti oleh kehendak untuk menghancurkan sisa-sisa tatanan yang dianggap usang.
Dalam konteks pergerakan kaum muda, anarkisme semacam ini, yang merusak fasilitas publik, menghancurkan properti, atau menolak dialog, telah jatuh ke dalam perangkap filosofis yang sama dengan musuhnya: kegagalan berpikir secara konstruktif. Jika penguasa korup gagal berpikir secara etis, kaum anarkis destruktif gagal berpikir secara sosial-ekonomis. Tindakan mereka, meskipun dipicu oleh amarah yang sah, berpotensi menciptakan kekacauan Hobbesian:
“In such condition there is no place for industry… no knowledge of the face of the earth; no account of time; no arts; no letters; no society; and which is worst of all, continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short.” ⁵
— Thomas Hobbes
Kekacauan yang dihasilkan dari anarkisme murni bukan hanya mengancam kekuasaan, tetapi juga sendi-sendi sosial yang paling rentan: pedagang kecil, pekerja harian, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Ini adalah ironi moral yang tragis: dalam upaya menuntut keadilan, mereka justru menghadirkan ketidakadilan baru bagi sesama yang tertindas.
Sintesis: Episteme, Phronesis, dan Pencerahan Spiritual
Jalan keluar dari dilema Sumbu Kembar ini terletak pada sebuah sintesis filosofis dan spiritual yang mendalam, yang menggabungkan Epistemologi yang jernih dengan Filsafat Moral yang berbasis pada kearifan praktis.
Epistemologi Praktis dan Keadilan Struktural
Pergerakan kaum muda harus memulai dengan Episteme Gerakan. Bukan lagi hanya sekadar protes reaktif, tetapi sebuah gerakan yang memahami secara mendalam struktur kekuasaan (Foucault), mekanisme korupsi, dan implikasi sosial-ekonomi dari setiap tindakan.
Michel Foucault mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada negara, tetapi tersebar di seluruh jaringan masyarakat (Power/Knowledge).⁶ Perjuangan yang efektif harus melampaui sekadar menggulingkan individu atau penguasa, tetapi harus mendekonstruksi sistem pengetahuan dan norma yang memungkinkan Keserakahan dan Banalitas Kekuasaan untuk beroperasi.
Hal ini menuntut kaum muda untuk mengadopsi Nalar Etis Pembedaan. Mereka harus mampu membedakan: mana Revolusi Etis (perubahan fundamental yang bertujuan pada Kebaikan Bersama) dan mana Kudeta Kekerasan (pergantian aktor yang belum tentu menghasilkan perubahan sistem), serta apa itu Nihilisme Destruktif (penghancuran tanpa arah etis) dan apa itu Jalan Tengah: Phronesis dan Spiritualisme Tindakan.
Aristoteles, dalam etika kebajikannya, menawarkan konsep Phronesis atau kebijaksanaan praktis: kemampuan untuk menilai apa yang baik dan buruk dalam situasi tertentu dan memilih tindakan yang sesuai.⁷ Kaum muda perlu mempraktikkan Phronesis ini untuk menavigasi Sumbu Kembar. Perjuangan mereka harus berakar pada:
1. Keutamaan (Arete): Tindakan didasarkan pada keberanian (andreia) untuk melawan, tetapi juga keadilan (dikaiosyne) untuk melindungi tatanan yang adil.
2. Aksi Non-Destruktif: Menolak Anarkisme destruktif dan memilih bentuk perlawanan yang secara moral lebih tinggi –seperti disobedien sipil ala Thoreau atau Satyagraha ala Gandhi, yang meruntuhkan legitimasi tirani tanpa meruntuhkan fondasi masyarakat.
Narasi spiritual masuk di sini. Revolusi yang sejati bukanlah pertumpahan darah, melainkan Revolusi Jiwa—mengembalikan fitrah _(kemurnian spiritual) dari nalar publik dan kepemimpinan. Ini adalah panggilan untuk istiqamah (keteguhan) dalam menegakkan nilai, bahkan ketika hasilnya tampak jauh. Pergerakan yang berlandaskan spiritualitas (yang dipahami sebagai komitmen mendalam terhadap Martabat Manusia dan Keadilan Universal) akan menemukan kekuatan untuk menolak baik godaan kekuasaan yang korup maupun rayuan nihilisme yang menghancurkan.
“Be the change that you wish to see in the world.”⁸
— Mahatma Gandhi
Mengendalikan dan Menjaga Nyala Api Revolusi
Dilema Sumbu Kembar adalah ujian spiritual dan intelektual bagi pergerakan kaum muda. Mereka berdiri di antara api dingin Keserakahan Institusional dan api panas Anarkisme Destruktif. Kedua sumbu tersebut, meskipun saling bertentangan, memiliki potensi yang sama-sama mematikan bagi pembangunan peradaban yang berkeadilan.
Penyelesaian dilema ini menuntut kaum muda untuk melangkah ke Jalan Tengah (Mésotēs) yang dimaknai secara epistemik dan moral. Mereka harus menjadi penjaga Kebenaran, menggunakan nalar dan data untuk membongkar banalitas korupsi, dan pada saat yang sama, menjadi pelaksana Moralitas, menolak godaan kekerasan yang akan mengubah mereka menjadi cerminan dari kegilaan yang mereka lawan.
Api Revolusi yang sejati harus memiliki Sumbu Etis Tunggal: perjuangan yang didasarkan pada Phronesis, di mana setiap tindakan adalah manifestasi dari Imperatif Kategoris. Hanya dengan demikian, kaum muda dapat memastikan bahwa energi transformatif mereka tidak hanya menghasilkan perubahan aktor, tetapi juga transformasi struktural dan spiritual menuju tatanan sosial-ekonomi yang adil, di mana martabat manusia dan kebenaran ditegakkan sebagai nilai tertinggi. Inilah panggilan spiritual dan filosofis mereka: untuk menenun kembali permadani sosial-ekonomi yang robek dengan benang keadilan, kebijaksanaan, dan cinta kasih yang teguh.
Begitulah!
***
Catatan Kaki
¹ Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New York: Penguin Classics, 2006), hal. 287.
² Aristoteles, Nicomachean Ethics, V.2, membahas keadilan distributif dan pleonexia sebagai lawan dari keseimbangan moral.
³ Arendt, Eichmann in Jerusalem, op. cit., hal. 289.
⁴ Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals, ed. dan terjemahan. oleh Mary Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 4:429.
⁵ Thomas Hobbes, Leviathan, ed. C. B. Macpherson (Harmondsworth: Penguin Books, 1968), Bab XIII, hal. 186. Kutipan ini merujuk pada keadaan alamiah (state of nature) yang dihindari oleh tatanan sosial.
⁶ Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), terutama bab tentang Disciplinary Power.
⁷ Aristoteles, Nicomachean Ethics, VI.5, mendefinisikan phronesis sebagai kebajikan intelektual yang esensial untuk tindakan etis.
⁸ Kutipan populer yang dikaitkan dengan Gandhi, merefleksikan prinsip Satyagraha (kekuatan kebenaran) dan pentingnya integritas diri sebagai prasyarat untuk perubahan sosial.
Daftar Pustaka
Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Penguin Classics, 2006.
Aristoteles. Nicomachean Ethics. Diterjemahkan oleh W. D. Ross. Diedit oleh Lesley Brown. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. Diedit oleh Colin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
Hobbes, Thomas. Leviathan. Diedit oleh C. B. Macpherson. Harmondsworth: Penguin Books, 1968.
Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Diterjemahkan oleh Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Nietzsche, Friedrich. On the Genealogy of Morality. Diterjemahkan oleh Maudemarie Clark dan Alan J. Swensen. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1998.
—
*Gus Nas Jogja, Budayawan.