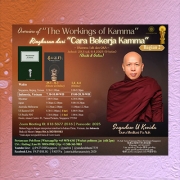Yang Melintas Batas
Oleh: Halim HD.- Networker-Organizer Kebudayaan
Seorang rekan lama yang bergerak pada bidang manajemen pertunjukan dan festival atau lebih tepatnya forum, yang telah lama berkecimpung di mancanegara selama belasan tahun, setelah beberapa tahun kerja serabutan sebagai penerjemah dan “guide” nampaknya menikmati profesinya di negeri lain yang dianggapnya bisa menyalurkan gagasannya dalam praktek profesi, bahkan dia menyatakan, eksistensiku sebagai manusia hadir bersama berbagai festival dan proses kerja kolaborasi tanpa beban birokrasi yang berbelit, tulisnya pada suatu kiriman imel. Jika kita mendengar tentang festival jangan anda bayangkan rekan saya ini mengelola festival-festival besar yang selalu dibayangkan oleh kebanyakan pelaku kesenian di Indonesia. Dia melakukan pekerjaannya bersama komunitas-komunitas kecil di berbagai perkotaan dan wilayah sub-urban dalam proyek yang dia sebut sebagai laboratorium dan rehearsal festival. Seperti yang kamu lakukan, Mas, katanya dalam percakapan via WA, bahkan saya memasuki ruang-ruang sebagai fasilitator manajerial, disamping sebagai rekan diskusi dalam kaitannya dengan tematik estetika-artistik dalam perspektif kesejarahan lingkungan, ekologi dan, tentu saja pendekatan biografis yang menjadi salah satu titik poin. Karena saya berangkat dari pendekatan personal kearah praktek jaringan sosial.
Saya bisa memahami jika dia mampu dan bisa memasuki berbagai negeri dan bangsa lain sejak belasan tahun, ketika dia memutuskan untuk mencari pengalaman dengan magang kepada berbagai grup kesenian di Australia, lalu di beberapa negeri di Asia Tenggara, dan lalu loncat ke Eropa. Pada tahun 1990-an Ketika dia masih mahasiswa jurusan Bahasa Inggris yang hanya diikutinya selama setahun, lalu pindah ke jurusan Perancis selama dua tahun, dan loncat ke fakultas Ekonomi, yang juga ditinggalkannya, dan masuk ke dalam jurusan Sejarah serta belajar Antropologi. Nampaknya dalam lima-enam tahun dia hanya menjadi pelaku pencari ilmu yang tanpa beban untuk mendapatkan ijazah. Saya kurang tahu, ketika awal mengenalnya, dari mana dia mendapatkan biaya hidup. Keluarganya memang lumayan berada, dan yang menarik membiarkan dia untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Sebagai anak bungsu dari tiga anak, dua saudaranya, kakak perempuan dan laki-laki meneruskan usaha orangtuanya, sebagai pengusaha agen bahan bangunan dan peralatan pertanian. Kedua kakaknya lulusan fakultas Hukum dan Hubungan Internasional, yang hanya menyimpan ijazah dalam berkas.
Aku cari uang dari menerjemahkan yang hasilnya nggak seberapa, Mas, tapi menarik karena bisa sambil belajar berpikir, katanya suatu hari. Yang lumayan honornya jadi “guide”, sambil memperlancar bahasa dan juga mengetahui latar belakang kultur orang-orang itu. Dia memang bisa berbahasa Inggris, Perancis, dan juga sedikit Bahasa Jerman pada waktu awal saya mengenalnya, bahkan juga bahasa Spanyol walaupun ala kadarnya seperti juga bahasa Jepang. Kemampuan bahasanya itulah yang membuat saya tertarik, ketika dalam suatu diskusi buku dia komentar soal kekeliruan terjemahan berkaitan dengan pemaknaan “discourse” sebagai “wacana”. Menurutnya, “wacana” itu suatu pernyataan mengandung kepastian, sedangkan “discourse” justru sebaliknya, proses berpikir yang menyatakan pernyataan gugatan.
Perkenalan yang dilanjutkan dengan beberapa pertemuan dalam diskusi buku dan kesenian, walaupun dalam diskusi dia cenderung hanya mendengarkan, dan hanya mencatat. Hanya sesekali dia komen jika ada sesuatu yang nampaknya dirasa kurang pas berkaitan dengan cita rasa bahasa. Karena dia memiliki cita rasa bahasa yang baik itulah saya mengajak, atau tepatnya meminta bantuan dia untuk terlibat dalam suatu festival di Solo dan Surabaya, sambil saya katakan, saya tak punya honor untuk kamu. Dia cuma menjawab dengan ketawa ngakak, dan mengiyakan ajakan saya. Pada beberapa festival di Solo dan Surabaya dia tak tercantum sebagai salah seorang panitia, dan dia tak peduli dengan soal itu, hanya bertanya, apa tugasnya. Saya libatkan dia ke dalam festival untuk menemani beberapa seniman dari beberapa negeri lain dan nampaknya dia menikmati. Dalam suatu obrolan sambil ngebir dia bilang menarik kongko dengan kaum seniman, yang berbeda dengan kebanyakan orang manca secara umum ketika dia menjadi “guide”. Karena menjadi “guide” juga suatu malam tiba tiba dia nongol di Makassar, dan kami kongko sampai larut malam, besoknya dia mengantarkan rombongan ke Toraja. Waktu itu saya sedang menyiapkan Makassar Dance Festival (MDF-97) 1997.
Kenapa dia tak mau disebut sebagai “professional guide”, walaupun dengan kemampuan dan cita rasa yang bagus itu? Ini bukan pilihan utama, katanya, ketika saya bertanya. Lalu pilihan utamanya apa? Nantilah katanya, lagi lagi dia ngakak sambil menyemburkan asap rokok filter kretek. Apakah jika menjadi “guide” itu terasa tak memiliki suatu kebanggaan? Dia menolak itu. Walaupun saya cari uang sebagai “guide”, saya menganggap “kerja” ini sebagai kegembiraan saya dalam belajar bahasa, yang terus berlanjut dan bisa menghidupi saya, dan saya bisa ikut terlibat ke dalam berbagai kegiatan lain yang tak menuntut mendapatkan bayaran.
Karena itulah juga nampaknya dia bisa melintasi batas-batas negeri lain dan memasuki negeri lainnya melalui jenis pekerjaan yang sangat menggembirakan, dan disitu pula ketika dia mendapatkan bekal cukup masuk ke dalam pilihan sebagai manajer kegiatan kesenian. Tapi sesungguhnya dia juga bukan sekedar manajer. Tepatnya organizer sosial pada fokus kesenian melalui lontaran gagasan yang dia organisir dalam berbagai pertemuan yang dianggapnya sebagai laboratorium gagasan. Awal ketertarikan dirinya kepada hal itu, ketika suatu hari pada tahun 1990-an dia tertarik dengan tawaran yang saya sodorkan untuk ke Filipina, Muangthai dan Bangladesh dalam acara lokakarya organizer kebudayaan selama tiga bulan berkeliling ketiga negeri itu. Dia berminat walaupun lokakarya itu tanpa honor, hanya ada tiket, akomodasi dan konsumsi sederhana.
Sejak lokakarya itulah dia membangun jejaring relasi personal di antara organizer dan seniman dari berbagai negeri di Asia Tenggara, Australia dan berlanjut ke Eropa, dan bertemu jodoh di Perancis walaupun setelah beberapa tahun akhirnya mereka berpisah. Seperti Ketika dia menjadi “guide” yang tak disebutnya sebagai profesi, demikian juga ketika dia menerjemahkan buku dan tulisan, namanya tak pernah disebutkan seperti yang tertulis di KTP-nya. Anonim, itulah yang dilakukannya, seperti laboratorium gagasannya yang terus bergerak, tak pernah menetap pada suatu kota-daerah dan juga tak bertajuk. Dia membiarkan apa yang dikerjakannya dengan gonta ganti rekan kolaboratif tanpa label apapun. Stempel atau cap dan pelabelan itu cenderung claiming, pendakuan, Mas, katanya. Saya ingin masuk ke dalam suatu sistem kerja yang siapapun tak bisa mendaku miliknya. Tapi hal itu bisa hilang begitu saja, respon saya kepada pernyataannya yang terasa mengesankan archaic, seperti suatu masyarakat lampau. Bisa hilang secara teknis administratif, katanya, tapi secara substansial memori sosial itu tetap mengendap dan akan menyebar, tanpa suatu distribusi informasi, tapi melalui DNA sosial di mana benih itu bisa berwujud sebagai keringat, ingatan dan percakapan yang mungkin tanpa harus menjadi referensi formal.
Pernyataannya terasa radikal bagi pelaku kesenian dan kaum manajer festival yang punya kecenderungan dan kesadaran hak cipta dan ambisi sebagai pelaku sejarah. Sejarah itu nggak harus dinyatakan sebagai tulisan! Dan kita juga, ini penting dan sangat penting, kita nggak bisa mendaku bahwa apa yang kita kerjakan bermakna sejarawi. Itu arogansi! Mendengarkan pernyataannya rasanya saya diajak ke awang-awang masa lampau yang melayang layang seperti dalam dongeng. Tapi saya pikir, apa yang dinyatakannya dan wujud kegiatannya yang menyebar, menarik juga untuk bahan permenungan kita sebagai manusia moderen yang bersibuk dengan pendakuan menciptakan sejarah dan glorifikasi sejarah diolah menjadi mitos-mitos, mistifikasi, dan sebagai pemilik hak cipta yang ada kaitannya dengan sirkulasi kapital.
Yang menyenangkan bagi saya jika kongko dengan dia, kami masing-masing tak memiliki beban untuk bersilang saling sengkarut. Saya mencoba memahami percikan pemikirannya yang sering segar di antara keriuhan yang cenderung kumuh dalam kehidupan seni kontemporer dan bahkan di dalam tradisi sekalipun yang begitu banyak melakukan pendakuan atas nama masa lampau demi bersaing dengan zaman yang terus berubah. Salah satu masalah mendasar dalam dunia tradisi di manapun, khususnya di negeri kita, katanya bersibuk dengan pendakuan dan meminta pengakuan, sementara proses kerjanya kian menjauh dari makna masa lampau yang pernah menjadi inspiratif. Bagi saya, katanya, itu manipulatif propaganda yang berhimpitan dengan masalah politik ekonomi, dan diujung akhirnya hal itu justru digerakan bukan oleh diri tradisi sendiri tapi oleh akumulasi kapital yang kian kuat akarnya dalam cara berpikir kita. Bukankah dunia kontemporer yang demikan menarik dan inspiratif pada akar sejarahnya telah dibekuk oleh pendakuan sepihak yang satu dengan lainnya sesungguhnya saling meniadakan demi politik ekonomi? Kenapa kompetisi menjadi akar masalah, dan kenapa pula kaum seniman justru bergairah memasuki ruang kompetitif yang sesungguhnya ruang itu bukan miliknya, dan dirinya sekedar tamu undangan yang batas waktunya ditentukan oleh sirkulasi kapital yang mengatasnamakan pembaharuan kebudayaan dan kesenian? Dunia moderen menciptakan sejenis perbudakan yang canggih yang bahkan mereka yang diperbudak tak merasakan sebagai budak.
Nafas saya tersengal, dan saya mencoba mengatur dengan tarikan perlahan bersama isapan kretek. Kedipan-kedipan mata saya nampaknya dibaca sebagai keraguan saya terhadap pernyataannya. Anda juga pernah menyatakan itu kan, tudingnya. Saya hanya bisa meringis, mencoba menggapai ingatan-ingatan dari masa lalu. Tapi daya ingat saya yang kian rapuh karena dipenuhi oleh sikon politik Mutahir di Indonesia membuat saya hanya bisa mencoba meraba melalui elusan jari tangan di kepala. Mungkin saya sedang berpikir, tapi mungkin juga saya sedang berusaha mengasihani diri, mencari apologi dan berusaha berkilah bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain, jalan lain yang bisa dipilih. Tentu saja, katanya, mosook nggak ada pilihan, dan justru lebih banyak pilihan jika tanpa pertaruhan dan pertarungan pendakuan. Apakah anda menganggap bahwa pendakuan (claiming) demokratisasi itu menciptakan banyak pilihan? Tak ada satupun di dalam sejarah ada grand design demokratisasi dengan latar belakang ideologi apapun yang bisa memberikan banyak pilihan. Grand design itu tak datang dari ke kedalaman bumi yang kita pijak dan bukan lahir dari aliran air yang telah dicemari oleh kerusakan ekosistem kita. Juga tak datang dari akar pepohonan yang bertumbangan dampak urbanisasi dan pertambangan atas nama pilihan. Justru grand design itulah yang membatasi pilihan kita, dan pilihan kita membentuk validitasi, pengesahan dan legitimasi suatu kekuasaan yang melihat mulut-mulut menganga membutuhkan asupan dan bahkan jejalan. Sesungguhnyalah manusia moderen itu hewan yang melahap bukan atas nama dirinya, tapi atas nama suatu produk.
Saya merasa didesak untuk meminggirkan diri dari deretan barisan tapi saya ragu karena pikiran masih melayang-layang ke dalam ruang berbagai kemungkinan, mencari celah untuk bisa menerobos, tapi adakah saya masih memiliki daya untuk menyempal bukan hanya dari barisan dan deret hitung populasi demokratisasi, tapi juga dari tawaran yang kian melesak ke dalam cerebral cortex, berdenyar seperti getaran dari gema lengking yang terus mendenging…… Gendang telinga saya memang rusak sejak belasan tahun yang lalu, ketika saya tenggelam di laut dekat pulau Passitalu dan Latondu di Sulawesi Selatan pada waktu saya mengikuti grup Sandiwara Petta Puang pada tahun 2001 berkeliling di Taka Boneratte, dan jauh sebelumnya saya tenggelam di dalam arus Sungai Cibanten di belakang rumah Pakde-Bude saya di Gang Rendah, Serang, Banten, ketika saya masih duduk di Sekolah Rakyat pada zaman Bung Karno. Adakah denging itu karena gendang telinga yang rusak ataukah isyarat lain…..Urip tan kena kinira.
Sudah lama saya tak mendengar kabar beritanya. Tahun yang lalu saya dengar dia kena sejenis kanker prostat.
—
Studio Plesungan, Plesungan, Karanganyar 17 Maret 2024