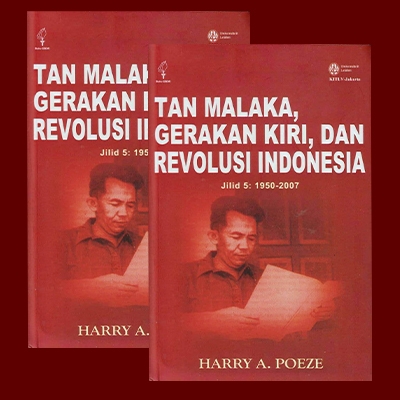Sastra, Memori, dan Wabah Pandemi
Oleh Djoko Saryono
/1/
Ada bermacam wujud rangsang-rangsang kreatif dan imajinatif bagi pengarang ketika mencipta karya sastra. Peristiwa dan pengalaman merupakan dua di antaranya. Selain gagasan tertentu, pertistiwa dan pengalaman insani tertentu banyak memantik imajinasi dan kreativitas pengarang. Tak heran, Umar Junus, salah seorang kritikus terkemuka, dalam buku Dari Peristiwa ke Imajinasi merumuskan adagium sastra bertolak dari peristiwa ke imajinasi. Demikian juga sudah banyak pihak – baik ahli maupun pengarang – bersaksi bahwa sastra bermula dari pengalaman menuju imajinasi. Imajinasi bersumber peristiwa dan atau pengalaman itu kemudian melahirkan kreativitas sastra baik sajak maupun fiksi.
Dalam rentangan formula dari peristiwa dan pengalaman ke imajinasi dan kemudian kreativitas sastra tersebut pengarang menghasilkan corak karya sastra tertentu. Pada satu ujung, ada corak karya sastra yang “terang-terangan” bersumbu pada peristiwa nyata atau pengalaman. Dahulu ada fiksi bercorak “tjeritera betoel soeda kedjadian”, sekarang marak fiksi bercorak “based on true story”, “berdasarkan kisah nyata”, dan “tuturan naratif”. Pada ujung lain, ada corak karya sastra yang “tegas mengelak” bersandarkan peristiwa nyata atau pengalaman. Karya sastra jenis ini umum dilabeli “…cerita ini fiktif belaka….” meskipun pembaca “meraba dan merasakan” ada peristiwa nyata yang menjadi rangsang kreatif.
Tanpa diberi label atau maklumat tersurat, di antara dua ujung tersebut tentu saja ada corak karya sastra yang dimaklumkan mendulang peristiwa nyata dan atau pengalaman. Dengan proses kontemplasi dan sublimasi, peristiwa nyata atau pengalaman disaring dan disuling sedemikian rupa oleh pengarang, kemudian diramu dengan imajinasi, dan selanjutnya distrukturasi (distrukturkan) dengan peranti-peranti sastra agar mengejawantah menjadi bentuk sastra tertentu, boleh jadi sajak dan mungkin juga fiksi. Kendati pun begitu halus dan lembut saringan dan sulingan yang dilakukan pengarang, getaran-getaran atau sinyal-sinyal kuat peristiwa nyata atau pengalaman dalam karya sastra tetap tertangkap oleh radar pembaca.
Banyak karya sastra tak lekang zaman, terkenang masa atau masyhur diciptakan “berbahan peristiwa nyata atau pengalaman” yang sudah disaring dan disuling dengan sangat halus dan lembut, bukan makin hilang dan tak teraba peristiwa atau pengalaman itu, malah makin gamblang dan terang. Novel gemilang Gulag diciptakan oleh Solzhenytsin dengan bersumberkan peristiwa dan pengalaman kekejaman dan penindasan Perang Dunia II. Novel-novel Elie Weisel, misalnya Malam, diciptakan bersumberkan peristiwa nyata dan pengalaman kekejaman Nazi dan Holocoust. Novel La Peste (Sampar) ditulis Camus dengan mendulang peristiwa wabah pandemi sampar di Aljazair dan pengalaman hidup di bawah Nazi. Novel Max Havelaar diciptakan oleh Multatuli bersumberkan peristiwa dan pengalaman tentang ketakadilan dan diskriminasi multidimensial kolonial Belanda dalam kapitalisme perkebunan dan perdagangan kopi. Demikian juga tetralogi Bumi Manusia karya Pram diciptakan berdasarkan peristiwa dan pengalaman nyata selama revolusi Indonesia.
Bukan hanya menjadi aksesori atau dekorasi, peristiwa nyata atau pengalaman di dalam teks sastra malah sering tampak sebagai dokumentasi, memori atau malah testimoni – maknawi dan bukan material – atas peristiwa nyata dan atau pengalaman tertentu. Di sini sastra terutama fiksi menjadi ruang dokumentasi, memori atau testimoni, tak sekadar rekaman mentah kejadian atau pengalaman. Babad Bedhah ing Ngayogyakarta karya Pangeran Aryo Panular condong menjadi dekorasi dan dokumentasi wabah pandemi kolera; demikian pula Killing Fields (Ladang Pembantaian) karya Haing S Ngor tampak kuat menjadi dokumentasi kekejaman, malah kebrutalan rezim Komunis Vietnam. Karya-karya Kazuo Ishiguro, misalnya Never Let Me Go dan The Buried Giant tampak menjadi memori pengalaman traumis pengarang. Sebagian karya besar novel Nh Dini dapat dikatakan sebagai memori atau testimoni pengalaman personal pengarang. Demikianlah, teks sastra memang lazim menjadi medium dokumentasi, memori, dan testimoni tentang peristiwa nyata atau pengalaman tertentu.
Sensibilitas, sensitivitas, dan reponsivitas pengarang memegang peranan penting dalam menentukan peristiwa nyata atau pengalaman apakah yang diangkat dan dituangkan ke dalam karya sastra mereka. Dengan kata lain, peristiwa dan atau pengalaman insan yang terpantul atau tergambar dalam karya sastra – baik sajak, lakon maupun fiksi – sangat bergantung pada kadar sensibilitas, sensitivitas, dan responsivitas pengarang. Bisa terjadi peristiwa sederhana atau pengalaman kecil personal-subjektif ditangkap dan dituangkan oleh pengarang ke dalam karya sastra, tetapi malah peristiwa kompleks atau pengalaman besar sosial-kolektif tidak tertuang di dalam karya sastra karena pengarang luput menangkapnya. Sebagai contoh, peristiwa besar-kompleks dan pengalaman traumatis “Petrus (Penembakan Misterius)” tak banyak hadir dan tak kental hadir dalam fiksi Indonesia selama masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru fiksi populer Indonesia banyak menghadirkan kemanjaan kaum muda kota (kelas menengah kota yang baru tumbuh). Jadi, teks sastra bisa tidak mempresensikan (menghadirkan), malah bisa mengabsenkan suatu peristiwa nyata atau pengalaman insani. Semua itu sedikit banyak ditentukan oleh sensibilitas, sensitivitas, dan responsivitas para pengarang.
/2/
Salah satu peristiwa nyata atau pengalaman insani yang penting yang acap ditangkap dan dituangkan (baca: distrukturasi) ke dalam karya sastra adalah wabah epidemi dan atau pandemi suatu penyakit yang disebabkan oleh penyebab tertentu bukan-manusia (non-human). Para pengarang terbukti memiliki cukup sensibilitas, sensitivitas, dan responsivitas terhadap wabah epidemi dan atau pandemi suatu penyakit menular; mereka menjadikan wabah penyakit menular sebagai “bahan utama atau bahan pelengkap” dan pokok persoalan suatu teks sastra. Dalam sepanjang sejarah sastra baik dalam bentuk sajak, lakon maupun fiksi kita dapat menemukan karya sastra tertentu “mengangkat dan menuangkan” wabah pandemi penyakit menular sebagai pokok persoalan dan unsur karya sastra.
Bila kita tengok ke belakang, sastra klasik Yunani dari masa Sebelum Masehi sudah mengangkat dan menuangkan persoalan wabah pandemi penyakit. Meskipun berjalin-kelindan dengan pokok persoalan lain, antara lain persoalan permusuhan dan perang Troya dengan Yunani, kita dapat menemukan pokok persoalan wabah pandemi dalam karya puncak Yunani berjudul Iliad karya Homer (Abad VI SM), sebagaimana diuraikan oleh Chelsea Haith dalam Pandemics from Homer to Stephen King: What We Can Learn from Literary History (Maret 2020). Menurut Chelsea, Iliad yang berkisah tentang babak akhir Perang Troya. Dalam khazanah sastra klasik Yunani, kita juga mendapati gambaran bencana wabah epidemi yang mengerikan di negeri Thebes dalam naskah lakon Oedipus Sang Raja (Oedipus Rex) karya dramawan terkemuka Sopochles (Abad V SM). Walaupun berjalin-kelindan dengan persoalan kekuasaan dan filsafat manusia, dalam Oedipus Sang Raja kita melihat persoalan wabah pandemi penyakit di Thebes – yang dibawa oleh makhluk Sphinx dan kemudian disebabkan oleh murka dewa – memegang peranan penting dalam menggerakkan lakon. Bahkan lakon Oedipus di Colonus dan Oedipus Berpulang (sebagai bagian trilogi Oedipus Sang Raja) menghadirkan ekses atau dampak lanjutan wabah pandemi penyakit yang sudah terbeber dalam Oedipus Sang Raja.
Wabah pandemi penyakit juga menjadi pokok persoalan sastra Eropa Kontinental pada masa-sama sesudah Masehi. Berbagai negara yang dapat dikatakan sudah sejak lama menjadi pusat perkembangan budaya dan sastra, di antaranya Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, dan Jerman, juga melahirkan pengarang yang mengangkat dan menuangkan peristiwa atau pengalaman wabah pandemi penyakit dalam karya mereka. Lazimnya orang menyebut fiksi Decameron (1353) karya Giovanni Boccaccio, A Journal of the Plague Year (1722) karya Daniel Defoe, The Last Man (1826) karya Mary Shelley, dan The Masque of the Read Death (1842) karya Edgar Allan Poe sebagai contoh karya sastra Eropa yang dengan kental dan gamblang mengisahberitakan wabah pandemi penyakit menular yang telah menimbulkan kepanikan moral, sosial, ekonomi, dan politik. Seperti diuraikan dalam berbagai kajian, berbagai karya Shakespeare juga sering dijadikan contoh fiksi yang mengangkat pokok persoalan wabah penyakit menular.
Fiksi kontemporer (Eropa dan Amerika) yang sering dijadikan contoh sastra yang mengisahberitakan pokok persoalan wabah penyakit menular adalah Sampar (La Peste) (1947) karya puncak Albert Camus, The Andromeda Strain (1969) karya Michael Crichton, The Stand (1978) karya Sthephen King, The Hot Zone (1994) karya Richard Preston, Blindness (1995) dan The Pesthouse (2007) karya Jim Grace. Novel Love in the Time of Cholera (1985) karya Garcia Marquez sering disinggung pula meskipun penggambaran atau pengisahberitaan wabah penyakit menularnya tak sekental dan sebanyak Sampar. Di luar itu, ada novel ada novel Nemesis (2010) karya Philip Roth yang berkisah tentang epidemi polio yang merenggut nyawa anak-anak. Juga ada novel The Old Drifft (2019) kaerya Namwalli Serpell (Zambia) yang berkisah bencana epidemi HIV/AIDS. Berbagai karya sastra tersebut tentu saja mengisahberitakan jenis wabah epi-/pan-demi berbeda-beda dengan teknik-teknik kesastraan berbeda pula. Inilah wujud sensibilitas, sensitivitas, dan responsivitas sastra terhadap peristiwa atau pengalaman insani.
Dalam batas-batas tertentu, sastra (di) Indonesia pun memiliki sensibilitas, sensivitas, dan responsivitas terhadap wabah epi-/pan-demi penyakit menular. Cerita rakyat Jawa dan Bali berjudul Calon Arang yang kemudian diangkat oleh berbagai pengarang ke dalam fiksi dan puisi panjang, misalnya novela Calon Arang karya Pram, puisi panjang Calon Arang karya Toety Heraty, dan Janda dari Dirah karya Cok Sawitri, berkisah tentang wabah epidemi penyakit yang menelan banyak korban nyawa warga Kerajaan Daha. Di samping itu, dalam Babad Bedhah ing Ngayogyokarta (100 pupuh berbentuk tembang) karya Bendoro Pangeran Aryo Panular mencatat wabah pandemi penyakit kolera pada sepanjang tahun 1821 di Jawa (terutama Jawa Tengah) yang membuat setidak-tidaknya 125 ribu orang terenggut nyawanya (setara 7 persen penduduk Jawa wafat akibat keganasan Cholera Asiatica yang dibawa pelaut dari Pulau Pinang dan Melaka ke Semarang). Konon, di Surakarta tiap hari 70 orang terenggut hidupnya sehingga muncul frasa “isuk urip sore mati”. Wabah pandemi kolera ini – diungkapkan dalam Babad Bedhah – konon juga menimbulkan kekalutan moral, sosial, politik, dan ekonomi yang berjalin-kelindan; elite sosial politik juga kalut ikut-ikut berebut uang, “kesesa rebut picis”.
Sastra Indonesia kontemporer juga mengandung sensibilitas dan sensitivitas terhadap wabah epi-/pan-demi penyakit yang disebabkan oleh penyebab tertentu. Sekalipun bukan peristiwa kontemporer dan terjadi pada masa kini, melainkan jauh di tempat lain pada masa lampau yang sangat jauh, puisi Sodom dan Gommora karya Subagio Sastrowardoyo, Balada Nabi Luth AS karya Taufiq Ismail, dan Apakah Kristus Pernah? Karya Darmanto Jatman merefleksikan wabah penyakit luar biasa yang menimpa umat Nabi Luth AS akibat kepanikan moral-etis dan sosial-kultural. Cerpen Malam Wabah karya Sapardi Djoko Damono, Lampor karya Joni Ariadinata, dan Wabah karya Jujur Prananto juga menggelar kisah tentang wabah penyakit yang menimpa masyarakat Jawa di permukiman. Novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dibuka oleh keadaan dan suasana hancur lebur masyarakat Dukuh Paruk yang pelahan bangkit setelah sekian lama hancur akibat pagebluk yang di luar nalar mereka. Dalam batas-batas tertentu novel Aruna dan Lidahnya karya Laksmi Pamuntjak mencatat dan mengisahkan kilasan-kilasan wabah flu unggas. Contoh-contoh tersebut menandakan bahwa para pengarang Indonesia juga memiliki sensibilitas, sensitivitas, dan responsivitas terhadap pagebluk penyakit menular pada satu sisi dan pada sisi lain mereka menuangkan (mengimajinasi dan menstrukturasi) ke dalam karya sastra mereka.
/3/
Bisa dikatakan, sekarang seluruh dunia sedang dihempas-kandas gelombang badai wabah pandemi virus korona baru yang mendatangkan penyakit virus korona baru (yang disingkat COVID-19 – COronaVIrus Disease 2019). Semua orang, masyarakat, pemerintahan, wilayah, dan atau negara merasakan kecepatan dan keluasan hempasan COVID-19 sehingga mengalami kepanikan moral, sosial, ekonomi, dan politik akibat tidak siap, kurang siaga, dan kurang daya sangka. Semua kalangan tidak ada yang benar-benar siap dan siaga mengantisipasi, menanggulangi, dan mencegah pandemi COVID-19 yang memiliki daya biak dan daya tular cepat sekali. Tidak tersedia sistem manajemen krisis kesehatan dan sistem migitasi bencana yang siap digunakan untuk menanggulangi dan mencegah secara efektif wabah pandemi penyakit menular COVID-19. Di samping itu, juga tidak tersedia sistem pengetahuan siap pakai untuk mengatasi COVID-19 karena sebagai penyakit baru deskripsi tentangnya masih minim, alam proses, dan terus berubah. Secara global semuanya – baik individu, institusi, komunitas, maupun negara – terdampak COVID-19 beserta segala ikutannya. Tak heran, ketakutan, kecemasan, dan kesilangsengkarutan yang masif dan internsif terjadi di mana-mana dan di kalangan siapa saja. Paradoks, kontradiksi, dan ambiguitas merebak dan marak dalam pikiran, langkah, dan tindakan individu. Bisa dimengerti kalau Slavoj Zizek kemudian menulis buku Pan(dem)ic! COVID-19 Shakes The World (Maret 2020, New York: O/R Books) – seluruh dunia sedang tergulung-guncang COVID-19.
Selain berbagai negara, institusi, korporasi, dan komunitas, individu dan kelompok masyarakat sudah pasti tidak tinggal diam. Semua tidak mau menyerah begitu saja, “lempar handuk begitu saja” berhadapan dengan jazad renik mikroba bernama virus korona baru. Sesuai kapasitas, otoritas, kemampuan, kesempatan, dan kesempatan masing-masing, mereka berupaya, berbuat, dan bertindak untuk melakukan sesuatu guna mendukung penanangan, penanggulangan, dan pencegahan pandemi COVID-19. Kalangan pemerintahan, kalangan bisnis dan perusahaan, kalangan profesi, kalangan pekerja, kalangan masyarakat awam, kalangan komunitas, dan lain-lain bahu-membahu (kadang bersinggungan, kadang bertabrakan akibat kekalangkabutan) melaksanakan berbagai kegiatan untuk menanggulangi dan mencegah COVID-19 beserta dampak ikutnya; baik kegiatan preventif maupun kuratif, bahkan antisipatif.
Kalangan kesenian (baca: pekerja seni atau seniman) merupakan salah satu kalangan yang ikut terdampak gempuran badai dahsyat COVID-19 yang dengan sekuat daya dan upaya disertai semangat kuat melakukan kegiatan baik kegiatan berkenaan dengan penanggulangan COVID-19 (boleh dibaca: kegiatan kerelewanan dan filantropi) maupun kegiatan kesenian (boleh dibaca: kegiatan profesional) di tengah gempuran cepat pandemi COVID-19. Di tengah bayangan-bayangan (di-/me-)seram(-kan) wabah pandemi COVID-19 yang merambat melalui media sosial dan media digital/elektronis, sensibilitas, sensitivitas, dan bahkan responsivitas kalangan kesenian atau pekerja seni diejawantahkan ke dalam karya seni mereka dengan berbagai modus dan medium yang mungkin. Perupa, penari, pemusik/pencipta musik/penyanyi, sastrawan, dan lain-lain berusaha berkarya di bidang masing-masing secara kontekstual. Di tengah himpitan situasi batas dalam pengertian Karl Jaspers (sok gaya saja!), mereka merespons berbagai peristiwa dan atau pengalaman berada di dalam dan berhadapan dengan wabah pandemi COVID-19 di dalam karya seni mereka masing-masing. Sekadar catatan tambahan, Jaspers (sang filsuf eksistensi – bukan eksistensialis – dari Jerman itu) berkata bahwa manusia selalu berada di dalam situasi batas umum dan khusus – situasi batas umum berupa faktisitas dan nasib dan situasi batas khusus berupa kematian, penderitaan, perjuangan, dan kesalahan. Jadi, di dalam berbagai situasi batas yang tersedia di tengah kepungan fakta-fakta dan tafsir-tafsir/imaji-imaji wabah pandemi COVID-19, masing-masing pekerja seni atau seniman menciptakan karya seni sebagai respons pandemi global COVID-19.
Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan beberapa karya seni sebagai wujud respons pandemi global COVID-19 yang dihasilkan oleh beberapa cabang seni. Pertama, sebagaimana tampak pada akun FB, Cak Marsam Hidayat membuat kidungan jula-juli berjudul Ngidung Jula-Juli ndik Omah Ae [Menembang Jula-Juli di Rumah Saja] (lihat postingan 17 April 2020 di akun Cak Marsam Hidayat) dan Ngidung Jula-Juli Korona (lihat postingan 22 Maret 2020) sekaligus menembangkannya. Selama masa darurat pandemi COVID-19, Cak Marsam hampir setiap hari menciptakan kidung Jula-Juli berkenaan dengan wabah pandemi COVID-19 dan diunggah di akun FB-nya. Kedua, Sawir Wirastho membuat lukisan-lukisan berbahan cethe (ampas kopi) yang berkenaan atau berkaitan dengan dimensi-dimensi wabah pandemi COVID-19. Lukisan-lukisan itu sering diunggah di akun FB Sawir Wirastho. Selain pelukis, berdasarkan resepsi dan persepsi serta pilihan objeknya, ada pula para kartunis yang membuat kartun-kartun tentang berbagai aspek dan dimensi wajah pandemi COVID-19. Ketiga, dengan mendayagunakan teknologi digital yang terjangkau dan memungkinkan, pencipta lagu atau pemusik menciptakan lagu atau musik berkenaan dengan aspek tertentu COVID-19. Bimbo menciptakan lagu Corona Datang yang sempat heboh karena berkembang informasi sudah dicipata 30 tahun lalu. Redy Eko Prasetya melalui Saling Silang Bunyi Online Music Room mengajak kawan-kawan pemusik berkolaborasi memainkan komposisi tertentu sebagai respons COVID-19 melalui medium digital. Keempat, dengan difasilitasi oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud melalui pertunjukan daring yang disiarkan lewat Youtube, berbagai seniman pertunjukan (tari, teater, musik, lukis, dan lain-lain) menggelar pertunjukan digital guna merespons situasi pandemi COVID-19. Keempat ilustrasi di atas menggambarkan kreativitas dan inovasi para seniman di tengah situasi batas wabah pandemi COVID-19. Terobosan-terobosan kreatif atau inovatif dilakukan oleh seniman atau pekerja seni di antara guncangan global COVID-19.
/4/
Dalam situasi-situasi batas yang dihadapinya, penulis sastra atau lebih khusus sastrawan (di) Indonesia juga merupakan kalangan kesenian yang dengan penuh semangat dan semarak ikut merespons wabah pandemi COVID-19. Berbagai peristiwa yang berkenaan dengan gonjang-ganjing wabah pandemi COVID-19 disaring dan disuling sedemikian rupa untuk dijadikan pokok persoalan karya sastra yang mereka anggit. Demikian juga berbagai pengalaman baik psikologis, personal, subjektif maupun sosiokultural, sosial, dan objektif diolah begitu rupa menjadi teks sastra berbentuk puisi dan fiksi. Sensibilitas, sensitivitas, dan atau responsivitas para pengarang (di) Indonesia terhadap “seribu wajah” pandemi COVID-19 tertuang dalam karya sastra terutama puisi dan cerpen. Sampai tulisan ini dibuat memang belum tersiar kabar ada novelis menggarap novel dengan pokok persoalan COVID-19. Kita berharap kejadian luar biasa yang menyedunia ini juga sedang memantik rangsang kreatif para novelis sehingga kemudian akan lahir novel-novel, melengkapi puisi dan cerpen tentang “tragedi kemanusiaan” wabah pandemi COVID-19.
Puisi dan cerpen, bahkan novel seputar gonjang-ganjing pandemi COVID-19 yang dihasilkan oleh para penyair dan penulis fiksi Indonesia dapat berisi refleksi, resepsi, persepsi, interpretasi, bahkan prediksi “seputar pagebluk COVID-19” yang tentu saja diolah dengan imajinasi dan stilisasi tertentu oleh pengarang sehingga menghasilkan puisi, cerpen atau bentuk sastra lainnya. Puisi dan fiksi tersebut sudah banyak yang dipublikasikan di media cetak, media digital, dan media sosial selain dikumpulkan dalam buku antologi. Sebagai ilustrasi, laman Cakradunia.Co menyediakan rubrik khusus puisi COVID-19 dalam Rubrik Puisi. Penyair-penyair dari berbagai tempat negeri, malah negeri jiran mengirimkan puisi-puisi mereka dan laman Cakradunia.Co menyiarkannya secara ajek selama masa Pandemi COVID-19. Sekarang juga sudah beradar demikian banyak buku yang merekam, mencatat, dan mengingat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.
*Penulis adalah Sastrawan dan Guru Besar Universitas Negeri Malang.