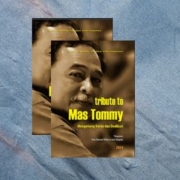Rekonsialisasi Dalam Tenun : Sebuah Kisah Dari Atadei, Lembata
Oleh: Lusiana Limono
1
Saya menginjakkan kaki di Pulau Lembata, NTT di tahun 2018. Saya ingat pengalaman kesenian yang pertama kali saya alami adalah menari Dolo-dolo bersama. Tarian dengan komposisi melingkar, diikuti oleh seluruh masyarakat, bersifat partisipatif, dengan bergandengan tangan sambil bernyanyi bersama. Sesekali ada permainan mengalungkan selendang untuk mengajak penonton pasif untuk ikut bergabung dalam lingkaran, sehingga semua akan menjadi partisipan.
Sepertinya semua pendatang akan mengalami menari bersama seperti ini, karena menurut mereka, tarian Dolo-dolo, tarian Oha, dan masih banyak lagi merupakan tarian sambutan tiap acara, menari bersama sebagai simbol kebersamaan. Benar saja, selama di Lembata, kita akan dengan mudah melihat warga menari bersama di sore hari diiringi musik dari radio ataupun tape recorder. Berdendang dan bergoyang sudah menjadi keseharian mereka.
Niat saya adalah melihat dengan mata kepala sendiri, wastra (kain tradisional) seperti apa yang ada di Lembata, mengalami tinggal bersama warga sambil melakukan pencatatan motif wastra. Bermodal daftar nama desa yang saya catat dan kumpulkan dari berbagai literatur ternyata tak semuanya bisa saya kunjungi meski satu setengah bulan saya habiskan di sana. Yang dimaksud dengan wastra di sini merujuk pada KBBI adalah: kain tradisional yang memiliki makna dan simbol tersendiri yang mengacu pada dimensi ukuran, warna, dan bahan, contohnya batik, tenun, songket dan sebagainya.


foto dokumentasi penulis, 2018
2
Dalam bayangan saya sebelumnya, akan mudah menemukan angkutan umum, transportasi darat yang bisa memindahkan saya dari satu desa ke desa yang lain, seumpama tidak ada, setidaknya tersedia mobil atau sepeda motor sewaan. Bayangan ini ternyata keliru. Transportasi umum sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ada, persewaan sepeda motor juga nyaris tidak ada, kalaupun ada, harganya bisa untuk beli sepeda motor baru kalau di Jawa. Ojek hanya ada dalam kota Lewoleba saja. Persoalan transportasi saja sudah di luar bayangan awal sebelum menginjakkan kaki di sini. Ditambah perbedaan skema waktu antara saya yang terbiasa tinggal di kota dengan warga lokal. Sebagai contoh, ketika dijanjikan ojek motor yang bisa mengantar saya pukul 8 pagi hari. Ojek tersebut bisa saja baru datang pukul 5 sore. Banyak alasan yang bisa dikatakan, mulai dari antre BBM, motor mendadak mogok, dan lain sebagainya.
Hal yang sama ketika seorang kenalan menjanjikan kapal untuk menyeberang ke Pulau Siput. Setelah dijanjikan seminggu dan jadual sudah pasti, sampai detik hendak menyeberang pun, ternyata kapal belum juga ada dan harus menjemput pemilik kapal, beli BBM, yang tentu saja semakin menyita waktu lagi. Pengalaman tersebut membuat saya mulai memperhatikan rumah, warung, dan kantor-kantor yang saya datangi. Saya temui bahwa ternyata di rumah-rumah, bahkan kantor-kantor pemerintahan tak pernah ada jam dinding. Ini menjadi pertanda sekaligus titik tolak saya untuk keluar dari kebiasaan, berdamai dengan diri dalam hal memaknai waktu.
Mengenai transportasi, saya perhatikan hampir semua sepeda motor yang berseliweran di jalan tidak mempunyai plat nomor, ban kendaraan halus semua, alias sudah tipis. Suara musik dalam mobil selalu terdengar sangat kencang, antrean BBM mengikuti aturan ganjil genap selalu panjang tiap harinya. Maklum hanya ada satu depo BBM, itu pun bukan milik Pertamina. Awalnya saya agak kesulitan menentukan mana motor ojek, mana yang bukan. Karena tidak ada pangkalan ojek ataupun nomor rompi seperti di Jawa. Saya merasa memasuki lorong waktu dan kembali seperti masa kecil saya di Malang awal tahun 1980-an, ketika ojek memang belum terorganisir seperti sekarang, helm tidak diwajibkan, semua kendaraan membuka lebar-lebar jendelanya.
Suasana Lewoleba ini jika diambil persamaan waktu, aku bayangkan kira-kira sama dengan kondisi Malang sekitar tahun 1950-1970-an. Namun unik dan kontrasnya adalah, gawai telepon seluler sudah banyak dimiliki orang Lewoleba. Sedangkan gerai fotokopi saja hanya ada 1-2 saja, Tempat cetak foto terdekat adalah di Larantuka, Flores Timur. Perlu menyeberang 2 pulau untuk tiba di sana.
3
Masyarakat Lembata termasuk dalam keluarga suku Lamaholot, terkecuali masyarakat Kedang yang konon tidak termasuk dalam suku Lamaholot. Suku Lamaholot tersebar dari Flores Timur, Solor, Adonara, dan Lembata. Berdasarkan info dari beberapa sumber lisan, saya bertekad mendatangi empat wilayah di Pulau Lembata yaitu: wilayah Ile Ape, wilayah Atadei, wilayah Kedang, dan Lamalera yang terkenal dengan perburuan ikan paus. Sebagai gambaran, Ile Ape, terletak di bagian utara, Atadei, di tengah, Lamalera di selatan, dan Kedang di Timur Pulau Lembata. Tulisan ini lebih spesifik akan mengulik motif ata diken yang ditemukan di wilayah Atadei.
Dalam upaya mengumpulkan data mengenai tenun, saya seringkali memperoleh informasi mengenai legenda Paji dan Demon, yang kadang juga disebut dengan demong. Legenda ini ternyata berpengaruh pada motif tenun yang ada. Motif tenun di Lembata menurut sebagian orang, terbagi menjadi dua kelompok motif, yaitu: kelompok motif Demong (Demonara) dan kelompok motif Paji (Pajinara). Kelompok motif Demong merupakan kelompok wilayah Utara, didominasi oleh motif ayam, bunga, burung, dan kadal. Kelompok motif Paji merupakan kelompok wilayah Selatan yang didominasi oleh motif ikan pari, biota laut, bintang, ekor naga, manusia, dan perahu.
Dari kisah Paji dan Demong ini, kita akan melihat pengaruh Hindu dan India dalam kebudayaan dan tentu saja wastra Lembata. Terlihat keterkaitan antara kepercayaan terhadap Dewa Indra yang dibawa dari India, dengan wastra Lembata. Pengaruh pengikut Indra, dewa dalam mitologi Hindu. Kisah Demon(g) dan Paji oleh Arndt dikatakan serupa dengan mitos yang ada pada suku Munda di India. Arndt memperkirakan, bahwa orang Munda mengungsi ke Kepulauan Solor sekitar tahun 300 Sebelum Masehi (Arndt, Paul 2002: 15).
Mitologi tentang bulan yang religius berpengaruh pada pemaknaan secara politis. Pengaruh Brahmanisme dari India, dapat kita temui pada simbol motif ular pada kain tenun, susunan batu sebagai tempat pemujaan, binatang kerbau sebagai binatang kurban.
Cerita Paji dan Demong, yang mengisahkan dua bersaudara bermusuhan, sangat melekat di benak masyarakat. Sekaligus merupakan sesuatu yang sangat sensitif bagi masyarakat Lamaholot. Kisah tentang Paji dan Demong ini pulalah yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang sering berseteru hingga bertumpah darah. Kisah ini berasal dari Lite, Adonara Tengah. Kisah yang menceritakan asal usul, perseteruan, kepercayaan, ritual, hingga belis. Lera Wulan (Matahari dan Bulan / Yang Tertinggi) dan Tana Ekan (Bumi), mitos tentang bulan, dualisme dalam kehidupan manusia, antara cinta dan benci, memaknai gejala alam yang dikaitkan dengan kehidupan. Lera Wulan Tana Ekan, jika diterjemahkan bebas berarti langit dan bumi / alam semesta.
Tiap kali muncul perselisihan akan tetapi selalu berakhir dengan rekonsiliasi. Mereka selalu mengadakan rekonsiliasi setelah terjadi pertikaian, dan itu diatur dalam ritual adat. Rekonsiliasi ini menarik untuk dicermati dalam kaitannya dengan motif tenun yang akan diulas. Kelompok motif ini hanya digunakan untuk membantu pemetaan motif tenun yang ada di lapangan. Saya lebih tertarik membaca wastra sebagai artefak kebudayaan. Wastra menjadi wujud budaya material yang menubuh dalam masyarakat, terutama perempuan dengan wilayah kerja domestik-rumah. Ideologi, spiritualitas masyarakat merasuk, dan seringkali tersirat secara simbolik dalam wastranya. . Wastra sebagai produk budaya, bisa jadi merupakan ungkapan non-verbal dari pembuatnya. Dengan demikian, wastra merupakan alat ungkap, ada semacam ‘alih wahana’ (meminjam istilah Sapardi Djoko Damono, 2014) untuk mengungkap sesuatu melalui bahasa simbolik yang tertuang dalam wujud budaya material.
4
Saya melakukan pengamatan di dua kampung. Kampung Watuwawer, desa Atakore, kecamatan Atadei dan kampung Atawolo, desa Lusilame, kecamatan Atadei. Ata berarti manusia, Dei berarti berdiri. Di kampung ini masih banyak terdapat korke/koker (rumah adat/rumah leluhur/rumah persembahan). Tiap suku masih mempunyai koker masing-masing. Perlengkapan yang di simpan di dalam koker antara lain: gading gajah, berbagai wadah anyaman lontar, kain tenun, kain patola India. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya Lembata, tidak pernah ditemukan habitat gajah. Sedangkan gading gajah mempunyai nilai yang sangat tinggi di masyarakat.
Demikian pula dengan kain patola yang merupakan kain tenun ikat ganda dari India. Adanya kain patola dan gading gajah di dalam rumah adat ini memperkuat kaitan dengan India, sebagaimana dikatakan oleh Arndt (2002). Kedua benda yang ‘dikeramatkan’ ini menandakan adanya hubungan dengan India dan dunia luar. Kedatangan orang dari jauh ini, dimana mereka selalu menyebut bahwa leluhur mereka berasal dari Luwuk, Sina Jawa, Semenanjung Malaka, dan lain-lain, bisa jadi karena adanya perdagangan rempah dan sutra, karena NTT merupakan penghasil cendana, kemiri, dan vanili. Dengan demikian, cikal bakal jalur rempah pra kolonial bisa ditelusuri melalui wastra.
Setelah menaklukkan Bandar Malaka, tahun 1511, kapal-kapal dagang Portugis berlayar menuju kepulauan Maluku dan Banda untuk mencari rempah rempah. Sebagian kapal-kapal Portugis itu kadangkala bergerak tajam ke arah selatan ketika melewati Laut Flores atau Laut Banda. Mereka singgah di pulau-pulau yang menghasilkan kayu cendana putih yang tumbuh subur di sana. Jenis kayu ini sudah sejak lama menjadi barang dagangan yang dicari oleh pedagang-pedagang asal Cina dan dipakai sebagai bahan pembuatan dupa (joss-sticks), minyak wangi, dan peti mati yang berbau wangi. Harga kayu cendana ini di pelabuhan Kanton, bisa mencapai tiga kali harga di Pulau Timor (Daus 1989, 41). (Pradjoko, Didik dan Bambang Budi Utomo, 2013:257)
Dari keterangan di atas, terlihat bahwa, perdagangan rempah sudah dilakukan dengan orang-orang Cina jauh sebelum pra kolonial. Hal ini diperkuat lagi dengan keterangan berikut ini.
Keadaan ini tidak berlangsung lama karena muncul para bajak laut dari Jawa dan Sulawesi yang menjarah desa-desa di tepi pantai. Musuh yang lain dari Portugis disini adalah kapal-kapal Belanda yang mulai berdatangan sekitar tahun 1600 untuk mencari rempah-rempah dan juga pergi ke selatan Laut Flores untuk mencari kayu cendana. Penaklukan Belanda atas Solor pada tahun 1613 membuat Portugis memerlukan pangkalan dagang baru bagi kapal-kapalnya. Mereka kemudian membuka pelabuhan di Lifau, sebelah Utara Timor sebagai P,dan lilin lebah, labuhan dagang. Pelabuhan Lifau ramai dikunjungi oleh para pedagang dari makasar untuk membeli kayu 272 cendana , sementara mereka menjual besi , porselin, sutera, dan emas….(Pradjoko, Didik dan Bambang Budi Utomo, 2013:271-272)

Kain petek haren 3 lirang, foto: dokumentasi penulis, 2018
5
Wastra tenun identik dengan perempuan. Namun, sifat lembut, penurut, tak berdaya tidak serta merta melekat pada perempuan. Bagi masyarakat Lamaholot, kayu adalah perempuan. Sejak bangun pagi, perempuan sudah berurusan dengan kayu untuk memasak, alat pintal dan tenun, juga dari kayu, bahan pewarna alam yang dikumpulkan juga kebanyakan berasal dari kayu, sore hari mereka harus mengumpulkan kayu bakar lagi. Jadi, persepsi saya selama ini tentang kain bersifat feminin dan, kayu bersifat maskulin terpatahkan di sini.
Yang menarik dari budaya Lamaholot adalah adanya kesetaraan antara pria dan wanita. Perbedaan gender lebih merupakan pembagian peran dan dalam masyarakat, namun bukan dominasi ataupun subordinasi. Hal ini juga saya rasakan dan temukan ketika berada di Lembata. Lelaki akan berdiskusi sendiri, demikian pula perempuan juga akan berkelompok sendiri membicarakan hal-hal sesuai masalahnya masing-masing. Masyarakat lamaholot menyebut wujud tertinggi dengan (Lera Wulan Tana Ekan); Sang Pencipta dan Leluhur. Simbol Ina/ibu dan Ama/bapak sebagai orang tua, dikaitkan dengan kosmos. Ama lera Wulan berarti Bapak Matahari dan Bulan yang melindungi, sedangkan Ima Tana Ekan (ibu pertiwi) yang menghidupi.
Wastra sebagai produk domestik yang dihasilkan perempuan, mempunyai nilai tinggi dalam adat. Kerja perempuan penenun, dihargai, sehingga penenun mempunyai martabat dalam masyarakat. Motif diwariskan menurut garis keturunan ibu. Ketika menikah, seorang perempuan harus memutuskan akan melanjutkan motif Ibu atau melepasnya dan mengikuti motif pihak lelaki. Ada ritual yang mengikuti apabila keputusan yang diambil adalah melepas motif dari Ibu.
Sarung laki-laki disebut nowin, berwarna merah kotak-kotak, hitam kotak-kotak. Sarung perempuan disebut petek, lebih banyak variasi dari 2 hingga 5 lembar sarung yang disambung. Sarung tenun dibuat dari ikat lungsi berkesinambungan. Sarung untuk upacara tidak dipotong, jadi tetap berbentuk silinder, sebagai simbol bahwa hidup selalu berputar dan berkesinambungan. Sedangkan sarung yang untuk dipakai sehari-hari dipotong, lalu dijahit.
Motif yang nampak dominan di Atadei adalah motif hiraten (bintang bersudut delapan), tenar (perahu). mokung (ikan pari) dan motif ata diken (manusia bergandengan tangan). Keempat motif ini buat saya terkait dengan tiga hal yang saya alami ketika tinggal di sini. Motif bintang bisa sangat berkaitan dengan bintang bertaburan yang selalu nampak dengan jelas di langit Atadei di malam hari. Bintang rupanya erat dengan masyarakat Lembata, bandara di Lewoleba bernama Wunopito yang berarti bintang tujuh. Masyarakat yang sangat erat dengan alam, bintang sebagai penunjuk musim. Bintang sebagai pemandu, digambarkan dalam wastra. Hubungan dengan Lera Wulan (matahari sebagai bintang dan bulan) yang melindungi.
Tenar (perahu), bisa saja berkaitan dengan cerita lintas generasi mengenai asal muasal leluhur mereka yang datang dari berbagai wilayah, antara lain Luwuk (kerjaan Bugis tertua, di Sulawesi), Sina Jawa (orang yang datang dari arah Barat yang jauh seperti Cina, Jawa). Leluhur yang selalu disebut dalam tiap upacara adat.
Moku, motif ikan pari ini awalnya saya sedikit heran darimana asalnya, karena kecamatan Atadei berada di atas bukit dan masyarakatnya berkebun, jauh dari pantai. Setelah beberapa hari, saya menemui sekelompok perempuan yang berdagang dari Lamalera. Mereka melakukan tradisi peneta berdagang dengan cara barter, sebagai kewajiban adat perempuan Lamalera. Sekelompok perempuan ini berjalan dari desa Lamalera di bibir pantai, menaiki bukit pada malam hari untuk melakukan barter bahan pangan, bentuk perdagangan tradisional. Seringkali mereka membawa ikan untuk ditukarkan dengan jagung dan hasil kebun lain. Dari sini, saya bisa memaklumi munculnya motif ikan pari yang muncul pada wastra. Motif yang menunjukkan relasi sosial dengan sesama manusia, perdagangan sumber pangan, hubungan harmonis dengan Tana Ekan (tanah dan bumi) yang menghidupi.
6
Dan motif Ata diken, motif manusia bergandengan tangan ini langsung mengingatkan saya pada tarian Dolo-dolo dan kebersamaan masyarakat Lamaholot. Motif manusia bergandengan tangan biasanya bergambar selang-seling lelaki dan perempuan. Gambar yang menyiratkan kebersamaan, semangat rekonsiliasi, dan kerjasama antara lelaki dan perempuan, tidak ada diskriminasi gender. Tidak ada penjelasan mengenai makna motif yang ada. Namun, motif manusia, yang disebut dengan ata diken, hanya boleh ditenun oleh orang tertentu saja. Bagi saya, motif ini menyiratkan pentingnya keharmonisan hubungan antar manusia. Lebih lanjut, motif ini bisa ditelusuri dalam kaitannya dengan ritual ‘rekonsiliasi’. Saya mencoba menafsir motif ata diken dalam kaitannya dengan semangat rekonsiliasi dan visual kebersamaan dalam ragam tarian ritual di Lembata.
Ritus rekonsiliasi merupakan ungkapan nyata tentang keutamaan hidup masyarakat Lamaholot (Adonara) yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (ata diken). Filosofi ata diken menegaskan tentang keadaban, kemanusiaan, dan berbudi adat. Filosofi ini memotivasi setiap orang Lamaholot, termasuk para pihak yang bertikai untuk selalu menjunjung tinggi kemanusiaan. (Bebe, 2014: 107)
Menurut Michael Boro Bebe dalam bukunya berjudul Panorama Budaya Lamaholot: Kekerabatan, Ritus Perjamuan, Adat Kematian, Rekonsiliasi, dan Bahasa Arkais, 2014 disebutkan adanya Upacara Adat Kenirek dalam sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Lamaholot yang banyak berkaitan dengan proses pembuatan benang dari kapas hingga proses tenun. Upacara adat ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan kaum perempuan.
Jika kita melihat wastra sebagai teks budaya dan sosial, maka wajar saja jika motif ata diken bisa dianggap sebagai ‘kutipan’ yang berasal dari sumber budaya lain, seperti yang dikemukakan Sapardi Djoko Damono dalam buku Alih Wahana (2014:210). Kutipan yang dimaksud di sini adalah menerjemahkan/mengalihwahanakan filosofi rekonsiliasi, yang tertuang dalam bentuk tarian dolo-dolo, ke dalam teks wastra tenun.
Kain motif ata diken hanya boleh ditenun oleh orang tertentu saja yang diwariskan melalui garis keturunan ibu. Penenun yang mewarisi ‘ramuan motif ikat ini, berkewajiban menjalankan pantangan seumur hidup. Pantangan tersebut adalah; tidak makan nasi hitam, tebu hitam, dan ikan kebakor/kebeku. Entah apa maknanya. Saya belum menemukan teks yang berkaitan dengan hal tersebut. Proses yang mengawalinya pun diatur sedemikian rupa dalam ritual pengorbanan ayam dan iringan mantra/doa. Sebuah ‘pertunjukan’ eksklusif yang tidak sering dijumpai. Saya cukup bernasib baik, menyaksikan sepotong ritual dalam tahap menyambung lembaran kain tersebut.
Mungkin saja ada ‘gagasan’ yang tidak disadari oleh kelompok pengarang ‘motif’. Bisa jadi penciptaan motif ata diken ini merupakan upaya ‘mengawetkan’ sebuah konsep/ ideologi tentang gemohing (gotong royong). Mengawetkan tarian ritual sebagai simbol kerukunan, kesetaraan, dan kebersamaan, sehingga selalu ada rekonsiliasi adat, setelah terjadi pertikaian. Setidaknya itulah makna yang saya tangkap ketika melihat motif ata diken, mengalami ritual dan merasakan suasana ketika tinggal bersama, dan menyerap makna tarian dolo-dolo, dua bolo, hamang, dan tarian ritual lainnya, ideologi warga Atadei.
*Penulis adalah penjelajah tekstil, studi di Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta
BIBLIOGRAFI
Arndt, Paul SVD, Demon dan Paji: Dua Bersaudara yang Bermusuhan di Kepulauan Solor. Seri Etnologi Candraditya No. 1. Penerbit Puslit Candraditya, Maumere, Flores 2002
Barnes, Ruth. The Ikat Textiles of Lamalera, Lembata Within the Context of Eastern Indonesian Fabric Traditions. 1984
Bebe, Michael Boro. Panorama Budaya Lamaholot: Kekerabatan, Ritus Perjamuan, Adat Kematian, Rekonsiliasi, dan Bahasa Arkais, YPPS Press 2014
Damono, Sapardi Djoko. Alih Wahana, 2018. PT. Gramedia Pustaka Utama
Pradjoko, Didik dan Bambang Budi Utomo. Atlas pelabuhan-pelabuhan Bersejarah di Indonesia. Disunting oleh Endjat Djaenuderadjat. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2013
Orinbao, P. Saerang. Tenun Ikat Flores Ditinjau dari Segi Dualisme dengan Nilai Real dan Nilai-nilai Religio-Magi. Ledalero, Flores 1982
Oleona, ambrosius dan Pieter Tedu Bataona. Masyarakat Nelayan Lamalera dan Tradisi Penangkapan Ikan Paus.Lewoleba 2000