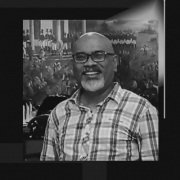Immanuel Kant dan Vasubandhu: Perbincangan tentang “No-Self” dan “Idea Jiwa”
Oleh Tony Doludea
Pada suatu hari seorang wartawan muda di stasiun kereta api melihat seorang biksu dan berusaha mewawancarainya. Ia bertanya pada biksu itu, ‘Menurut bhante, apa masalah terbesar dunia saat ini? Emisi Karbon? Kelaparan? Korupsi? Artificial Intelligence? Transhumanisme?’
Biksu itu tersenyum dan menjawab, ‘Baik, tapi saya ingin tahu terlebih dahulu. Siapa anda?’
‘Saya wartawan,’ jawab anak muda itu.
‘Bukan, itu pekerjaan anda,’ kata si biksu. ‘Siapa kamu?’
‘Saya Badu,’ jawab si wartawan.
‘Bukan, itu nama kamu,’ jawab biksu. ‘Siapa anda?’
‘Saya manusia,’ anak muda itu tegas.
‘Bukan, itu spesies anda,’ kata biksu itu. ‘Siapa anda?’
Ini terus berlanjut, sampai akhirnya, wartawan muda itu menyerah dan berkata, ‘Baiklah, baik… Sepertinya saya sendiri tidak tahu siapa sebenarnya diri saya!’
Lalu biksu itu berkata kepadanya, ‘Inilah masalah terbesar dunia dari dulu hingga saat ini.’
********
Vasubandhu lahir di Puruṣapura, di wilayah Gandhara India (saat ini Peshawar), pada sekitar abad ke-4 M. Ayahnya seorang brahmana dan Vasubandhu memiliki kakak tiri Asanga, seorang tokoh kunci Buddhisme Yogacara. Vasubandhu berati “sanak yang berkelimpahan”.
Vasubandhu awalnya belajar Buddhisme Sarvāstivāda (Vaibhāṣika, yang memegang ajaran Mahavibhasa) aliran yang umum di Gandhara, dan kemudian ia pergi ke Kashmir untuk mempelajari Sarvastivada kepada ketua cabang aliran itu.
Sekembalinya dari sana, Vasubandhu mulai mempertanyakan pandangan Sarvāstivāda-Vaibhāṣika itu, lalu belajar kepada Manoratha, seorang guru aliran Sautrāntika. Kemudian Vasubandhu menjadi pengikut Mahayana karena pengaruh Asanga.
Selama mendalami ajaran Vaibhashika, Vasubanhu telah mengumpulkan lebih dari enam ratus ayat dan memberikan tafsiran atasnya. Kemudian ia memberi judul karyanya itu Abhidharmakosha. Dalam Abhidharmakosha itu, Vasubandhu menganalisa dan mencatat tujuh puluh lima dharma (peristiwa/kejadian fenomenal), yaitu unsur dasar dalam pengalaman manusia untuk mencapai Pencerahan (Bodhi).
Dalam Abhidharmakosha, Vasubandhu juga menguraikan segala jenis keberatannya terhadap ajaran Sarvastivada Abhidharma dengan menggunakan sudut pandang Sautantrika. Termasuk di antaranya kritik atas pandangan Sarvastivada tentang Diri (Atman) dan Pribadi (Pudgala), teori tentang dharma yang berada dalam waktu (masa lalu, saat ini dan akan datang) serta pandangan tentang Allah Pencipta (Ishvara), juga teori tentang avijñaptirūpa, yaitu benda yang tak terpahami atau tak terjangkau (unperceived physicality atau invisible physicality).
Kritik Vasubandhu atas keberadaan “Diri” itu demi mempertahankan ajaran Buddhis tentang “Anatman” dan mengritik pandangan tentang “Pribadi” atau “Jiwa” aliran Buddhis Personalis dan kaum Hindu.
Vasubandhu bertujuan memperlihatkan ketidakrealan “Diri” atau “Jiwa” atau “Pribadi”, yang berada di atas dan melampaui lima skandha, yaitu Rupa (materi, fisik), Vedana (perasaan), Sanna (persepsi atau pengenalan), Sankhara (bentukan atau konstruksi mental) dan Vinnana (kesadaran). Lima skandha tersebut menyatakan tentang sifat sementara pengalaman manusia.
Vasubandhu melakukan pembuktian “No-Self” tersebut berdasarkan kajian epistemologis (Pramana). Bahwa realitas itu nyata ada hanya dapat diketahui atau dari presepsi (Pratyakṣa) atau dari penyimpulan (Anumāṇa). Sesuatu itu nyata ada karena dapat dipersepsi secara langsung dan ini meliputi tujuh hal. Yaitu lima objek panca indra, objek mental dan pikiran itu sendiri. Sedangkan penyimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan panca indra dan pikiran manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga pengetahuan ini bersifat tidak langsung. Misalnya, Pratyakṣa mengamati ada asap, lalu Anumāṇa menyimpulkan ada api.
Namun dari proses epistemologis tersebut, orang tidak dapat membuat dan sampai pada penyimpulan tentang adanya “Diri” yang kokoh terlepas dari persepsi dan kegiatan mental yang selalu berubah secara terus-menerus. Sehingga menurut Vasubandhu, karena “Diri” itu tidak disebabkan secara kausalitas, maka “Diri” tidak lebih merupakan hasil kesepakatan (prajñapti) dan sebuah konstruksi konseptual (parikalpita).
Misalnya, saat orang melihat, mencium dan merasakan durian. Masing-masing orang dapat mengalami pengalaman indrawi yang berbeda-beda dan dipadukan dengan kesadaran mereka masing-masing. Lalu durian menjadi dan merupakan konstruksi pikiran, yaitu sebuah konsep yang dibangun berdasarkan pengalaman indrawi masing-masing orang yang berbeda itu.
Pengalaman indrawi itu nyata, namun durian pada dirinya sendiri itu tidak. Demikian halnya dengan “Diri”, yang dibangun berdasarkan pada pengalaman indrawi yang selalu berubah-ubah, gagasan-gagasan dan peristiwa mental. Hal tersebut membedakan antara kenyataan yang bersifat momentari dengan bayangan tentang kenyataan “Diri” yang utuh dan bersifat tetap dan ini suatu proyeksi yang tidak benar.
Lebih lanjut, terkait dengan pandangan tentang kontiunitas “Pribadi”, Vasubandhu menilai bahwa hal tersebut tidaklah logis. Karena “Diri” itu diciptakan oleh proses panca indra dan pikiran yang terus-menerus berubah, maka membayangkan “Personalitas” yang utuh dan tetap itu merupakan sebuah kekeliruan.
Karena apabila “Jiwa” itu sungguh merupakan suatu yang bersifat abadi dan tak disebabkan, maka “Jiwa” tidak dapat dipengaruhi oleh penyebab yang bersifat fisik dan mental. Maka sulit untuk menjelaskan bagaimana mungkin “Jiwa” yang ada secara independent dan berada di luar pikiran manusia dapat berinteraksi secara kausal. Dampaknya adalah bahwa setiap ajaran yang melihat “Diri” itu memiliki realitas yang independen tidak barguna bagi pencapaian Nirwana.
Kritik Vasubandhu ini tentu bersifat soteriologis, yang tidak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran Buddha. Maka bagi orang di luar Buddhisme, bagi Vasubandhu tidak ada kemungkinan untuk dapat meraih pembebasan. Karena semua sistem keyakinan yang lain itu mengajarakan suatu bentuk “Diri” yang salah, yang sesungguhnya merupakan sekumpulan skandha yang terangkai secara berkelanjutan.
Karena memahami bahwa “Diri”-lah yang memunculkan penderitaan mental (kleśa), maka pembebasan dari penderitaan tersebut menjadi tidak mungkin bagi orang yang memiliki pemandangan yang salah, bahwa “Diri” itu merupakan kenyataan yang berdiri sendiri.
Lalu apabila tidak ada “Diri”, kemudian apa yang sama dalam diri seseorang ketika ia masih bayi sampai saat ia dewasa? Bagi Vasubandhu, segala hal yang nyata atau substansial (dravya) itu disebabkan secara kausalitas, memiliki hubungan sebab-akibat secara khusus dengan hal lain.
Segala hal yang tidak memiliki hubungan seperti itu adalah sesuatu yang tidak nyata dan merupakan sebuah konstruksi konseptual(parikalpita) dan suatu kesepakatan (prajñapti). Maka apa yang disebut “Pribadi”, seperti hal lainnya, harus nyata atau tidak nyata atau terkondisi secara kausal atau dikonstruksi secara konseptual.
Dikotomi khusus yang dibuat Vasubandhu, antara nyata dan kausal vs. tidak nyata dan konseptual itu digunakan bukan hanya sebagai alat untuk menolak “Diri”. Tetapi juga sebagai metode untuk menolak relasi-relasi subjek/objek atau substansi/kualitas dan memahaminya sebagai urut-urutan yang bersifat kausal.
Misalnya objek kesadaran itu tidak dapat dibedakan dari kesadaran itu sendiri. Karena kesadaran disebabkan oleh objek yang nampak, yang darinya ia mendapatkan bentuk khususnya (ākāra). Maka segala hal yang terkondisi dan secara konseptual dikonstruksi “conceptual construction” (parikalpita) seperti itu bersifat tidak tetap, selalu berubah-ubah. Segala hal yang ada itu bersifat “sebuah momen” atau rangkaian urut-urutan kausalitas.
Misalnya, ketika orang mengatakan bahwa “Aku lemas”, ia tahu bahwa itu hanya tubuhnya saja, bukan “Diri”-nya yang “abadi” yang lemas. Juga ketika ia mengatakan “Aku” melakukan atau mengalami sesuatu. Kelihatannya “Diri” itu nyata ada melakukan dan mengalami sesuatu. Namun itu kelihatan dan nampaknya saja, seperti senut berbaris nampak sebagai garis hitam di dinding.
Vasubandhu menyadarkan orang betapa manusia itu cenderung melihat dirinya sebagai tubuh, perasaan, pikiran dan tindakan. Maka dengan itu Vasubandhu menolak adanya “Diri” manusia, termasuk ingatan, nama dan karma untuk berbagai kehidupan sebelum dan sesudah manusia ada di dunia ini.
Bagi Vasubandhu, Buddhisme merupakan suatu metode untuk membersihkan aliran pikiran dari pencemaran dan kotoran “Diri”. Percaya adanya keberadaan “Diri” itu mengakibatkan kesusahan dan perbudakan yang menghasilkan penderitaan manusia.
********
Sekitar seribu dua ratus tahun setelah Vasubandhu, Immanuel Kant (1724–1804) filsuf Jerman dan seorang pemikir utama Pencerahan berkiprah di zamannya. Kant lahir dan dibesarkan dalam keluarga Lutheran Prussia Jerman di Königsberg (saat ini Kaliningrad, Rusia). Keluarga Kant sangat menekankan nilai-nilai kehidupan pietis, kesederhanaan dan pembacaan Alkitab secara literal. Kant dari kecil telah mendapatkan pendidikan yang kaku, ketat dan disiplin lebih tentang bahasa Latin dan agama daripada matematika dan ilmu pengetahuan.
Saat belajar di Collegium Fridericianum, Kant telah memperlihatkan dirinya sebagai seorang pelajar yang sangat berbakat dan berkeinginan kuat. Pada umur 16 tahun Kant mulai belajar di Universitas Königsberg. Kant belajar filsafat Gottfried Leibniz (1646–1716) dan Christian Wolff (1679–1754) di bawah bimbingan Martin Knutzen (1713–1751).
Knutzen menghindarkan Kant dari teori-teori keselarasan, yang meninabobokan sehingga pikiran Kant dapat menjadi malas. Ia juga menghindarkan Kant dari Idealisme, yang percaya bahwa kenyatan itu hanya murni pikiran saja. Sehingga Kant kemudian sangat dikenal dengan teori Idealisme Transendentalnya dalam the Critique of Pure Reason (1781), yang menentang Idealisme tradisional tersebut.
Pada dasarnya Kant sangat kagum dengan kemajuan ilmu pengetahuan alam yang dipelopori oleh Isaac Newton (1643-1727). Kemajuan karena penemuan hukum fisika yang bersifat mekanistik, di mana alam seluruhnya diatur oleh hukum sebab-akibat. Ini telah membuktikan kekuatan pikiran manusia yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengembangkan kehidupan umat manusia.
Namun perkembangan tersebut kemudian mendatangkan krisis, karena kekuatan tradisional agama, moral dan budaya mulai dikesampingkan bahkan ditolak. Oleh hukum sebab-akibat yang mekanistik itu, tidak ada lagi tempat bagi kebebasan manusia dan keberadaan jiwanya. Kekuatan pikiran bebas manusia modern itu menggantikan kekuasaan agama, moral dan budaya.
Maka Kant menanggapi krisis tersebut melalui The Critique of Pure Reason, yang bertema metafisika. Karena bagi Kant, metafisika itu merupakan ranah pikiran, yaitu inventaris segala pikiran murni manusia yang tertata secara sistematis, yang dapat dipertanyakan lagi.
Tujuan utama Kant di sini adalah untuk menyelamatkan kebebasan manusia, agama dan moral dari bahaya hukum sebab-akibat mekanis itu, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan pun dapat tetap dijalankan, dengan menyadari keterbatasan dan dampaknya.
Filsafat Kant dibangun atas usaha mengatasi pertentangan dua pandangan besar pada waktu itu, yakni rasionalisme dan empirisme. Khususnya rasionalisme Gottfried Leibniz (1646–1716) dan empirisme David Hume (1711‐1776). Memang Kant dipengaruhi oleh mereka, namun kemudian mengkritik kedua pemikiran filosofis tersebut dengan menunjukkan kelemahan‐kelemahan mereka. Lalu Kant merumuskan pandangannya sendiri sebagai sintesis kritis kepada keduanya.
Empirisme percaya bahwa pengetahuan manusia berasal sepenuhnya dari pengalaman indrawi. Pengalaman aposteriori indrawi memberi informasi kepada manusia tentang apa yang menjadi objek pengamatan dan pengalamannya itu. Sementara pikiran manusia kemudian diisi oleh konsep dan gagasan hasil dari pengalaman indrawi tentang dunia objektif itu. Pengalaman indrawi tentang dunia objektif tersebut mengajarkan semuanya, termasuk konsep identitas, sebab-akibat dan sebagainya.
Sementara Rasionalisme melihat pengetahuan tentang dunia, jiwa dan Allah sudah ada melekat dalam pikiran manusia sebagai innate ideas (idea bawaan). Bahwa dunia atau realitas objektif dapat diketahui secara apriori melalui analisis ide‐ide secara logis. Pengetahuan dapat diperoleh cukup dengan menggunakan pikiran saja.
Dalam kritiknya itu Kant menerangkan tentang konsep dasar metafisika itu sebagai “idea”, yang terdiri dari “Jiwa”, yang menjamin realitas mental; “Dunia”, yang menjamin keseluruhan realitas fisik; dan “Allah”, sebagai dasar utama segala kemungkinan realitas mental dan fisik.
Namun bagi Kant tiga “Idea” itu tidak dapat dijadikan objek pikiran manusia untuk diketahui dan dipahami. Tiga “Idea” tersebut telah melekat di dalam dan merupakan sifat pikiran manusia, yang mendorong pemahaman manusia agar bersifat utuh dan tertata.
Ketiga “Idea” ini mengatur daya pengertian manusia dan tidak menambah pengetahuan serta kebenaran baru bagi manusia. “Idea” ini secara transendental bersifat semu, formal dan tidak memiliki isi, serta tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang objektif. Ia tidak memberikan gagasan tentang sesuatu yang nyata ada.
Kant menegaskan bahwa daya pengenalan manusia itu meliputi tiga jenjang, yaitu pengamatan indrawi (Sinnlichkeit), akal (Verstand) dan rasio (Vernunft). Rasio merupakan “sesuatu di belakang” pengamatan indrawi dan akal. Tiga “Idea” itu berada pada rasio sebagai pengatur dan penjamin kesatuan pengetahuan manusia, sebagai idea regulatif.
Bagi Kant pengetahuan manusia selalu bersifat sintesis. Pengetahuan indrawi merupakan sintesis antara kenyataan objektif yang dialami dan ditangkap oleh panca indra (aposteriori) dengan konsep ruang-waktu dalam pikiran manusia (apriori). Semua pengalaman indrawi dan semua objek yang dialami adalah “penampakan”, fenomen atau gejala (Erscheinungen). Namun sifat mendasar objek itu sebagaimana ada pada dirinya sendiri, tidak dapat diketahui.
Sedangkan pengetahuan akal merupakan sintesis antara pengetahuan indrawi dengan kategori dalam pikiran manusia. Ada 12 kategori yang dibagi ke dalam empat bagian: Kuantitas (Kesatuan, Kemajemukan, Keseluruhan); Kualitas (Relasi, Negasi, Limitasi); Relasi (Substansi, Kausalitas, Komunitas); Modalitas (Kemungkinan-Kemustahilan, Eksistensi-Non Eksistensi, Keniscayaan-Kontengensi).
Sementara pengetahuan rasio merupakan sintesis antara konsep atau pernyataan (proposisi) dari pengetahuan akal tadi dengan tiga “Idea” itu menjadi suatu kesimpulan dan cakrawala pengertian. Rasio hanya bersifat penalaran, bukan pemahaman. Bagi Kant metafisika itu bukan suatu pengetahuan.
Dalam the Critique of Pure Reason, Kant membeberkan kemampuan dan batas kemampuan rasio teoritis dan temuan ini menghasilkan pembedaan antara fenomen yang dialami secara indrawi dalam pengenalan manusia, dengan noumena yang tidak dapat ditembus oleh daya pengenalan manusia.
Bagi Idealisme Transendental Kant, noumena (objek yang berada dalam dirinya sendiri) itu berada di luar dan melampaui jangkauan pengetahuan manusia sebagai objek pengenalannya.
Demikian juga dengan Jiwa, Dunia dan Allah sebagai “Idea” regulatif, yang mengatur keutuhan dan tatanan pemahaman manusia itu bukan merupakan objek pengenalan manusia. Maka “Aku” yang berpikir dalam seluruh jenjang pengenalan manusia tidak dapat dijadikan sebuah objek pengenalan itu sendiri.
********
Pandangan Buddhis yang diwakili oleh Vasubandhu seperi itu melihat bahwa “Diri” manusia itu merupakan keberlanjutan (continuum) penampakan fisik dan mental, yang terkondisi dan tidak mempunyai esensi mendasar yang tetap.
Keberlanjutan ini tergantung pada agregat (skandha), yang terdiri dari lima wujud eksistensi dan terbagi dalam dua kategori, yakni bagian mental, immaterial (nâma) yang terdiri dari vedanâ (sensasi), sañña (persepsi), sankhâra (konasi), vijñana (kesadaran); dan bagian material, yaitu rûpa (tubuh). Masing-masing dan semua perwujudan agregat ini bersifat fana, berubah, hilang dan musnah.
Masalah mendasar di sini adalah bukan bahwa manusia hidup dalam dunia yang ilusif. Namun bahwa manusia itu tertipu dengan menerima realitas khayalan yang diberi dan dihasilkan oleh persepsi dan konsep pengetahuannya sendiri. Saat orang dapat menyadari kesesatan ilusif itu dan tidak lagi mempercayainya. Maka khayalan itu menghilang dan orang dapat mengalami kebenaran yang berada di balik ilusi itu, yaitu ada yang tak terkatakan sedemikian adanya (tathata).
Jika tidak ada “Pribadi” atau “Diri” atau “Jiwa”, maka tidak ada sesuatu pun yang menetap dari manusia. Tetapi kemudian muncul masalah etis, yaitu bagaimana menjelaskan hubungan antara tindakan seorang “Pribadi” atau “Diri” dengan tanggung jawab etisnya. Siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan seseorang, ketika ia ‘meng-aku’ (âhamkara) melakukan atau ‘men-daku’ (mamamkara) suatu tindakan?
Padahal pada sisi lain, Buddhisme memiliki ajaran karma terkait dengan hukuman dan ganjaran dalam kelahiran kembali. Lalu siapakah yang dilahirkan kembali, jikalau tidak ada “Diri” yang tetap itu?
Namun Buddha memperlihatkan bahwa banyak pertanyaan yang diajukan dalam filsafat tidak berdampak bagi pembebasan. Seperti orang yang mempersoalkan anak panah yang menancap di dada temannya, namun tidak mempedulikan keselamatan temannya itu.
Buddha menjelaskan bahwa hidup religius itu tidak tergantung pada ajaran apakah dunia abadi atau dunia tidak abadi. Entah dunia ini abadi atau dunia ini tidak abadi. Lahir, menjadi tua, sakit, sedih, kemalangan, keputusasaan dan kematian masih terus berlangsung.
Entah secara metafisis, epistemologis, terkait apa yang diketahui atau apa adanya “Diri” itu. Buddha menolak untuk menjelaskan hal tersebut. Karena semua itu tidak berdampak untuk sesuatu hal dilakukan dalam kehidupan. Karena ia bukan merupakan pertimbangan pragmatis, tidak dalam rangka merunut buah-buah dan konsekuensi karma. Maka penjelasan semacam itu tidak diperlukan, karena itu merupakan avyâkrtas (yang tak terselami, yang tak terjelaskan).
Bahwa pertanyaan tentang apakah manusia mempunyai “Diri” (âtman) yang substansial, justru merupakan pertanyaan yang memperlihatkan sikap posesif. Karena orang menginginkan kepastian jawaban tentang ‘aku punya’ “Diri”.
Pertanyaan itu menghasratkan jawaban yang pasti tentang “Diri” sebagai milik. Maka ia tidak sejalan dengan ‘kebenaran mulia’ (âryasatyani). Pertanyaan posesif itu menimbulkan hasrat (tanha) kepemilikan, yang menimbulkan duhkha (penderitaan).
Buddha juga menolak untuk menjelaskannya pernyataan sebaliknya, bahwa “Tiada Diri” (No-Self) untuk menyangkal pertanyaan yang pertama. Sebagai bentuk penolakan atas sikap kepemilikan, bahwa manusia mempunyai entah “Diri” atau pun “Tiada Diri”.
Bagi Buddha pertanyaan taktis lebih berguna untuk dijawab, daripada pertanyaan metafisis dan epistemolgis seperti itu. Misalnya, apa itu kusala (baik) dan akusala (buruk), siapakah âriya (mulia) dan anâriya (hina), apa itu duhkha, duhkha-samudaya, duhkha-nirodha dan apakah itu dukkhanirodha-gamini-patipada. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bersifat taktis-praktis untuk dilakukan, bukan untuk dipikir-pikir dan diperdebatkan.
Namun secara umum, Buddhisme melihat bahwa segala macam bentuk pembicaraan doktriner dan abidhamma itu seperti sebuah rakit atau tangga untuk menyeberang atau naik ke Nirvâna. Apabila sudah sampai maka seluruh pembicaraan itu harus dibuang, karena sia-sia dan tidak ada gunanya lagi.
Sedangkan Immanuel Kant dalam kritiknya tersebut mengungkap spekulasi berlebihan metafisika tradisional. Mereka salah memahami bentuk apriori ruang-waktu, yang telah ada sebelum pengamatan indrawi, yang bersifat mental dan melekat dalam pikiran manusia itu sebagai suatu realitas alamiah objektif.
Demikian juga dengan substansi dan sebab-akibat, alat kerja (kategori) pikiran untuk menangani objek-objek indrawi yang dicerap, disalahpahami sebagai realitas almiah objektif yang berada di luar manusia.
Kant membongkar kegagalan usaha pikiran teoritis manusia untuk sampai pada pengetahuan tentang objek, yang berada pada dirinya sendiri (noumena), berdiri sendiri dan terlepas dari pikiran manusia.
Bagi Kant usaha rasional seperti itu ternyata gagal, karena pikiran manusia hanya mampu menjangkau “penampakan” atau fenomen (Erscheinungen). Bukan objek itu sebagaimana ada pada dirinya sendiri. Kemudian justru membuat kesimpulan yang jauh dari pengetahuan tentang objeknya tersebut.
Kant juga mengungkap mitos dan dongeng metafisika tradisional tentang “Diri” sebagai substansi yang esensial, yang dapat menjadi objek pikiran manusia sebagai “Aku yang berpikir”. Di sini Kant membongkar berbagai macam keyakinan metafisik tradisional tentang jiwa sebagai substansi dan identitas yang dipegang selama ini.
Kant berusaha adalah menyelamatkan kebebasan manusia, agama dan moral dari rongrongan keyakinan hukum sebab-akibat mekanis itu. Dengan memberi ruang dan mengembalikan iman (Glaube), yang telah disingkirkan oleh keyakinan ilmu pengetahuan modern tersebut.
Jika usaha rasional teoritis murni manusia itu tidak mampu memberi pengetahuan tentang hal-hal adi-indrawi tersebut. Maka menurut Kant, kesadaran moral manusia dapat menghantar manusia untuk meninggalkan bidang empiris aposteriori menuju pemahaman bidang apriori.
Kesadaran moral manusia merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah, meskipun bukan merupakan objek pengetahuan indrawi. Menurut Kant moralitas itu merupakan hal yang manyangkut baik dan buruk, namun bukan baik dan buruk biasa. Melainkan baik dan buruk pada dirinya sendiri, tepatnya baik yang mutlak. Baik yang mutlak ini hanya satu, yaitu Kehendak Baik. Kehendak Baik itu selalu baik, seorang yang berkehendak baik, ia baik dan kebaikannya tidak bergantung pada sesuatu di luarnya.
Fakta moralitas itu tidak bersifat teoritis dan abstrak, tetapi bersifat praktis. Maksudnya, suatu refleksi atas suatu pengalaman yang tidak dapat disangkal, yang oleh Kant disebut sebagai kesadaran moral. Kesadaran moral artinya kesadaran adanya kewajiban mutlak.
Kesadaran moral itu adalah suatu fakta, meskipun bukan fakta empiris, namun sudah diketahui dan dirasakan. Fakta empiris dapat dibuktikan lepas dari kesadaran manusia. Tetapi fakta moralitas hanya ada dalam kesadaran manusia. Kesadaran moral ini merupakan Fakta Akal Budi.
Akal Budi Praktis mewujudkan dirinya dalam bentuk Kewajiban. Orang berkehendak baik apabila ia menghendaki melakukan Kewajiban, yaitu Perintah Tanpa Syarat atau “Imperatif Kategoris”.
Perintah Tanpa Syarat ini merupakan perintah, “Bertindaklah secara moral!” Kant merumuskan isi Imperatif Kategoris ini sebagai ”Bertindaklah hanya menurut maksim atau prinsip yang dapat menjadi hukum universal!”
Kant melanjutkan bahwa kenyataan moralitas ini hanyalah mungkin apabila diandaikan bahwa manusia memiliki kebebasan dan jiwa manusia tidak dapat mati serta Allah benar-banar ada. Ketiga hal ini disebut Kant sebagai “tiga postulat rasio praktis” yang tidak dapat dibuktikan tetapi merupakan tuntutan fakta moral.
Menerima ketiga postulat ini oleh Kant disebut sebagai iman (Glaube). Bagi Kant iman itu bersifat subjektif dan secara rasional tidak memiliki cukup objektivitas, yang disebut juga bersifat assertoric, yaitu yang terbukti dengan sendirinya.
Kant menggunakan kata iman, namun tidak mengaitkannya sama sekali dengan agama-agama yang ada. Bagi Kant moralitas itu memimpin pada agama. Agama merupakan hasil dari kesadaran dan tindakan moral. Jika agama dapat disadarkan dari belenggu “ilmu pengetahuan”-nya itu, maka akan muncul “agama moral” yang universal. Sehingga kemudian orang mulai dapat membayangkan terciptanya perdamaian abadi berdasarkan moralitas tersebut.
Vasubandhu telah membuat rakit dan tangga “No Self” bagi orang yang dalam perjalanan menuju ke penyadaran. Sedangkan Immanuel Kant melalui kritiknya tersebut, telah berusaha keras memugar kembali nilai-nilai agama, moral dan budaya, yang telah digusur dan dilongsorkan oleh semangat Pencerahan di zamannya itu.
Kant meletakkan kembali ilmu pengetahuan pada porsi rasionalitas teoritis murninya dengan semua keterbatasannya. Lalu Kant merayakan moral dan pengharapan manusia berdasarkan iman itu melalui Golden Rule, “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu kepada mereka.” (Matius 7: 12). Maka Kant mengakui bahwa kemuliaan Allah itu berbicara melalui “coelum stellatum supra me, lex moralis intra me” (Langit yang berbintang di atas ku dan hukum moral di dalam ku).
—————–
Kepustakaan
Ameriks, Karl. Interpreting Kant’s Critiques. Clarendon Press, Oxford, 2003.
Anacker, Stefan. Seven Works of Vasubandhu: The Buddhist Psychological Doctor. Motilal Banarsidass Publishing House, New Delhi, 2024.
Duerlinger, James. Indian Buddhist Theories of Persons: Vasubandhu’s Refutation of the Theory of a Self. Routledge, London, 2003.
Edelglass, William and Garfield, Jay. (Ed.) Buddhist Philosophy: Essential Readings. Oxford University Press, Oxford, 2009.
Guyer, Paul. The Cambridge Companion to Kant. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
Guyer, Paul. Kant. Routledge, London, 2014.
Hadiwijono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Kanisius, Yogyakarta, 1980.
Harvey, Peter. Introduction to Buddhism. Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
Kenny, Anthony. Immanuel Kant: A Very Brief History. SPCK, London, 2019.
Keown, Damien. Buddhism Ethics: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford, 2005.
Laumakis, Stephen J. An Introduction to Buddhist Philosophy. Cambridge University Press, Cambridge, 2023.
Scruton, Roger. Kant: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford, 2001.
Suseno, Franz Magnis. 13 Tokoh Etika. Kanisius, Yogyakarta, 1997.
Ypi, Lea. The Architectonic of Reason: Purposiveness and Systematic Unity in Kant’s Critique of Pure Reason. Oxford University Press, Oxford, 2022.
*Penulis adalah Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia.