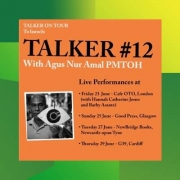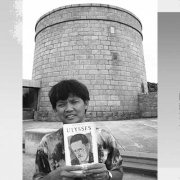Hantakarana: Pesan Sandi Ki Sunata dari Gunung Windya
Oleh Tony Doludea
Pertanyaan yang tidak dapat dihindari dalam Filsafat adalah tentang makna dan kemungkinan ultim (terakhir) kehidupan manusia. Tidak sedikit filsuf memberikan jawaban bernuansa absurditas, kemuakan, kebosanan dan ketidakbermaknaan.
Zaman ini ditandai dengan keadaan muram, terancam, terasing, jenuh dan tanpa arti. Mungkin hal ini yang membuat kebusukan kepribadian dan hati nurani, sehingga manusia tidak lagi dapat mengenali dirinya dan bahkan mengkhianati kemanusiaannya.
Dalam keadaan pandemik global COVID-19, pikiran manusia terbukti menjadi lemah dan menyelewengkan serta menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, kultus kehidupan dan keberagamaan sekaligus longsornya norma-norma moral semakin parah.
Semasa hidupnya, Sokrates pernah mengajarkan bahwa hidup yang tidak dikaji itu tidak layak untuk dihidupi. Sumber ungkapan Sokrates tersebut adalah sebuah amsal yang tertulis di kuil Apollo di Delphi, γνῶθι σεαυτόν: gnōthi seauton. Kenalilah dirimu sendiri. Aristoteles kemudian menyimpulkan bahwa kebijaksanaan itu dimulai dari mengenal diri sendiri.
Mengaji dan merenungkan makna dan tujuan kehidupan manusia yang paling sederhana dan terdekat adalah Memento Mori, sadar bahwa semua manusia itu pasti akan mati. Seneca menyadari bahwa seluruh usaha Filsafat adalah suatu meditation mortis “permenungan mengenai kematian”. Orang sakit mati, orang sehat mati; orang miskin mati, orang kaya mati; rakyat mati, raja juga mati; orang fasik mati, orang saleh mati; orang kafir mati dan orang beriman pun mati.
Karl Jaspers menyadarkan orang bahwa pada saat “situasi-situasi batas”: kesusahan, penyakit, bahaya dan ancaman maut seperti ini, pertanyaan tentang makna dan kemungkinan ultim manusia itu muncul dan menjadi sangat nyata. Pertanyaan yang membuat manusia gelisah dan dapat saja merusak kesenangan dan ketenangan hidupnya. Mungkin juga pertanyaan itu justru kemudian dipendam dalam-dalam karena sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan. Terutama pertanyaan tentang kematiannya sendiri.
Seneca bersama para filsuf Stoa lainnya percaya bahwa makna dan kemungkinan terakhir (necessitas ultima) kehidupan manusia itu terletak pada hidup secara manusiawi, yaitu sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodrat manusia itu berarti hidup menurut rasio. Karena rasio (logos) manusia itu merupakan percikan atau sebagian kecil dari Roh Ilahi (Logos). Hidup menurut rasio berarti hidup menurut kehendak dan maksud Tuhan.
Manusia berbeda dengan mahluk-mahluk lainnya karena rohnya, karena logos. Sementara tubuhnya sama saja dengan mineral, tumbuhan serta binatang dan mahluk lainnya di alam semesta. Jadi manusia harus hidup berdasarkan rohnya, menurut batinnya.
Kemungkinan tertinggi manusia adalah menjalankan kehidupan rasional. Orang bijak secara teguh hidup dipimpin oleh rasio. Orang yang dipimpin oleh rasio adalah orang yang menerima kematian dengan pasrah kepada Tuhan, nahkoda kapal hidupnya, bagian terbesar rasionya. Dengan sadar, senyum dan hati gembira menyambut kematian, karena kematian itu tidak lain daripada terurainya unsur-unsur material yang membentuk setiap mahluk hidup. Dengan demikian manusia mencapai keadaan di mana ia tidak tergantung dan terpengaruh lagi oleh apa pun yang berada di luar dirinya (aturakeia).
Cita-cita tertinggi filsuf-filsuf Stoa adalah kebebasan. Manusia bebas dari keresahan (ataraxia) dan dari penderitaan (apathia). Maka keberuntungan tidak membuatnya bahagia dan kemalangan tidak membuatnya resah serta menderita. Kaum Stoa ingin membangun manusia yang berwatak kuat. Orang yang berwatak kuat harus merupakan seorang pemberani. Orang yang pemberani bukan sekadar dapat mengatasi rasa takut, namun tidak memiliki rasa takut. Ia tidak membungkuk dan tunduk kepada apa pun juga yang berasal dari luar dirinya.
Nasib apa pun yang dialaminya tidak membuatnya resah dan menderita. Apa pun dihadapinya dengan tenang dan baik hati. Dalam kemalangan dan penderitaan pun ia tetap bebas. Dalam keadaan paling aneh dan paling sulit pun ia tetap tenang dan tak tergoyahkan. Ia tegak berdiri dengan kepala di awan-awan dan kakinya di aliran banjir deras, tenang sekali tak dapat diganggu dan rasionalistis.
Bagi kaum Stoa hidup manusia itu seperti sebuah drama yang terdiri dari tiga babak: lahir-hidup-mati. Manusia hanya bertanggung jawab atas babak kedua saja, yaitu kehidupan yang terentang antara lahir dan mati. Kesudahan hidup manusia ditentukan oleh Tuhan yang pernah bertanggung jawab atas kelahiran dan kini atas peleburannya. Manusia tidak bertanggung jawab atas kelahiran dan kematiannya. Maka manusia pergi dengan sikap baik, sebab Dia yang membuyarkannya itu bersikap baik juga.
Orang bijak menyongsong kematiannya dengan tenang. Epikuros juga pernah mengingatkan bahwa kematian itu tidak perlu ditakuti. Selama manusia masih hidup, dia belum mati, apabila dia mati, dia sudah tidak ada lagi. Jadi dia tidak sadar dan tidak merasakan apa-apa lagi. Kalau manusia berusaha hidup dengan baik, maka dia akan mati dengan baik pula.
********
Di Tanah Nusantara, diperkirakan sekitar awal abad 16 sampai akhir abad 18. Ki Sunata, seorang Kawi yang tidak pernah dikenal, yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang berlagak pandai, pura-pura menjadi penyair, sangat sombong, selalu menderita malu dan sengsara, miskin sejak masih kanak-kanak dan selalu terlunta-lunta. Sang Kawi ini berusaha menarasikan persolan filosofis tersebut di atas dalam sebuah syair lagu. Dia berharap siapa saja yang membaca kidungya ini dapat memperoleh kegembiraan dan kesehatan, merasa senang berada di gunung berhutan, laku kuat konsentrasinya dalam laku mengabdi di gunung berhutan.
Kidung Surajaya disusun dalam bentuk puisi bermetrum, dalam hal ini macapat, dengan tembang Dhandhanggula, Bubuksah, Pangad, Mahesalangit. Sebuah puisi yang terikat dengan metrum, yang diatur pola sajak (rima) dalam suatu bait, jumlah suku kata dalam satu baris dan jumlah baris dalam satu bait.
Kidung Surajaya menggunakan bahasa Jawa Baru yang arkais dalam beberapa irama yang terdiri dari 7 pupuh seperti Dandanggula/Hartati, Witaning Panggalang, Bubhuksah dan Meswalangit. Kidung Surajaya ditulis dalam tujuh pupuh dan sekitar 796 bait. Seperti halnya Kidung Subrata, Kidung Surajaya memang berisi pelajaran mistik yang menekankan laku yoga, terutama tentang cara mengendalikan indra.
Kidung Surajaya adalah karya sastra Jawa bergenre siswa lelana brata. Di dalam genre siswa lelana brata, tokoh utama selalu diceritakan sebagai seorang petualang perjalanan spiritual, yang berusaha mengubah tingkah laku dan menghilangkan hawa nafsu demi mencapai kesempurnaan hidup.
Kidung Surajaya merupakan salah satu bagian dari kumpulan Naskah Merapi-Merbabu. Kidung Surajaya terdapat dalam manuskrip daun lontar 87.101.158, 208, 245, 262, 306, dan 504. Naskah no 208 selesai disalin tahun kira-kira 1618 tahun Jawa (1696 Masehi), sedangkan naskah no 262 kira-kira tahun 1607 tahun Jawa (1685 Masehi).
Naskah Merapi-Merbabu merupakan kumpulan naskah yang ditemukan pada tahun 1822 di perabuan Ki Ajar Windusana (1759) di Desa Kendakan Lereng Barat Merbabu, Keresidenan Kedu. Naskah-naskah tersebut milik keluarga Pak Kojo, cicit Ki Ajar Windusana, seorang pendeta Buddha yang ketika Islam masuk ke Jawa Tengah menyingkir ke lereng Merapi dengan membawa serta lebih kurang 1000 naskah. Namun, seiring dengan perjalanan waktu naskah-naskah tersebut telah menyusut dan kini hanya tinggal kurang lebih dari 357 naskah, yang terdiri 330 beraksara Buda dan 27 beraksara Jawa.
Sang Kawi menuturkan dalam kidung Mahesalangit itu tentang Singamada anak penguasa di Wilwatikta (Majapahit) yang pergi meninggalkan kota raja dan masuk ke hutan karena hatinya sangat sedih. Setelah ayah mereka wafat, dia merasa bahwa saudara-saudaranya tidak ada yang mencintainya.
Dalam perjalanan itu, Singamada singgah di dukuh Welaharja, berjumpa dengan Ki Panguwusan. Singamada mengungkapkan maksudnya mengungsi ke gunung, yaitu agar dapat menguasai nafsu. Namun Ki Panguwusan meragukan niat Singamada yang masih muda itu. Ki Panguwusan memberi nasihat dan menyarankan agar Singamada pergi ke seorang pertapa mumpuni dan berguru kepadanya. Singamada meninggalkan dukuh Welaharja.
Singamada sampai di Nirbaya dan diterima oleh Ki Ajar. Suasana di pertapaan itu sangat hening pada malam dan sangat syahdu di pagi hari, suasana tersebut telah meliputi persiapan upacara untuk Singamada. Setelah upacara, Singamada berganti nama menjadi Surajaya atau sebutan lainnya Surawani. Di tengah keriangan dan keceriahan hidup para gadis di Nirbaya, Ki Ajar memberi nasihat Surajaya. Di Nirbaya Surajaya menjalani tapa selama 2 tahun. Ki Ajar memberi nasihat kepada Surajaya, lalu ia minta diri untuk melanjutkan perjalanan.
Ni Tejasari, seorang putri yang cantik. Ni Tejasari dipercaya merupakan mahluk kahyangan turun ke bumi, yang melakukan mati raga. Ia bercerita kepada ayahnya bahwa ia bermimpi berjumpa dengan seorang pertapa muda. Ki Darmakawi menasihati Ni Tejasari agar berhenti mati raga lalu menikah.
Surajaya kemudian melanjutkan perncariannya itu dan disambut oleh Hamongraga, pemimpin padepokan Samaharja (Adisukma). Surajaya menceritakan alasannya pergi dari kota raja. Hamongraga berbincang dengan Surajaya dan memberi nasihat kepada Surajaya tentang laku tapa.
Ketika Ni Darmakawi dan Ki Sekarsara mengunjungi Hamongraga. Ni Darmakawi berjumpa dengan Surajaya. Surajaya menceritakan kepada Ni Darmakawi bahwa dirinya berasal dari Majapahit. Penjelasan Surajaya itu mengejutkan Ni Darmakawi, ternyata Surajaya adalah keponakan Ni Darmakawi. Ni Darmakawi mengajak Surajaya untuk datang ke Wanapala.
Tiba di Wanapala, Surajaya bertemu dengan Ni Tejasari. Tak pelak lagi, Surajaya dan Ni Tejasari rupa-rupanya memiliki perasaan saling tertarik yang sama satu dengan yang lainnya. Di Wanapala pada malam itu Surajaya melantunkan kidung, banyak orang terjaga dan tidak dapat tidur mendengar lantunan suara merdu Surajaya. Keesokan paginya, Tejasari keluar dari rumah untuk menemui Surajaya. Kedua sejoli itu sedang dimabuk asmara, pikiran dan perasan mereka berkecambuk, mereka tidak dapat menikah karena saudara misan.
Surajaya minta diri pada Ki dan Ni Darmakawi. Tejasari mengajak Surajaya untuk melarikan diri. Surajaya menghibur Tejasari dan menyuruhnya untuk pulang karena khawatir perbuatan mereka diketahui banyak orang. Surajaya berpamitan pada Tejasari. Tejasari termangu-mangu setelah Surajaya pergi berlalu. Tejasari akhirnya pulang ke rumah.
Surajaya yang sakit asmara dalam pencariannya itu bertemu dengan Ragasamaya di Kagenengan. Keduanya merasa senasib, mereka berdua saling mengangkat saudara, kemudian diadakan upacara pengangkatan saudara.
Dalam perjalanan selanjutnya, Surajaya dan Ragasamaya bertamu kepada Ki Satawang di Widapuspa, tetua padepokan di situ. Ni Sekarja gundah hatinya karena jatuh cinta pada Surajaya. Surajaya menceritakan kepada Ki Satawang bahwa ia jatuh cinta pada Tejasari. Hati Surajaya sangatlah gundah karena sakit asmara pada Tejasari dan Sekarja. Ni Sekarja nekad mendatangi Surajaya dan merayu serta mengajaknya untuk pergi melarikan diri. Namun Ragasamaya mengingatkan Surajaya agar tidak memperdulikan ajakan Ni Sekarja untuk pergi.
Surajaya dan Ragasamaya melanjutkan perjalanan, mereka berdua singgah di padepokan Ki Mudatiwas. Pada malam itu, Surajaya mimpi bercinta dengan Tejasari. Mimpi tersebut melukiskan betapa sedih dan sakit hati Surajaya. Dalam perjalanannya, Surajaya selalu merasa sedih, Ragasamaya selalu menasehati dan menghibur Surajaya. Perjalanan mereka sampai di Cempakajati.
Pencarian itu menjadi semakin mengerikan ketika mereka seperti orang bermimpi, menyaksikan pertempuran dari tempat persembunyian. Pertempuran Jebugwangi, antara 5 bersaudara, yaitu Panji Wisaya, Lalanasambu, Banyakputeran, Lalana Huwah-hawih, Mahisabotho melawan 3 bersaudara dari Gagelang, yaitu Ki Sora, Ki Samun dan Gajahpningset.
Surajaya dan Ragasamaya melanjutkan perjalanan. Mereka berdua sampai pada bekas kraton dan melihat-lihat keadaan di sekelilingnya. Selama perjalanan bayangan Tejasari selalu mengikuti Surajaya, Ragasamaya selalu menghibur dan menguatkan hatinya.
Perjalanan itu menghantar mereka sampai di Lemahbang, bermalam di rumah Ki Rujaksela. Terjadi percakapan dan perdebatan antara Ki Rujaksela dengan Surajaya. Rujaksela merasa terkalahkan. Rujaksela memutuskan untuk mengikuti ke mana pun Surajaya pergi, tetapi tidak dikabulkan. Surajaya dan Ragasamaya minta diri melanjutkan perjalanan.
Surajaya menemukan pertapaan kosong yang diberinya nama Sunyagati. Di situlah Surajaya berhenti berkelana. Surajaya berpisah dengan Ragasamaya. Di pertapaan Sunyagati itu, Surajaya melakukan mati raga. Di tengah Surajaya bertapa, keluarlah nafsu dari raganya. Sang Hyang Sukma menghampiri dan memberi petunjuk, bahwa Surajaya kini bernama Hantakarana. Bagi Surajaya peristiwa itu terasa seperti mimpi saja. Sang Hyang Sukma pergi setelah memberi petunjuk tersebut.
Ragasamaya mengunjungi Surajaya, yang telah bernama Hantakarana. Hantakaran dan Ragasamaya melakukan samadi tujuh malam untuk mengusahakan moksa. Hantakarana berhasil melepas raganya, Ragasamaya gagal. Sukma Hantakarana melesat jauh, Ragasamaya mengurus raga Surajaya yang ditinggalkannya.
Di Widapuspa Ni Tejasari sedih mendengar Surajaya telah meninggal di Pamrihan (Gunung Merbabu). Ni Tejasari melakukan yoga, sukmanya kembali ke kahyangan bertemu dengan teman-temannya para bidadari yang datang menyongsongnya. Ragasamaya mengenang Surajaya.
********
Pada tahun 65 M, Seneca dituduh terlibat dalam konspirasi Pisonian, yang bertujuan membunuh Nero. Untuk itu Nero menjatuhkan hukuman dengan memerintahkan orang yang pernah mendidiknya dan menjadi penasihatnya itu untuk bunuh diri.
Seneca kemudian memotong beberapa urat nadinya, cara yang biasa dilakukan orang kala itu untuk mengakhiri hidupnya. Pompeia Paulina, istrinya itu berusaha mengikuti nasib suaminya, namun Seneca berhasil menenangkannya sehingga tidak ikut bunuh diri.
Namun Seneca tidak segera mati juga, karena darahnya tidak mengalir deras keluar dan membuat penderitaannya itu justru semakin pedih. Lalu ia minum racun, yang juga tidak berhasil membantunya untuk segera mati. Kemudian ia dimasukkan ke dalam bak mandi dengan air hangat, supaya darahnya cepat mengalir keluar dan memperingan penderitaannya. Mayat Seneca kemudian dibakar tanpa upacara yang selayaknya.
Ketenangan dan ketabahan Seneca menghadapi kematian, sebagaimana Sokrates juga tunjukkan, dijadikan sebuah teladan yang sangat berharga, yang ia tinggalkan sebagai pelajaran dan kenangan bagi keluarga dan para sahabatnya. Dengan demikian Seneca telah mencapai keadaan di mana ia tidak tergantung dan terpengaruh lagi oleh apa pun juga yang berada di luar dirinya (aturakeia). Seneca telah bebas dari keresahan (ataraxia) dan dari penderitaan (apathia). Demikian juga halnya bagi Ragasamaya dan Ni Tejasari, menyaksikan Surajaya dalam menghadapi kematian.
Kidung Surajaya adalah cerita tentang perjalanan. Perjalanan lahiriah Surajaya melewati hutan, gunung dan pertapaan. Setelah melakukan perjalanan lahiriah Surajaya berhenti melakukan perjalanan. Dalam perhentian itulah Surajaya melakukan perjalanan jiwa, yaitu moksa. Sebelum moksa ada laku yang dijalani: tapa brata, keheningan, pewahyuan, kemudian baru moksa.
Moksa adalah kelepasan, kebebasan, keselamatan dan hidup kekal, yaitu persekutuan atau menyatunya seorang manusia, mahluk dengan Tuhan, Sang Pencipta. Bila seseorang sudah mengalami moksa, maka dia lepas dan bebas dari ikatan dan kemelekatan duniawi. Terlepas dan terbebasnya Atman dari ikatan maya. Moksa hanya dapat dirasakan oleh orang yang telah mencapainya. Moksa adalah suatu misteri besar ilahiah.
Kisah perjalanan spiritual Surajaya tersebut mengandung makna bahwa setiap manusia adalah peziarah (homo viator) tîrthayâtrâ. Tîrthayâtrâ mula-mula adalah bahwa setiap orang keluar dari rahim seorang ibu. Rahim ibu adalah tempat yang sangat nyaman. Hanya dengan meninggalkan tempat tersebut orang dapat hidup, tumbuh, berkembang dan kemudian mati.
Semua manusia sejatinya selama hidupnya adalah tîrtha, yaitu jalan penyeberangan bagi orang lain, yang memberi pencerahan bagi orang lain; bukannya malah menjadi penghalang dan kegelapan bagi orang lain. Menjadi tîrtha bagi orang lain, berarti menghantar orang lain untuk dapat mencapai pencerahan, baik pikiran maupun jiwa, menuju ke tempat yang lebih tinggi, yang akhirnya mencapai moksa. Inilah makna dan kemungkinan ultim kehidupan manusia bagi Surajaya.
Surajaya mula-mula melakukan perziarahan tîrthayâtrâ, kemudian menjadi tîrtha, tempat pencerahan, guru dan pembimbing bagi Rujaksela dan Ragasamaya. Kehidupan Surajaya adalah peziarahan. Surajaya adalah peziarah dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat suci. Perjalanan Surajaya itu adalah tirthayatra, Surajaya sendiri juga disebut sebagai tirthayatra. Tempat-tempat yang dikunjungi Surajaya adalah kabuyutan, pertapaan (wanasrama). Orang-orang yang dikunjungi Surajaya adalah para ajar. Kedua tempat tersebut baik kabuyutan maupun wanasrama atau pun para ajar adalah tirtha dan patirthan.
Di tempat tersebut Surajaya membersihkan diri dari kekotoran batin mala dan minum air berupa nasihat para ajar, sehingga Surajaya menjadi bersih dari kekotoran batin dan lepas dari dahaga kekosongan batin. Semua laku sudah dijalani, semua guru Siwa Budha sudah didatangi, tetapi Surajaya belum menemukan yang dicarinya.
Isi nasihat dari para ajar mencakup penguasaan raga, penyadaran pikiran bahwa manusia itu makhluk lemah, orang harus waspada pada pikirannya dan keinginan badan. Para ajar itu merupakan ‘tempat penyeberangan’ bagi Surajaya, tidak saja penyeberangan lahiriah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga penyeberangan batiniah, dari kegelapan, kebodohan hati, dari pikiran menuju ke hati dan pikiran yang cerah dan ke kepandaian.
Ketika bertapa Surajaya menjalani laku mati raga. Segala macam mati raga dijalani, seperti ngrowot (makan buah-buahan saja), mutih, berendam dalam air, mengubur diri, tidur beratapkan langit. Laku tapa yang dilakukan ketika samadi adalah membakar kayu bakar dan dupa, tidak makan dan tidak tidur.
Surajaya gagal mencari Sang Hyang Hayu karena Surajaya mencarinya dan mencari di luar dirinya; padahal Sang Hyang Hayu ada di badan Surajaya sendiri. Di Sunyagati Surajaya berhenti sebagai tiîrthayâtrâ secara lahiriah karena dalam kenyataannya Surajaya tidak lagi berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Surajaya mengusahakan kematian.
Dengan cara ini segala nafsu badan Surajaya keluar, terbang ke angkasa. Raga Surajaya kosong. Dengan raga kosong Sang Hyang Suksma baru dapat menemui Surajaya, memberi nasehat tentang laku tapa dan memberi petunjuk bahwa kini nama Surajaya menjadi Hantakarana. Kedatangan Sang Hyang Suksma merupakan tîrtha (tempat penyeberangan) bagi Surajaya untuk melakukan peziarahan berikutnya.
Hantakarana berarti bagian tubuh yang terdalam, pusat pikiran dan perasaan. Hantakarana merujuk pada kesatuan dua tingkat kesadaran manusia, yaitu pertimbangan (budi) dan pikiran (manas). Hantakarana merupakan keseluruhan proses “psikologis”, yaitu pertimbangan dan pikiran yang melibatkan pancaindera (tubuh).
Ketika Surajaya berusaha menyatukan kesadarannya itu dan berhasil, maka ia disebut sebagai Hantakarana oleh Sang Hyang Suksma. Dengan petunjuk Sang Hyang Suksma, Surajaya melakukan peziarahan batin (raganya diam di Sunyagati) dengan segala daya.
Kemudian Surajaya bahkan menjadi tîrtha (pembimbing) bagi Ragasamaya dalam peziarahan batin. Surajaya dan Ragasamaya mengupayakan kalepasan. Surajaya dengan cepat melepas raganya, sukmanya melesat mengangkasa.
Kini tidak ada lagi yang harus dicapai dan lagi tidak ada yang harus dipastikan. Tidak ada tempat untuk menemukan selama orang mencari. Dia yang berusaha memperoleh pun tidak mendapatkannya. Nafsulah penyebabnya. Memberitahukan yang diberitahukan. Manusia sendirilah yang menjadi asal mula dari segala yang rahasia.
Telah sempurna jalan Hantakarana, sampai pada tujuan laku, tidak ada sorga ataupun neraka, terbebas dari siang ataupun malam. Kosong, sunyi tujuannya sangat jauh tidak dapat dipikirkan. Sangat luar biasa kesunyian yang lipat tujuh itu, perjalanan dia yang sudah sempurna, sukma tiada, tanpa arah tujuan, suci tidak ada yang tertinggal di kesunyian, tidak berkeinginan apapun, di kesunyian yang senyatanya terabaikan. Paling dalam tujuan laku tidak dapat dibicarakan lagi.
*******
Konsep keselamatan merupakan muatan terpenting dalam lontar-lontar koleksi naskah Merapi-Merbabu. Ajaran untuk mencapai keselamatan tersebut tercermin dalam lontar-lontar siswa lelana brata, salah satunya diwakili oleh Kidung Surajaya. Keselamatan meliputi seluruh segi kehidupan manusia termasuk kehidupan abadi di dunia sana sesudah kematian.
Karya kakawin Penyair Jawa Kuna biasanya merupakan suatu bentuk pemujaan dan bakti sang penyair pada Sang Ilahi, yang digambarkan sebagai dewa keindahan. Menurut Zoetmulder, dalam pandangan seorang penyair, dewa bukan saja asal mula dan tujuan terakhir segala yang indah. Tetapi juga menampilkan diri dalam segala yang indah dan ia akan berusaha untuk mencapai kemanunggalan dengan dewa pujaannya dan syair itu menjadi suatu hal yang penting.
Bagi Ki Sunata, menulis sebuah syair merupakan suatu praktik yoga. Seorang yogi berusaha mempersatukan dirinya yang imanen itu dan sekaligus menyelami transendensi Yang Mutlak. Penyair kakawin ini berharap mencapai tujuan itu lewat jalan keindahan yang paling sesuai bagi seorang penyair sebagai objek meditasinya, karya keindahan itu sendiri, yaitu kakawin karyanya. Sang Kawi adalah seorang penyair yang menulis syair berulang-ulang, seperti mendirikan sebuah candi bagi dewa yang dipujanya.
*Penulis adalah Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia.
—————–
Kepustakaan
Casparis, J.G.De. Indonesian Paleography. A History of writing in Indionesian from the beginning to c. AD 1500. Brill, Leiden/Köln, 1975.
Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy Vol. II. Cambridge University Press, Cambridge, 1952.
Hamersma, Harry. Filsafat Eksistensi Karl Jaspers. Gramedia, Jakarta, 1985.
Hicks, R. D. Stoic and Epicurean. Dover Publication Inc., New York, 2019.
Pigeaud, Th.G.Th. Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History. The Nagarakrtagama by Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D. Volume I. Martinus Nijhoff. The Hague, 1960.
Pigeaud, Th.G.Th. Literature of Java, Vol I, Synopsis of Javanese Literature, 900-1900 AD. Martinus Nijhoff. The Hague, 1967.
Pudjiastuti, Titik. Naskah-Naskah Koleksi Merapi-Merbabu. MataRantai Sejarah Kesusastraan Jawa. Makalah disajikan dalam Seminar Naskah-Naskah Merapi-Merbabu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jakarta, 2001.
Setyawati, Kartika. Kidung Surajaya. Disertasi Universitas Leiden, Belanda, 2015.
Setyawati, Kartika., Wiryamartana, I. Kuntara., van der Molen, W. Katalog Naskah Merapi-Merbabu. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Universitas Sanata, Yogyakarta, 2002.
Van Der Weij, P.A. Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia. Gramedia, Jakarta, 1988.
Wiryamartana, I Kuntara. and Van Der Molen, W. The Merapi-Merbabu Manuscripts. A Neglected Collection. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Old Javanese texts and culture 157, no: 1, 51-64. Leiden, 2001.
Zoetmulder, P.J. Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Djambatan, Jakarta, 1983.