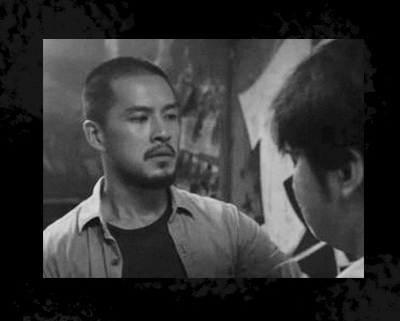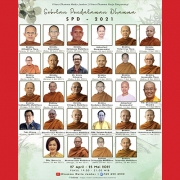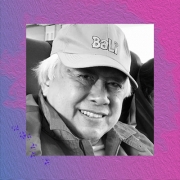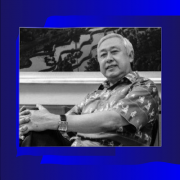Pengepungan Tak Selesai: Sebuah Tafsir Eksistensial atas Film Joko Anwar
Oleh Drupadi Astuti*
Bukit Duri, yang dalam kenyataan adalah hamparan pinggiran ibu kota yang penuh luka penggusuran, dalam film ini menjelma menjadi tanda, metafora, labirin kesadaran kolektif. Joko Anwar, lewat Pengepungan di Bukit Duri, tidak hanya membuat film—ia membongkar memori kota, memori kelas, memori negara, dan memori kita sebagai bangsa yang terlalu sering lupa kepada yang lemah.
Film ini tidak menceritakan satu tokoh, tetapi satu nasib kolektif. Edwin, sang guru, adalah tubuh yang ditempati oleh jutaan jiwa yang terpinggirkan. Ia bukan hanya simbol dari institusi pendidikan, tapi juga dari ketelanjangan struktur, dari betapa rapuhnya kemanusiaan ketika berhadapan dengan kekuasaan yang tidak punya wajah.
Kita melihat sebuah ruang kelas, tapi sejatinya kita sedang menatap ruang batin bangsa ini—yang gaduh, timpang, dan tanpa harapan. Anak-anak yang tak mampu menyebutkan nama pahlawan, atau mengucap sila pertama Pancasila, adalah kenyataan yang setiap hari lewat di berita, namun gagal masuk ke dalam kebijakan.
Di balik kisah sederhana tentang guru dan murid, film ini menyimpan struktur naratif yang rumit: satu sisi adalah negara, dengan aparat dan birokrasi yang menormalisasi kekerasan struktural; sisi lain adalah rakyat, yang tercerai, bingung, dan sering dipaksa berdiam karena takut kehilangan penghidupan.Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi soal hegemonik epistemologi—soal siapa yang berhak menyebut sesuatu sebagai “pengetahuan yang sah”.
Dalam tafsir ala Gramsci, Edwin adalah representasi intelektual organik, seseorang yang tumbuh dari dalam masyarakat dan berusaha mengartikulasikan kesadaran kritis. Dan dalam negara yang dibentuk oleh warisan feodal-kolonial seperti Indonesia, tokoh seperti itu tidak diberi tempat. Ia dikepung. Ia dimiskinkan. Ia dibungkam.
Joko Anwar dalam Pengepungan di Bukit Duri tidak sedang bicara soal guru semata. Ia bicara soal tubuh sosial yang sedang diatur, diawasi, dikontrol. Ia sedang membentangkan arena tempat kekuasaan bekerja dalam bentuk yang paling halus sekaligus brutal: melalui institusi pendidikan.Dalam kerangka Foucault, sekolah adalah bagian dari “dispositif” kekuasaan—institusi yang membentuk subjek-subjek yang taat. Edwin, sebagai guru, adalah anomali dalam sistem. Ia tidak mengulang-ulang dogma, tapi menanamkan pertanyaan. Maka negara tidak bisa membiarkannya hidup. Ia harus disingkirkan, karena ia mengganggu produksi subjek yang patuh.
Jika kita pakai lensa Heidegger, Edwin bukan hanya agen pengetahuan, tapi dasein—manusia yang “ada di dunia”, yang mengalami keterlemparan (geworfenheit) ke dalam sistem yang tidak ia pilih, namun harus ia hidupi. Dalam kelas kecilnya, Edwin berusaha membuka kemungkinan-kemungkinan otentik bagi muridnya. Tapi dunia (yang dimediasi oleh kekuasaan) menutupnya.Bukit Duri, sebagai ruang, bisa dibaca sebagai locus keterlemparan. Sebuah wilayah sosial di mana eksistensi manusia diganggu oleh keterbatasan ekonomi, birokrasi yang tidak transparan, dan aparat yang memaksakan kebenaran tunggal. Maka “pengepungan” dalam film ini bukan cuma tindakan fisik, tapi pengepungan ontologis—dunia yang tidak memungkinkan subjek-subjeknya menjadi diri sendiri.
Dari aspek sinematografi, film ini tidak berusaha menampilkan keindahan. Sebaliknya, ia memilih realisme kasar: lorong sempit, papan tulis usang, wajah-wajah yang lelah, dan suara kelas yang retak. Semuanya diarahkan untuk menciptakan rasa canggung dan getir—bahwa ini bukan ruang untuk nostalgia, tapi ruang untuk menggugat.
Kamera Joko Anwar bergerak seperti mata rakyat: tidak selalu stabil, kadang menyipit karena silau, kadang kabur karena air mata. Tapi justru di situlah kita melihat yang sebenarnya.Jika Joko Anwar dalam film-film sebelumnya banyak bermain di wilayah suspense dan horor sebagai metafora sosial, maka di Pengepungan di Bukit Duri, horor itu tak lagi simbolik. Ia hadir sebagai realitas kasar. Polisi berseragam masuk kelas, aktivis digiring, guru diinterogasi karena mengajar terlalu jujur. Di sini, yang diserbu bukan rumah, tetapi pikiran-pikiran merdeka.
Dan di sanalah letak kekuatan film ini. Ia membuat kita tidak nyaman. Kita dipaksa bertanya, bukan tentang jalan cerita, tetapi tentang siapa kita di tengah cerita itu. Apakah kita Edwin? Atau justru aparat yang menggeledahnya? Atau kita penonton pasif, yang cukup puas dengan mencemooh negara di Twitter?
Tapi seperti karya-karya besar yang menyisakan ruang kontemplasi, film ini juga tidak lepas dari kritik. Di beberapa bagian, narasi terasa terlalu ingin mengajari, terlalu pedagogis. Padahal justru dalam keheningan, jeda, dan kegamangan, pesan film ini paling kuat terasa. Kita tidak butuh Edwin bicara panjang tentang ideologi—cukup kita melihat air matanya saat muridnya ditangkap karena membaca, dan kita tahu: kebenaran sedang dikepung.
Ending-nya, yang mencoba memberi cahaya, terasa seperti lampu kecil yang redup dalam kabut tebal. Apakah harapan masih mungkin, jika negara terus membisukan suara-suara dari pinggiran? Joko Anwar memberi kita kemungkinan, tapi tak memaksakan optimisme. Ia menyerahkan pada kita, penonton, untuk menentukan bentuk perjuangan kita masing-masing.
Pengepungan di Bukit Duri bukan hanya film. Ia adalah catatan kaki dari sejarah yang tak diajarkan di sekolah. Ia adalah sajak panjang tentang pengkhianatan negara terhadap kaum kecil. Ia juga adalah doa sunyi, agar kita yang menontonnya tidak hanya merasa, tapi juga bergerak.
Dan dalam sunyi itu, kita dengar suara Hamzah Fansuri, Wiji Thukul, dan guru-guru yang tak pernah disebutkan dalam buku pelajaran, tapi hidup dalam kesadaran kita yang belum sepenuhnya hilang.
—
*Seorang pengajar Parapsikologi