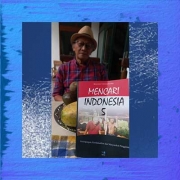Logika Abjeksi dalam Memori Kolektif dan Kuasa Komodifikasi Ketakutan
Oleh Purnawan Andra
Film horor Indonesia telah mengukir tempat tersendiri dalam industri hiburan, dengan ratusan judul yang diproduksi setiap tahunnya. Data dari Laporan Industri Film Indonesia (2020) telah menunjukkan bahwa film horor menyumbang sekitar 25–30% dari total produksi film nasional. Harian Kompas (29/3/2025) menyebut pada periode 2017–2024 data jumlah penonton film horor menunjukkan pergeseran signifikan, dari 21,3 juta menjadi lebih dari 110 juta penonton, melampaui popularitas drama yang hanya tumbuh moderat ke angka 83,8 juta penonton.
Popularitas genre ini bukanlah suatu kebetulan. Tulisan ini tidak bermaksud menambah asin garam di lautan kajian film horor, tapi hanya sebuah pemikiran sederhana atas pemaknaan kondisi sosial politik bangsa yang (dirasa) sejajar dengan logika simbolik kebiasaan menonton film horor masyarakat kita. Ada yang tersirat di balik produksi dan konsumsi film horor di Indonesia.
Warisan Budaya
Secara historis, film horor Indonesia berakar dari warisan budaya yang kaya dengan mitos dan kepercayaan gaib. Cerita-cerita rakyat tentang kuntilanak, pocong, dan tuyul telah lama menghuni alam bawah sadar dan ruang lisan masyarakat. Seiring waktu, narasi-narasi ini diadaptasi ke dalam bentuk sinema, sehingga ketakutan kolektif yang pernah tersimpan dalam cerita turun-temurun berubah menjadi produk massal yang terus di(re)produksi.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Theodor Adorno dalam Aesthetic Theory (1970) yang menyatakan bahwa seni harus mampu mengekspresikan konflik dan ambiguitas zaman modern. Dalam film horor, dualitas antara keindahan dan kengerian memberikan pengalaman estetis yang mendalam. Efek visual tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, melainkan juga sebagai medium untuk mengungkapkan perasaan kolektif yang tersembunyi di balik struktur sosial yang mapan.
Joko Anwar adalah contoh sutradara Indonesia yang karya-karya film horornya diakui di berbagai festival film internasional, seperti Pengabdi Setan (2017), Modus Anomali (2012), dan Pintu Terlarang (2009). Terakhir, film Pabrik Gula karya sutradara Awi Suryadi menembus pasar internasional setelah mampu bekerjasama dengan perusahaan film ternama Hollywood, Lionsgate. Film-film ini mengangkat kisah-kisah yang dekat dengan budaya lokal tapi memiliki daya tarik horor yang universal.
Benedict Anderson dalam Imagined Communities (1983) mengemukakan bahwa identitas kolektif dibangun melalui simbol-simbol budaya yang menghubungkan masa lalu dengan imajinasi masa depan. Dengan mengemas mitos tersebut ke dalam film, industri horor tidak hanya memperkuat narasi identitas komunal, melainkan juga mengartikulasikan kegelisahan yang terakumulasi dari berbagai pengalaman sejarah dan budaya.
Katarsis atas Ketakutan Kolektif
Di satu sisi, dari perspektif antropologis, kehadiran hantu dan makhluk gaib dalam film horor menunjukkan bagaimana masyarakat menginternalisasi ketidakpastian dan trauma yang dialami. Victor Turner dalam The Ritual Process: Structure and Anti-Structure (1969) berargumen bahwa ritual berfungsi sebagai mekanisme untuk menandai peralihan antara tatanan yang teratur dan kekacauan.
Film horor dapat dilihat sebagai “ritual modern”, di mana penonton secara simbolis menghadapi dan mengatasi ketakutan yang sering kali direpresi dalam kehidupan sehari-hari. Film horor menyediakan ruang bagi pengalaman katarsis—suatu bentuk penyembuhan emosional melalui konfrontasi dengan apa yang dianggap tabu atau mengganggu.
Terkait hal ini, Julia Kristeva dalam Powers of Horror (1982) menjelaskan teori abjeksi (abjection) sebagai proses psikologis di mana individu menolak apa yang dianggap “kotor” atau tidak dapat diterima, untuk menjaga batas antara diri dan yang lain. Dalam film horor, gambaran kepala berlumur darah, tubuh dengan usus terurai, makhluk hibrida, dan fenomena supranatural lainnya merupakan simbol abjeksi—suatu ketidaknyamanan yang muncul pada saat kita akan berhadapan dengan hal-hal yang dikecualikan pada norma sosial yang ada pada masyarakat
Di Indonesia, representasi hantu-hantu ini mencerminkan ambivalensi antara ketakutan dan daya tarik yang menyusun memori kolektif. Proses abjeksi ini, seturut Kristeva, merupakan bagian tak terpisahkan dari pembentukan identitas subyektif. Ketika penonton menyaksikan gambaran kegelisahan yang dikomodifikasi melalui layar lebar, mereka tidak hanya terhibur, tetapi juga secara tidak langsung mengakui, menginternalisasi dan mengkonfrontasi ketakutan dan trauma kolektif. Film horor membuka ruang aman bagi penonton sehingga mereka dapat menemukan mekanisme katarsis melalui pengalaman menonton—pengalaman emosional yang intens sekaligus menyembuhkan.
Dengannya, film horor menggambarkan pergolakan antara tatanan sosial dan kekuatan yang dianggap mengancam stabilitas kultural. Mereka menjadi cermin dari trauma kolektif yang diwariskan, dari cerita rakyat yang bertransformasi menjadi metafora modern atas ketidakpastian dan kegelisahan masyarakat, ketakutan kolektif, kecemasan sosial yang tidak bisa diungkapkan secara langsung dalam konteks politik atau kehidupan sehari-hari. Tokoh-tokoh seperti pengusaha kaya, rentenir atau lelaki kuat bertubuh kekar menjadi “standar klasik” antagonisme film horor yang bisa dibaca sebagai representasi kondisi riilnya.
Komodifikasi
Terkait hal ini, Naomi Klein dalam The Shock Doctrine (2007) mengkritik bagaimana sistem kapitalis mengeksploitasi krisis dan ketakutan untuk mendorong agenda politik-ekonomi tertentu. Dengan mengemas ketakutan sebagai komoditas, produsen film horor mengubah kecemasan sosial menjadi produk pasar yang menguntungkan.
Dalam kerangka logika produksi, industri film horor di Indonesia telah mengadaptasi mekanisme komersial untuk memanfaatkan ketakutan sebagai nilai jual. Produsen film menyusun narasi yang memanfaatkan simbol-simbol tradisional dan modern untuk menciptakan atmosfer menakutkan yang resonan dengan kondisi sosial-politik.
Industri ini tidak hanya menghasilkan efek visual yang intens, tetapi juga mengolah ketakutan kolektif menjadi produk pasar yang terus berputar dalam siklus industrialisasi emosi. Proses ini menciptakan ruang di mana ketakutan, yang pada awalnya merupakan reaksi emosional spontan, diubah menjadi narasi yang sistematis dan komersial.
Mark Fisher dalam Capitalist Realism (2009) menyebut budaya populer sering mengolah pesimisme dan ketakutan sebagai bagian dari logika pasar. Simbol-simbol supranatural dan makhluk gaib dalam film horor bukan hanya sebagai elemen naratif, tetapi juga sebagai metafora untuk kekuatan yang menindas tatanan sosial. Film horor, melalui pemasaran dan distribusi massal, menguatkan narasi kegelisahan yang pada akhirnya mencerminkan kondisi sosial-politik yang kian tidak stabil.
Dalam konteks sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, yang ditandai oleh krisis kepercayaan, konflik identitas, dan ketidakpastian ekonomi, semakin memperkuat daya tarik film horor sebagai ruang aman bagi penonton untuk menghadapi ketakutan secara simbolis. Seturut Stuart Hall dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (1997), representasi horor tidak hanya mengungkapkan ketakutan emosional, tapi juga menjadi media untuk mengkritisi struktur kekuasaan dan konflik identitas dalam masyarakat dalam realitas sosial-politik yang, harus diakui, semakin tidak stabil dan “horor” saat ini.
Dengannya, kita bisa memaknai film horor bukan sekadar hiburan, tapi medium untuk mengungkap trauma, menginternalisasi dan mengatasi ketakutan yang ada, untuk mendekonstruksi realitas, dan memicu dialog kritis tentang identitas dan kekuasaan. Simbol-simbol supranatural dan kekacauan estetis di layarnya menjadi bahan untuk merakit alternatif identitas kolektif yang lebih resilient. Film horor berpotensi menjadi kekuatan inovatif dan basis logika transformasi sosial untuk membayangkan kembali masa depan yang lebih adil dan kritis.
—-
*Purnawan Andra, bekerja di Direktorat Bina SDM, Lembaga & Pranata Kebudayaan, Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan & Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan.