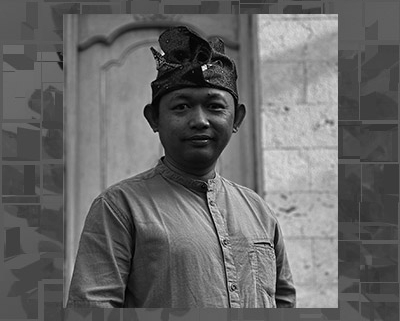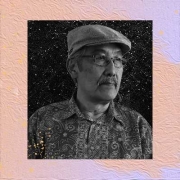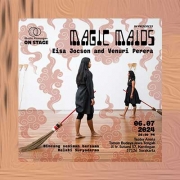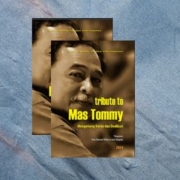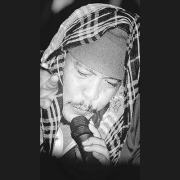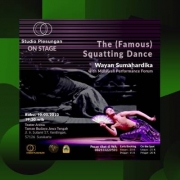Bioskop sebagai Ruang Budaya dan Estetika Kuasa
Oleh Purnawan Andra*
Ruang bioskop selama ini dipahami sebagai tempat pelarian dari rutinitas. Gelapnya ruangan, dentuman suara, dan layar raksasa memberi kesempatan bagi penonton untuk memasuki dunia lain—dunia fiksi, imajinasi, dan kadang refleksi. Namun belakangan, pengalaman ini berubah.
Sebelum film dimulai, layar bioskop di Indonesia dipenuhi video capaian pemerintah, menampilkan Presiden Prabowo dengan narasi pembangunan, stabilitas, dan optimisme nasional. Praktik ini bukan sekadar tambahan iklan, melainkan upaya kuasa untuk menempatkan narasi politik dalam ruang paling intim dari konsumsi budaya populer.
Fenomena ini mengingatkan pada gagasan filsuf politik dan estetika Prancis, Jacques Rancière, tentang distribution of the sensible, yaitu bagaimana kekuasaan mengatur apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan masyarakat. Menonton film bukan hanya hiburan, tapi ia menjadi bagian dari ekologi kultural yang menentukan horizon imajinasi kolektif (The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible, 2004).
Dengan menyisipkan capaian pemerintah sebelum film, negara sedang menegaskan kehadirannya pada momen yang seharusnya netral dari politik elektoral. Ruang gelap bioskop menjadi ladang penetrasi ideologi.
Ruang Publik
Jurgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1962) menggambarkan bagaimana ruang publik seharusnya memungkinkan diskusi kritis antarwarga. Namun dalam praktik kontemporer, ruang publik kerap dikolonisasi oleh kepentingan kapital maupun negara.
Bioskop, meski berbayar, adalah ruang publik kultural yang mempertemukan warga dari berbagai latar. Di sini, penyisipan video pemerintah berfungsi menggeser ruang diskusi menjadi ruang konsumsi politik sepihak. Tidak ada dialog, yang ada hanya monolog kekuasaan.
Pengalaman menonton pun berubah. Alih-alih sekadar menantikan cerita fiksi, penonton terlebih dulu harus menyerap narasi resmi negara. Habitus kultural penonton, meminjam istilah Pierre Bourdieu, sedang diatur ulang: bahwa menonton film berarti juga menonton capaian negara.
Orang bisa berargumen bahwa video ini hanyalah bentuk informasi publik. Namun di baliknya ada logika propaganda halus yang mengingatkan pada teknik yang pernah dipakai rezim otoritarian. Hannah Arendt, dalam The Origins of Totalitarianism (1951), menekankan bahwa propaganda bekerja bukan hanya dengan kebohongan terang-terangan, melainkan dengan pengulangan simbolik yang menanamkan citra kekuasaan sebagai satu-satunya horizon yang mungkin. Dalam konteks bioskop, pengulangan ini bekerja lewat audiovisual yang menyusup ke ranah hiburan, sehingga pesan politik menjadi bagian dari keseharian.
Yang lebih menarik, praktik ini juga bisa dibaca sebagai normalisasi. Michel Foucault, lewat konsep governmentality, menjelaskan bagaimana kekuasaan modern bekerja bukan semata-mata lewat represi, melainkan lewat pengaturan halus atas perilaku dan persepsi warga. Menyisipkan video capaian negara di bioskop bukan tindakan represif; tidak ada larangan menolak menonton. Tetapi ia menormalisasi kehadiran negara dalam ruang personal, membentuk imajinasi bahwa pembangunan dan presiden adalah bagian inheren dari aktivitas budaya.
Jejak Sejarah Propaganda
Praktik penyusupan kuasa ke layar bioskop bukan hal baru. Pada era Orde Baru, film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer (1984) dijadikan instrumen propaganda utama. Negara mewajibkan penayangan film ini setiap 30 September di televisi dan sekolah-sekolah, bahkan kadang di bioskop. Pesan politiknya jelas, yaitu menanamkan narasi tunggal tentang kekejaman PKI sekaligus memuliakan militer sebagai penyelamat bangsa.
Di titik ini, kita melihat bagaimana layar audiovisual bukan sekadar medium seni, melainkan senjata ideologis. Seperti dicatat Ariel Heryanto dalam State Terrorism and Political Identity in Indonesia (2006), film tersebut bekerja dengan membentuk memori kolektif yang penuh trauma. Imaji kekerasan, penyiksaan, dan wajah bengis Gerwani terus direproduksi sehingga generasi demi generasi tumbuh dengan ketakutan pada “hantu komunisme.”
Jika pada era Orde Baru layar dipakai untuk menciptakan musuh bersama, maka kini layar dipakai untuk memoles citra negara dan pemimpin. Polanya berbeda, namun logikanya sama: merebut ruang audiovisual demi mengendalikan imajinasi publik. Apa yang dulu dikelola lewat film panjang, kini dilakukan lewat klip singkat. Bedanya, yang dulu menakut-nakuti, kini menenteramkan dengan janji pembangunan.
Pertanyaan lainnya mengapa jaringan bioskop bersedia memutar video ini? Di sini logika kapital masuk. Theodor Adorno dan Max Horkheimer, dalam Dialectic of Enlightenment (1944), menyebut industri budaya sebagai mesin homogenisasi yang menundukkan seni pada logika komoditas. Jika bioskop hidup dari kapital, maka menyediakan ruang bagi pesan politik negara dapat dilihat sebagai simbiosis: negara mendapat legitimasi, sementara industri mendapat perlindungan atau akses.
Dengan demikian, bioskop tidak lagi sekadar ruang seni, melainkan juga perpanjangan tangan politik. Ia menyamarkan propaganda dalam bentuk hiburan yang wajar, tanpa resistensi eksplisit dari penonton. Publik yang membayar tiket pada akhirnya ikut membiayai reproduksi pencitraan kekuasaan.
Imajinasi Kolektif
Benedict Anderson pernah menyebut bangsa sebagai imagined community, komunitas yang ada karena dibayangkan bersama melalui media dan simbol. Jika dulu media cetak menjadi alat utama, kini layar bioskop ikut dipakai. Yang dipertaruhkan bukan sekadar informasi, melainkan arah imajinasi kolektif bangsa. Apa yang kita bayangkan tentang Indonesia kini diarahkan lewat representasi audiovisual capaian pemerintah, bukan lewat keragaman narasi warga.
Bioskop seharusnya membuka kemungkinan imajinasi alternatif—tentang cinta, kesedihan, perlawanan, atau harapan. Namun ketika layar diawali dengan narasi tunggal kekuasaan, horizon imajinasi itu dipersempit. Seperti yang diingatkan filsuf, kritikus sosial, dan aktivis politik Amerika Serikat, Cornel West, demokrasi membutuhkan “prophetic imagination” untuk menantang status quo (Democracy Matters: Winning the Fight Against Imperialism, 2004). Bioskop justru berisiko kehilangan peran kritisnya karena dibebani narasi hegemonik.
Di sisi lain, kehadiran video pemerintah di bioskop juga harus dilihat dalam konteks ekosistem digital. Saat algoritma media sosial kian dipertanyakan karena manipulasi informasi, bioskop—yang dianggap ruang analog, lebih “netral”—ternyata juga tidak steril. Jean Baudrillard pernah menulis tentang hyperreality, di mana representasi mendahului kenyataan. Tayangan capaian negara berpotensi membentuk realitas hiper, seakan pembangunan berjalan sempurna, tanpa memberi ruang bagi realitas kontradiktif di lapangan.
Di sini, politik layar bukan lagi sekadar urusan propaganda klasik, melainkan bagian dari strategi visual untuk mengendalikan persepsi di berbagai medium: televisi, media sosial, papan iklan, hingga bioskop. Publik dikepung oleh visualisasi kekuasaan dari segala arah.
Maka pertanyaannya apakah kita rela membiarkan layar bioskop, ruang intim imajinasi itu, menjadi panggung spektakel kekuasaan? Atau justru kita perlu mengingatkan diri bahwa demokrasi hanya hidup jika ruang budaya tetap memberi tempat bagi imajinasi alternatif, bukan sekadar gema monolog negara?
——
*Purnawan Andra, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan.