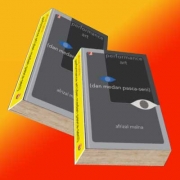Dunia Ahmad Syubbanuddin Alwy: Spiritualitas, Sejarah, dan Eksistensi dalam Puisi Modern Indonesia
Oleh Abdul Wachid B.S.*
I. Pendahuluan
Di jagat sastra Indonesia modern, nama Ahmad Syubbanuddin Alwy berdiri sebagai fenomena yang menautkan sejarah, spiritualitas, dan pengalaman eksistensial dalam suatu harmoni puisi yang jarang kita temui. Ia bukan hanya penyair lokal yang menulis tentang kota asalnya, Cirebon, melainkan seorang pengembara batin yang merentang kesadaran manusia ke dalam waktu, ruang, dan dimensi spiritual. Dalam setiap sajaknya, kita menemukan kesungguhan yang melampaui estetika semata: puisi menjadi medium suluk, tempat perenungan, dan catatan batin atas sejarah, realitas sosial, dan relasi manusia dengan Tuhan.
Ahmad Syubbanuddin Alwy lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 26 Agustus 1962. Latar kultural kota pesisir yang sarat sejarah ini kelak menjadi sumber imaji, simbol, dan refleksi dalam puisinya. Pendidikan formalnya ditempuh di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; sebuah ruang intelektual yang turut membentuk sensibilitas spiritual dan kesadaran etik dalam cara pandangnya terhadap dunia. Kumpulan puisinya Bentangan Sunyi yang terbit dan diluncurkan pada tahun 1996 menandai kematangan estetik Alwy dalam merajut kesunyian, sejarah, dan pencarian makna. Selain itu, karya-karyanya tersebar dalam sejumlah antologi penting, antara lain Puisi Indonesia (1987), Titian Antar-Bangsa (1988), Negeri Bayang-Bayang (1996), Cermin Atom (1997), dan Horison Sastra Indonesia I: Kitab Puisi (2001). Dalam lanskap sastra Indonesia, Alwy menempati posisi khas sebagai penyair yang bekerja dengan kesabaran, riset, dan visi jangka panjang, menjadikan puisi sebagai hasil disiplin batin, bukan sekadar letupan emosi sesaat.
Esai ini bertujuan membuka tabir dunia Alwy melalui lima puisinya: “Lirik Airmata” (1992), “Bentangan Sunyi” (1993), “Cirebon, 630 Tahun Kemudian…” (2000), “Apologia Sepasang Mata” (1996), dan “Kenangan Seperempat Abad Silam” (1999–2000). Dengan menelaah puisi-puisi ini secara utuh, kita dapat menyaksikan bagaimana Alwy menata bahasa sebagai cermin pengalaman spiritual, imaji sejarah, dan eksistensi manusia. Puisi bagi Alwy bukan sekadar bentuk, melainkan perjalanan batin yang menuntut pembaca untuk hadir dalam ritme, gema, dan renungan yang ia ciptakan.
Signifikansi esai ini terletak pada dua hal. Pertama, secara dokumentatif, kita menghadirkan dunia puisi Alwy secara sistematis: teks, konteks, dan imaji disajikan sebagai arsip yang dapat dijadikan rujukan kritik sastra. Kedua, secara analitis, esai ini menawarkan perspektif orisinal: melihat perpuisian modern Indonesia melalui integrasi spiritualitas, sejarah, dan kesunyian eksistensial, yang menjadi ciri khas Alwy. Dalam pengertian ini, studi ini bukan sekadar interpretasi, melainkan percakapan dengan ruh penyair, menghadirkan sumbangan baru bagi kritik puisi Indonesia yang selama ini fragmentaris atau normatif.
II. Landasan Teori dan Pendekatan
Membaca puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy membutuhkan landasan yang mampu menampung kedalaman pengalaman batin, sejarah lokal, dan eksistensi manusia. Puisi bagi Alwy tidak berhenti pada garis atau rima; ia adalah medium pengalaman spiritual dan catatan jiwa yang menuntut pembaca hadir dalam kontemplasi. Oleh karena itu, kerangka analisis yang digunakan dalam esai ini bersifat reflektif-argumentatif, menekankan dialog antara teks dan pembaca, antara pengalaman historis dan pengalaman batin, antara kesunyian dan cahaya spiritual.
Kerangka reflektif-argumentatif ini memandang puisi sebagai ruang batin yang hidup, di mana simbol-simbol religius, imaji sejarah, dan pengalaman eksistensial bergerak secara simultan. Setiap kata bukan sekadar lambang fonetik, tetapi titik temu antara kesadaran manusia dan semesta, antara pengalaman individu dan kolektif, antara masa kini dan sejarah yang membentuk ingatan kota dan masyarakat.
Dalam membaca puisi Alwy, esai ini merujuk pada metodologi kritik sastra A. Teeuw dalam Tergantung pada Kata (1980), yang menekankan pembacaan tokoh penyair secara mendalam, menghubungkan kehidupan, karya, dan konteks budaya. Pendekatan ini diperkuat oleh hermeneutik, yaitu upaya memahami makna teks secara menyeluruh melalui interpretasi simbol, konteks, dan struktur bahasa. Dengan pendekatan ini, teks puisi menjadi hidup; ia bukan sekadar dokumen estetis, melainkan pengalaman batin yang dapat dirasakan, direnungkan, dan diterjemahkan ke dalam pemahaman tentang dunia penyair.
Berdasarkan kerangka tersebut, kriteria analisis puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy dirumuskan dalam lima dimensi yang saling terkait:
1. Dimensi Spiritual dan Religius
Puisi Alwy senantiasa menautkan pengalaman batin dengan hubungan manusia kepada Tuhan. Dzikir, doa, dan simbol sufistik menjadi motor penggerak imaji, menjadikan puisi bukan sekadar ekspresi estetis, tetapi suluk modern yang dapat dihayati.
2. Sejarah dan Lokalitas
Sejarah kota Cirebon dan pengalaman lokal menjadi tubuh puisi Alwy. Ia tidak hanya merekam fakta sejarah, tetapi mentransformasikannya menjadi catatan batin dan panorama emosional yang hidup.
3. Pengalaman Eksistensial dan Kesunyian
Kesunyian, kehilangan, kerinduan, dan penderitaan merupakan tema universal yang diolah secara personal. Puisi Alwy menghadirkan pengalaman eksistensial manusia melalui simbol, metafora, dan narasi batin yang kuat.
4. Imajinasi Visual dan Alegoris
Alwy memiliki kemampuan visualisasi yang tinggi. Kota, pelabuhan, pesisir, masjid, dan keraton diimajinasikan sebagai metafora batin yang alegoris. Imaji ini bersifat simultan: nyata secara visual, simbolik secara spiritual, dan naratif secara historis.
5. Dedikasi dan Disiplin Penyair
Karya-karya Alwy lahir dari kesungguhan yang ekstrem: penelitian sejarah, perjalanan ke lokasi, pencatatan rinci, meditasi batin, dan refleksi personal. Dedikasi ini menuntut pembaca dan kritik untuk memahami proses kreatif, bukan sekadar hasil akhir.
Dengan lima dimensi ini, analisis puisi Alwy menjadi holistik: ia memadukan batin, sejarah, imaji, dan disiplin kreatif menjadi satu kesatuan, sehingga puisi modern Indonesia dapat dibaca tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai dunia pengalaman yang utuh, dunia Ahmad Syubbanuddin Alwy.
III. Presentasi dan Analisis Puisi
1. Lirik Airmata
Dalam lorong-lorong gelap itu, aku kini pengembara
gemuruh kesunyian dan bentangan airmata
seribu masjid menyeduh jiwaku yang merana
dengan zikir-zikir luka. Tapi sepanjang mabuk ini
kuseberangi lautan cintamu bersama doa-doa Rumi
dan nyanyian-nyanyian Rabi’ah. Di manakah puncakmu?
Di padang-padang yang membara, aku berlayar
menjemput fajar demi fajar dari ufuk hatimu
yang jauh. Kepedihan telah kuhanguskan
dengan sinar matahari. Dan aku menggigil
menerima puisi yang dikirimkan gema azan
bintang-bintang kudekap dalam sujud darah
Bagaimanakah cahayamu bisa menerangi kembali?
mulutku dipenuhi lumpur dan labirin beku
menutup seluruh ungkapan panjang pertobatanku
aku harus berlari menyusuri jalan-jalan perih
melayang dalam badai, meniti tangga langit kelam
memanggil-manggil namamu dan mengimanimu lagi
Cirebon, 1992
Sumber: Dari Amerika ke Catatan Langit (Antologi Puisi Mastera), Editor: Dendy Sugono & Abdul Rozak Zaidan, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
Puisi ini menampilkan dunia batin yang sepenuhnya spiritual, di mana pengalaman kesedihan dan kerinduan tidak terpisahkan dari dialog dengan Yang Maha Kuasa. Dzikir dan doa menjadi inti narasi; “seribu masjid menyeduh jiwaku yang merana / dengan zikir-zikir luka” bukan sekadar citraan religius, tetapi ekspresi batin yang mengalir sebagai aliran pengalaman mistik. Alwy menggabungkan sufisme klasik (melalui rujukan Rumi dan Rabi’ah) dengan perjalanan personal modern, menciptakan suluk puitik kontemporer yang membimbing pembaca masuk ke lorong-lorong kesadaran spiritual.
Visualisasi Alwy tidak literal; ia membangun metafora gelap dan cahaya sebagai manifestasi batin. “Lautan cintamu bersama doa-doa Rumi” menjadi medan pertemuan antara pengalaman manusia dan pengalaman transenden. Badai, tangga langit, dan sujud darah bukan sekadar citraan dramatis, tetapi lambang perjuangan batin untuk menemukan puncak spiritualitas.
Secara hermeneutik, puisi ini menunjukkan integrasi yang utuh antara pengalaman eksistensial, spiritualitas, dan imaji visual. Kesedihan, rindu, dan pertobatan diarahkan pada kesadaran yang lebih tinggi; bahasa menjadi medium meditasi, bukan sekadar estetika formal. “Lirik Airmata” memperlihatkan bagaimana puisi modern Indonesia dapat menembus dimensi kontemplatif, menjadikan teks sebagai ruang suluk batin yang hidup dan bergerak.
2. Bentangan Sunyi
Inilah jarak kita; bentangan sunyi —-
debur ombak, gugusan kabut dan keluasan langit
semua bergelombang menyalakan api pada tungku
keimananku. Di sini, di mihrab masjid yang terbuka
ke muaramu, ribuan gerimis mendekapku dalam irama tangis
tetap setiap cahaya datang, kembali membakar doa-doa
dan sujud khusyukku kepadamu. Seperti baris rumpun ilalang
dari belantara hatiku, segera tumbuh menjulang
menutup ungkapan-ungkapan cinta yang membatu
mungkin tinggal wangi sajadah dan simponi airmata
menggenang dalam keremangan malam. Demikian pedih
menerima serpihan-serpihan ayat keabadian
kitab-kitab dari gulungan semesta, mengepung sukmaku
dalam deraian bahasa hujan yang melelahkan
melepas hari-hariku ke segala penjuru pertobatan
Inilah jarak kita: bentangan sunyi —-
suara gema, goresan luka, dan kecemasan waktu
berguguran menuliskan abad-abad panjang di helaian
rambutku. Betapa getar kerinduan menghunuskan sembilu
samudra tasbih, mengasah alunan dzikir serta tarian laut
yang menyala, hingga menyentuh lambaian pucuk-pucuk perdu
dari pematang kehidupanku. Matahari bagai lapis kepompong
mekar di kelam jiwa. Diam-diam mengulurkan ricik kenangan
dalam dadaku. Kubah-kubah bergelora mengirimkan riuh adzan
melukiskan lengkung pagi, juga bianglala sore masa kecil itu
membawaku bertapa di atas keheningan panggilanmu. O, Allah
telah sempurna badai mengajarkan gemuruh langkahku, bergairah
menerima seruan takbir sebagai arah kiblat yang gelisah
kau sematkan percik fajar bersama titik kesadaran di keningku
dan aku, tak bisa mengelak untuk senantiasa memujamu!
Cirebon, 1993
Sumber: Ahmad Syubbanuddin Alwy, Bentangan Sunyi (Forum Sastra Bandung, 1996).
Dalam “Bentangan Sunyi”, Alwy menghidupkan kesunyian sebagai medium pengalaman batin. Bentangan sunyi bukan sekadar ruang fisik, tetapi medan spiritual dan eksistensial: jarak antara manusia dengan Tuhan, antara masa lalu dan masa kini, antara pengalaman personal dan sejarah kolektif. Setiap unsur, ombak, kabut, langit, gerimis, berfungsi sebagai simbol metaforis perjalanan batin, menautkan pengalaman religius dengan sejarah personal penyair.
Dzikir dan sujud tidak hadir sebagai praktik formal, melainkan sebagai narasi batin yang mengalir, menembus lapisan waktu dan ruang: “samudra tasbih, mengasah alunan dzikir serta tarian laut / yang menyala, hingga menyentuh lambaian pucuk-pucuk perdu”. Alwy memadukan simbol sufistik klasik dengan pengalaman personal, sehingga pembaca dapat menyelami keintiman batin sekaligus kesadaran historis.
Kesunyian di sini juga memunculkan kerinduan dan nostalgia. Masa lalu, masa kanak-kanak, dan pengalaman religius membaur menjadi satu, membentuk panorama kontemplatif yang mendalam. Bahasa yang digunakan Alwy (campuran metafora alam, simbol religius, dan pengalaman personal) menjadi medium refleksi yang menyatukan spiritualitas, sejarah, dan eksistensi.
Puisi ini menunjukkan bahwa kesunyian dan kerinduan bukan hanya tema puitik, tetapi sarana memahami kedalaman batin manusia. Di sini, Alwy menegaskan bahwa puisi modern Indonesia bisa menjadi ruang kontemplatif, bukan sekadar estetika formal, dan menuntut pembaca untuk menyelami pengalaman batin, bukan sekadar kata-kata.
3. Cirebon, 630 Tahun Kemudian …
(1. Pohon-pohon Api)
…..
Dari buritan pantai yang koyak, kapal-kapal Laksamana Cheng Ho
bertolak, menyusuri jejak kaki ribuan mil puteri kaisar Cina Ong Tien Nio
para prajurit dengan seragam menyala, membenamkan malam di atas pundak
burung-burung bangau, anak-anak-anak rantau, hutan jati serta gemuruh geladak
angin risau, uap air kemarau, empat ratus tahun dari 1600 masehi yang kelam
gerimis menetes di masjid tua, abdi-dalem bersila, batuk-batuk dan semedi
menuangkan perih doa, menaburkan sesaji pada pintu gapura yang terkunci
seperti seorang sunan yang gelisah, kususun kembali retak-retak sejarah
di antara tembikar, pelepah lontar, dan kitab-kitab yang bertuliskan darah
Lautan abrasi
rembulan sunyi
jalanan berduri
dan mata-angin bersaksi
Di tengah sayatan suluk dangdanggula yang bergetar, dukamu berlayar
ribuan kelelawar terbang dari remang keraton, udara gusar, pecahan marmar
alun-alun merah kesumba membelit langit bagai ular, meniti gulungan primbon
keramik guci, bongkahan terasi, sumur tujuh, dan rusuh babad tanah Cerbon
menghunjam di pematang cakrawala, menuruni aras tangga-tangga pendakian
lima abad silam: khutbah, jubah dan terompah sunan, terlepas dari gurat waktu
gugusan lapis pualam, uang logam, kelir hitam dan riang selendang ratu
menjemputku di riuh subuh, menari serimpi, mengusir arwah peri
dengan sekerat jimat, gema shalawat yang telah melampaui pusaran bumi
…..
Cirebon, 2000
Sumber: Ahmad Syubbanuddin Alwy, Fantasia Cirebon (Cirebon: Penerbit Mesti, 2017).
Alwy menempatkan sejarah lokal sebagai medium batin yang hidup dalam setiap baris puisinya. Dalam puisi “Cirebon, 630 Tahun Kemudian…”, ini barulah satu fragmen (“1. Pohon-pohon Api”) dari rencana besar seratus sajak yang akan ditulisnya. Keterbatasan sumber menunjukkan sajak ini “belum rampung” (baru sampai fragmen “2. Ilalang-ilalang Sembilu”), dan di sinilah humor khas Alwy muncul. Saat ditanya tentang karya yang tak kunjung selesai itu, ia berseloroh: “Begitu puisi itu selesai, maka selesailah sejarah kesusasteraan Indonesia!” Sindiran ringan ini menegaskan ambisi besar sekaligus kesadaran penyair akan keterbatasan hidup dan waktu.
Alwy menelaah arsip sejarah dan mengunjungi lokasi-lokasi penting di Cirebon, membangun panorama epik kota yang terasa hidup dan abadi. Setiap elemen sejarah, dari kapal Laksamana Cheng Ho hingga jejak puteri kaisar, tidak hanya direkam sebagai kronologi, tetapi dibaca melalui lensa batin penyair. Imaji-imaji visual yang terangkai, buritan pantai, remang keraton, alun-alun merah, guci keramik, bongkahan terasi, hingga rusuh babad tanah Cerbon, membentuk jaringan simbolik yang mengekspresikan perjalanan waktu, kehidupan sosial, dan kesadaran spiritual. Dengan cara ini, Cirebon hadir sebagai tubuh dan napas puisi, ruang kontemplatif di mana sejarah, lokalitas, dan pengalaman batin bersatu.
Dedikasi Alwy memberi nilai metodologis yang penting bagi kritik puisi Indonesia. Proses kreatifnya menegaskan bahwa puisi dapat menjadi hasil penelitian lapangan dan pengalaman empiris, bukan sekadar inspirasi spontan. Kritik yang membaca puisi semata dari permukaan bahasa dan estetika akan kehilangan inti karya: interaksi antara pengalaman batin, penelitian sejarah, dan simbolisme yang menyatukan realitas kota dengan kesadaran personal penyair.
Dalam perspektif saya, kutipan sajak ini menegaskan bahwa puisi Indonesia modern tidak hanya berfungsi sebagai medium estetis, tetapi juga sebagai medium kontemplatif sejarah. Setiap sajak dapat dibaca sebagai laboratorium batin, di mana lokalitas, dedikasi penelitian, refleksi spiritual, dan bahkan humor penyair membentuk narasi puitik yang kompleks dan alegoris. Kritik yang menyelami lapisan-lapisan ini akan mampu menempatkan karya Alwy dalam posisi strategis: sebagai dokumen kontemplatif sekaligus arsip batin yang merekam jejak manusia dan kota.
4. Apologia Sepasang Mata
— Abdurrahman Wahid
1
Di bawah bentangan malam yang semakin memanjang
ke ujung dermaga, dari semenanjung kota-kota tua:
mungkin Batavia, atau barangkali teluk Surabaya
yang kini dipenuhi prasasti, bidadari, berhala, boneka
condominium, dan jangan lupa tahun yang gores
juga seorang pendekar renta yang gelisah memainkan orkes
masih bertahan dalam remang waktu, mengabadikan sunyi
2
Tetapi, di tengah gerimis, pendar kegelapan dan percik luka
kita terlanjur gugup, memasuki kota-kota lain yang miskin :
mungkin Negeri Poci, atau gubuk-gubuk pesisir laut utara
yang berserakan di antara pohon api, amis ikan, rawa-rawa
ladang garam, dan yang menggetarkan perahu-perahu bertapa di
atas kerontang dada nelayan, menghadap keheningan cuaca
serpihan hari-hari seperti seratus senja yang berayun letih
3
Dan, di bawah bentangan malam, lambaian perih gerimis pagi
kembali kita menemukan sisa-sisa kenangan kota revolusi:
mungkin sebuah metropolitan kecil, atau noktah serambi mekah
yang berjuntaian dengan retakan kraton, grafis candi, labirin
seperti arkeologi, ada yang ingin menceritakan kisah-kisah purba
kepadamu, yang dituliskan dan dilukiskan pada sepasang mata
Cirebon, 1996
Sumber: Dari Amerika ke Catatan Langit (Antologi Puisi Mastera), 2005.
“Apologia Sepasang Mata” menghadirkan dimensi visual yang luar biasa kuat, di mana kota-kota tua, pelabuhan, dan pesisir laut utara tidak sekadar latar, tetapi menjadi medium alegoris pengalaman batin. Alwy membangun narasi dengan lapisan sejarah, sosial, dan spiritual, di mana setiap elemen, baik “prasasti, bidadari, berhala, boneka condominium” maupun perahu nelayan, menjadi simbol ketegangan antara kenangan, kehilangan, dan kesunyian.
Puisi ini menegaskan pengalaman eksistensial: manusia berjalan dalam sejarah yang berat, memasuki ruang-ruang miskin dan terlupakan, menghadapi “percik luka” dan “gerimis pagi” sebagai metafora perjalanan batin. Puisi ini menunjukkan bahwa imaji visual dan alegoris Alwy tidak dipisahkan dari refleksi batin, sehingga pembaca tidak hanya melihat kota, tetapi juga merasakan kesunyian, rindu, dan keterasingan yang dialami penyair.
Menurut saya, “Apologia Sepasang Mata” menekankan integrasi sejarah, eksistensi, dan refleksi spiritual sebagai metode kreatif. Kota bukan sekadar setting geografis; ia menjadi subjek dialog batin penyair. Keseriusan Alwy dalam menata imaji, menautkan sejarah lokal, dan mempersonalisasi pengalaman sosial menjadikan puisi ini contoh khas perpuisian Indonesia modern yang kontemplatif, alegoris, dan reflektif.
5. Kenangan Seperempat Abad Silam
jalan-jalan masih berdarah, liku pohon
berkabut dalam risik gelisah, riuh pertempuran
menghambur hancur ke pelukanku semalaman, dan …
Aku terlunta memandang pematang tubuhku penuh ilalang
halilintar menggelepar, bayang-bayang kematian terbentang
juntai bunga api, bilur fajar pagi, dan kilau cahaya galaksi
merayakan kesepian panjang. Dan seperti tak pernah mengenalmu
senantiasa, kuciptakan kembali busur kiblat untuk mengungsi
dan puing-puing, juga retakan waktu yang berangkat tua
menyentuh ulu hatiku dengan sisa kenangan, seperempat abad silam:
alunan dzikir, samudera takbir, dan gemerincing gerimis muram
berpendaran dari sayatan hari-hariku menjadi rintihan puisi
Di lereng tebing ruhaniku, serpihan masa kanak-kanak itu
melukiskan gelombang tangis nyeri pada gari,
doa-doa para sufi beterbangan meniti tangga-tangga
dan pintu langit ampunanmu
rasi bintang-bintang menyisih dari pusaran lambung matahari
deru angin berhamburan membelah pecah imanku yang menyangga
tapi seperti Ibrahim, aku masih menemukan isyarat dan getar rahasia
wajah pualam rembulan, hamparan laut kelam, kemudian kesunyian
di kejauhan, seribu purnama menyepuh berhelai-helai airmataku
yang tergerai dan berdarah, mencium sajadah dan hulu tanah
menara-menara masjid menjulang, ayat-ayat suci bermekaran
di tengah kolam teratai yang bertasbih perih dalam rongga dadaku
seperti orang alim, kuterima gulungan lumpur dan gosong rawa-rawa
juga semenanjung karang, perahu para perusuh yang datang dari jauh
melewati metabolisme darah untuk menyalahkan serat api yang angkuh
kelak melumuri separoh kota menjadi kilang minyak, kuseduh dengan gembira
jaritan caci-maki, lengking gelak-tawa dan rangkaian panjang selongsong senjata
mengapakah perkampungan miskin yang papa kauhanguskan juga menjadi arang
dan menyekapku di tengah kepulauan negeri, dihujani arak serta ledakan perang?
kini, kulupakan kenangan seperempat abad silam masa kanak-kanak yang syahdu:
pesisir bendungan dengan tanah segar, laut ganggang dan mendung bagai salju
Cirebon, 1999–2000
Sumber: Buruan.co, 16 Februari 2018
“Kenangan Seperempat Abad Silam” memperlihatkan puisi sebagai arsip batin, di mana memori masa kecil, pengalaman traumatis, dan refleksi spiritual berlapis dalam satu aliran narasi. Alwy tidak sekadar menulis tentang kenangan personal; ia menautkan masa lampau dengan pengalaman sosial, eksistensi kolektif, dan simbol religius, sehingga puisi ini berfungsi sebagai ruang kontemplatif yang menembus waktu dan kesadaran.
Imagi alam (“pesisir bendungan”, “laut ganggang dan mendung bagai salju”) berpadu dengan simbol sufistik, dzikir, dan ayat-ayat masjid, menciptakan simfoni batin yang kompleks. Rasa kehilangan dan kesepian dihadirkan melalui metafora yang kuat, seperti “juntai bunga api, bilur fajar pagi, dan kilau cahaya galaksi” yang menandai perpaduan antara pengalaman kosmik, personal, dan historis.
Dalam pandangan saya, puisi ini menegaskan beberapa dimensi:
1. Spiritualitas sebagai motor imaji, di mana dzikir, doa, dan simbol sufistik membentuk inti pengalaman batin;
2. Sejarah dan trauma sebagai kesadaran kolektif, tercermin dalam puing-puing, perahu perusuh, dan ledakan perang;
3. Eksistensi dan kesunyian: masa kanak-kanak dan pengalaman pribadi menjadi medium untuk merenungkan realitas manusia dan relasi dengan Tuhan;
4. Dedikasi dan metodologi penyair: penggabungan pengalaman lapangan, sejarah lokal, dan meditasi batin menunjukkan disiplin kreatif yang tinggi.
Puisi ini menutup rangkaian lima karya yang kita kaji, menegaskan bahwa dunia Alwy adalah pertemuan antara spiritualitas, sejarah lokal, dan refleksi eksistensial, yang menjadikan perpuisian modern Indonesia lebih kaya dan kontemplatif.
IV. Sintesis Tematik dan Dunia Ahmad Syubbanuddin Alwy
1. Spiritualitas dan Estetika: Puisi sebagai Suluk Modern
Dalam puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy, spiritualitas tidak hadir sebagai ornamen atau pesan normatif, melainkan sebagai sumber imaji, ritme, dan simbol yang menghidupi keseluruhan bangunan puisi. Pengalaman batin (kesedihan, kerinduan, cinta, dan pencarian) ditransformasikan menjadi bahasa puitik yang bergerak seperti perjalanan ruhani. Puisi, bagi Alwy, berfungsi sebagai suluk modern: jalan batin yang ditempuh melalui kata.
Hal ini tampak jelas dalam “Lirik Airmata” (Cirebon, 1992), ketika dzikir, doa, dan tradisi sufistik menjadi kerangka penghayatan pengalaman personal: “seribu masjid menyeduh jiwaku yang merana / dengan zikir-zikir luka. Tapi sepanjang mabuk ini / kuseberangi lautan cintamu bersama doa-doa Rumi / dan nyanyian-nyanyian Rabi’ah.”
Baris-baris tersebut memperlihatkan bagaimana pengalaman eksistensial dipadukan dengan rujukan spiritual yang hidup. Dzikir tidak berfungsi sebagai simbol abstrak, melainkan sebagai ritme batin; doa menjadi jembatan antara luka personal dan cinta ilahiah. Enjambement dan pilihan diksi menghadirkan kesan kontemplatif, seolah pembaca diajak berjalan perlahan menapaki tangga kesadaran bersama penyair.
Kecenderungan serupa muncul dalam “Bentangan Sunyi” (Cirebon, 1993), ketika ruang ibadah dan pengalaman sejarah personal bertaut dalam satu lanskap puitik: “Di sini, di mihrab masjid yang terbuka / ke muaramu, ribuan gerimis mendekapku dalam irama tangis / tetap setiap cahaya datang, kembali membakar doa-doa / dan sujud khusyukku kepadamu.”
Religiusitas dan estetika tidak berdiri terpisah; keduanya saling menembus. Kesadaran spiritual hadir melalui pengalaman inderawi dan emosional, sehingga puisi tidak hanya dibaca, tetapi juga dialami. Dalam konteks ini, Alwy menegaskan bahwa puisi modern mampu menjadi medium pengalaman mistik kontemporer, bersifat personal, historis, dan sekaligus kosmik.
Integrasi ini menuntut kritik sastra untuk membaca puisi tidak semata sebagai permainan bahasa atau bentuk, tetapi sebagai ruang pemaknaan batin. Simbol sufistik, doa, dan dzikir berfungsi sebagai perangkat naratif dan konseptual yang menyatukan pengalaman individual dengan kesadaran semesta. Puisi Alwy dengan demikian berperan sebagai arsip batin sekaligus dokumen estetis.
2. Sejarah dan Lokalitas: Cirebon sebagai Ruang Kontemplatif
Sejarah dan lokalitas dalam puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy tidak ditempatkan sebagai latar atau informasi faktual, melainkan sebagai medium batin yang memberi kedalaman spiritual dan emosional. Kota Cirebon, khususnya, hadir bukan sekadar sebagai ruang geografis, tetapi sebagai tubuh hidup yang menyatu dengan kesadaran penyair.
Hal ini terlihat dalam puisi “Cirebon, 630 Tahun Kemudian…”, ketika jejak sejarah, kapal Laksamana Cheng Ho atau puteri Ong Tien Nio, menjadi pintu masuk bagi refleksi eksistensial: “Dari buritan pantai yang koyak / kapal-kapal Laksamana Cheng Ho bertolak / menyusuri jejak kaki ribuan mil puteri kaisar Cina Ong Tien Nio.”
Puisi tersebut lahir dari proses penghayatan yang panjang. Alwy berulang kali mendatangi situs-situs sejarah, menelusuri arsip, dan menyerap atmosfer kota secara langsung. Sejarah tidak diperlakukan sebagai kronik, tetapi diinternalisasi sebagai pengalaman batin. Kota hadir sebagai napas yang menghidupi ingatan personal dan kolektif.
Dalam puisinya, retakan kraton, labirin candi, dan lanskap pesisir bukan sekadar bangunan atau panorama, melainkan simbol perjalanan batin manusia. Sejarah lokal ditautkan dengan pengalaman religius dan eksistensial, sehingga puisi berfungsi sebagai mekanisme penataan memori: menghubungkan fakta lahir dengan kesadaran batin.
Ketidakrampungan “Cirebon, 630 Tahun Kemudian…” akibat wafatnya penyair (2 November 2015), justru mempertegas bahwa karya Alwy adalah proses pencarian yang terus berlangsung. Memahami Cirebon berarti memahami perjalanan batin penyair. Kota, dalam puisinya, menjadi metafora tubuh yang hidup, bernapas, dan berinteraksi dengan kesadaran manusia.
3. Kesunyian dan Eksistensi: Medan Batin Pengalaman Universal
Kesunyian merupakan salah satu poros utama dalam dunia puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy. Ia tidak dimaknai sebagai ketiadaan suara, melainkan sebagai dimensi batin tempat refleksi eksistensial dan meditasi spiritual berlangsung. Puisi-puisi seperti “Lirik Airmata” dan “Bentangan Sunyi” menjadikan kesunyian sebagai ruang pertapaan batin: “Dalam lorong-lorong gelap itu, aku kini pengembara / gemuruh kesunyian dan bentangan airmata.”
Kesunyian di sini bersifat aktif; ia menggerakkan kesadaran, membuka ruang bagi doa, rindu, dan perenungan atas keterbatasan manusia. Dalam “Kenangan Seperempat Abad Silam” (Cirebon, 1999–2000), kesunyian berkelindan dengan pengalaman personal dan sejarah: “Aku terlunta memandang pematang tubuhku penuh ilalang / halilintar menggelepar, bayang-bayang kematian terbentang.”
Pengalaman individual, trauma sosial, dan ingatan kolektif disusun dalam lanskap batin yang hening. Kesunyian menjadi simbol kontemplasi manusia modern yang mencari makna di tengah sejarah, penderitaan, dan kefanaan. Puisi Alwy menunjukkan bahwa pengalaman eksistensial, baik personal maupun kolektif, dapat dijelajahi melalui ruang batin yang sunyi, tempat doa dan refleksi bertemu.
Kontribusi Alwy bagi puisi Indonesia tampak pada penegasan bahwa puisi modern tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga menjadi medium eksplorasi kesadaran eksistensial. Kritik sastra, karenanya, dituntut untuk menelusuri lapisan batin ini, bukan hanya berhenti pada analisis bentuk dan gaya.
4. Imajinasi Visual dan Alegoris: Kota, Sejarah, dan Batin
Kekuatan lain puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy terletak pada imajinasi visual yang tajam dan bersifat alegoris. Lanskap kota, situs sejarah, dan panorama alam diolah menjadi simbol perjalanan batin. Dalam “Apologia Sepasang Mata” (Cirebon, 1996), kota tua dan pesisir laut tampil sebagai ruang kontemplatif: “Dan, di bawah bentangan malam, lambaian perih gerimis pagi / kembali kita menemukan sisa-sisa kenangan kota revolusi … / retakan kraton, grafis candi, labirin / seperti arkeologi …”
Kraton, labirin, dan candi berfungsi sebagai medium alegoris yang menghubungkan realitas fisik dengan refleksi batin. Kota tidak sekadar digambarkan, tetapi ditafsirkan sebagai ruang di mana masa lalu, pengalaman personal, dan simbolisme spiritual saling berinteraksi.
Dalam kerangka kritik sastra, imajinasi semacam ini menegaskan bahwa puisi modern memerlukan pembacaan simbolik yang menembus realitas sehari-hari. Seperti dikemukakan John Sturrock, puisi modern menuntut tafsir atas struktur imaji dan simbol, bukan sekadar kenikmatan bahasa (Structuralism and Since: From Levi-Strauss to Derrida. Oxford: Oxford University Press, 1979). Dalam puisi Alwy, lanskap historis menjadi sarana mengekspresikan pengalaman spiritual, sosial, dan eksistensial secara bersamaan.
Imaji visual Alwy selalu berakar pada pengalaman nyata dan penelitian lapangan. Oleh karena itu, kota dan sejarah tidak berfungsi sebagai dekorasi, melainkan sebagai medium batin. Puisi menjadi arsip batin sekaligus dokumen simbolik yang menyatukan pengalaman personal, sejarah lokal, dan kontemplasi spiritual.
5. Disiplin Kreatif dan Dedikasi Personal
Seluruh dunia puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy ditopang oleh disiplin kreatif yang kuat. Ia tidak mengandalkan spontanitas semata; setiap puisi lahir dari perpaduan penelitian, pengamatan lapangan, dan pengendapan batin. Proses kreatif menjadi ruang kerja intelektual sekaligus spiritual.
Dalam “Cirebon, 630 Tahun Kemudian…”, Alwy menelusuri arsip sejarah, mengunjungi situs-situs penting, dan menghayati tradisi lokal sebelum menyusunnya menjadi puisi. Fakta sejarah tidak disajikan secara mentah, tetapi diolah menjadi pengalaman emosional dan spiritual bagi pembaca. Hal serupa tampak dalam karya-karya religiusnya, ketika dzikir, doa, dan gema alam muncul sebagai hasil pengamatan mendalam terhadap kehidupan sehari-hari.
Disiplin ini juga mencerminkan etika berkarya. Kesungguhan Alwy menghadirkan Cirebon sebagai tubuh dan napas puisi menuntut kesabaran dan komitmen jangka panjang. Bahkan dalam kondisi fisik yang terbatas, ia tetap hadir dalam ruang budaya dan forum sastra, menegaskan bahwa puisi adalah tanggung jawab moral dan sosial, bukan sekadar ekspresi personal.
Dari sudut pandang kritik sastra, disiplin dan dedikasi ini menghadirkan model pembacaan yang lebih utuh. Karya Alwy menuntut pemahaman atas proses kreatif (penelitian, pengalaman batin, dan refleksi spiritual) yang melahirkan teks. Dengan demikian, puisi modern tampil sebagai hasil perjalanan batin yang panjang, sekaligus medium kontemplatif yang mengintegrasikan sejarah, spiritualitas, dan pengalaman hidup.
V. Kontribusi bagi Kritik Sastra Indonesia
1. Puisi Modern sebagai Ruang Kontemplasi dan Arsip Kemanusiaan
Kehadiran puisi-puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy dalam lanskap sastra Indonesia memperluas pemahaman tentang fungsi puisi modern. Puisi tidak lagi semata dipahami sebagai medan eksperimen bahasa atau ekspresi subjektivitas individual, melainkan sebagai ruang kontemplasi yang merekam pengalaman manusia dalam hubungannya dengan sejarah, tempat, dan Yang Transenden. Dalam pengertian ini, puisi berfungsi sebagai arsip batin: bukan arsip faktual, tetapi arsip pengalaman kemanusiaan.
Kontribusi ini penting karena kritik sastra Indonesia selama beberapa dekade cenderung memisahkan antara puisi modern dan muatan spiritual-historis. Modernitas sering dipahami sebagai pemutusan dari tradisi, lokalitas, dan kesadaran religius. Puisi Alwy justru menunjukkan arah sebaliknya: modernitas puisi terletak pada kemampuannya mengolah sejarah, spiritualitas, dan pengalaman eksistensial secara reflektif, personal, dan sadar bentuk.
Dengan demikian, kritik sastra ditantang untuk membaca puisi modern bukan hanya sebagai teks estetik, tetapi sebagai medan kesadaran. Puisi menjadi tempat di mana sejarah lokal, pengalaman religius, dan pergulatan batin manusia direkam secara simbolik. Perspektif ini memperkaya kritik sastra Indonesia dengan membuka kemungkinan pembacaan yang lebih etis, reflektif, dan kontekstual, tanpa harus meninggalkan ketajaman estetika.
2. Proses Kreatif sebagai Horison Pembacaan Kritik
Salah satu sumbangan konseptual penting dari dunia puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy adalah penegasan bahwa proses kreatif bukan wilayah pinggiran, melainkan inti dari pemaknaan karya. Puisi tidak lahir dari spontanitas kosong, tetapi dari perjalanan batin yang panjang, disiplin penghayatan, dan keterlibatan langsung penyair dengan realitas sosial, sejarah, dan spiritual.
Dalam konteks kritik sastra, hal ini menggeser orientasi pembacaan dari sekadar “apa yang tertulis” menuju “bagaimana teks itu menjadi”. Proses kreatif (pengendapan batin, pencarian makna, keterlibatan dengan ruang dan waktu) menjadi horison penting untuk memahami struktur imaji, simbol, dan alegori dalam puisi. Kritik yang mengabaikan dimensi ini berisiko mereduksi puisi menjadi artefak bahasa semata.
Model ini menawarkan koreksi terhadap kecenderungan kritik formalistik yang terlalu menutup diri pada konteks penciptaan. Dalam puisi Alwy, teks tidak dapat dilepaskan dari perjalanan batin penyairnya. Oleh karena itu, kritik sastra Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih dialogis: membaca puisi sebagai hasil interaksi antara kesadaran penyair, realitas sosial-historis, dan pengalaman spiritual yang membentuk teks secara organik.
3. Menuju Metodologi Kritik Puisi yang Integratif
Dari keseluruhan karya dan sikap kreatif Ahmad Syubbanuddin Alwy, tampak sebuah tawaran metodologis yang relevan bagi kritik puisi modern Indonesia. Metodologi ini tidak hadir sebagai rumusan teoretis eksplisit, tetapi sebagai praktik estetik yang konsisten: membaca puisi sebagai pertemuan antara spiritualitas, sejarah, dan pengalaman personal dalam satu kesatuan makna.
Metodologi integratif ini menolak dikotomi antara estetika dan makna, antara modernitas dan tradisi, antara subjektivitas dan sejarah. Puisi dipahami sebagai ruang di mana semua lapisan itu saling berkelindan. Kritik sastra, karenanya, dituntut untuk bersifat hermeneutik: menafsir teks dengan kesadaran atas lapisan batin, simbol, dan pengalaman yang melahirkannya.
Dalam konteks sastra Indonesia yang plural, baik secara budaya, sejarah, maupun religius, pendekatan semacam ini menjadi penting. Ia memungkinkan kritik sastra bergerak melampaui penilaian teknis menuju pemahaman yang lebih utuh tentang pengalaman manusia yang dihadirkan puisi. Melalui dunia puitiknya, Ahmad Syubbanuddin Alwy tidak hanya menyumbang karya, tetapi juga membuka jalan bagi kritik sastra yang lebih reflektif, berakar, dan manusiawi.
VI. Kesimpulan
Dari keseluruhan pembacaan yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa dunia puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy dibangun melalui perpaduan yang erat antara spiritualitas, sejarah, dan pengalaman eksistensial manusia. Ketiga unsur tersebut tidak hadir sebagai tema-tema terpisah, melainkan sebagai struktur makna yang saling berkelindan dan membentuk satu kesadaran puitik yang utuh. Spiritualitas bekerja sebagai energi batin yang menggerakkan imaji dan ritme bahasa; sejarah dan lokalitas menjadi ruang konkret tempat kesadaran itu berjejak; sementara pengalaman eksistensial (kesunyian, luka, rindu, dan pencarian) menjadi medan penghayatan yang menghubungkan keduanya. Dunia puisi Alwy, dengan demikian, bukan sekadar representasi realitas, melainkan proses pemaknaan manusia atas keberadaannya di dalam sejarah dan di hadapan Yang Transenden.
Puisi-puisi Alwy sekaligus menunjukkan bahwa puisi modern Indonesia memiliki kemungkinan integratif yang luas. Pengalaman batin, kesadaran estetik, dan pendekatan dokumentatif tidak saling meniadakan, melainkan dapat dipadukan secara reflektif dan sadar bentuk. Sejarah dan lokalitas, seperti Cirebon, tidak direkam secara kronikal, tetapi dihayati, ditelusuri, dan diendapkan menjadi pengalaman batin yang kemudian ditransformasikan ke dalam bahasa simbolik. Dalam konteks ini, puisi berfungsi sebagai arsip kemanusiaan: merekam ingatan, pergulatan spiritual, dan kesadaran eksistensial manusia tanpa kehilangan daya estetiknya. Modernitas puisi, sebagaimana diperlihatkan Alwy, justru terletak pada kemampuannya mengolah pengalaman konkret dan sejarah lokal menjadi medan kontemplasi yang hidup dan terbuka bagi pembacaan ulang.
Implikasi dari dunia puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy terhadap kritik sastra Indonesia menjadi sangat signifikan. Kritik sastra tidak lagi memadai jika hanya berhenti pada analisis bentuk, gaya bahasa, atau struktur teks. Karya-karya Alwy menuntut pendekatan yang lebih reflektif dan integratif; pendekatan yang memberi perhatian pada dimensi batin, disiplin kreatif, dan pengalaman personal penyair sebagai bagian tak terpisahkan dari makna teks. Proses kreatif (yang mencakup penghayatan lapangan, penelitian sejarah, pengendapan spiritual, dan dedikasi etis) perlu dibaca sebagai horison penting dalam memahami puisi modern.
Dengan cara pandang demikian, kritik sastra Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi estetika, tetapi juga sebagai ruang dialog kemanusiaan. Dunia puisi Ahmad Syubbanuddin Alwy, pada akhirnya, membuka jalan bagi kritik sastra yang lebih berakar pada pengalaman hidup, lebih peka terhadap kompleksitas batin manusia, dan lebih manusiawi dalam membaca puisi modern; bukan sekadar sebagai teks, tetapi sebagai jejak perjalanan kesadaran.***
Daftar Pustaka
Alwy, Ahmad Syubbanuddin. 1996. Bentangan Sunyi. Bandung: Forum Sastra Bandung.
Alwy, Ahmad Syubbanuddin. 2000. “Cirebon, 630 Tahun Kemudian…”. Pikiran Rakyat, 21 November 2015.
Alwy, Ahmad Syubbanuddin. 2005. “Apologia Sepasang Mata”, “Bentangan Sunyi”, “Lirik Airmata”. Dari Amerika ke Catatan Langit (Antologi Puisi Mastera), Editor: Dendy Sugono & Abdul Rozak Zaidan, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
Alwy, Ahmad Syubbanuddin. 2017. Fantasia Cirebon. Cirebon: Penerbit Mesti.
Alwy, Ahmad Syubbanuddin. 2018. “Kenangan Seperempat Abad Silam.” Buruan.co, 16 February 2018. https://www.buruan.co/ketika-seorang-ibu-mengenang-sang-penyair/.
Sturrock, John. 1979. Structuralism and Since: From Levi-Strauss to Derrida. Oxford: Oxford University Press.
Teeuw, A. 1980. Tergantung pada Kata. Jakarta: Pustaka Jaya.
——
*Penulis adalah penyair dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.