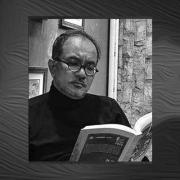Puisi-puisi Abdul Wachid B.S.
BALADA GETHUK GORENG SOKARAJA
Malam jatuh di Sokaraja.
Pelan.
Seperti daun singkong
yang tahu kapan harus gugur.
Di dapur kecil,
air mendidih tanpa saksi.
Singkong direbus
seperti hidup direbus waktu,
tidak boleh terlalu cepat,
tidak boleh mengeluh.
Gethuk… gethuk…
ora nasi ora napa,
yen ati eling lan sabar,
weteng ya bisa diajak rembugan.
Alu memukul alu.
Bunyi tumpul
seperti dada orang kecil
yang jarang didengar.
Singkong ditumbuk
hingga lupa
bahwa ia pernah keras.
Gula kelapa mencair,
coklatnya pekat
seperti senja yang terlalu lama
menunggu pulang.
Gethuk digodhog,
gethuk digoreng,
sing ora digoreng
mung nasibe wong kesrakat.
Wajan hitam dipanaskan.
Minyak menunggu.
Takdir tidak pernah ramah,
hanya setia.
Gethuk dilempar ke dalamnya.
Minyak mendesis
seperti doa yang kepanasan.
Sebentar saja,
agar tidak hangus,
agar bisa bertahan
lebih lama dari hari ini.
Aja kesusu, Le,
urip ora dikejar setan,
sing gosong dudu gethuk,
nanging ati sing kebacut panas.
Di luar,
jalan Sokaraja lengang.
Belanda pernah lewat.
Waktu juga lewat.
Yang tinggal
hanya bau minyak
dan tangan yang tetap bekerja.
Anak-anak menggigit gethuk
dengan gigi susu
dan tawa yang belum tahu beban.
Orang tua mengunyah pelan,
seperti membaca nasib
tanpa mengeja.
Manise ora njerit,
gurihé ora ngapusi,
kaya urip wong Banyumas:
cukup yen ora dumeh.
Malam makin dalam.
Wajan dingin.
Gethuk habis.
Tapi di udara
sesuatu masih tinggal,
bukan bau,
melainkan tekad
yang tidak suka dipamerkan.
Dan Sokaraja tidur
tanpa merasa kalah.
Sebab dari singkong,
ia belajar satu hal:
bahwa hidup
tidak harus mewah
untuk bisa hangat.
Gethuk… gethuk…
saka lemah bali menyang lemah,
yen Gusti paring cukup,
urip ora perlu akeh polah.
2025
BALADA WAYANG SUKET
1.
Di tepi galengan,
anak-anak menunduk memunguti rumput,
bukan untuk pakan,
tetapi untuk cerita.
Sukêt dilipat pelan,
seperti doa orang kecil
yang tidak berani keras-keras.
2.
Jari-jari itu belum tahu Mahabharata,
belum hafal silsilah dewa,
tetapi sudah paham satu hal:
hidup bisa disusun
dari apa saja
asal sabar dan niatnya lurus.
3.
Gatotkaca lahir dari lipatan,
bukan dari langit.
Sayapnya miring,
tangannya membawa jejak
bengkok takdir,
namun keberaniannya tumbuh
sebab ia dibentuk
dengan kesabaran para dewa.
4.
Wayang ini tak tahan lama.
Sore kering,
malam lembap,
besok pagi mungkin hancur.
Tetapi justru di situlah ajarannya:
bahwa yang cepat hilang
sering paling jujur.
5.
Tidak ada kelir,
tidak ada blencong.
Hanya dinding bambu,
lampu sentir,
dan suara anak
yang mendalang dengan terbata-bata.
Cerita berjalan pincang,
namun maknanya sampai.
6.
Seorang dalang dewasa
pernah mengangkatnya ke panggung.
Bukan rumputnya yang ia besarkan,
tetapi napas ceritanya.
Sukêt boleh berganti,
tetapi tutur
harus tetap hidup.
7.
Ia mendalang dengan apa saja:
rumput, daun,
bahkan serpihan sunyi.
Karena baginya,
wayang bukan soal bentuk,
tetapi kemampuan
menuntun imajinasi
agar pulang ke dirinya sendiri.
8.
Seperti gamelan kadang menyela,
kadang diam.
Seperti tubuh penari bergerak,
lalu berhenti.
Panggung tidak menetap,
seperti hidup
yang selalu berubah latar
tanpa izin.
9.
Penonton dibawa masuk
ke bayangan yang lebih dalam,
tempat manusia melihat dirinya
sebagai wayang
yang digerakkan
oleh niat dan lupa.
10.
Wayang suket mengingatkan:
bahwa cerita tidak butuh kemewahan,
pendidikan tidak selalu bernama sekolah,
dan kebijaksanaan
bisa tumbuh
di tangan anak desa.
11.
Ia rapuh,
ia sederhana,
ia tidak ingin abadi.
Tetapi selama masih ada
orang yang mau melipat rumput
menjadi makna,
wayang tidak akan mati.
12.
Malam selesai.
Sukêt ditinggal di tanah.
Besok ia kembali menjadi rumput.
Namun cerita
telah berpindah
ke dalam dada manusia,
dan di sanalah
ia bertahan lebih lama.
2025
BALADA WAYANG SUKET MBAH GEPUK
1.
Di gubuk tegalan pinggir hutan,
rumput kasuran menunggu tangan tua.
Mbah Gepuk duduk bersila,
mata menatap daun yang jatuh perlahan.
Tangan mengangkat, memukul – gepuk pertama,
seperti manusia yang harus menempuh cobaan
sebelum kata bisa keluar dari dada.
2.
Helai demi helai direndam, dilembutkan,
hati ikut lentur sebelum menerima ilmu.
Batang kuning kecoklatan, lentur, menari
menjadi tulang tokoh-tokoh yang hidup
di balik bayangan,
di balik napas anak-anak yang menahan rasa penasaran.
3.
Wisanggeni lahir dari tangan tua itu,
bukan dari Mahabharata,
tapi dari napas desa,
dari ketekunan, dari kesabaran, dari keberanian,
mengalir di anyaman suket
ke jiwa yang menonton, bergetar dalam senyap.
4.
Hidung diikat, wajah terbentuk, kepala tersusun,
setiap anyaman mengikuti alur hidup:
wajah → kepala → badan → kaki.
Anak belajar dari urutannya,
bahwa baik dan buruk lahir dari pilihan
dan kesabaran yang menempel di tangan.
5.
Tangan Mbah Gepuk menari perlahan,
menganyam gelang, sumping, kunca,
tidak rata, tidak berimbang,
tapi indah dalam ketidaksempurnaan.
Pelajaran hidup: sabar, telaten, tekun, ulet,
bersama napas dan ketukan kecil dari daun.
6.
Setiap tokoh, setiap bayangan,
mengajar anak-anak desa
tentang jalan hidup yang bercabang,
tentang setan yang menggoda,
tentang ujian yang harus dilewati
dengan hati terbuka dan dada lapang.
7.
Dalang tua itu bukan penguasa,
ia pangon, penjaga arah dan rasa.
Ia membiarkan bayangan menari sendiri,
mengikuti napas penonton,
belajar dari cahaya lampu,
belajar dari kegelapan panggung.
8.
Dan ketika Wisanggeni menoleh,
tangan anak-anak menahan napas,
jiwa mereka menyerap pelajaran tanpa suara,
hidup bukan tentang cepat atau lambat,
tapi tentang sabar, kendali diri, dan hati yang teguh.
9.
Rumput kasuran kembali ke bumi,
bayangan lenyap di matahari sore,
Mbah Gepuk tersenyum, diam.
Setiap ciptaan manusia
adalah pelajaran bagi jiwa,
desa, tangan, dan iman
bersatu dalam satu napas:
menata dunia dari daun, tangan, dan hati.
10.
Dan malam turun perlahan,
anak-anak pulang membawa bayangan,
pelajaran, dan rasa hormat.
Wayang suket tetap di gubuk,
tetapi nilai yang dihidupkan Mbah Gepuk
mengalir di sawah, di rumah, di hati mereka,
seperti doa tak terucap
yang terasa di seluruh hidup.
2025
BALADA GEBUG BEGALAN
1.
Siang datang dengan sinar lembut di atas genting desa,
Gunareka memanggul brenong kepang
seolah bayi yang rewel,
Rekaguna menari di atas atap bambu,
kucing pun mundur hormat,
kentongan menatap dengan mata bulat, siap menjerit:
“Siapa berani menertawakan,
dia akan tersambar tawa ini!”
2.
Pedang kayu berputar di udara,
menebas daun yang bergoyang,
Brenong terlempar,
melayang seperti bintang yang tersesat,
anak-anak berteriak, melompat dari atap,
sementara ibu-ibu menabur palawija
seperti hujan berkah,
tetua berdiri, mulut tersenyum tapi mata mengerling:
“Ini bukan perkelahian, Nak, ini ujian sabar…
dan keberanian untuk tertawa!”
3.
Gunareka tersandung,
benda-benda beterbangan mengikuti langkahnya,
Rekaguna menepuk pundak tanpa izin,
lalu melesat ke tumpukan beras,
Brenong bergetar seperti hati desa,
“Dengar, Nak, suara ini bisikan leluhur:
Jika rumah tangga keras, pukulannya harus tepat,
jangan sampai tawa hilang di udara!”
4.
Di jalan setapak,
kelinci ikut menari, ayam menunduk hormat,
tumpeng meluncur ringan seperti daun jatuh di sawah,
daun jati bergoyang mengikuti irama mengejutkan,
Gunareka tertawa keras,
“Ini rumah tangga, bukan medan laga!”
Tetua mengangguk,
Rekaguna melempar nasi ke arah langit.
5.
Setiap langkah memecah keheningan,
anak-anak menjerit, tertawa,
berlari sambil membawa daun,
tangan-tangan tak terlihat menepuk pundak,
palawija menirukan suara tetua:
“Rumah tangga bukan soal siapa menang,
tapi siapa bisa menari
sambil tersenyum di tengah hujan beras!”
6.
Kentongan menjerit, bres… bres… duk-dug…
seperti jantung desa yang berdebar,
Rekaguna menekuk,
tersenyum sambil menabur tumpeng,
Gunareka menepuk bahunya sendiri:
“Jika kau bisa tertawa
atas kebingunganmu sendiri, Nak,
kau telah menemukan doa paling manis.”
7.
Adegan mengejutkan dimulai,
tumpukan padi berubah warna,
ayam dan kucing menonton dengan mata bulat,
anak-anak melompat dari genting,
menangkap buah yang jatuh,
tetua berkata: “Jika kalian masih takut,
biarkan daun jati mengajarkan sabar,
bukan kata-kata!”
8.
Palawija bergetar, berbisik, seolah bernyanyi sendiri,
Brenong terbang ke atap, lalu kembali ke tanah,
Gunareka tersenyum, Rekaguna mengangguk,
“Rumah tangga adalah tarian liar:
kadang lucu, kadang mengejutkan,
dan selalu ada pelajaran di balik setiap gelak tawa.”
9.
Sore menurunkan sinar ke sawah,
angin membawa aroma nasi dan daun palawija,
anak-anak menatap Gunareka dan Rekaguna,
“Ini sungguh permainan, atau pelajaran?”
Tetua menjawab: “Keduanya.
Rumah tangga adalah permainan suci, gelak tawa
yang mengikat hati,
dan doa yang menari di udara.”
10.
Dan ketika senja menutup hari,
Brenong kosong dibawa pulang,
tapi tawa tetap menempel,
tumpeng yang melayang menemukan rumah baru
di atap tetangga,
dan manusia menatap rumah tangganya sendiri,
tersenyum, sadar:
jika bisa tertawa bersama,
jika bisa menari bersama di tengah kekacauan,
maka rumah tangga menjadi suci,
lebih dari doa yang hanya di ucapan,
lebih dari nasihat yang disimpan.
2025
BALADA EBEG BANYUMASAN
Siang terbelah di tanah lapang.
Matahari berdiri,
bulat, merah,
seperti genderang tua
yang dipukul takdir.
Dari bambu-bambu
kuda diangkat ke udara.
Ijuk bergetar di tangan angin.
Bumi menahan napasnya
— oh bumi,
yang selalu tahu
kapan kaki akan jatuh.
Calung bersuara dari tulang waktu.
Kendang memanggil dada
agar ingat cara berdebar.
Para penunggang menanggalkan nama,
menaruh wajah di pinggir lapangan,
lalu masuk ke tubuh
seperti masuk ke malam
yang pernah mereka kenal.
Mereka bukan pahlawan cerita.
Bukan ksatria dari kitab.
Mereka debu yang bangkit,
langkah yang belajar tegak,
rakyat yang menari
melawan gentar
tanpa teriak,
tanpa pedang,
hanya kaki
dan nyali.
Kuda bambu meringkik
tanpa suara.
Namun tanah mendengarnya.
Debu naik,
doa yang belum bersih.
Keringat jatuh,
air asin dari kerja hidup.
Tembang-tembang tua mengalun
seperti nasihat
yang tak perlu dipahami.
Di tepi lapangan
bayang macan membuka rahang.
Bukan lapar darah,
bukan amarah rimba.
Ia berjaga,
penjaga garis tipis
antara sadar dan hanyut,
antara manusia
dan yang sedang menumpang
di dalamnya.
Napas menebal.
Mata menjadi pintu.
Tubuh disinggahi sesuatu
yang lebih tua
dari silsilah dan doa.
Daun, padi, bunga
masuk ke mulut
sebagai bahasa rahasia
yang hanya dimengerti tanah
dan akar.
Tak ada jerit pecah.
Tak ada penghakiman.
Tetua berdiri,
pasak tua menahan langit.
Ia tahu:
yang bergerak bukan kegilaan,
melainkan titipan
yang ingin pulang
melalui tubuh manusia.
Penonton ikut bergeser.
Bukan karena dipanggil.
Bukan karena ingin.
Melainkan karena tubuh
menyimpan lorong gelap
yang kadang terbuka sendiri.
Dan denyut lama
tak pernah lupa
alamatnya.
Kendang diperlambat.
Satu per satu tubuh kembali.
Kuda bambu diturunkan
dengan tangan gemetar-sabar.
Ijuk diselimuti debu sore.
Matahari condong,
lelah,
jinak,
seperti ayah
yang akhirnya diam.
Yang tinggal bukan kisah.
Yang tinggal rasa.
Bahwa manusia pernah hidup
tanpa banyak kata.
Bahwa tubuh pernah menjadi kitab.
Bahwa desa,
dengan tarian,
dengan debu,
dengan nyali,
pernah menjaga dunia
agar tidak retak.
2025
Abdul Wachid B.S., lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Wachid lulus Sarjana Sastra dan Magister Humaniora di UGM, lulus Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, dan menjadi Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Buku terbarunya : Kumpulan Sajak Nun (CV. Cinta Buku, Yogya, 2018), Dimensi Profetik dalam Puisi Gus Mus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan (Nuansa, Bandung, 2020), Kumpulan Sajak Biyanglala (CV. Cinta Buku, Yogya, 2020), Kumpulan Sajak Jalan Malam (Basabasi, Yogya, 2021), Kumpulan Sajak Penyair Cinta (Jejak Pustaka, Yogya, 2022), Kumpulan Sajak Wasilah Sejoli (Basabasi, Yogya, 2022), Kumpulan Sajak Kubah Hijau (CV. Cinta Buku, Yogya, 2023), Sekumpulan Esai Sastra Hikmah (Pustaka Jaya, Bandung, 2024), Buku Puisi Balada Kisah untuk Anak Cucu (Diva Press, Yogya, 2025). Melalui buku Esai Sastra Pencerahan (Basabasi, Yogyakarta, 2019), Abdul Wachid B.S. menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) sebagai karya tulis terbaik kategori pemikiran sastra, pada 7 Oktober 2021 (tepat di ulang tahunnya yang ke-55).***