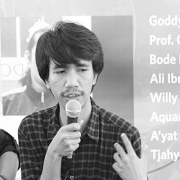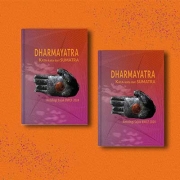Puisi-puisi Abdul Wachid B.S.
BALADA NYADRAN BANYUMAS
1.
Di pematang yang lembut oleh angin,
aroma kenanga menuntun langkah warga
menapaki jalan setapak menuju pemakaman desa;
bau tanah yang baru disapu embun
terasa seperti lembaran kitab
yang terbuka perlahan,
menunggu dibaca dengan hati.
2.
Mereka datang membawa ambeng,
kendi doa, dan bunga dari halaman rumah masing-masing.
Setiap kelopak memuat kisah yang tak diucapkan,
setiap warna memantulkan kerinduan
pada asal-usul yang sering diabaikan.
Dialek Banyumasan yang renyah dan jujur
mengalir di antara langkah, tangan, dan doa
menjadi pelataran tempat sedih dan syukur
saling merawat satu sama lain.
3.
Rumput disisih dengan sapu lidi
agar nisan menemukan kembali bentuknya,
seperti wajah yang disinari ingatan.
Dari bibir mereka, tahlil mengalir
serupa arus kecil, meninggalkan suara bening
di tikungan hati setiap peziarah.
4.
Aku melihat bagaimana tangan-tangan itu
menabur harap di atas tanah yang teduh,
seakan memulangkan beban
kepada rahasia yang lebih luas.
Setiap sujud, setiap kata yang lirih,
mengikat manusia dan leluhur dalam satu napas,
menghubungkan yang hidup dan yang telah pergi.
5.
Dari Nyadran, aku belajar
bahwa leluhur tidak pernah meminta apa pun
selain dijaga namanya;
bahwa manusia datang dan pergi
dalam irama yang ditentukan
oleh Yang Maha Mengembalikan;
bahwa pulang adalah perjalanan
yang tidak menuntut jawaban
kecuali ketundukan dan keikhlasan.
6.
Maka aku merasai
bahwa setiap tabur bunga, setiap sujud yang lirih,
adalah cara tanah mengajar cahaya:
siapa pun yang merunduk
akan ditinggikan oleh waktu,
dan siapa pun yang mendoakan
akan dibukakan jalan pulang
sebelum malam benar-benar turun
ke ladang ingatan.
7.
Dan ketika malam menelan alun-alun,
angin menggerakkan kenanga dan embun,
tahlil masih menari di udara,
suara manusia dan doa bergabung menjadi simfoni gelap,
menghidupkan cahaya di tempat yang tak terlihat.
2025
BALADA NYADRAN LARUNG SERAYU
1.
Di bawah beringin purba
yang akar-akarnya menjuntai
seperti tasbih yang tak pernah putus,
Modin Kasan berdiri.
Wajahnya diterangi cahaya pagi
yang turun lirih ke bibir Serayu,
seperti wahyu kecil
yang memilih tempatnya sendiri.
Orang-orang desa berkumpul,
membawa sesaji
beserta niat yang telah disucikan musim.
2.
“Nyadran ini bukan adat belaka,”
suara Modin Kasan mengalun
seperti gema dari lorong yang jauh.
“Ini ikhtiar untuk ingat,
untuk kembali kepada Yang
menciptakan aliran hidup.”
Ia membuka kitab warisan
halaman-halamannya masih menyimpan
bau tanah selepas hujan pertama
turun ke bumi.
3.
Ketika perahu bambu diletakkan
di permukaan Serayu,
air bergetar pelan,
seakan mengenali tamu lama
yang datang membawa syukur.
Angin dari pegunungan merunduk,
menyentuh ujung tumpeng
seperti malaikat menyentuh ubun-ubun
orang yang berserah.
4.
Dalam barisan tahlil,
suara-suara bertaut
menjadi jembatan tipis
antara bumi dan langit.
Arus membawa gema itu jauh,
hingga terdengar oleh ikan-ikan tua
yang menjaga dasar sungai
sejak zaman sunyi,
ketika dunia baru belajar berdenyut.
5.
Randi, bocah bermata jernih, berbisik:
“Ibu… mengapa sesaji itu tidak kembali?”
Ibunya tersenyum, menunduk pelan.
“Yang kembali itu ampunan, Nak.
Yang pergi — rasa memiliki.”
Modin Kasan menoleh,
dan di mata bocah itu
ia melihat riwayat manusia
dalam bentuk paling polosnya.
6.
Arus tiba-tiba menguat.
Perahu sesaji berguncang
hampir terbalik, hampir hilang suara.
Orang-orang menahan napas;
tahlil menjadi bisu.
Namun pada detik yang genting,
Serayu membuka jalur di antara pusaran,
membiarkan perahu itu
melaju kembali ke garis takdirnya.
7.
“Tanda ini baik,” gumam Modin Kasan,
mengangkat tangannya yang bergetar
bukan karena usia,
melainkan oleh haru
yang turun dari langit.
“Ya Tuhan, terimalah syukur ini.
Jangan tinggalkan orang-orang desa
yang hanya bisa menata hati
dan menawarkan ketulusan.”
8.
Larungan melaju ke hilir
seperti pertapa kecil
yang menembus kabut pagi.
Puncak bukit memantulkan cahaya,
burung-burung meninggalkan sarang,
dan bayang-bayang beringin memanjang
seperti kisah tua
yang menunggu generasi berikutnya
untuk membacanya kembali.
9.
Ketika perahu itu hilang
di tikungan tempat angin bersuluk,
orang-orang tidak pulang sebagai semula.
Ada sesuatu yang berubah
di ruang terdalam dada mereka
ruang yang diisi oleh gema tahlil,
oleh restu sungai,
oleh cahaya yang tak terlihat
kecuali oleh hati yang waspada.
10.
Malam itu, desa Tambek
tidak berpesta.
Hanya kedamaian yang meresap
dari tanah hingga langit,
seolah Serayu telah menyampaikan
doa mereka kepada Yang Maha Halus.
Di batas waktu yang tak bernama,
Modin Kasan menutup kitabnya
dan berbisik lirih:
“Hidup ini larungan yang panjang.
Yang kembali — hanya cahaya.”
2025
BALADA MENDOAN
1.
Di dapur desa, tungku menari
panas menjalar, minyak mendesis,
tempe menunggu, tipis, setengah matang,
diamnya lembut seperti doa
yang jatuh perlahan di antara rumah-rumah tua.
Orang-orang berkumpul, tangan terulur,
niat, adonan, bawang, doa
semua bercampur, menembus udara,
menjadi satu aroma
yang menari di antara jiwa dan raga.
2.
“Iki tempe… Iki sedekah… Iki salam…”
kata sesepuh berulang, bergetar,
seperti gema yang menembus dinding waktu.
Seperti mendoan yang lembut,
hidup harus luwes
tidak keras, namun penuh makna.
Lunak menembus jiwa,
sederhana meneguhkan persaudaraan
yang tak terucap, tapi terasa
di denyut yang sama.
3.
Celup tepung, wajan panas mendesis,
anak-anak menahan napas.
Tunggu—tunggu—tunggu!
Hangat pertama bukan untuk dimakan,
tapi untuk hati yang menunggu sambutan.
Tawa merekah, aroma menyebar,
mengalir dari rumah ke halaman,
dari jalan ke lorong-lorong kecil,
mengikat yang jauh, menghangatkan yang dekat,
seperti sungai Logawa
yang menyalurkan kehidupan dari hulu ke muara.
4.
Tampah bambu menampung mendoan
persembahan kecil untuk tanah, tetangga, langit.
Gigitan pertama membuka percakapan,
rasa gurih meredakan jarak,
aroma tepung membawa tawa
yang melompat dari hati ke hati,
dari rumah ke rumah,
dari generasi ke generasi,
menjadi jembatan yang tak pernah patah.
5.
Mendoan lenyap di meja panjang
seperti doa yang mengalir tanpa suara,
seperti senyum yang tak terhitung.
Orang-orang pulang,
jiwa mereka tetap di dapur,
di aroma minyak, di suara tawa,
di tangan-tangan yang saling memberi,
meninggalkan jejak hangat
di ruang yang tak terlihat,
di ruang yang hanya bisa dirasa.
6.
Mendoan, setengah matang dan kenyal,
mengajar kita luwes, tegas memberi,
hangat tanpa menuntut,
lembut meninggalkan rasa
di mulut, di hati, di ingatan,
mengalir seperti sungai Serayu
yang menembus malam,
yang menyalurkan hidup
dari tangan ke tangan, dari hati ke hati.
7.
Malam turun di Purwokerto
tungku padam, wajan bersih,
tetapi kebersamaan tetap hidup.
Dalam cerita anak-anak,
dalam pelajaran tetangga,
dalam mendoan yang menunggu digoreng lagi,
dalam tawa yang mengalir tanpa lelah,
dan dalam aroma yang tak lekang oleh waktu.
Inilah mendoan:
sedekah, kebersamaan, dan cahaya
yang mengalir lembut di setiap rumah.
2025
BALADA BLAKA SUTA
1.
Di alun-alun desa,
suara menembus udara
canda, tegur, brecuh
mengalir tanpa tedheng aling-aling.
Orang-orang duduk melingkar,
mata bertemu mata,
telinga mendengar,
hati menimbang pelan,
seperti padi yang menunggu masa panen.
Kata-kata lahir dari jujur,
dari yang apa adanya
bening seperti air yang turun
dari hulu ke muara
tanpa menoleh.
2.
“Iki apa sing kudu diomong…
Iki apa sing kudu ditindakake…”
kata sesepuh,
pelan,
tapi menembus tulang sumsum.
Kalimat itu menjadi embun
yang hinggap di daun-daun pagi,
menjadi pedoman
yang menegakkan punggung.
Tidak ada topeng,
tidak ada pura-pura
hanya Blaka Suta,
warisan turun-temurun,
lugu, polos,
jujur semurni senggakan sungai kecil.
Ia mengikat kita semua
dalam satu degup persaudaraan
yang tidak meminta balasan.
3.
Anak-anak meniru,
tertawa, menjerit,
mengulang kata-kata yang tajam
namun hangat
sehangat pawon
yang tak pernah menolak tamu.
Gelegak suara
mengisi lorong-lorong rumah,
menempel di dinding bambu
seperti gema
yang menolak tidur.
Lalu kita mengerti:
keterusterangan adalah jembatan
yang menghubungkan hati ke hati,
bukan pedang
yang memisah.
4.
Bagus Mangun berdiri
di hadapan orang banyak,
mengucap niat dan tekad
tanpa ragu,
tanpa tirai
blak-blakan
sebagaimana ajaran sesepuh.
“Iki sing tak lakoni…
Iki sing tak tanggung…”
Setiap kata menjadi saksi,
melekat seperti cap
pada kayu tua.
Setiap jawaban
menjadi warisan
yang menyalakan keberanian baru
dari masa lalu
yang tersimpan dalam Babad Banyumas
hingga napas anak cucu
yang hidup hari ini.
5.
Malam tiba,
api tungku padam,
bayangan merayap
di dinding-dinding rumah.
Namun suara Blaka Suta
tetap bergema
di jalan, di pasar,
di ruang yang menampung gelisah.
Siapa pun yang mau mendengar
akan menemukan
cahaya yang sederhana.
Kejujuran mengalir,
apa adanya,
menembus gelap
menjadi dasar persaudaraan sejati:
yang tidak lahir
dari kata manis,
tetapi dari keberanian
membuka dada
di hadapan sesama manusia.
2025
BALADA PERLON UNGGAHAN
1.
Di kening hutan Pekuncen, kabut meraba daun-daun
seperti tangan arwah yang kembali mencari rumah.
Anak Putu berjalan perlahan — lirih, berat, dalam
membawa panen, jenang,
dan isyarat yang tak semuanya terlihat.
Setiap langkah seakan membangunkan tanah,
setiap helaan napas memanggil nama
yang usianya lebih tua dari sejarah.
Di balik kesunyian itu, kisah Patih pengelana
mendesir seperti bayang yang tak pernah selesai
menyertai perjalanan doa.
2.
Malam merapat, menutup desa
seperti tirai yang digerakkan sesuatu
yang tidak selalu tampak.
Lilin bergoyang,
rempah menguapkan mantra tak bersuara,
dan muji pecah dari dada manusia
menjadi gelombang yang memukul-mukul hati.
Pakaian hitam berisik seperti hutan bergerak,
jarit mengikat tubuh dengan
ingatan perempuan-perempuan lama.
Di antara mereka, dzikir menjelma jembatan gelap terang:
satu langkah ke bumi, satu langkah ke langit,
satu langkah ke sesuatu yang lebih jauh dari keduanya.
3.
Di dapur yang merah oleh bara,
api dan asap menulis perjanjian
yang tak pernah dibacakan.
Sapi, kambing, ayam: nama-nama makhluk
yang kembali pada asalnya
dengan ketenangan yang nyaris menggetarkan.
Laki-laki bekerja dengan ritme purba,
perempuan menata hidangan
seolah merajut kesunyian
menjadi bentuk yang bisa disentuh.
Setiap suapan jenang, setiap bulir yang dipilih tangan,
adalah pengakuan gelap
bahwa manusia hanya tamu
yang meminjam rahmat bumi.
4.
Fajar tumbuh perlahan
seperti mata yang dibuka dari mimpi panjang.
Langkah menuju makam
bergerak bagai arak-arakan tak terlihat,
tangan dibasuh untuk membersihkan sisa-sisa dunia,
kepala ditundukkan agar langit bisa melihat jiwa.
Nama Kyai Bonokeling disebut dengan getar
yang menggetarkan batu dan daging sekaligus.
Ia, penabur iman yang menyadarkan cahaya,
kini hadir sebagai gema dalam tubuh Anak Putu,
sebagai napas yang tak bisa diusir
meski dunia berganti kulit.
5.
Di sela nisan yang dingin,
lima ajaran hidup bersuara pelan namun tajam:
Monembah, Moguru, Mongabdi, Makaryo,
Ages manunggaling kawula Gusti.
Mereka mengalir seperti sungai hitam
menuju samudra tak bernama,
mengikat usia muda pada usia tua,
mengikat rumah pada perjalanan,
mengikat manusia pada rahasia
yang menjadikannya hidup.
Di sanalah waktu ditenun
menjadi selembar kain gelap bercahaya,
tempat jiwa menunduk dan diangkat sekaligus.
6.
Malam turun lagi — lebih pekat, lebih dalam
namun cahaya tak sepenuhnya padam.
Perlon Unggahan berdenyut di dada
seperti jantung yang dijaga leluhur.
Ia bukan ritual, bukan upacara,
tetapi api bening yang menyalakan kesadaran
ketika Ramadan membuka celah rahmatnya.
Di sana, warisan hidup sebagai aliran tak putus,
mengikat tanah dengan langit,
mengikat manusia dengan cahaya yang ia cari.
Anak Putu Bonokeling menghidupkannya,
dan dalam mereka ia akan terus hidup
meski malam semakin gelap.
2025
*Abdul Wachid B.S., lahir 7 Oktober 1966 di Bluluk, Lamongan, Jawa Timur. Wachid lulus Sarjana Sastra dan Magister Humaniora di UGM, kemudian lulus Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Abdul Wachid B.S. menjadi Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Buku terbarunya : Kumpulan Sajak Nun (2018), Bunga Rampai Esai Sastra Pencerahan (2019), Dimensi Profetik dalam Puisi Gus Mus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan (2020), Kumpulan Sajak Biyanglala (2020), Kumpulan Sajak Jalan Malam (2021), Kumpulan Sajak Penyair Cinta (2022), Kumpulan Sajak Wasilah Sejoli (2022), Kumpulan Sajak Kubah Hijau (2023), Sekumpulan Esai Sastra Hikmah (2024), Buku Puisi Balada Kisah untuk Anak Cucu (2025). Melalui buku Sastra Pencerahan, Abdul Wachid B.S. menerima penghargaan Majelis Sastrawan Asia Tenggara (Mastera) sebagai karya tulis terbaik kategori pemikiran sastra, pada 7 Oktober 2021 (tepat di ulang tahunnya yang ke-55).