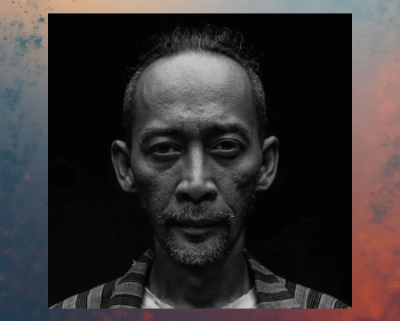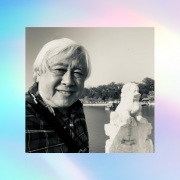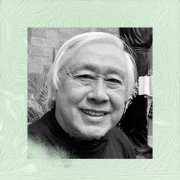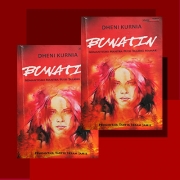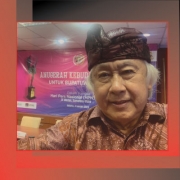Catatan Pasca-Festival
Oleh: Roy Julian*
1. Catatan Pasca-Festival: Tentang Penonton FTJ 2025
Festival Teater Jakarta 2025 sudah selesai. Para pemenang telah diumumkan; piala dan penghargaan sudah diserahkan. Panggung digulung, lampu-lampu dipadamkan. Para aktor menanggalkan kostum dan kembali menjadi diri mereka yang sehari-hari. Para penonton pun telah pulang, membawa sisa gema dari pertunjukan dalam diri mereka. Yang tersisa kini hanyalah ruang kosong dan keheningan setelah riuh rendah itu; sebuah ruang yang justru membuka kesempatan untuk membaca kembali apa yang sebenarnya terjadi selama festival berlangsung.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, selama 15 hari pertunjukan berlangsung, kursi penonton di Gedung Kesenian Jakarta hampir selalu penuh terisi. Bahkan pada malam-malam yang berhujan sekalipun. Ada sesuatu yang menghangat di ruang itu; semacam kerinduan kolektif untuk kembali berkumpul, untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang disajikan di atas panggung. Situasi ini menunjukkan bahwa FTJ masih memiliki daya magnet yang kuat bagi publik teater Jakarta. Mungkin bukan semata karena kualitas pertunjukannya, tetapi karena festival ini telah menjadi semacam ritus tahunan, tempat orang-orang teater datang menonton, sekaligus memastikan bahwa mereka masih menjadi bagian dari denyut itu.
Kepadatan penonton itu menciptakan suasana yang khas: ruang yang ramai namun intim, penuh obrolan, desas-desus, gosip dan tatapan yang berlapis antara para penonton dan penonton lainnya dan antara penonton dan panggung yang ditonton. Setiap malam, FTJ terasa seperti perayaan kecil yang melampaui pertunjukan itu sendiri.
Pertanyaan tentang siapakah sebenarnya penonton FTJ ini bukan sekadar soal jumlah kursi yang terisi atau siapa saja nama-nama mereka. Ia menyentuh persoalan yang lebih dalam, yaitu, untuk siapa festival ini diadakan, dan bagaimana posisi penonton di dalamnya? Jika FTJ dimaksudkan sebagai cermin perkembangan teater Jakarta, maka penontonnya pun bagian dari refleksi itu. Mereka bukan sekadar saksi, tetapi juga kontributor makna, karena tanpa tatapan, tubuh di panggung kehilangan konteks sosialnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, penonton FTJ tampak terbagi ke dalam beberapa lapisan. Ada komunitas teater yang datang dengan intensi belajar dan membandingkan, di mana mereka menonton dengan mata pelaku, bukan sekadar penikmat. Ada juga kalangan akademik dan jurnalis yang hadir dengan kerangka analisis tertentu, menjadikan pertunjukan sebagai bahan baca situasi kesenian kota. Lalu ada penonton umum; mereka yang mungkin tertarik oleh nama besar festival, mencari hiburan, sekedar ingin tahu atau ingin mengalami pengalaman kultural sesaat.
Namun di sisi lain, ada juga penonton yang datang sebagai pencari pengalaman; mereka yang menonton untuk merasakan sesuatu yang berbeda, untuk mencari semacam pengalaman artistik melalui pertunjukan yang dihadirkan, atau bahkan pengalaman yang bersifat spiritual. Penonton jenis ini hadir dengan kesiapan yang lain. Di hadapan mereka, teater menjadi semacam makanan batin; sesuatu yang mengisi relung jiwa. Mereka datang bukan karena nama besar kelompok atau reputasi festival, tetapi karena keyakinan bahwa setiap pertunjukan menyimpan kemungkinan untuk menyentuh sesuatu yang personal dalam diri mereka.
Namun di balik keberagaman itu, muncul satu pola menarik: penonton FTJ kerap menjadi bagian dari ekosistem yang menonton dirinya sendiri. Banyak yang datang bukan hanya untuk melihat karya, tetapi juga untuk dilihat; untuk hadir dalam jejaring sosial teater yang mempertemukan pelaku, pengamat, dan pembuat kebijakan. Dalam konteks ini, FTJ bekerja bukan hanya sebagai ruang pertunjukan, melainkan juga sebagai arena sosial, tempat para seniman teater saling mengukur posisi dan relevansinya.
Pertanyaan tentang “siapa penonton FTJ” tak bisa dijawab dengan kategori demografis, melainkan harus dibaca sebagai persoalan performatif: bagaimana penonton menempatkan dirinya dalam peristiwa teater. Karena di FTJ, penonton tak pernah benar-benar pasif; ia ikut bermain dalam dramaturgi festival itu sendiri, menjadi bagian dari pertunjukan yang lebih besar: pertunjukan tentang teater Jakarta yang sedang menonton dirinya sendiri.
Dalam setiap festival, penonton bukan hanya pihak yang menerima pertunjukan, melainkan juga kekuatan yang menentukan bagaimana pertunjukan itu dibaca, diingat, bahkan dinilai. Di FTJ, tatapan penonton sering kali bekerja seperti semacam mekanisme legitimasi. Sebuah karya bisa tampak “berhasil” atau “gagal” bukan semata karena kekuatan artistiknya, tetapi karena bagaimana ia diterima di ruang sosial festival itu sendiri. Tepuk tangan yang panjang, reaksi tawa atau diam, unggahan media sosial, hingga percakapan-percakapan kecil di warung FTJ atau teras GKJ; semuanya membentuk sistem nilai yang tak tertulis, tapi sangat menentukan arah persepsi publik terhadap teater hari ini.
Tatapan penonton FTJ, dengan demikian, mengandung dimensi kuasa. Ia tidak hanya melihat, tapi juga mengatur apa yang layak disebut “baik”, “eksperimental”, “gagal”, atau “berani”. Dalam ruang festival yang serba terbatas, setiap karya tampil di bawah tekanan pandangan kolektif ini; pandangan yang datang dari sesama pelaku, kritikus, penonton setia, dan jaringan institusional yang melekat pada festival. Dengan kata lain, panggung FTJ tidak hanya menampilkan pertunjukan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teater menatap dirinya sendiri melalui mata orang lain.
Namun di sisi lain, relasi ini tidak bersifat tunggal. Ada juga momen-momen ketika karya justru berhasil menggeser arah tatapan itu, membuat penonton kehilangan pijakan kategorinya. Ketika itu terjadi, ketika penonton berhenti menilai dan mulai merasakan, ketika mereka terseret ke dalam wilayah yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan; di situlah kuasa berpindah: dari penonton kepada pertunjukan. Di momen-momen seperti itulah teater menemukan alasan keberadaannya yang paling purba, yaitu pertemuan antara tubuh yang tampil dan tatapan yang terguncang.
Relasi antara panggung dan penonton di FTJ 2025 memperlihatkan dinamika ini secara jelas. Ada pertunjukan yang kuat justru karena berani menantang ekspektasi penontonnya, bukan karena tunduk pada selera festival. Ada pula karya yang terasa aman, teratur, rapi, tapi kehilangan denyut karena terlalu ingin disukai. Membaca FTJ tak cukup dengan menilai kualitas karya, tapi juga bagaimana setiap karya menegosiasikan hubungannya dengan tatapan publiknya. Sebab di festival seperti ini, penonton adalah bagian dari dramaturgi, bukan sekadar pelengkap pertunjukan.
2. Catatan Pasca-Festival: Restart ke Ruang Kolonial
Tulisan ini berangkat dari percakapan antara Malhamang Zamzam, Ugeng T. Moetidjo dan saya di dalam kereta, saat kami pulang bersama dari Gedung Kesenian Jakarta usai menghadiri acara penutupan Festival Teater Jakarta (FTJ) 2025. Dalam obrolan itu, kami sama-sama mempertanyakan alasan DISBUD DKI memindahkan lokasi festival dari Taman Ismail Marzuki (TIM) ke Gedung Kesenian Jakarta (GKJ). Sebuah hal, yang meski tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh persoalan yang jauh lebih dalam tentang arah ideologis FTJ hari ini.
GKJ bisa dikatakan sebagai gedung kolonial dengan struktur bangunan yang terkesan angkuh, megah, tetapi kaku dan hierarkis. Bahkan, jika ditarik lebih jauh, GKJ juga mewarisi jejak feodalisme budaya. Berbeda dengan TIM yang lebih egaliter dan terbuka, menyediakan beragam ruang pertunjukan yang memungkinkan teater bernapas lebih bebas: dari Teater Kecil yang menghadirkan format prosenium, Teater Wahyu Sihombing yang berbentuk arena, Teater Tuti Indra Malaon yang menawarkan konsep outdoor, hingga kolam Planetarium yang sering diolah menjadi ruang eksperimental yang cair batasnya. TIM bukan hanya kompleks pertunjukan, tetapi ekosistem artistik yang memungkinkan teater bekerja secara lintas disiplin dan lintas ruang, di mana eksperimen bentuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kesenian.
Sementara di GKJ, satu-satunya panggung adalah prosenium di dalam gedung; sebuah ruang yang sudah menuntut bentuk yang frontal, teratur, dan berjarak. Pemindahan lokasi ini karenanya bukan sekadar persoalan tempat, melainkan juga pergeseran paradigma estetika, di mana ruang prosenium hadir menjadi satu-satunya penentu wacana pertunjukan.
Secara historis, perbedaan antara GKJ dan TIM mencerminkan dua model kebudayaan yang sangat berbeda. GKJ, dibangun pada akhir abad ke-19 sebagai Schouwburg Weltevreden, adalah warisan kolonial yang dirancang untuk menampilkan seni Eropa di hadapan kaum elite Hindia Belanda. Arsitekturnya yang simetris, kursi penonton yang berjenjang, dan panggung prosenium yang tinggi menunjukkan hierarki antara pemain dan penonton; antara yang tampil dan yang berkuasa untuk menatap. GKJ adalah simbol budaya representasional; panggung di mana tubuh tunduk pada pandangan.
Sementara TIM, yang diresmikan pada 1968 lahir dari semangat modernitas Indonesia pascakolonial. Di dalamnya terkandung gagasan tentang keterbukaan, partisipasi, dan ruang yang egaliter. TIM menjadi tempat seniman berkumpul, bereksperimen, dan berdebat; ruang di mana teater tidak hanya sekedar dipentaskan, tetapi juga dipertaruhkan. Jika GKJ adalah ruang institusi dengan tata nilai yang mengatur cara menonton, maka TIM adalah ruang produksi wacana dan kemungkinan, tempat para seniman teater bisa menolak tatanan dan membentuk bahasa panggungnya sendiri.
Dalam konteks itu, keputusan memindahkan FTJ ke GKJ bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan juga pergeseran ideologis dari ruang yang demokratis menuju ruang institusional yang dikontrol oleh arsitektur kolonial. Ironisnya, FTJ tahun ini mengusung tema “re-start”, sebuah ajakan untuk menata ulang kembali teater dan membangun energi baru perteateran di Jakarta.
Namun, “re-start” itu dilakukan justru di ruang yang mewarisi sistem penglihatan dan relasi kuasa masa lalu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah FTJ benar-benar memulai ulang, atau justru kembali mengulang pola lama dalam bentuk yang lain?
Dalam FTJ 2025, semua peserta festival dituntut untuk bermain di dalam aparatus yang sama, yaitu panggung yang membatasi arah pandang dan jarak. Akibatnya, kelompok-kelompok yang seharusnya bermain dalam format non-konvensional mesti menyesuaikan diri (kalau tak mau dibilang memaksakan diri). Contohnya kelompok Marooned Actor Society, yang di FTJ Wilayah Utara sebelumnya bermain dalam format arena. Di GKJ, bentuk itu tak mungkin dipertahankan karena keterbatasan teknis dan struktur gedung. Mereka pun harus berkompromi, menyesuaikan gagasan agar dapat “muat” dalam bingkai prosenium yang menuntut frontalitas dan disiplin visual.
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana “re-start” FTJ justru terjebak dalam bentuk lama yang menegaskan hierarki antara panggung dan penonton. Hal ini memicu pertanyaan lain: apakah FTJ harus dimulai ulang dari ruang kolonial yang menjadi simbol keteraturan dan kekuasaan visual? Ataukah “re-start” seharusnya dimulai dari ruang-ruang yang lebih terbuka dan membangun kemungkinan baru bagi pertumbuhan FTJ yang lebih bebas, kritis, dan kontekstual?
Jika “re-start” memang dimaksudkan sebagai upaya untuk menata ulang arah Fesival Teater Jakarta, maka ia semestinya dimulai dari ruang yang membuka kemungkinan dan merangkul keragaman, bukan yang menegaskan hierarki. Dalam pemahaman itu, TIM telah terbukti mampu menjadi ruang di mana kebebasan bentuk dan gagasan dapat tumbuh tanpa dikungkung oleh arsitektur kekuasaan.
Maka alangkah baiknya jika tahun depan Festival Teater Jakarta bisa kembali ke Taman Ismail Marzuki. Mengembalikan FTJ ke TIM adalah mengembalikan festival ini pada habitat alaminya sebagai ruang yang terbuka, di mana ide, bentuk, dan tubuh dapat bertemu secara luwes tanpa sekat hierarki. Di sanalah FTJ bisa menemukan denyutnya sebagai praktik kesenian yang memungkinkan untuk terus bereksperimen, dan mencari bahasa panggung yang relevan dengan zamannya.
—–
*Roy Julian, pengamat teater.