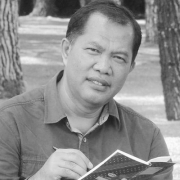BRICS Literary Award, Para Sastrawan Pemimpi Hadiah dan Echo Chamber: Refleksi Epistemologis dan Moral atas Komodifikasi Kebenaran dalam Ekosistem Kebudayaan
Oleh: Gus Nas Jogja*
Esai ini menganalisis fenomena hadiah sastra internasional, mengambil BRICS Literary Award sebagai lensa simbolik, dalam konteks Pendidikan Literasi dan Ekosistem Kebudayaan global. Tulisan ini mengupas ketegangan filosofis antara Sastra Sejati—sebagai pencarian kebenaran intrinsik dan keindahan (kalokagathia)—dengan Sastra Hadiah—sebagai komoditas budaya yang tunduk pada validasi ekstrinsik, geopolitik, dan bias juri. Melalui pendekatan reflektif dan sastrawi, dikaji bagaimana mimpi para sastrawan karbitan menerima hadiah menciptakan echo chamber (ruang gema) yang merusak keberagaman suara dan memiskinkan kurikulum literasi pendidikan. Dengan mengutip pemikiran para penerima Nobel Sastra dan Perdamaian, esai ini menyimpulkan bahwa kesehatan ekosistem kebudayaan menuntut pengembalian nilai-nilai pada Phronesis (kebijaksanaan praktis) membaca dan menulis, di luar hiruk-pikuk validasi institusional.
Kontradiksi Abadi Hadiah dan Hakekat Seni
Dalam panggung peradaban, seni dan sastra selalu berdiri di persimpangan jalan antara kemurnian inspirasi dan kebutuhan pengakuan. Hadiah, dari yang paling lokal hingga yang paling bergengsi seperti Nobel atau, kini, BRICS Literary Award yang merefleksikan pergeseran poros geopolitik, berfungsi sebagai ritual modern: sebuah pengesahan kolektif atas keunggulan artistik. Namun, di balik kemilau medali dan amplop berisi cek, tersembunyi sebuah dilema filosofis yang mendasar: Apakah hadiah menegaskan hakekat sastra, atau justru mengkomodifikasikannya?
Sastra sejati, sebagaimana diyakini para mistikus pena, adalah proses pencarian kebenaran (aletheia) yang rentan, sebuah dialog antara penulis dan Kosmos yang tidak memerlukan penonton, apalagi juri. Karya besar adalah keharusan batin, bukan pencapaian yang ditargetkan.
Namun, di era Kapitalisme Budaya, karya seni tak lepas dari validasi pasar dan institusi. Fenomena BRICS Literary Award, sebagai representasi dari kekuatan ekonomi dan politik yang mencari validasi budaya tandingan, menyoroti betapa validitas sastra kini terjalin erat dengan narasi geopolitik, bukan semata-mata estetika atau kedalaman moral. Kaum muda, para penulis pemula, dan bahkan akademisi, terhipnotis oleh hadiah ini, sehingga mimpi hadiah menjelma menjadi sumbu ideologis yang membentuk cara mereka berkarya dan mengajar. Ini adalah titik awal refleksi kita: bagaimana mimpi ini membelah jiwa sastra, menciptakan distorsi dalam pendidikan literasi, dan memperkuat echo chamber kebudayaan.
Epistemologi Hadiah dan Krisis Validitas
Validitas sebuah karya sastra, dari sudut pandang epistemologi, seharusnya bersifat intrinsik: ditentukan oleh kekoherenan internal, kedalaman eksplorasi tema kemanusiaan, dan kebaruan wawasan. Namun, hadiah mengubah validitas ini menjadi ekstrinsik, yang ditentukan oleh konsensus sekelompok kecil elit (Dewan Juri) yang, tak terhindarkan, membawa bias latar belakang, selera, dan—yang paling berbahaya—agenda.
Dalam filsafat Platonik, dunia terbagi antara Episteme (pengetahuan sejati, kebenaran mutlak) dan Doxa (opini, pandangan yang bervariasi). Sastra yang dihasilkan dari dorongan murni untuk menyampaikan kebenaran spiritual atau sosial harusnya mendekati Episteme. Tetapi ketika karya ditulis atau disaring dengan harapan memenangkan hadiah, ia berisiko merosot menjadi Doxa: karya yang sengaja disesuaikan dengan selera institusional yang dominan.
Di sinilah letak krisisnya: sastra yang diapresiasi oleh Hadiah BRICS (atau hadiah global lainnya) seringkali harus memenuhi kriteria naratif tertentu: representasi keberagaman, kritik sosial yang ‘aman’ (tidak terlalu radikal bagi kekuatan sponsor), atau gaya yang sedang fashionable di pusat-pusat budaya metropolitan.
“The power of literature is to make one see the world anew, to expose the darkness, and to resist the easy answers.” ¹
— Toni Morrison, Pemenang Nobel Sastra 1993
Morrison menggarisbawahi fungsi oposisional sastra: menyingkap kegelapan. Tetapi ketika penulis harus menyesuaikan nadanya, misalnya, dengan “suara global” yang diharapkan (atau sebaliknya, “suara lokal” yang eksotis dan mudah dikonsumsi), daya oposisional ini tumpul. Epistemologi hadiah mengajarkan bahwa kebenaran dalam sastra adalah apa yang diakui sebagai kebenaran oleh komite, bukan apa yang benar-benar ada di dalam jantung karya itu sendiri.
Pendidikan Literasi di Bawah Bayang-Bayang Glorifikasi
Dampak mimpi hadiah merambat langsung ke dalam ranah pendidikan literasi. Sekolah, universitas, dan kurikulum bacaan cenderung memprioritaskan karya-karya yang telah divalidasi oleh institusi bergengsi, menganggapnya sebagai kanon yang tak terbantahkan. Dampaknya, muncul Kurikulum yang Terkomodifikasi.
Ketika para pendidik hanya mengajarkan karya-karya yang telah “disucikan” oleh Nobel, Booker, atau sejenisnya, mereka secara tidak sadar mengajarkan dua pelajaran berbahaya kepada siswa:
1. Nilai Seni Bersifat Hierarkis: Hanya karya yang berstatus elit yang layak dikaji.
2. Kreativitas adalah Target: Menulis adalah tentang meniru gaya yang sukses memenangkan hadiah, bukan tentang menemukan suara unik diri sendiri.
Implikasinya terhadap pendidikan literasi sangat merusak. Siswa didorong untuk menganalisis narasi yang mungkin tidak relevan dengan pengalaman lokal mereka, hanya karena narasi tersebut telah disahkan oleh sebuah yayasan di belahan dunia lain.
Paradigma ini mengabaikan konsep penting yang diusung oleh Paulo Freire: bahwa literasi sejati adalah Praxis—refleksi dan tindakan yang ditujukan untuk transformasi dunia.² Literasi yang terkomodifikasi oleh hadiah mengedepankan refleksi pasif (mengagumi karya pemenang) dan mengebiri tindakan transformatif (menciptakan sastra baru yang menantang status quo lokal).
Si Sastrawan Karbitan dan Telepon Stockholm
Mari kita sisipkan anekdot satir untuk menyingkap kegilaan ini.
Hiduplah seorang penulis, sebut saja Megalomania, yang menulis tentang kepedihan petani di sawah yang tergusur, dengan bahasa yang indah sekaligus bergetar. Namun, ia tidak pernah benar-benar membaca karyanya sendiri; ia membaca review dari juri di Eropa dan Asia. Setiap pagi, Megalomania memulai ritualnya: bukan menyentuh pena, tetapi memeriksa zona waktu Stockholm dan London. Ia tahu, jam 1 siang waktu setempat adalah saat-saat telepon sakral berdering.
Megalomania mulai menyesuaikan diri. Ketika ia tahu tren sastra Barat bergeser ke Magical Realism yang meredakan kritik sosial menjadi dongeng yang menghibur, ia pun menenggelamkan padi yang tergusur itu ke dalam lautan susu mistis yang diseduh oleh nenek sihir. Ketika tren bergeser ke Metafiksi Post-Human, ia membuat petani-petani itu berdebat tentang algoritma dengan roh padi.
Ia tidak menulis kebenaran; ia menulis target. Ia tidak menciptakan seni; ia menciptakan protokol estetik yang diyakininya akan menarik perhatian dewan juri. Tentu saja, telepon itu tak pernah berdering, sebab kebenaran sejati telah lama meninggalkan rumah Megalomania, digantikan oleh gema kosong dari ekspektasi global. Ia menjadi korban echo chamber pribadinya sendiri.
Ekosistem Kebudayaan: Ancaman Echo Chamber Global
Fenomena echo chamber bukanlah monopoli media sosial, melainkan juga terjadi dalam ekosistem kebudayaan global. Hadiah sastra, terutama yang bersifat geopolitik seperti yang disimbolkan oleh BRICS Award, berpotensi memperkuat ruang gema ini dalam skala besar.
Hegemoni Kultural dan Filter Bubble
Hadiah cenderung melahirkan konsensus—sebuah filter bubble budaya di mana karya yang dibaca dan dibicarakan adalah karya yang sama. Negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) memiliki sejarah dan tradisi sastra yang kaya dan sangat berbeda. Namun, ketika mereka membentuk penghargaan bersama, ada risiko bahwa kriteria penilaian akan menyatu pada irisan kultural terkecil (atau kriteria yang paling mudah diterjemahkan dan dikonsumsi secara global), mengorbankan kedalaman naratif lokal yang unik.
Pengalaman Gabriel García Márquez, yang karyanya baru diakui setelah ia berani menulis secara radikal tentang realitas Amerika Latin, adalah kontras yang menyakitkan. Márquez, pemenang Nobel Sastra 1982, berkata:
“The interpretation of our reality through patterns of our own is essential… We must urgently invent a new system of reference for our own reality.” ³
— Gabriel García Márquez
Gabo menyerukan sistem referensi baru yang otentik. Namun, echo chamber hadiah justru mendorong sastrawan untuk kembali menggunakan sistem referensi lama (Barat) atau menciptakan sistem referensi tandingan (BRICS) yang, ironisnya, masih beroperasi di bawah logika validasi yang sama: mencari stempel keunggulan dari sebuah institusi.
Ketika ekosistem kebudayaan hanya mempromosikan dan mendanai karya yang sudah terkonfirmasi (validated), kita kehilangan suara-suara marginal yang paling penting—suara yang, persis karena ketidaknyamanannya, mampu memecahkan hegemoni pemikiran. Echo chamber ini merusak keanekaragaman hayati naratif, meninggalkan kita dengan hutan monokultur yang indah di permukaan, tetapi rapuh di dasarnya.
Filsafat Moral dan Panggilan Kemanusiaan
Jika Epistemologi Hadiah menyangkut Krisis Kebenaran, maka Filsafat Moral Hadiah menyangkut Krisis Keutamaan (Arete). Pergerakan literasi dan kebudayaan harus menemukan jangkar moralitas untuk melepaskan diri dari daya tarik komodifikasi.
Etika Kewajiban dan Sastra sebagai Tugas
Filsafat Moral Immanuel Kant mengajarkan Imperatif Kategoris, yang menuntut kita untuk bertindak hanya berdasarkan maksim yang kita harapkan menjadi hukum universal. Jika kita menerapkan ini pada seni, Sastra Sejati harus ditulis berdasarkan kewajiban batin untuk menciptakan kebenaran dan keindahan, terlepas dari hasil atau hadiah. Tugas sastrawan, secara moral, adalah untuk melayani kebenaran, bukan ambisi.
Ancaman terbesar echo chamber adalah bahwa ia menciptakan moralitas instrumental: menulis sebagai alat untuk mencapai ketenaran dan kekayaan. Padahal, karya-karya yang paling transformatif seringkali lahir dari keterasingan, penolakan, atau bahkan penderitaan, yang secara moral memaksa penulisnya untuk berbicara.
Pemenang Nobel Perdamaian Nelson Mandela mengajarkan tentang pentingnya integritas moral dalam perjuangan:
“A good head and a good heart are always a formidable combination.” ⁴
— Nelson Mandela, Pemenang Nobel Perdamaian 1993
Sastra, sebagai “kepala” (nalar) dan “hati” (moral), harus berpadu. Sastra yang hanya mencari hadiah adalah kepala yang cerdas dalam merancang strategi pasar, tetapi hati yang kerdil dalam menyampaikan empati universal. Sastra yang mampu bertahan adalah yang berani, bahkan dalam penolakan, untuk menyuarakan keadilan, solidaritas, dan harapan.
Untuk menyelamatkan ekosistem kebudayaan dari virus mimpi hadiah dan echo chamber yang membisukan, diperlukan sebuah revolusi hening yang berakar pada sintesis filosofis.
Phronesis dalam Membaca dan Menulis
Jalan keluar dari dilema ini adalah kembali pada Phronesis (kebijaksanaan praktis) Aristoteles, yang merupakan kemampuan untuk menilai apa yang baik dan benar dalam situasi konkret dan memilih tindakan yang bijaksana. Dalam konteks literasi:
1. Phronesis Menulis: Penulis harus menggunakan kebijaksanaan untuk membedakan antara kebutuhan Ekspresi Otentik (Phronesis) dengan dorongan Konformitas Estetika (Doxa Hadiah). Mereka harus berani menulis tentang realitas mereka, bahkan jika realitas itu tidak ‘populer’ atau tidak ‘memenuhi syarat’ untuk diterjemahkan dan dipromosikan secara global.
2. Phronesis Membaca/Mengajar: Para pendidik literasi harus menggunakan kebijaksanaan untuk memilih karya bukan berdasarkan stempel keunggulan, tetapi berdasarkan daya resonansi moral dan relevansi kontekstual karya tersebut terhadap siswa. Kurikulum harus memuat suara-suara lokal, yang belum (dan mungkin tidak akan pernah) memenangkan hadiah, tetapi secara etis lebih mendesak dan mendidik.
Malala Yousafzai, Pemenang Nobel Perdamaian 2014, memberikan pandangan tentang kekuatan pendidikan sejati:
“One child, one teacher, one book, one pen can change the world.” ⁵
— Malala Yousafzai
Ini adalah panggilan untuk merayakan unit dasar literasi—buku dan pena—bukan lembaga megah yang memberikannya stempel. Ekosistem kebudayaan yang sehat adalah yang dibangun dari bawah ke atas: dari kegairahan membaca di sekolah dasar hingga forum diskusi kritis di masyarakat, yang semuanya bebas dari hiruk-pikuk validasi eksternal.
Sastra Sejati di Luar Gerbang Emas
BRICS Literary Award dan hadiah serupa adalah artefak dari kebutuhan peradaban untuk memberi penghargaan. Namun, obsesi terhadap artefak ini berisiko mengubur hakekat sastra: pencarian abadi akan kebenaran kemanusiaan.
Perjuangan kaum muda—baik sebagai penulis maupun pembaca—adalah perjuangan untuk merebut kembali Otonomi Estetika mereka. Mereka harus menolak menjadi para penulis target dan menjadi penulis tugas, menulis karena kebenasan itu harus ditulis, dan karena jiwa menuntutnya.
Revolusi hening ini dimulai ketika kita menyadari bahwa stempel emas dari sebuah komite juri hanyalah doxa (opini), sedangkan resonansi kebenaran dan keadilan yang tercipta antara pembaca dan pena adalah episteme (kebenaran sejati). Pendidikan literasi harus mengajarkan keberanian untuk menulis dan membaca di luar gerbang emas hadiah, memastikan bahwa api revolusi sastra menyala dari sumbu otentik kebajikan moral dan kedalaman reflektif, jauh dari gema kosong echo chamber yang mematikan. Hanya dengan demikian, sastra dapat kembali berfungsi sebagai kompas moral bagi peradaban.
***
Catatan Kaki
¹ Toni Morrison, Nobel Lecture, 1993, mengenai tanggung jawab bahasa dan sastra dalam menolak kebohongan politik dan sosial.
² Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Continuum, 1970), mempopulerkan konsep literasi sebagai alat pembebasan dan kesadaran kritis (conscientização).
³ Gabriel García Márquez, The Solitude of Latin America, pidato penerimaan Nobel 1982. Seruan untuk otentisitas naratif yang melawan stereotip Eurosentris.
⁴ Nelson Mandela, dikutip dari Long Walk to Freedom (Boston: Little, Brown and Company, 1994), mencerminkan nilai etika dan kecerdasan dalam kepemimpinan.
⁵ Malala Yousafzai, pidato di PBB pada tahun 2013 setelah upaya pembunuhan, menekankan kekuatan transformatif dari pendidikan dasar.
Daftar Pustaka
Aristoteles. Nicomachean Ethics. Diterjemahkan oleh W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Freire, Paulo. Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum, 1970.
García Márquez, Gabriel. The Solitude of Latin America. Pidato Penerimaan Nobel, 1982.
Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Diterjemahkan oleh Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Mandela, Nelson. Long Walk to Freedom. Boston: Little, Brown and Company, 1994.
Morrison, Toni. Nobel Lecture, 1993. Stockholm: The Swedish Academy.
Plato. The Republic. Diterjemahkan oleh G.M.A Grube. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1992.
—-
Gus Nas Jogja, Budayawan.