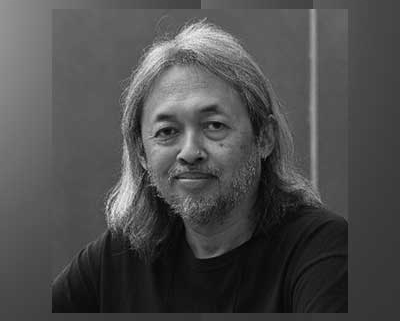Estetika Fisika Theppanom: Esai Pichet
Oleh Seno Gumira Ajidarma*
Di balik tubuh, tak hanya ada rasa, melainkan juga pikiran, meskipun konteks pernyataan ini adalah tari. Ini terejawantah dengan gamblang pada koreografi berjudul “No. 60” yang dibawakan Pichet Klunchun Dance Company, pada malam penutupan Indonesian Dance Festival, Jumat 28 Oktober 2022 di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Pada adegan pembuka, layar menampilkan foto-foto adegan tari tradisi Thai, Khon, yang bahasa geraknya disebut kanon Theppanom. Ditampilkan foto-foto, dan bukan film yang akan memperlihatkan gerak, karena gerak ternyata ditampilkan dengan cara lain: dua penari menari dalam siluet berlatar jingga. Bukan menari sebetulnya, tetapi menampilkan rangkaian pose, yang meski seperti terputus-putus, tetap saja mengalir dengan memperlihatkan rincian gerak yang merupakan cirinya.

Pichet Klunchun (Foto: https://www.dansenshus.com)
Artinya penari menjadikan dirinya peralatan untuk memberi gambar. Siluet itu seperti guntingan kertas hitam, tetapi yang bergerak dengan kesadaran tinggi: bukan saja agar rincian ciri gerak tampak jelas, sehingga tangan dan kaki tak pernah bergerak di depan bidang tubuh yang hitam, melainkan sebagai gerak berpasangan hadir dalam nuansa estetis. Bentuk dan gerak yang menjadi gambar, sampai serinci gerak jari-jari, tampil efisien sekaligus artistik dalam siluet seluas pangggung itu.
Namun presentasi pose-pose kerincian itu hadir untuk dijelaskan. Sementara pose-pose patah-patah itu kemudian mengalir luwes sebagai tarian, layar memperlihatkan diagram yang menguraikan aliran gerak itu sebagai gejala fisika. Dari tahap ke tahap, penari menyebutkan nomor bagian demi bagian, yang bersambut animasi diagram, seperti tari itu peragaan suatu konsep, meski kali ini animasi diagram itulah peragaannya, menjadikan gubahan ini suatu estetika fisika.

Foto karya Pichet Klunchun ‘NO. 60’ (Foto:indonesiandancefestival.id)
Tanpa fisika, tentu tiada kelenturan jatuh bangunnya tari dalam gravitasi, tetapi estetika fisika artinya keterberian alam yang diberi makna. Pada layar, apa yang semula deskripsi fisika dari gerakan tari dalam animasi, kemudian beralih menjadi metafora dalam berbagai penamaan gerak baku tradisional, yang pada masa kelahirannya merupakan cara-cara penjelasan juga.
Jika menengok konsep Pichet dalam katalog Rasa: Beyond Bodies, apa yang tersaksikan di atas merupakan pembongkaran dari 59 pose dan gerakan dalam kanon Theppanom, sebagai sistem 700 tahun, yang disusun kembali menjadi prinsip praktik tari dalam kombinasi enam elemen sebagai prinsip baru. Diakui sebagai bukan bentuk koreografi atau gerak, dalam kenyataannya “No. 60” ini lebih dari bisa ditonton, justru karena lebih memberikan konsumsi estetik kepada otak, pikiran, daripada rasa—jika keduanya secara konseptual mau dipisahkan; lebih ternikmati yang dimengerti daripada yang dirasakan.
Pichet membagi pembelajarannya sebagai abstraksi logika formal dan afeksi mimetik dalam ekspresi tari Khon. Kata yang menarik di sini adalah “leksikon”, prinsip gerak Theppanom dilihat sebagai bahasa yang bisa dibongkar dan disusun kembali sebagai ekspresi koreografer dan para penarinya. Maka setelah 59 pose terlalui, yang disebut dialog tradisi dan inovasi ini memasuki yang ke-60, meski tentu keseluruhannya “No. 60”, sebagai milik para pementasnya: Pichet sendiri, Komkarn Rumsawang, dan seniman CG (computer graphics) Jaturakom Pinpech, ditambah segenap pendukung panggung yang kontribusinya setara.

Poster pertunjukan NO. 60 karya Pichet Klunchun. (Foto: FB Indonesian Dance Festival)
Pada tahap ini penonton dapat menyaksikan ujung dari perjalanan tujuh abad tersebut, ketika bermain pula variabel kontemporer seperti rancangan musik dan suara (Zai Tang), rancangan panggung dan cahaya (Ray Tseng), maupun tentunya dramaturgi (Tan Fu Kuen). Pemahaman ini tampak menyodok, ketika layar dan gelembung pada tata pentas di bagian atas secara jenial dimanfaatkan untuk mengubah aspect ratio panggung, sehingga bagi penonton tinggal tersisa tarian kaki kedua penari.
Jangan pula dilupakan, betapa segenap elemen yang hadir ini tersatukan oleh orkestrasi musik yang lapis-lapis repetisinya sungguh efisien, menggiring penonton untuk terus berada dalam alur dramaturgi. Membebaskan tubuh dan pikiran tari, tapi mengikat perhatian penonton.
Jika perspektif ditarik lebih jauh, keluar dari dunia tari, dalam perbandingan dengan genre susastra, pernyataan bahwa “No. 60” bukan koreografi maupun gerak, menempatkannya pada posisi sebuah esai. Sedangkan esai memang ditujukan kepada otak, pikiran, meski digerakkan dan menggerakkan rasa.
*Sastrawan, Pengelola PanaJournal.com