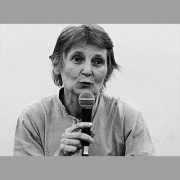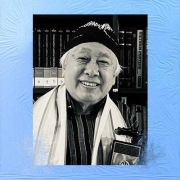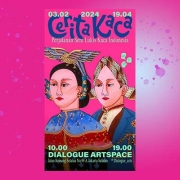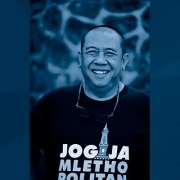Sastra, Pemuda, dan Narasi Kebangsaan: Membaca Nalar Filosofis Sumpah Pemuda
Oleh: Gus Nas Jogja*
Wacana kebangsaan di Nusantara, sebagaimana terartikulasi dalam Sumpah Pemuda (1928), bukanlah sekadar manifestasi politis; ia adalah sebuah proyek ontologis, sebuah upaya radikal untuk menegasi struktur kekuasaan kolonial yang telah mendehumanisasi subjek. Peristiwa historis ini, sering kali dicatat secara linear sebagai pilar nasionalisme, sesungguhnya merupakan ruptur epistemik yang lahir dari kesadaran eksistensial Pemuda – subjek yang menemukan kemerdekaannya bukan dalam janji masa depan, melainkan dalam pilihan radikal saat ini.
Esai ini bertujuan membongkar historiografi Sumpah Pemuda dari pembacaan struktural-linear menuju penafsiran eksistensial-struktural melalui tiga lensa kritikal: Politik Linguistik, Ekologi Kenusaan, dan Artikulasi Kebangsaan. Sastra, dalam konteks ini, dipahami sebagai medan perlawanan di mana diksi dan frasa menjadi senjata utama untuk mendekonstruksi episteme kolonial, menuntut pengakuan atas eksistensi yang telah lama dinegasikan. Puncak dari proyek ontologis ini termanifestasi dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebuah aktus puncak yang mengubah potensi struktural (Sumpah) menjadi realitas eksistensial (Negara).
Sumpah Pemuda adalah aksi linguistik yang menciptakan struktur baru, yang kemudian menuntut eksistensi baru. Ini adalah dialektika antara kekakuan teks (struktur) dan agensi penuh risiko (eksistensi) dari para pemuda yang berani melakukan inversi kekuasaan (Foucault), mengubah peta wilayah jajahan menjadi peta Tanah Air yang berdaulat.
Sumpah sebagai Penemuan Eksistensial
Sumpah Pemuda terdiri dari tiga klausa struktural yang terkesan lugas: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Namun, dalam konteks Artikulasi Kebangsaan pasca-kolonial, tiga klausa ini adalah tiga tahap pembebasan eksistensial:
Teks dan Hegemoni Linguistik. Sebelum 1928, kekuasaan kolonial beroperasi melalui hegemoni linguistik. Bahasa Belanda (sebagai bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan) dan bahasa Melayu pasar (sebagai bahasa komersial yang dilemahkan) adalah instrumen pengkotak-kotakan subjek, memisahkan inlander (pribumi) dari akses ke pengetahuan dan kekuasaan. Sumpah Pemuda adalah deklarasi untuk menolak skema ini, sebuah pernyataan ontologis bahwa eksistensi kebangsaan menuntut wadah linguistik yang mandiri.
Teks tersebut menciptakan fondasi, sebuah signifier (‘Indonesia’) yang kosong namun mampu mengisi seluruh signified (makna) yang selama ini terfragmentasi oleh sistem etnis-feodal kolonial.
Keputusan para pemuda untuk menerima Bahasa Indonesia adalah sebuah pilihan radikal (Sartre). Ini bukan sekadar kompromi, melainkan pembebanan diri dengan tanggung jawab menciptakan makna baru. Dalam ketiadaan bahasa persatuan yang mapan, mereka memilihnya sebagai proyek masa depan, sebuah perlawanan terhadap bad faith (ketidakjujuran eksistensial) yang ditawarkan oleh kepatuhan linguistik kolonial.
“Memilih sebuah bahasa, dalam keadaan terjajah, bukanlah tindakan pragmatis, melainkan tindakan metafisis untuk menolak dilahirkan kembali dalam kerangka makna yang ditentukan oleh Penjajah. Itu adalah negasi total terhadap diskursus pengasingan.”¹
Politik Linguistik: Dari Dialek ke Dialektika Perlawanan
Politik Linguistik Sumpah Pemuda adalah jantung dari narasi perlawanan ini. Ia bukan hanya tentang memilih bahasa, tetapi memilih identitas yang akan diartikulasikannya.
Pilihan atas Bahasa Melayu Riau –yang kemudian diangkat menjadi Bahasa Indonesia, secara politik adalah sebuah strategi untuk menyingkirkan tiga ancaman: Hegemoni Belanda, Jawanisasi, dan Fragmentasi Etnis. Bahasa Indonesia menjadi wadah tanpa sejarah etnis, sebuah ruang liminal yang memungkinkan setiap subjek untuk berpartisipasi setara dalam menciptakan narasi Kebangsaan.
“Bahasa Indonesia adalah bahasa revolusioner, karena ia adalah satu-satunya bahasa yang tidak membawa beban mitos asal-usul feodal yang eksklusif, melainkan janji kebersamaan yang dibentuk.”²
Sastra Perjuangan dan Pembentukan Subjek
Setelah 1928, Sastra Perjuangan menjadi medium di mana Politik Linguistik ini diuji dan dihidupkan. Sastra menjadi medan pertarungan untuk menciptakan subjek baru yang terlepas dari belenggu kolonial.
Chairil Anwar (1922–1949), dengan puisi “Aku”, melakukan deklarasi eksistensial tertinggi:
Kalau sampai waktuku / ‘Ku mau tak seorang ‘kan merayu / Tidak juga kau.
Aku mau hidup seribu tahun lagi!
Puisi ini adalah penolakan struktural terhadap kepasrahan dan penerimaan nasib. “Aku” yang disuarakan Chairil bukan lagi inlander yang lemah, melainkan subjek otonom, individu yang berani mendefinisikan waktu dan keabadiannya sendiri, sebuah penemuan diri yang menjadi landasan filosofis bagi keberanian Proklamasi.
Idrus (1921–1979) melalui karya-karya realisnya (misalnya, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma) menggunakan bahasa yang lugas dan tidak romantis untuk menggambarkan kehancuran yang ditinggalkan kolonialisme, memutus tradisi bahasa Melayu lama, dan menegaskan narasi yang lebih sinis, jujur, dan oleh karenanya, lebih revolusioner. Sastra menjadi alat de-kolonisasi kesadaran.
Ekologi Kenusaan: Tubuh yang Membebaskan Tanah
Klausa pertama, Satu Tanah Air, adalah sebuah klaim yang secara radikal mengubah cara subjek Pemuda berhubungan dengan ruang dan geografi. Ini adalah pembongkaran terhadap Ekologi Kenusaan versi kolonial.
Kolonialisme memandang Nusantara sebagai ruang yang terpetakan, terkuantifikasi, dan tereksploitasi – sebuah ekologi penjarahan. Klausa Satu Tanah Air melakukan inversi ontologis: Tanah (sebagai objek eksploitasi) diubah menjadi Tanah Air (sebagai subjek kasih sayang, motherland).
“Pemuda adalah tubuh ekologis dari bangsa yang baru lahir. Setiap jengkal tanah yang diakui sebagai Tanah Air adalah perpanjangan dari integritas tubuh, menolak mutilasi geografis oleh kekuasaan asing.”³
Dengan mendeklarasikan “Satu Tanah Air”, Pemuda telah melakukan aksi struktural yang menciptakan peta baru di benak kolektif, jauh sebelum peta fisik kemerdekaan terwujud. Tindakan ini adalah refleksi dari kesadaran eksistensial bahwa kebangsaan adalah pilihan untuk berdiri bersama di atas wilayah yang sama.
Artikulasi Kebangsaan: Negasi, Kesadaran, dan Proklamasi
Klausa kedua, Satu Bangsa, adalah puncak dari Artikulasi Kebangsaan dan sintesis antara pilihan linguistik dan klaim teritorial, yang kemudian memuncak pada Proklamasi 1945.
Sumpah Pemuda adalah negasi terhadap kesadaran palsu yang diwariskan kolonial. Dengan mendeklarasikan Satu Bangsa, Pemuda menciptakan Subjek Kolektif yang melampaui garis-garis etnis, didasarkan pada keinginan untuk bersama (Renan), sebuah kontrak sosial eksistensial.
“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir dari ketiadaan historis yang tunggal. Ia bukan hasil evolusi etnis, melainkan hasil pilihan etis untuk menanggalkan identitas lokal yang membelenggu demi identitas nasional yang membebaskan.”⁴
Proklamasi (1945): Aktus Puncak Eksistensial
Jika Sumpah Pemuda adalah perencanaan struktural-eksistensial, maka Proklamasi adalah perwujudan finalnya.
Proklamasi Kemerdekaan, yang hanya terdiri dari dua kalimat, adalah Aktus Performative (Austin) tertinggi: teks itu sendiri, melalui pengucapannya, mengubah realitas. Dalam narasi eksistensial, Proklamasi adalah momen ketika bangsa Indonesia memilih kebebasannya secara total, melemparkan dirinya ke dalam risiko dan tanggung jawab penuh atas nasibnya sendiri.
Soekarno, sebagai penyambung lidah Sumpah 1928, mewujudkan Artikulasi Kebangsaan ini. Ia mendefinisikan kebangsaan bukan sebagai individualisme, melainkan sebagai Gotong Royong (kebersamaan):
“Bukan Indonesia untuk satu orang, bukan Indonesia untuk satu golongan, tetapi Indonesia untuk semua. Inilah dasar kita, yang kita gali di dalam-dalamnya.”⁶
Gotong Royong adalah struktur etis yang memastikan bahwa eksistensi individual selalu terjalin dalam kesadaran kolektif. Ini adalah penolakan terhadap individualisme liberal yang diimpor kolonial.
Mohammad Hatta menekankan bahwa Proklamasi hanyalah permulaan dari proyek struktural dan etis yang lebih besar:
“Kemerdekaan hanyalah jembatan, walaupun jembatan emas. Di seberang jembatan itulah kita menyempurnakan kewajiban kita.”⁷
Hatta melihat Proklamasi bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pilihan eksistensial untuk memikul beban moral dalam membangun kedaulatan (struktur) yang adil. Tugas setelah Proklamasi adalah menyempurnakan Politik Linguistik dan Ekologi Kenusaan dengan struktur politik yang berdemokrasi.
Kesadaran sebagai Revolusi
Sutan Sjahrir, mewakili intelektual Pemuda yang paling awal menyadari krisis eksistensial kolonial, menekankan bahwa revolusi sejati harus dimulai dari kesadaran internal. Proklamasi, baginya, adalah hasil dari pencerahan kesadaran kolektif:
“Perjuangan kita sekarang bukanlah perjuangan berdarah, tetapi perjuangan untuk menimbulkan kesadaran yang baru.”⁸
Kesadaran baru inilah yang membuat Pemuda berani menuntut Proklamasi, bahkan ketika kondisi politik internasional (kekalahan Jepang) masih liminal. Mereka melakukan pilihan penuh risiko (Sartre) untuk mengambil nasib di tangan sendiri.
Sastra dan Keabadian Perlawanan
Pembongkaran historiografi Sumpah Pemuda hingga Proklamasi menunjukkan bahwa perjalanan kebangsaan adalah sebuah rantai aksi-negasi-artikulasi. Ruptur linguistik 1928 menghasilkan kerangka struktural yang diperjuangkan secara eksistensial, dan dimanifestasikan secara performatif pada 1945.
Tugas Sastra kontemporer adalah menjaga Artikulasi Kebangsaan agar tetap tajam. Sastra adalah cermin etis bangsa, yang wajib terus menyuarakan ‘Aku’ Chairil Anwar, menolak kepasrahan, dan terus menuntut pertanggungjawaban ontologis terhadap janji Proklamasi. Sastra harus terus melawan segala bentuk kolonialisme modern (ekonomi, budaya, struktural) dengan bahasa yang jujur dan revolusioner. Selama Pemuda menggunakan bahasa untuk menyuarakan kritik dan memberontak terhadap ketidakadilan, eksistensi Sumpah Pemuda dan Proklamasi akan tetap relevan, hidup, dan progresif.
***
Catatan Kaki
¹ Konsep ini mengadopsi pemikiran Jacques Derrida mengenai logosenstrisme dan bahasa sebagai penentu realitas, yang dalam konteks perlawanan diinversikan menjadi pilihan radikal akan logos baru.
² Merujuk pada pemikiran post-kolonial Benedict Anderson tentang imagined community (komunitas yang dibayangkan), di mana bahasa persatuan (terutama melalui media cetak/sastra) menciptakan kesamaan dan ikatan melampaui batas-batas suku.
³ Adaptasi dari pandangan Merleau-Ponty tentang tubuh sebagai subjek eksistensial yang berinteraksi dengan dunia, di mana pembebasan tubuh sama dengan pembebasan ruang yang didiaminya (tanah).
⁴ Mengacu pada kritik struktural-historis Ernest Renan dalam “Qu’est-ce qu’une nation?” (Apa itu Bangsa?), yang mendefinisikan bangsa sebagai kehendak bersama yang terus menerus diperbarui.
⁵ Pilihan diksi “ruptur” bersandar pada konsep Michel Foucault, di mana perubahan sejarah besar adalah hasil dari putusnya rantai diskursus lama, bukan evolusi gradual. Sumpah Pemuda adalah ruptur diskursif.
⁶ Kutipan dari Pidato Soekarno tentang Pancasila (1 Juni 1945), yang menekankan inklusivitas Artikulasi Kebangsaan.
⁷ Kutipan dari Mohammad Hatta, menekankan kemerdekaan sebagai sarana, bukan tujuan akhir, menandakan proyek struktural yang berkelanjutan.
⁸ Kutipan dari Sutan Sjahrir, yang menitikberatkan pada pentingnya revolusi mental dan kesadaran (pilihan eksistensial) dalam pergerakan melawan kolonialisme.
Daftar Pustaka
Anderson, Benedict R. O’G. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition. Verso.
Foucault, Michel. (1972). The Archaeology of Knowledge. Pantheon Books.
Sartre, Jean-Paul. (2007). Existentialism is a Humanism. Yale University Press.
Hatta, Mohammad. (1953). Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Ke Ekonomi dan Kooperasi. Jakarta: Djambatan.
Soekarno. (1964). Lahirnya Pantjasila: Kumpulan Pidato 1 Juni 1945. Jakarta: Departemen Penerangan.
Sjahrir, Sutan. (2005). Renungan Indonesia: Perjuangan Sosial dan Politik Sebelum dan Sesudah 1945. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Anwar, Chairil. (1949). Deru Campur Debu. Jakarta: Jajasan Kebudajaan.
Idrus. (1948). Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Jakarta: Balai Pustaka.
Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. Oxford University Press.
(Relevansi: Dasar teoritis untuk memahami Proklamasi sebagai Aktus Performative yang mengubah realitas hanya dengan pengucapannya.)
Slametmuljana. (1956). Politik Bahasa Nasional. Djambatan.
—–
*Gus Nas Jogja, Budayawan.