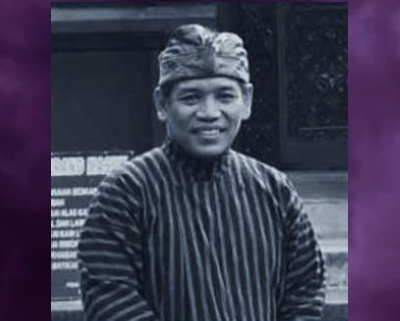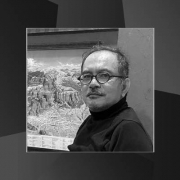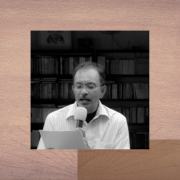Tafaqquh fi Tamaddun: Dialekta Santri di Jantung Disrupsi Digital
Oleh: Gus Nas Jogja*
Melampaui Batas Kitab Kuning Menuju Samudra Peradaban: Santri di Persimpangan Kosmos
Santri, sejak berabad-abad, adalah metafora hidup tentang sebuah perenialitas: kesinambungan spiritual yang dibentuk oleh disiplin asketik dan intelektual. Ia adalah pewaris tradisi kenabian, yang mandat utamanya terangkum dalam diktum suci: Tafaqquh Fiddin—pendalaman dan pemahaman mendalam atas agama. Dalam lorong-lorong pesantren yang sunyi, di bawah temaram lampu minyak dan wanginya kitab-kitab tua, santri ditempa menjadi penjaga api keimanan (hifzh al-din). Namun, hari ini, dinding-dinding pesantren bukan lagi benteng yang tak tertembus. Angin disrupsi digital, sebuah badai epistemologis dan ontologis, telah merobohkan sekat-sekat geografis dan mental. Santri menemukan dirinya di persimpangan kosmos, di mana tuntutan untuk memahami Haqq (Kebenaran Ilahi) bertemu dengan keharusan mendekode Tamaddun (Peradaban Modern) yang bergerak dengan kecepatan cahaya.
Jika Tafaqquh fiddin adalah kompas ke dalam diri, sebuah perjalanan spiritual menuju Sakinah (Ketenangan Ilahi) dan Istiqlal (Integritas Diri), maka di hadapan gelombang disrupsi, lahir sebuah keniscayaan baru: Tafaqquh fi Tamaddun. Ini bukan sekadar belajar teknologi atau menguasai bahasa asing; ini adalah sebuah ijtihad filosofis dan antropologis untuk memahami struktur, etika, dan bahaya yang inheren dalam peradaban digital, agar api tradisi tidak padam ditiup angin modernitas, melainkan menjadi suluh yang menerangi kegelapan.
Esai ini akan menganalisis transisi mendesak ini melalui spektrum filsafat, antropologi, pendidikan karakter, dan ekosistem kebudayaan, merangkainya dalam narasi spiritual dan sastrawi.
Tafaqquh Fiddin: Fondasi Ontologis dan Epistemologis
Secara filosofis, Tafaqquh fiddin adalah proyeksi keimanan dalam ranah nalar. Ia mengajukan pertanyaan ontologis mendasar: Apa itu Wujud Sejati (al-Wujud al-Haqqi)? Jawabannya terletak pada Tawhid (Keesaan Tuhan), yang menjadi sumber tunggal bagi seluruh struktur realitas, etika, dan hukum. Epistemologi santri tradisional berpusat pada sanad (rantai transmisi) yang otentik, di mana ilmu tidak hanya dihafal, tetapi diwariskan melalui riyadhah (latihan spiritual) dan ta’zhim (penghormatan) kepada guru.
Narasi Spiritual: Epifani Kitab Kuning
Pesantren adalah ruang epifani yang sunyi. Seorang santri duduk bersila, matanya menelusuri baris-baris Kitab Kuning yang ringkas dan padat. Ia tidak hanya membaca teks; ia tengah berdialog dengan jiwa para ulama terdahulu. Ilmu baginya bukan komoditas informasi, melainkan cahaya (nur) yang ditanamkan melalui kesabaran dan mujahadah (perjuangan jiwa).
“Kitab Kuning itu bukan batu. Ia adalah air yang mengalir dari hulu sejarah, dari mata air wahyu. Setiap kata yang tertulis adalah cermin yang mengembalikan wajah sejati santri itu sendiri—wajah yang merindukan Kehadiran.”
Dalam perspektif sastrawi, santri adalah penyair yang diam, yang sajaknya terukir dalam disiplin taqwa dan kerendahan hati. Filsafat pendidikan di sini adalah pembentukan al-Insan al-Kamil (Manusia Sempurna), yang memiliki integritas spiritual (istiqamah) sebagai jangkar dalam menghadapi badai duniawi. Tafaqquh fiddin mengajarkan bahwa sebelum memimpin peradaban, santri harus menaklukkan kerajaan batinnya sendiri.
Antropologi Disrupsi dan Keniscayaan Tafaqquh fi Tamaddun
Dunia hari ini bergerak dalam logika disrupsi—sebuah istilah ekonomi yang pada dasarnya adalah fenomena antropologis: perubahan radikal cara manusia hidup, berinteraksi, dan memahami realitas. Peradaban digital, Tamaddun al-raqmi, telah menciptakan sebuah “alam semesta kedua” (Second Universe) yang tak bertepi, di mana informasi adalah dewa, kecepatan adalah mantra, dan algoritma adalah hukum baru.
Analisis Antropologis: Manusia Digital dan Krisis Otoritas
Dari sudut pandang antropologi, digitalisasi adalah pembentukan suku (tribe) baru dan ritual (rite) baru. Santri tidak lagi berhadapan dengan desa atau kota; ia berhadapan dengan Global Village yang cair. Di era ini, authority (otoritas) tradisional—yang didasarkan pada sanad dan keturunan keilmuan—terancam oleh popularity (popularitas), yang didasarkan pada jumlah followers dan viralitas.
Tafaqquh fi Tamaddun adalah upaya untuk melakukan dekonstruksi terhadap struktur peradaban digital itu sendiri. Ia harus mampu bertanya secara filosofis: Apa hakikat data? Apakah kecerdasan buatan (AI) adalah wujud kesadaran baru, atau sekadar proyeksi matematis dari ‘aql atau akal manusia?
Filsafat di sini bergeser dari ontologi Wujud menuju ontologi Virtualitas. Santri dituntut untuk menguasai Literasi Digital Kritis—kemampuan tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga membedah kode (coding), memverifikasi kebenaran (fact-checking), dan menolak narasi-narasi yang merendahkan martabat kemanusiaan (al-karamah al-insaniyyah).
Kegagalan dalam Tafaqquh fi Tamaddun akan menghasilkan dua tragedi:
Pertama, santri yang terasing (The Alienated Santri): Menutup diri dari dunia baru, sehingga ajarannya menjadi tidak relevan dan terpinggirkan.
Kedua, santri yang terlarut (The Assimilated Santri): Terlalu larut dalam arus, kehilangan akar spiritual, dan menjadi budak teknologi.
Kebutuhan akan Tafaqquh fi Tamaddun adalah kebutuhan untuk menciptakan al-Barzakh (Jembatan) antara yang sakral (fiddin) dan yang profan (fi tamaddun).
Literasi Pendidikan Karakter: Integritas dan Fleksibilitas
Literasi pendidikan karakter dalam konteks dualitas Tafaqquh adalah sebuah proyek akhlak di tengah kekacauan informasi. Jika era tradisional menekankan Integritas Diri (Istiqlal), era digital menuntut Fleksibilitas Etis (Murunah Khuluqiyyah)—kemampuan mempertahankan nilai inti sambil beradaptasi dengan konteks yang berubah-ubah.
Filsafat Karakter: Integrasi Aql dan Qalb
Pendidikan karakter santri harus mengintegrasikan dimensi kognitif (‘aql), afektif (qalb), dan konatif (amal) dalam menghadapi fenomena digital:
Literasi Kognitif atau Tafaqquh Epistemologis: Kemampuan memproses informasi. Santri harus menjadi Produsen Konten (content creator) yang konstruktif, bukan sekadar konsumen pasif. Ini memerlukan pemahaman tentang media production sebagai dakwah (seruan kebaikan) modern.
Literasi Afektif atau Tafaqquh Spiritual): Kontrol emosi dan spiritual resilience. Di tengah echo chamber dan polarization digital, karakter santri harus memancarkan Rahmatan lil ‘Alamin (kasih sayang bagi semesta), menolak ujaran kebencian (hate speech), dan mempromosikan ukhuwah (persaudaraan).
Literasi Konatif atau Tafaqquh Aksiologis): Pengambilan keputusan etis. Bagaimana santri menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) secara beretika? Bagaimana menjaga privasi (hifzh al-nasl secara digital)? Ini adalah ranah aksiologi peradaban baru.
“Karakter sejati seorang santri bukan diukur dari seberapa dalam ia menghafal matan (teks inti), melainkan seberapa tangguh ia mempertahankan kebenaran dan kasih sayang ketika jari-jemari dunia maya memaksanya untuk membenci dan memecah belah.”
Ekosistem Kebudayaan: Santri sebagai Jembatan Peradaban
Ekosistem kebudayaan adalah arena tempat Tafaqquh fi Tamaddun diimplementasikan. Pesantren, sebagai sebuah mikrokosmos, harus didesain ulang bukan sebagai tempat pengasingan, melainkan sebagai Laboratorium Peradaban (Laboratorium at-Tamaddun).
Antropologi Ekosistem: Revitalisasi Peran Pondok
Secara antropologis, ekosistem pondok pesantren harus bertransformasi dari:
1. Dari Monolog menjadi Dialog: Kurikulum tidak hanya mengajarkan apa yang ada di kitab, tetapi juga dialog aktif dengan ilmu-ilmu kontemporer: ekonomi digital, fisika kuantum, dan psikologi modern.
2. Dari Lokalitas menuju Globalitas: Memanfaatkan jaringan digital untuk menyebarkan ilmu dan kearifan lokal (hikmah) ke panggung global. Santri harus menjadi Duta Perdamaian Digital yang menyuarakan Islam Nusantara sebagai model moderasi.
Santri, Sang Penenun Jaring
Dalam perspektif sastrawi, santri adalah Penenun Jaring. Ia menenun benang-benang spiritualitas dari tradisi yang tak lekang oleh waktu (fiddin) ke dalam kanvas modern yang bergerak cepat (fi tamaddun). Ia membawa air zamzam ke padang gurun digital, dan membawa algoritma ke dalam khazanah spiritual.
“Ia berjalan, bukan sebagai penentang, melainkan sebagai penyeimbang. Matanya tajam, membedakan kilau emas informasi dari serpihan debu hoax. Ia tahu, menara gading filsafat harus turun ke pasar, di mana manusia bergumul dengan virtualitas dan kesejatian. Inilah jihad literasi yang baru: membangun Budaya Digital Berakhlak, di mana setiap byte data mengandung jejak kemanusiaan dan keimanan.”
Keberhasilan Tafaqquh fi Tamaddun akan terlihat ketika santri tidak hanya menjadi ulama (orang yang berilmu agama), tetapi juga futuris (orang yang merancang masa depan) yang berlandaskan moralitas transenden. Mereka harus mampu merumuskan etika Artificial Intelligence (AI) berbasis maqashid syariah (tujuan hukum Islam) atau membangun sistem ekonomi digital yang adil berdasarkan prinsip muamalah.
Penutup: Ijtihad Abad ke-21 dan Janji Perenialitas
Tantangan santri di era disrupsi adalah anugerah tersembunyi. Ia memaksa ijtihad baru, sebuah pemikiran ulang mendasar tentang makna ilmu dan peran kehadirannya. Dualitas Tafaqquh fiddin dan Tafaqquh fi Tamaddun bukanlah kontradiksi, melainkan sebuah dialektika kreatif—sebuah tesis dan antitesis yang harus disintesiskan dalam diri setiap santri.
Tafaqquh fiddin memberikan akar yang tak tergoyahkan, sebuah pusat yang senantiasa mengarah pada Haqq. Tafaqquh fi Tamaddun memberikan sayap yang memungkinkannya terbang melintasi cakrawala peradaban, memahami bahasa baru dunia, dan berinteraksi secara efektif.
Inilah janji perenialitas: bahwa tradisi suci dapat bertahan dan memimpin di tengah gelombang perubahan tercepat dalam sejarah manusia. Santri tidak hanya ditakdirkan untuk menghafal masa lalu; ia ditugaskan untuk mengukir masa depan dengan pena kearifan dan kode moral yang tak lekang. Ia adalah Penjaga Pintu (Bab al-Hikmah) yang kini harus membuka pintu itu lebar-lebar bagi cahaya peradaban, memastikannya tetap bercahaya oleh Api Tawhid di jantungnya.
——
*Gus Nas. Budayawan.