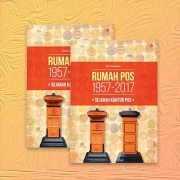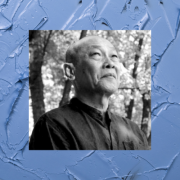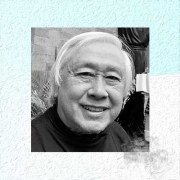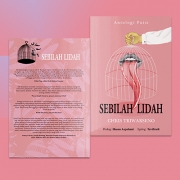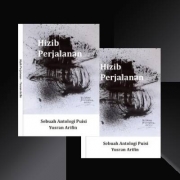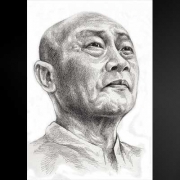Kearifan Timur dalam Kritik Pembangunan: Membaca Rendra Melalui Filsafat Jawa
Oleh: Tengsoe Tjahjono*
Kumpulan Potret Pembangunan dalam Puisi (1978) merupakan salah satu puncak perlawanan kultural W.S. Rendra, penyair kelahiran Solo, jantung kebudayaan Jawa, terhadap model pembangunan Orde Baru yang menindas rakyat dan mengebiri nurani kemanusiaan. Sebagai seorang wong Jawa yang lahir dan tumbuh dalam tradisi spiritual, kesenian, dan kebatinan yang kuat, Rendra membawa roh Jawa dalam setiap puisinya. Ia bukan hanya penyair yang memprotes ketidakadilan sosial, melainkan juga manusia Jawa sejati yang melihat dunia melalui laku batin (laku prihatin), rasa (rasa), dan kebijaksanaan (kautaman).
Kedekatan Rendra dengan tradisi Jawa dapat ditelusuri dari masa kecilnya di Solo, sebuah kota yang memadukan spiritualitas keraton, kesenian rakyat, dan semangat pembaruan sosial. Rendra tumbuh di lingkungan religius dan estetik: ayahnya seorang guru bahasa dan drama, ibunya penari tradisional. Dari situ, ia mewarisi dua hal penting yang membentuk visi estetiknya: rasa (intuisi estetis dan spiritual) dan tanggap ing sasmita (kepekaan terhadap tanda-tanda kehidupan), dua prinsip utama dalam filsafat hidup Jawa. Dalam puisinya, rasamenjadi sumber moral, sedangkan tanggap ing sasmita menjadi daya kritis terhadap realitas sosial yang timpang.
Melalui Potret Pembangunan dalam Puisi, Rendra tidak hanya melakukan kritik sosial terhadap kebijakan ekonomi-politik Orde Baru yang menindas rakyat kecil, tetapi juga berusaha membangun kembali kesadaran spiritual bangsa, sebuah kesadaran yang dalam filsafat Jawa disebut ngelmu kasampurnan urip: pengetahuan tentang hidup yang seimbang antara jasmani dan rohani, antara kepentingan pribadi dan harmoni semesta.
Bagi Rendra, pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa keseimbangan moral dan kemanusiaan adalah bentuk penyimpangan dari kodrat alam (dalam istilah Jawa: ngluwihi paugeraning urip). Ia mengingatkan bahwa kemajuan sejati bukanlah deretan angka statistik, melainkan tata tentreming bebrayan, keharmonisan hidup bersama. Kritiknya yang tajam terhadap penguasa, teknokrat, dan intelektual bukan semata-mata lahir dari ideologi politik, tetapi dari kesadaran kosmis bahwa manusia harus hidup selaras, seimbang, dan sadar akan keterbatasan diri di hadapan semesta.
Sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno (1984), inti etika Jawa adalah harmoni dan keseimbangan (rukun), yang menuntut manusia agar tidak melawan kodrat(Magnis-Suseno, 1984:72). Prinsip rukun bukan berarti pasif, melainkan upaya menjaga keseimbangan di tengah konflik dan perbedaan, serta menghindari kekerasan rasa. Dalam perspektif ini, puisi-puisi Rendra merupakan bentuk “nggugah rasa”, upaya penyadaran batin terhadap masyarakat yang kehilangan keseimbangannya akibat pembangunan materialistik yang menuhankan angka dan mengabaikan manusia.
Dengan demikian, Potret Pembangunan dalam Puisi dapat dibaca bukan sekadar sebagai dokumen kritik sosial-politik, tetapi juga sebagai naskah kebatinan Jawa modern, tempat Rendra menghidupkan kembali falsafah hidup Jawa dalam konteks krisis kemanusiaan modern. Melalui bahasa puisi yang penuh getar rasa dan semangat perlawanan, Rendra mengembalikan sastra pada fungsi aslinya sebagai laku batin dan laku sosial, yakni jalan untuk menemukan kembali keseimbangan antara akal, rasa, dan kebenaran hidup.
Etika Perlawanan dan Spirit Ngudi Kautaman
“Aku tulis pamplet ini / karena lembaga pendapat umum ditutupi jaring labah-labah.”
(Aku Tulis Pamplet Ini, Pejambon, 27 April 1978)
Puisi ini menggambarkan situasi sosial-politik yang menyesakkan: kekuasaan menutup ruang dialog dan menekan kebebasan berpikir. Dalam pandangan Rendra, keadaan seperti itu bukan sekadar krisis politik, melainkan juga krisis moral dan spiritual bangsa.
Dalam filsafat Jawa, kehidupan yang ideal menuntut adanya rembugan, yaitu dialog terbuka dan jujur antara manusia untuk menjaga rukun (harmoni). Rembugan bukan hanya praktik sosial, tetapi juga manifestasi dari kesadaran kosmis bahwa setiap suara memiliki tempatnya dalam tatanan semesta. Ketika kekuasaan menutup ruang rembugan, maka yang terganggu bukan hanya tatanan sosial, tetapi juga tata batin jagad, keseimbangan semesta itu sendiri.
Rendra menulis: “Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar. Duduk berdebat menyatakan setuju dan tidak setuju.” Bait ini merupakan penegasan atas semangat ngudi kautaman—pencarian kebijaksanaan sejati. Dalam pandangan Jawa, kautaman bukanlah kekuasaan atau kemenangan, melainkan kemampuan menjaga keselarasan antara budi, rasa, dan laku. Seorang yang ngudi kautaman adalah mereka yang berani berkata benar tanpa kehilangan kesantunan, berani melawan tanpa menebar kebencian.
Maka, perlawanan Rendra bukanlah bentuk kemarahan destruktif, melainkan “laku spiritual seorang ksatria pinandita”, pahlawan rohani yang menegakkan kebenaran dengan batin sing bening (jiwa yang jernih). Dalam istilah Zoetmulder (1990:185), kebenaran dalam pandangan Jawa bukan berasal dari kekuasaan eksternal, tetapi dari kejernihan batin yang menyatu dengan rasa alam.
Etika perlawanan semacam ini tampak pula dalam puisi Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon, ketika Rendra menulis:
“Aku berdiri di muka kantor polisi.
Aku melihat wajah berdarah seorang demonstran.
Aku melihat kekerasan tanpa undang-undang.”
Di sini, sosok “orang tua” berdiri sebagai saksi sunyi terhadap kehancuran moral bangsa.Ia tidak lagi mengumbar amarah, tetapi mengolah penderitaan menjadi kesadaran. Dalam tradisi Jawa, ini adalah bentuk laku prihatin—menanggung derita demi menjaga kemurnian hati. Iasadar bahwa perlawanan sejati bukanlah menghancurkan musuh, melainkan menyembuhkan kebutaan batin yang melahirkan ketidakadilan.
Rendra menutup puisi itu dengan pengakuan spiritual:
“Ya! Ya! Akulah seorang tua!
Yang capek tapi belum menyerah pada mati.
Kini aku berdiri di perempatan jalan.
Aku merasa tubuhku sudah menjadi anjing,
tetapi jiwaku mencoba menulis sajak sebagai seorang manusia.”
Ungkapan ini menggambarkan transformasi spiritual: tubuhnya mungkin hina, tetapi jiwanya tetap luhur—ngudi kautaman hingga akhir hayat. Ia tetap menulis sebagai tindakan laku, sebagai jalan menuju kasampurnan urip.
Semangat ngudi kautaman juga tampak jelas dalam Sajak Pertemuan Mahasiswa, di mana Rendra memosisikan mahasiswa sebagai generasi satrio pandita—pemuda yang dituntut tidak hanya pandai berpikir, tetapi juga berani mempertanyakan arah moral pengetahuannya.
“Kita bertanya: maksud baik saudara untuk siapa?
Saudara berdiri di pihak yang mana?”
Pertanyaan ini adalah bentuk ngilo rasa (introspeksi), inti dari kebijaksanaan Jawa.Dalam etika Kejawen, seseorang baru bisa disebut berilmu apabila ilmunya tidak menyesatkan rasa keadilan. Rendra menegaskan bahwa ilmu dan pembangunan tanpa budi pekerti hanya melahirkan kekosongan batin.
Etika perlawanan dalam puisi-puisi Rendra dengan demikian berbeda dari perlawanan revolusioner Barat yang cenderung menekankan konfrontasi frontal. Rendra menawarkan perlawanan berbasis spiritualitas, perlawanan yang lembut, sabar, namun tegas dalam moral. Iamenolak diam, tetapi juga menolak kekerasan. Sikap ini mencerminkan ideal Jawa tentang ksatria pinandita, yaitu sosok yang memadukan keberanian seorang prajurit dan kebijaksanaan seorang pendeta.
Gema etika ini kembali terasa dalam puisi berikut:
“Orang-orang harus dibangunkan.
Kesaksian harus diberikan.
Agar kehidupan bisa terjaga.”
Kalimat pendek dan lirih ini adalah mantra etis Rendra. Ia menyadari bahwa dalam dunia yang bising oleh propaganda kekuasaan, tugas penyair bukanlah berteriak paling keras, melainkan membangunkan kesadaran, sebuah bentuk nggugah rasa agar manusia kembali pada budi nurani.
Dengan demikian, “Aku Tulis Pamplet Ini” dan puisi-puisi lain yang sejiwa dengannya bukanlah sekadar pamflet politik, melainkan ajaran kebijaksanaan Jawa dalam konteks modern.Rendra menegakkan etika perlawanan yang berakar pada ngudi kautaman: keberanian berbudi, kebebasan yang berlandas welas asih, dan kekuasaan yang tunduk pada kebenaran batin. Dalam diri Rendra, penyair dan pandita menyatu—ia berjuang melawan tirani, namun tetap menyalakan lentera kesadaran dengan rasa yang lembut dan laku yang teguh.
Pendidikan dan Krisis Laku Urip
“Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya?”
(Sajak Seonggok Jagung, 12 Juli 1975)
Puisi ini merupakan kritik Rendra yang paling tajam terhadap sistem pendidikan modern yang tercerabut dari kehidupan rakyat. Rendra menggambarkan seorang pemuda tamatan sekolah menengah yang hanya memiliki “seonggok jagung di kamar,” simbol keterbatasan ekonomi sekaligus kemandulan sosial dari pendidikan yang tidak membekali kemampuan hidup nyata.Pendidikan, dalam pandangan Rendra, telah berubah menjadi instrumen reproduksi ketimpangan, bukan alat pembebasan.
Dalam filsafat Jawa, ilmu sejati (ngelmu sejati) tidak pernah berhenti pada pengetahuan rasional semata, tetapi harus manunggal dengan laku urip, yakni tindakan sehari-hari yang selaras dengan kehidupan nyata. Ngelmu tanpa laku hanyalah wacana kosong; sedangkan laku tanpa ngelmu mudah tersesat. Rendra melihat ketidakseimbangan ini dalam sistem pendidikan modern yang hanya menjejali hafalan dan teori Barat tanpa akar lokal.
“Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan.”
Baris ini menjadi gugatan terhadap pembangunan yang melupakan urip kang nyawiji, kehidupan yang menyatu dengan alam, masyarakat, dan spiritualitas. Dalam pandangan Kejawen, pengetahuan sejati harus menuntun manusia menuju kasampurnan urip, yakni kesempurnaan hidup yang tidak hanya mengandalkan akal, tetapi juga rasa, karsa, dan cipta.
Krisis laku urip yang ditunjukkan Rendra dalam puisi ini sesungguhnya adalah krisis moral kebudayaan. Pemuda yang “tamat SLA” itu bukan hanya miskin secara ekonomi, melainkan juga miskin secara batin: ia “melihat dirinya terlunta-lunta,” karena pendidikan tidak membekalinya dengan ketangguhan roso dan kebijaksanaan laku.
Kritik ini semakin menguat bila dibaca bersama puisi Sajak Sebatang Lisong, di mana Rendra mengungkapkan:
“Aku melihat delapan juta kanak-kanak tanpa pendidikan.
Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet,
dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan.”
Di sini, Rendra memperluas makna “pendidikan yang memisahkan” menjadi masalah struktural bangsa: bukan hanya siswa yang tercerabut dari kehidupan, tetapi juga para pendidik dan pengambil kebijakan yang kehilangan roh pendidikan itu sendiri. Dalam tradisi Jawa, pendidikan adalah proses mardika jiwa, membebaskan batin manusia dari kebodohan, keserakahan, dan kesombongan. Bila pendidikan justru menumbuhkan keterasingan dan ketimpangan, maka itu bukan ngelmu sejati, melainkan ngelmu kang ilang paugeran, ilmu yang kehilangan tata batin.
Sikap kritis Rendra terhadap pendidikan modern juga merefleksikan konsep sangkan paraning dumadi, kesadaran akan asal-usul dan tujuan hidup manusia. Ilmu seharusnya menuntun manusia untuk memahami tempatnya dalam semesta, bukan menjadikannya hamba mesin dan kekuasaan. Karena itu, pendidikan yang hanya berorientasi pada teknologi dan efisiensi dianggap menyalahi kodrat urip kang rukun, sebab ia menciptakan manusia yang terpisah dari akar budaya dan lingkungan sosialnya.
Pandangan ini diperkuat dalam Sajak Pertemuan Mahasiswa, ketika Rendra mempertanyakan fungsi ilmu dalam konteks sosial-politik:
“Kita ini dididik untuk memihak yang mana?
Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan,
ataukah alat penindasan?”
Pertanyaan tersebut bukan sekadar kritik ideologis, melainkan perenungan eksistensialdalam kerangka filsafat Jawa. Mahasiswa yang tercerahkan seharusnya menjalani laku bebrayan—berpihak pada kehidupan bersama, bukan menjadi alat sistem yang menindas rakyatnya sendiri. Dalam konsep ngudi kasampurnan urip, ilmu tanpa budi pekerti hanyalah jalan menuju kehampaan spiritual.
Lebih jauh lagi, puisi Orang-orang Miskin memperlihatkan konsekuensi tragis dari kegagalan pendidikan dalam menjalankan fungsi sosialnya:
“Jangan kamu bilang negara ini kaya
karena orang-orang miskin berkembang di kota dan di desa.”
Kalimat ini menggugat rasionalisme pembangunan yang mengukur kemajuan dari indikator ekonomi semata, tanpa memperhitungkan derita batin rakyat. Pendidikan yang tercerabut dari laku urip membuat manusia berilmu tetapi tidak berperasaan, pandai berhitung tetapi buta terhadap penderitaan sesama. Dalam kerangka etika Jawa, hal itu disebut wruh ing ngelmu nanging ora wruh ing rasa, menguasai ilmu, tetapi tidak menguasai kebijaksanaan hati.
Dengan demikian, Rendra menghadirkan etika Jawa sebagai alternatif humanistik terhadap rasionalisme teknokratik yang kering spiritualitas. Ia menolak pendidikan yang menjadikan manusia sekadar “alat pembangunan,” dan mengembalikannya pada fungsi sejatinya sebagai sarana penyadaran diri dan penghalusan budi. Dalam visi Rendra, pendidikan harus menjadi jalan nyawiji karo urip, tempat akal, rasa, dan karsa berpadu membentuk manusia yang waspada lan wening batin.
Puisi-puisi dalam Potret Pembangunan dalam Puisi dengan demikian bukan hanya seruan sosial, tetapi juga pangeling-eling, pengingat spiritual bahwa ilmu, bila terlepas dari laku urip, akan menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Rendra menggugah kesadaran bahwa modernitas tanpa ngelmu sejati hanya akan melahirkan manusia “bergelar tinggi, tetapi gersang rasa.” Seperti petuah Jawa kuno:
“Ngelmu iku kalakone kanthi laku,
lekase lawan kas, tegese kas nyantosani.”
(Ilmu sejati hanya dapat dicapai dengan laku,
dan laku harus dijalankan dengan tekun serta ketulusan hati.)
Rendra, dengan demikian, berdiri dalam garis panjang kebijaksanaan Jawa: iamenyerukan revolusi bukan melalui kekerasan, tetapi melalui pemulihan rasa dan laku, agar manusia kembali pada kasampurnan urip—kesempurnaan hidup yang menyatu antara ilmu, moral, dan kemanusiaan.
Citra Rakyat sebagai Korban Karma Politik
“Para tani-buruh bekerja, menanam bibit di tanah yang subur, namun hidup mereka sendiri sengsara.”
Puisi ini menampilkan wajah tragis rakyat kecil (petani dan buruh) yang bekerja keras menanam bibit kehidupan, tetapi hasilnya dinikmati oleh segelintir orang. Di tangan Rendra, penderitaan rakyat tidak dihadirkan sebagai keluhan sosial semata, melainkan sebagai tanda disharmoni kosmis, hasil dari kekuasaan yang kehilangan dharma.
Dalam tafsir filsafat Timur, terutama dalam kerangka Hindu-Jawa, penderitaan kolektif adalah karma sosial atau karma politik—buah dari tindakan manusia dan sistem kekuasaan yang tidak selaras dengan dharma, yakni kebenaran dan keadilan kosmis. Ketika kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan diri, maka keseimbangan alam terganggu dan penderitaan massal muncul sebagai akibatnya. Dalam puisi Rendra, burung-burung kondor yang menjerit di gunung melambangkan jiwa-jiwa rakyat yang tercerabut dari welas asih semesta, terasing dari tatanan moral yang seharusnya menegakkan harmoni.
“Beribu-ribu burung kondor, berjuta-juta burung kondor,
bergerak menuju ke gunung tinggi,
dan di sana mendapat hiburan dari sepi.”
Sepi dalam konteks ini bukan hanya kesunyian geografis, melainkan kesunyian spiritual bangsa, tempat nurani kehilangan tempatnya di tengah hiruk-pikuk pembangunan. Sepi menjadi simbol kegersangan batin nasional, buah dari ketimpangan sosial dan hilangnya rasa rukunantara penguasa dan rakyat.
Puisi ini beresonansi kuat dengan Orang-orang Miskin, yang memperluas potret penderitaan rakyat dari desa ke kota:
“Orang-orang miskin di jalan,
yang tinggal di dalam selokan,
yang kalah di dalam pergulatan,
yang diledek oleh impian,
janganlah mereka ditinggalkan.”
Rendra menempatkan kaum miskin sebagai cermin batin bangsa. Mereka bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi saksi moral dari sebuah peradaban yang gagal menegakkan dharma negara. Dalam pandangan Jawa, dharma ratu (kewajiban moral pemimpin) adalah ngayomi lanngayemi rakyat—melindungi dan menenteramkan rakyatnya. Bila pemimpin mengabaikan tanggung jawab ini, maka karma politik akan menimpa seluruh tatanan sosial: kegelisahan, kekerasan, dan kehilangan arah batin.
Itulah sebabnya Rendra menulis dengan nada profetik:
“Bila kamu remehkan mereka,
di jalan kamu akan diburu bayangan.
Tidurmu akan penuh igauan,
dan bahasa anak-anakmu sukar kamu terka.”
Ini bukan sekadar metafora sosiologis, melainkan juga peringatan metafisik: kejahatan struktural akan kembali menghantui pelakunya dalam bentuk disintegrasi sosial dan moral. Dalam istilah Jawa, ini disebut kualat marang rakyat, kutukan spiritual karena mengabaikan kesejahteraan sesama.
Penderitaan rakyat sebagai karma politik juga muncul dalam Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon, di mana tokoh tua menjadi saksi kerusakan moral bangsa:
“Aku melihat penggarongan dan pembusukan.
Aku meludah di atas tanah.
Aku mendengar orang berkata:
‘Hak asasi manusia tidak sama di mana-mana.’”
Tokoh tua dalam puisi ini bukan hanya representasi generasi yang lelah, tetapi juga residu kebijaksanaan Jawa yang memandang kekuasaan sebagai amanah kosmis. Ketika Rendra menulis, “Astaga, tahi kerbo apa ini!” ia bukan sedang melontarkan kemarahan vulgar, melainkan sasmita rasa, ungkapan spontan dari batin yang muak melihat kekuasaan kehilangan wirya lan darma.
Dalam ajaran Jawa, kesengsaraan rakyat bukanlah takdir (nasib), melainkan panggilan nurani bagi para pemimpin untuk melakukan tapa ngrame, yakni pengorbanan diri demi kemakmuran banyak orang (Endraswara, 2012:118). Tapa ngrame berarti menjalankan asketisme sosial: hidup sederhana, mendengar keluh rakyat, dan bertindak demi kesejahteraan umum. Pemimpin sejati bukan yang berkuasa atas rakyat, melainkan yang ngayomi rakyat dengan roso welas asih (belas kasih batin).
Kesadaran etis semacam ini juga muncul secara singkat namun kuat dalam puisi berikut:
“Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka.
Ada orang memanah rembulan.
Ada anak burung terjatuh dari sarangnya.
Orang-orang harus dibangunkan.
Kesaksian harus diberikan.
Agar kehidupan bisa terjaga.”
Puisi pendek ini memperlihatkan pandangan ekokosmologis Jawa, di mana penderitaan makhluk sekecil burung pun dianggap bagian dari penderitaan manusia. Segala bentuk ketidakadilan, bahkan terhadap alam, merupakan pelanggaran terhadap rasa jagad, rasa harmoni universal. Jerit hewan, jatuhnya anak burung, dan rembulan yang dipanah adalah simbol tandha-tandha alam (tanda-tanda kosmis) yang memberi isyarat bahwa keseimbangan dunia sedang goyah.
Dalam kerangka itu, Rendra berbicara sebagai manusia Jawa spiritualis, yang menolak memisahkan politik dari moralitas kosmis. Baginya, krisis bangsa bukan hanya kegagalan ekonomi, tetapi juga kegagalan rasa. Ia memandang penderitaan rakyat sebagai akibat dari pemimpin dan sistem yang kehilangan tata batin dharma.
Dengan demikian, melalui puisi-puisinya, Rendra membangkitkan kembali kesadaran bahwa keadilan sosial tidak bisa ditegakkan tanpa keseimbangan spiritual. Ia mengajak pembacanya untuk memahami pembangunan sebagai laku dharma, tindakan sadar yang berpihak pada kehidupan, bukan kekuasaan.
Puisi-puisi seperti Sajak Burung-burung Kondor, Orang-orang Miskin, Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon, dan Aku Mendengar Suara bersama-sama membentuk “tetralogi penderitaan dan kebangkitan rohani”, di mana rakyat bukan hanya korban sosial, tetapi juga korban disharmoni moral pemimpinnya. Rendra tidak menulis untuk mengutuk, melainkan untuk nggugah rasa: membangunkan kesadaran bangsa agar kembali pada keseimbangan antara kuasa dan welas asih, antara pembangunan dan kemanusiaan, antara materi dan batin.
Kesadaran Manembah dan Krisis Moral
“Aku melihat penggarongan dan pembusukan. Aku meludah di atas tanah.”
Puisi ini menampilkan sosok “seorang tua” yang berdiri di bawah pohon meranggas, simbol manusia yang telah sampai pada puncak pengalaman batin. Ia menyaksikan kebusukan moral dan kerusakan sosial, tetapi tidak lagi melawan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan reflektif seorang wong sepuh. Tokoh ini bukan lagi bagian dari keramaian dunia; iaberdiri di ambang antara dunia fana dan dunia rohani, antara kenyataan sosial dan kesadaran batin.
Dalam tradisi Jawa, sosok semacam ini disebut wong kang wus wusanan, orang yang telah mencapai kedewasaan rohani, yang manembah sejati. Manembah sejati bukan berarti tunduk kepada penguasa, melainkan penyerahan total kepada kebenaran Ilahi dan keseimbangan semesta. Ia menolak tunduk pada kekuasaan duniawi, tetapi tetap memelihara kasih dan kebijaksanaan di tengah kebobrokan.
Ketika Rendra menulis:
“Ya! Ya! Akulah seorang tua!
Yang capek tapi belum menyerah pada mati.”
kita mendengar gema laku sabar lan nrima, kesabaran yang bukan pasif, tetapi keteguhan spiritual untuk tetap menjaga rasa adiluhung meski dunia rusak. Nilai nrima dalam filsafat Jawa tidak berarti menyerah, melainkan ngerti marang kersaning urip, memahami kehendak hidup, dan dari pemahaman itu lahir kekuatan batin untuk tetap ngugemi kabecikan (berpegang pada kebaikan).
Inilah bentuk perlawanan khas Jawa yang disebut padhang mbulan: terang batin yang menolak gelap moral kekuasaan. Sosok tua itu tidak mengumbar kebencian, tetapi memancarkan padhang rasa, cahaya kesadaran yang mengingatkan bahwa kegelapan sosial hanya bisa diatasi dengan kejernihan batin.
Kesadaran manembah ini juga hadir dalam puisi Pamplet Cinta (Jakarta, 28 April 1978), ketika Rendra menulis:
“Aku menyaksikan zaman berjalan kalangkabutan.
Aku melihat waktu melaju melanda masyarakatku.
Aku merindukan wajahmu,
dan aku melihat wajah-wajah berdarah para mahasiswa.”
Puisi ini memadukan cinta manusia dengan cinta sosial; Rendra memandang kekasih sebagai lambang kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Dalam pandangan Jawa, cinta (tresna) yang sejati adalah bentuk manembah, penyatuan batin antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Rendra menjadikan cinta sebagai energi spiritual untuk melawan ketakutan, kekuasaan, dan ketegangan sosial.
Ketika ia berkata,
“Harapan adalah karena aku akan tetap menulis sajak.”
kita melihat bahwa menulis, bagi Rendra, bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi laku spiritual. Ia menulis sebagai bentuk manembah kepada kebenaran, sebagaimana seorang panditaberdoa di tengah zaman yang gersang moral. Dalam konteks Jawa, tindakan ini merupakan wujud ngesthi marang urip, menghidupi kehidupan dengan kesadaran spiritual, bukan dengan kepalsuan dan pamrih.
Puisi Nota Bene: Aku Kangen (Kotabumi, 24 Maret 1978) memperlihatkan dimensi yang lebih lembut dari kesadaran manembah. Di tengah kerinduan personal terhadap sang kekasih, Rendra menulis:
“Tanpa sekejap pun luput dari kenangan kepadamu
aku bergerak menulis pamplet, mempertahankan kehidupan.”
Baris ini menunjukkan bahwa cinta personal dan perjuangan sosial bagi Rendra saling berkelindan. Cinta menjadi sumber tenaga batin untuk bertahan di tengah kekacauan dunia.Dalam filsafat Jawa, cinta adalah manifestasi rasa sejati, dan rasa sejati itulah jalan menuju manunggal, penyatuan dengan semesta dan Tuhan. Maka, tindakan menulis pamflet bukan sekadar perlawanan politik, tetapi juga manembah dalam arti terdalam: menghidupi cinta dengan kesetiaan kepada kebenaran.
Sementara itu, puisi berikut memperlihatkan bentuk manembah yang lebih kosmis:
“Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka.
Ada anak burung terjatuh dari sarangnya.
Orang-orang harus dibangunkan.
Kesaksian harus diberikan.
Agar kehidupan bisa terjaga.”
Puisi ini adalah doa bagi kehidupan, semacam dzikir jagad, perenungan terhadap suara alam sebagai panggilan spiritual untuk menjaga keseimbangan kosmos. Dalam pandangan Jawa, mendengar jerit makhluk kecil berarti mendengar jerit semesta, sebab manusia adalah bagian dari keseluruhan hidup. Ketika Rendra mengatakan “kesaksian harus diberikan,” ia menegaskan panggilan moral manusia untuk bertanggung jawab terhadap ciptaan. Manembah sejati bukan hanya sujud di hadapan Tuhan, tetapi juga menyadari dan merawat kehadiran Ilahi dalam segala bentuk kehidupan.
Dengan demikian, Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon, Pamplet Cinta, Nota Bene: Aku Kangen, dan Aku Mendengar Suara membentuk satu garis spiritual yang sama: Rendra menggambarkan kesadaran manembah sebagai sumber moral perlawanan. Di tengah krisis nilai dan kemerosotan sosial, ia mengajukan alternatif etika yang berakar pada filsafat Jawa: kesadaran batin yang jernih, cinta yang universal, dan tanggung jawab kosmis terhadap kehidupan.
Krisis moral yang disorot Rendra bukan hanya akibat politik yang korup, tetapi juga hilangnya kesadaran manembah. Manusia modern kehilangan roso eling lan waspada, rasa sadar dan waspada akan keterhubungannya dengan kekuatan Ilahi dan alam. Karena itu, Rendra menempatkan penyair sebagai pandita sosial, yang tugasnya bukan mengutuk, melainkan membangunkan kesadaran spiritual bangsa.
Puisi-puisinya adalah bentuk tapa brata dalam zaman pembangunan; melalui bahasa, iabertapa untuk menyucikan batin bangsa. Dengan kesabaran nrima, kejernihan wening, dan keberanian ngugemi kabeneran, Rendra menegakkan kembali nilai padhangmbulan—cahaya batin yang menolak gelap moral kekuasaan dan memancarkan kembali nurani kemanusiaan yang adiluhung.
Filsafat Kejawen dan Etika Sosial
“Kita bertanya: maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana?”
Puisi ini menampilkan mahasiswa sebagai kawula muda yang terbangun dari tidur panjang intelektualnya, lalu memeriksa kembali arah moral pengetahuannya. Pertanyaan retoris “maksud baik untuk siapa?” bukan sekadar sindiran politik, tetapi wujud dari praktik ngilo rasa, introspeksi batin yang menjadi salah satu pilar utama dalam etika Kejawen.
Dalam tradisi Jawa, ngilo rasa adalah usaha melihat ke dalam diri dengan kejernihan hati untuk mengetahui apakah tindakan seseorang selaras dengan dharma (kebenaran dan keadilan).Rendra menggunakan bentuk pertanyaan ini untuk mengguncang kesadaran kaum terpelajar yang sering menjustifikasi kekuasaan dengan alasan “maksud baik pembangunan.” Ia mengingatkan bahwa kebaikan sejati harus selalu berlandaskan rasa adil, bukan kepentingan kelompok atau kekuasaan.
Puisi ini menggambarkan situasi sosial pada masa Orde Baru, ketika pendidikan tinggi dijadikan alat legitimasi politik pembangunan. Namun, Rendra membacanya dengan kacamata kebijaksanaan Timur: revolusi tanpa kebencian, perubahan dengan kesadaran batin. Ia tidak menyerukan perlawanan fisik, melainkan revolusi rasa, sebuah transformasi kesadaran yang lahir dari filsafat Kejawen.
Etika sosial Rendra dalam puisi ini berpijak pada prinsip sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu, ilmu untuk membebaskan manusia dari kegelapan batin dan sosial. Dalam ajaran Jawa, diyu (iblis) bukan makhluk metafisik, tetapi simbol hawa nafsu, keserakahan, dan egoisme manusia. Karena itu, Rendra menuntut agar ilmu dan pembangunan tidak melahirkan manusia yang diperbudak oleh ambisi. Ia menulis:
“Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini
akan menjadi alat pembebasan,
ataukah alat penindasan?”
Pertanyaan ini adalah panggilan untuk menegakkan dharma pendidikan: bahwa pengetahuan sejati seharusnya memerdekakan, bukan memperbudak. Pandangan ini selaras dengan prinsip filsafat Kejawen bahwa ilmu harus membawa padhang rasa, pencerahan batin bagi manusia dan lingkungannya.
Semangat etika sosial yang sama juga mengalir dalam Aku Tulis Pamplet Ini:
“Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar.
Duduk berdebat menyatakan setuju dan tidak setuju.”
Bait ini menunjukkan bahwa bagi Rendra, dialog dan keterbukaan adalah bagian dari tata krama sosial yang berakar dalam budaya Jawa. Ia menolak politik yang represif dan menggantinya dengan semangat musyawarah sejati, rembug yang berdasarkan rasa hormat dan welas asih. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan tanpa tata krama adalah dur angkara, kekuasaan yang lepas kendali, kehilangan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan.
Puisi Sajak Sebatang Lisong juga memperlihatkan kegelisahan etis yang sejalan dengan Sajak Pertemuan Mahasiswa. Rendra menulis:
“Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet,
dan papantulis-papantulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan.”
Baris ini menegaskan bahwa dalam sistem sosial yang kehilangan rasa dharma, pengetahuan tidak lagi menjadi sarana kebijaksanaan, melainkan alat pembenaran kekuasaan.Dalam filsafat Kejawen, hal ini disebut ilmu tanpa budi, pengetahuan yang tidak diimbangi oleh kesadaran moral. Bagi Rendra, ilmu semacam ini justru menjerumuskan bangsa ke dalam “kegelapan rohani,” seperti halnya diyu dalam mitologi Jawa yang melambangkan kebutaan batin.
Etika sosial Rendra selalu diwarnai kesadaran kasih universal yang berpijak pada prinsip rukun lan tanggung rasa. Prinsip ini muncul secara lembut dalam Pamplet Cinta, di mana iamenulis:
“Harapan adalah karena aku akan tetap menulis sajak.”
Menulis bagi Rendra bukan hanya tindakan intelektual, melainkan laku sosial, caraseorang pandita modern mengemban tanggung jawab moral terhadap bangsanya. Ia menulis bukan karena benci kepada penguasa, melainkan karena cinta kepada kehidupan. Pamplet Cintadengan demikian menjadi pengejawantahan konsep asih-tresna-karaharjan (kasih, cinta, dan kesejahteraan), tiga nilai yang menopang etika sosial dalam kebijaksanaan Jawa.
Rendra memperlihatkan bahwa tanggung jawab sosial tidak bisa dipisahkan dari kebersihan batin. Etika sosial dalam filsafat Kejawen berakar pada kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari tata jagad (tatanan kosmos). Maka, segala tindakan sosial harus mencerminkan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Inilah yang membuat perlawanan Rendra selalu berwajah spiritual, tidak hanya menolak penindasan, tetapi juga mengajak manusia menata batinnya.
Dengan demikian, Sajak Pertemuan Mahasiswa, Aku Tulis Pamplet Ini, Sajak Sebatang Lisong, dan Pamplet Cinta membentuk jejaring moral yang menggambarkan etos Kejawen dalam bentuk modern. Puisi-puisi ini menunjukkan bahwa pendidikan, politik, dan cinta sama-sama memerlukan laku batin agar tidak kehilangan arah dharma.
Rendra menghadirkan filsafat Kejawen bukan sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai etika pembebasan kontemporer:
Maka, Sajak Pertemuan Mahasiswa menjadi doa politik yang berakar pada kebijaksanaan Timur: revolusi tanpa kebencian, perubahan dengan kesadaran batin. Melalui ngelmu rasa, Rendra mengembalikan politik kepada nurani, dan melalui puisi, ia menegakkan kembali prinsip dharma sosial yang memuliakan manusia dan kemanusiaan.
Rendra dan Jalan Kebijaksanaan Timur
Rendra bukan hanya penyair protes, tetapi seorang resi modern yang menyuarakan kembali nilai-nilai kebijaksanaan Jawa di tengah zaman yang kehilangan rohnya. Dalam setiap puisinya, Rendra berfungsi seperti pandita nusantara, penjaga nurani bangsa, yang mengingatkan manusia Indonesia agar tidak terperangkap dalam arus modernitas yang melahirkan keterasingan batin.
Rendra mengajak bangsa untuk kembali kepada sangkan paraning dumadi: menyadari asal-usul keberadaannya sebagai bangsa yang berjiwa spiritual dan berlandaskan harmoni antara lahir dan batin. Konsep sangkan paraning dumadi dalam filsafat Kejawen menegaskan bahwa manusia dan bangsa tidak boleh melupakan asalnya, nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi moral peradaban. Lupa pada asal berarti kehilangan arah, sebab urip tanpa pangeling(hidup tanpa kesadaran asal dan tujuan) akan membawa bangsa pada kekacauan batin dan sosial.
Melalui sajak-sajaknya, seperti Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon dan Sajak Pertemuan Mahasiswa, Rendra terus mengingatkan bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan budi pekerti akan berakhir pada kehancuran harmoni sosial. Ketika ia menulis:
“Orang-orang harus dibangunkan. Kesaksian harus diberikan.
Agar kehidupan bisa terjaga.”
(Aku Mendengar Suara, 1974)
pesan itu masih relevan hingga kini. Ia adalah panggilan etis agar masyarakat modern tidak tenggelam dalam kenyamanan material, melainkan tetap waspada terhadap kerusakan moral dan sosial yang lahir dari ketamakan, ketidakadilan, dan kehilangan empati.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, puisi-puisi Rendra menjadi cermin dan peringatan spiritual. Fenomena korupsi, kesenjangan ekonomi, intoleransi, serta krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga moral dan politik adalah bentuk konkret dari ketidakseimbangan antara ngudi kamulyan (mengejar kemakmuran) dan ngudi kabecikan (mengejar kebaikan). Pembangunan fisik yang megah tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan rasa (kebersihan hati, keadilan sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan) adalah bentuk dur angkara (penyimpangan moral) yang sudah diantisipasi Rendra sejak tahun 1970-an.
Dalam Sajak Burung-burung Kondor, misalnya, Rendra menggambarkan bagaimana pembangunan yang tidak berakar pada keadilan sosial menimbulkan penderitaan rakyat:
“Para tani-buruh bekerja,
menanam bibit di tanah yang subur,
namun hidup mereka sendiri sengsara.”
Kini, lebih dari empat dekade kemudian, realitas itu tetap terasa: petani masih miskin di tengah tanah yang subur, buruh kehilangan daya tawar, dan suara kritis sering dibungkam oleh kekuasaan ekonomi-politik. Dengan membaca kembali Rendra, kita diajak untuk meninjau ulang arah pembangunan bangsa—bahwa kemajuan sejati tidak dapat diukur hanya dengan produk domestik bruto, melainkan dengan kesejahteraan spiritual dan martabat manusia.
Puisi-puisi Rendra juga relevan dalam konteks krisis moral dan komunikasi sosial masa kini. Di era digital yang serba cepat dan penuh kebisingan informasi, masyarakat sering kehilangan rasa sabar lan pangerten (kesabaran dan pengertian). Rendra, dalam Aku Tulis Pamplet Ini, mengajarkan pentingnya dialog dan rembugan, yang merupakan nilai luhur budaya Jawa:
“Aku ingin secara wajar kita bertukar kabar.
Duduk berdebat menyatakan setuju dan tidak setuju.”
Nilai ini sangat relevan untuk kehidupan demokrasi kontemporer Indonesia yang kerap diwarnai polarisasi, ujaran kebencian, dan fanatisme politik. Melalui semangat rembugan dan rukun, Rendra mengingatkan bahwa kebebasan berbicara hanya bermakna bila dilandasi oleh tata krama sosial dan welas asih, bukan oleh nafsu untuk menang sendiri.
Lebih jauh, dalam konteks globalisasi dan budaya konsumtif dewasa ini, Rendra menegaskan kembali makna ngelmu kasampurnan urip, ilmu kehidupan yang mengajarkan keseimbangan antara materi dan batin, antara kemajuan teknologi dan kesadaran spiritual. Dalam puisi Sajak Seonggok Jagung, ia bertanya dengan getir:
“Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya?”
Pertanyaan ini kini menjadi semakin penting di tengah pendidikan yang terjebak pada orientasi kompetitif, serbacepat, dan pragmatis. Rendra menegaskan bahwa pendidikan sejati harus melahirkan manusia eling lan waspada, manusia yang sadar akan jati dirinya dan tanggap terhadap penderitaan sesamanya.
Rendra juga menawarkan etika sosial yang menolak kekerasan dan kebencian, sebagaimana dalam Pamplet Cinta:
“Aku muak dengan gaya keamanan semacam ini.
Keamanan yang berdasarkan senjata dan kekuasaan adalah penindasan.”
Pesan ini menegaskan pentingnya kemanusiaan dan welas asih sebagai dasar keamanan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat kini, di mana konflik sosial dan intoleransi sering muncul, puisi Rendra mengingatkan bahwa keamanan sejati tidak bisa dibangun di atas ketakutan, tetapi di atas rasa percaya dan kasih.
Dengan demikian, jalan kebijaksanaan Timur yang ditawarkan Rendra adalah jalan keseimbangan, kesadaran, dan kasih. Ia mengajarkan bahwa peradaban tidak akan bertahan tanpa kebajikan batin, dan pembangunan tanpa rasa hanyalah kesombongan. Nilai-nilai Kejawen yang ia hidupkan, ngelmu rasa, ngudi kautaman, ngilo roso, manembah sejati, dan rukun bebrayan, menjadi tawaran etis dan spiritual untuk menjawab tantangan bangsa di abad ke-21: bagaimana menjadi modern tanpa kehilangan jiwa, menjadi kuat tanpa kehilangan kasih, menjadi maju tanpa kehilangan akar.
Maka, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, Rendra tetap hadir sebagai suara kebijaksanaan yang menembus zaman. Ia adalah penyair yang menjadi waspada purba, penyaksi zaman yang peka terhadap tanda-tanda kerusakan moral, sekaligus penjaga harmoni antara kebenaran dan welas asih. Jalan kebijaksanaan Timur yang ia tawarkan bukanlah nostalgia masa lalu, melainkan peta jalan moral menuju masa depan bangsa yang beradab, adil, dan bermartabat.
***
Daftar Pustaka
Endraswara, S. (2012). Filsafat Jawa: Menggali Butir-butir Kearifan Lokal. Yogyakarta: Narasi.
Magnis-Suseno, F. (1984). Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: Gramedia.
Rendra, W.S. (1978). Potret Pembangunan dalam Puisi. Jakarta: Pustaka Jaya.
Zoetmulder, P. J. (1990). Manunggaling Kawula Gusti: Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa. Jakarta: Gramedia.
——
*Tengsoe Tjahjono lahir di Jember 3 Oktober 1958. Penyair ini pernah mengajar di Hankuk University of Foreign Studies Korea (2014-2017). Sejak pensiun dari Universitas Negeri Surabaya (2023) ia mengajar di Universitas Brawijaya Malang. Pada tahun 2012 mendapat penghargaan sebagai Sastrawan Berprestasi dari Gubernur Jawa Timur.